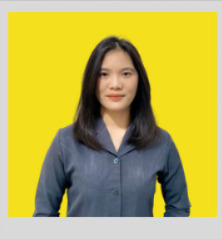FENOMENA tindak pidana korupsi dalam beberapa tahun terakhir memunculkan ironi besar dalam pemberantasan kejahatan luar biasa di Indonesia. Jika dahulu publik sudah terperangah ketika seorang pejabat tertangkap tangan menggerogoti satu miliar rupiah, kini angka korupsi berkembang menjadi sesuatu yang nyaris tak terbayangkan. Ratusan miliar hilang seketika, triliunan raib tanpa bekas, dan proses penggerogotan uang negara ini dilakukan dengan pola yang kian canggih, terstruktur, serta melibatkan banyak pihak.
Ironisnya, uang dalam jumlah fantastis itu tidak selalu dinikmati sendiri oleh pelaku, tetapi dibagikan kepada keluarga, kelompok politik, perusahaan terafiliasi, hingga dialirkan untuk berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Di sinilah problem moral mulai muncul yaitu bagaimana memaknai tindakan seorang koruptor yang menyumbangkan sebagian hasil korupsinya untuk membangun tempat ibadah, membantu anak yatim, atau membiayai kegiatan social kemasyarakatan?
Apakah tindakan tersebut dapat dipandang sebagai “sifat baik” terdakwa dan layak menjadi alasan meringankan hukuman sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman?
Baca Juga: Korupsi dan 3 Strategi Licin White Collar Crime
Pertanyaan ini bukan sekadar teknis yuridis, melainkan problem etis dan filosofis. Korupsi sebagai extra ordinary crime menempatkan hakim pada posisi moral yang tidak ringan. Hakim tidak hanya dituntut profesional, memahami elemen pasal, dan menemukan kebenaran hukum, tetapi juga mesti arif dan bijaksana dalam menilai sifat baik dan sifat jahat terdakwa, serta membedakan kebaikan sejati dari kebaikan palsu yang sengaja ditampilkan untuk mengurangi pidana. Selama ini, tidak sedikit terdakwa tipikor yang datang ke persidangan dengan membawa “rekam jejak sosial”, menunjukkan bahwa sebagian uang yang mereka korup digunakan untuk membangun jembatan desa, merenovasi tempat ibadah, menyumbang panti asuhan, hingga mendanai kegiatan social masyarakat. Mereka ingin tampil sebagai dermawan, seakan-akan perbuatannya tidak sepenuhnya memalukan. Padahal, di balik citra kedermawanan itu terdapat kenyataan
buruk bahwa uang yang mereka gunakan adalah milik publik yang dirampas dengan cara
sistematis.
Jika dianalisis lebih dalam, tindakan “amal” tersebut bukanlah bukti sifat baik, melainkan bentuk manipulasi moral. Dalam filsafat etika, suatu tindakan hanya dapat disebut baik jika bersumber dari hal yang benar dan dilakukan dengan motif kebajikan. Kedermawanan tidak dapat lahir dari sesuatu yang haram. Uang hasil korupsi yang dialirkan ke kegiatan social bukanlah kebaikan, tetapi keburukan berlapis: pertama, karena korupsi itu sendiri adalah kejahatan luar biasa; kedua, karena pelaku berupaya menutupi kejahatan itu dengan tirai amal semu. Para pelaku bersembunyi di balik simbol keagamaan dan kemanusiaan demi menciptakan kesan seolah mereka peduli rakyat. Padahal hakikatnya, mereka menyumbangkan uang rakyat kepada rakyat untuk menutupi fakta bahwa mereka telah merampok hak rakyat.
Dari perspektif a contrario terhadap Pasal 8 ayat (1) dan (2) UU 48/2009, “sifat baik” terdakwa yang dapat menjadi alasan meringankan seharusnya merupakan sifat atau tindakan positif yang sama sekali tidak terkait dengan tindak pidana yang dilakukan.
Misalnya, terdakwa memiliki kontribusi nyata bagi masyarakat sebelum melakukan tindak pidana, bersikap kooperatif selama persidangan seperti turut serta membongkar kejahatan
yang lebih besar, atau minimal menunjukkan penyesalan tulus. Namun, ketika terdakwa menyumbangkan uang yang berasal dari kejahatan, maka tindakan itu bukanlah nilai moral yang dapat dinilai sebagai kebaikan. Justru hal tersebut menunjukkan kecenderungan
manipulatif, sebab pelaku tidak hanya mengambil uang negara, tetapi juga menggunakan sebagian dari uang curian itu untuk membangun citra dirinya sebagai pahlawan sosial.
Dengan demikian, hakim tidak boleh terkecoh oleh “kebaikan palsu” ini. Kebaikan yang dipoles dari uang haram tidak dapat diakui sebagai keadaan yang meringankan. Menggunakan pendekatan filsafat, tindakan tersebut merupakan ekspresi sifat jahat: sifat jahat pertama adalah mencuri milik negara; sifat jahat kedua adalah menggunakan uang curian untuk menciptakan kesan kebaikan. Dua lapis sifat jahat inilah yang justru harus diberi bobot pemberat dalam pertimbangan hakim, bukan pertimbangan yang meringankan.
Di sinilah muncul analogi yang sering keliru, yakni ketika pelaku tipikor membandingkan dirinya dengan Robin Hood. Legenda Robin Hood adalah kisah pahlawan rakyat Inggris abad pertengahan yang mencuri dari kaum bangsawan korup untuk dibagikan kepada orang miskin. Ia beroperasi di Hutan Sherwood dan melawan penindasan Sheriff Nottingham saat Raja Richard I pergi berperang.
Dalam konteks moral legenda itu, Robin Hood mencuri dari sistem yang menindas untuk mengembalikan keadilan sosial. Sedangkan koruptor modern adalah antitesis dari itu semua. Mereka mencuri bukan dari penguasa tiran, tetapi dari rakyat. Mereka merampok anggaran pendidikan, kesehatan, bansos, dan Pembangunan infrastruktur. Mereka bukan memperjuangkan keadilan, tetapi menghancurkannya. Dan yang lebih ironis, sebagian dari mereka menyisihkan sedikit uang korupsinya untuk kegiatan sosial demi membangun citra sebagai Robin Hood masa kini. Padahal, apa yang mereka lakukan tidak lebih dari “pahlawan kesiangan” yang menyamarkan kejahatan sebagai kebaikan.
Oleh karena itu, hakim tidak boleh menjadikan mitos Robin Hood sebagai pembenaran moral. Koruptor yang menyumbang dari uang haram tidak sedang melakukan perbuatan baik, melainkan perbuatan jahat yang dibungkus rapi. Hakim harus membaca realitas bukan dari apa yang ditampilkan terdakwa, tetapi dari sumber dan motif tindakan tersebut. Jika motifnya adalah menutupi kesalahan, membentuk opininya, atau mengurangi pidana, maka tindakan itu adalah keburukan yang harus diperhitungkan sebagai hal yang memberatkan.
Pada akhirnya, memaknai Pasal 8 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman, jelas bahwa perbuatan terdakwa yang mengalirkan uang korupsi untuk kegiatan sosial keagamaan merupakan sifat jahat, bukan sifat baik. Tameng sosial dan agama yang digunakan koruptor untuk melindungi dirinya dari kecaman publik justru memperlihatkan kualitas moral yang lebih buruk.
Terdakwa yang demikian seharusnya dijatuhi hukuman yang lebih berat, sebab ia tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga memanipulasi nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan untuk kepentingan dirinya. Hakim dalam perkara tipikor dituntut menggali nurani terdalamnya, memahami manipulasi moral yang terselubung, dan memastikan bahwa keadilan tidak terkecoh oleh topeng kedermawanan palsu. Koruptor yang berlagak Robin Hood tetaplah koruptor, dan keadilan sejati menuntut agar ia dihukum sebagaimana hakikat kejahatannya, bukan sebagaimana citra yang ingin ia tampilkan.
Baca Juga: Duit Setan Dipangan Demit, Falsafah Jawa Anti Korupsi
Saut Erwin Hartono
Hakim PN Jaksel/Hakim pada Pengadilan Tipikor Jakarta
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI