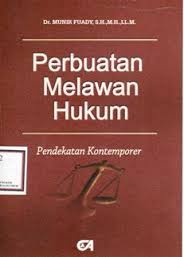Pasal 183 Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan pada intinya bahwa hakim
tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu
tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah
melakukannya. Frasa "keyakinan hakim" dalam pasal ini sebenarnya
telah menjadi pintu gerbang bagi berbagai persoalan mendasar dalam sistem
peradilan pidana Indonesia.
Masalah utama terletak pada ketiadaan
instrumen epistemik yang objektif untuk menilai validitas "keyakinan"
tersebut. Dalam praktik, keyakinan hakim sering diperlakukan sebagai ruang
hampa yang tidak dapat digugat, seolah-olah ia terbentuk dalam kevakuman
rasional. Dampaknya nyata, membuka ruang bagi bias personal, vonis yang tidak
logis, hingga ketidakadilan sistemik yang merugikan pencari keadilan.
Tulisan ini bertujuan mempertimbangkan ulang
tafsir konvensional “Keyakinan hakim” dalam sistem pembuktian yang terlalu
subjektif dan mengusulkan parameter epistemik minimal untuk menilai validitas
keyakinan hakim. Pertanyaan kunci yang ingin dijawab adalah apakah keyakinan
hakim dapat diuji secara rasional dan intersubjektif tanpa menafikan
independensinya?
Baca Juga: Saat Napi Curhat ke Hakim Wasmat PN Prabumulih: Malu hingga Ingin Cepat Bebas
Akar Masalah: Warisan Le Intime
Conviction
Konsep "keyakinan hakim" dalam
KUHAP merupakan warisan dari sistem le intime conviction yang berasal
dari tradisi hukum kontinental Eropa. Sistem ini memberikan kebebasan kepada
hakim untuk menilai bukti berdasarkan "hati nurani" tanpa terikat
aturan pembuktian yang kaku. Namun, transplantasi konsep ini ke Indonesia
terjadi tanpa diimbangi mekanisme kontrol epistemik yang memadai.
Selama ini, tafsir terhadap Pasal 183
KUHAP didominasi pendekatan subjektif individual yang memperlakukan keyakinan
sebagai produk psikologis murni. Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya
jarang mengoreksi "keyakinan" hakim karena dianggap sebagai hak
prerogatif yang tidak dapat diganggu gugat.
Berdasarkan perspektif fenomenologi
hukum, keyakinan hakim bukanlah entitas yang terisolasi, melainkan hasil
konstruksi persepsi dan pengalaman yang terbentuk melalui interaksi dengan
bukti-bukti (Alfred Schutz, 1967). Maurice Merleau-Ponty juga telah
mengingatkan bahwa persepsi manusia selalu "terwarnai" oleh latar
belakang pengalaman dan struktur kognitif yang dimilikinya (Maurice
Merleau-Ponty, 2012).
Lebih fundamental lagi, dari sudut
pandang epistemologi hukum, keyakinan tanpa justifikasi rasional hanyalah opini
pribadi, bukan pengetahuan hukum yang valid (Edmund Gettier, 1963). John Rawls
dalam A Theory of Justice telah menekankan pentingnya public reason
dalam institusi-institusi keadilan, argumen yang dapat dipahami dan dievaluasi
oleh publik (John Rawls, 1971).
Sistem hukum di negara lain telah
mengembangkan mekanisme untuk merasionalisasi “keyakinan hakim”. Di
Prancis, meskipun menganut sistem intime conviction, hakim wajib
memberikan alasan yang memadai (motivation suffisante) dalam putusannya.
Sistem common law di Amerika Serikat menggunakan standar beyond
reasonable doubt yang memiliki indikator objektif yang dapat diuji.
Problem Praktis di Indonesia
Analisis terhadap putusan pengadilan di
Indonesia menunjukkan adanya inkonsistensi dalam penerapan Pasal 183 KUHAP.
Studi yang dilakukan oleh MAPPI FH UI menemukan bahwa dalam kasus-kasus serupa,
hakim sering menghasilkan kesimpulan yang berbeda meskipun dengan alat bukti
yang relatif sama (Mappi FH UI, 2017).
Psikologi kognitif mengidentifikasi
berbagai bias yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan hakim, antara lain confirmation
bias (kecenderungan mencari bukti yang mendukung praduga awal), anchoring
effect (terlalu bergantung pada informasi pertama), dan availability
heuristic (menilai probabilitas berdasarkan kemudahan mengingat kasus
serupa) (Daniel Kahneman, 2012)
Sebenarnya, ketiadaan checklist
epistemik atau panduan objektif membuat keyakinan hakim menjadi "kotak
hitam" yang sulit dievaluasi. Sistem pembinaan hakim di Indonesia juga
lebih menekankan aspek administratif daripada kualitas penalaran yudisial¹³.
Akibatnya, hakim yang putusannya tidak logis atau bias jarang mendapat koreksi
yang memadai.
Usulan Redefinisi Epistemik “Keyakinan
Hakim”: sebagai Produk Penalaran Terstruktur
Usulan utama tulisan ini adalah
mendefinisikan ulang "keyakinan hakim" sebagai evidence-based
belief yang disertai logical justification. Keyakinan bukan lagi
sekadar "percaya" atau "yakin", tetapi harus mengandung
transparansi alur berpikir yang dapat ditelusuri dan dievaluasi.
Redefinisi ini tidak bermaksud mengekang
independensi hakim, melainkan meningkatkan kualitas dan akuntabilitas
putusannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Ronald Dworkin, independensi yudisial
harus diimbangi dengan tanggung jawab intelektual. (Ronald Dworkin, 1986).
Untuk mewujudkan redefinisi tersebut,
berdasarkan hasil eklektika penulis terhadap teori-teori yang berkembang, dapat
diusulkan empat indikator rasionalitas awal yang harus dipenuhi dalam
pembentukan keyakinan hakim:
- Koherensi
antara alat bukti dan narasi hukum: Keyakinan harus dibangun dari
bukti-bukti yang saling mendukung dan membentuk narasi yang utuh.
- Konsistensi
antar fakta, norma, dan konklusi: Tidak boleh ada kontradiksi logis antara
fakta yang ditemukan, norma yang diterapkan, dan kesimpulan yang diambil.
- Absennya
logical fallacy dalam pertimbangan: Hakim harus menghindari sesat
pikir seperti ad hominem, hasty generalization, atau false
dilemma.
- Refleksi
terhadap kemungkinan bias pribadi: Hakim perlu menunjukkan kesadaran akan
potensi bias dan upaya untuk meminimalkannya.
Parameter epistemik di atas dapat
dikembangkan menjadi Judicial Reasoning Checklist yang diintegrasikan
dalam Pedoman Teknis Mahkamah Agung. Checklist ini bukan untuk mengekang
kreativitas hakim, tetapi sebagai panduan untuk meningkatkan kualitas
penalaran.
Implementasi dapat dilakukan secara
bertahap. dimulai dari program pelatihan hakim, kemudian dimasukkan dalam
evaluasi kinerja, dan akhirnya menjadi dasar untuk revisi Pasal 183 dalam
pembaruan KUHAP di masa depan.
Penutup
Keyakinan hakim tidak boleh menjadi
ruang hampa yang kebal kritik. Dalam negara hukum yang demokratis, setiap
keputusan yang mempengaruhi hak asasi manusia harus dapat dipertanggungjawabkan
secara rasional. Redefinisi epistemik terhadap Pasal 183 KUHAP bukan ancaman
terhadap independensi yudisial, melainkan upaya memperkuat legitimasi dan
kualitas peradilan Indonesia.
Usulan parameter epistemik yang dikemukakan dalam tulisan ini masih memerlukan kajian empiris lebih lanjut dan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun, langkah awal menuju peradilan yang lebih rasional dan akuntabel harus segera dimulai. (ldr)
Daftar Bacaan
Alfred Schutz,
The Phenomenology of the Social World (Northwestern University Press,
1967)
Maurice
Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception (Routledge, 2012)
Edmund
Gettier, "Is Justified True Belief Knowledge?" Analysis, Vol.
23, No. 6 (1963)
John Rawls, A
Theory of Justice (Harvard University Press, 1971).
Code de
procédure pénale français, Article 427.
In re Winship, 397 U.S. 358 (1970).
MAPPI FH UI, Memaknai dan Mengukur
Dispraitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi,
Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Jakarta 2017
Baca Juga: Urgensi Tinjauan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Perkara Pidana Pada Putusan Pengadilan
Daniel Kahneman, Thinking, Fast and
Slow (Farrar, Straus and Giroux, 2011)
Ronald Dworkin, Law's Empire (Harvard University Press, 1986)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI