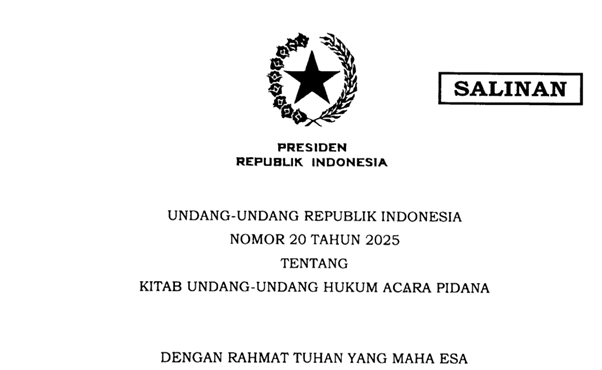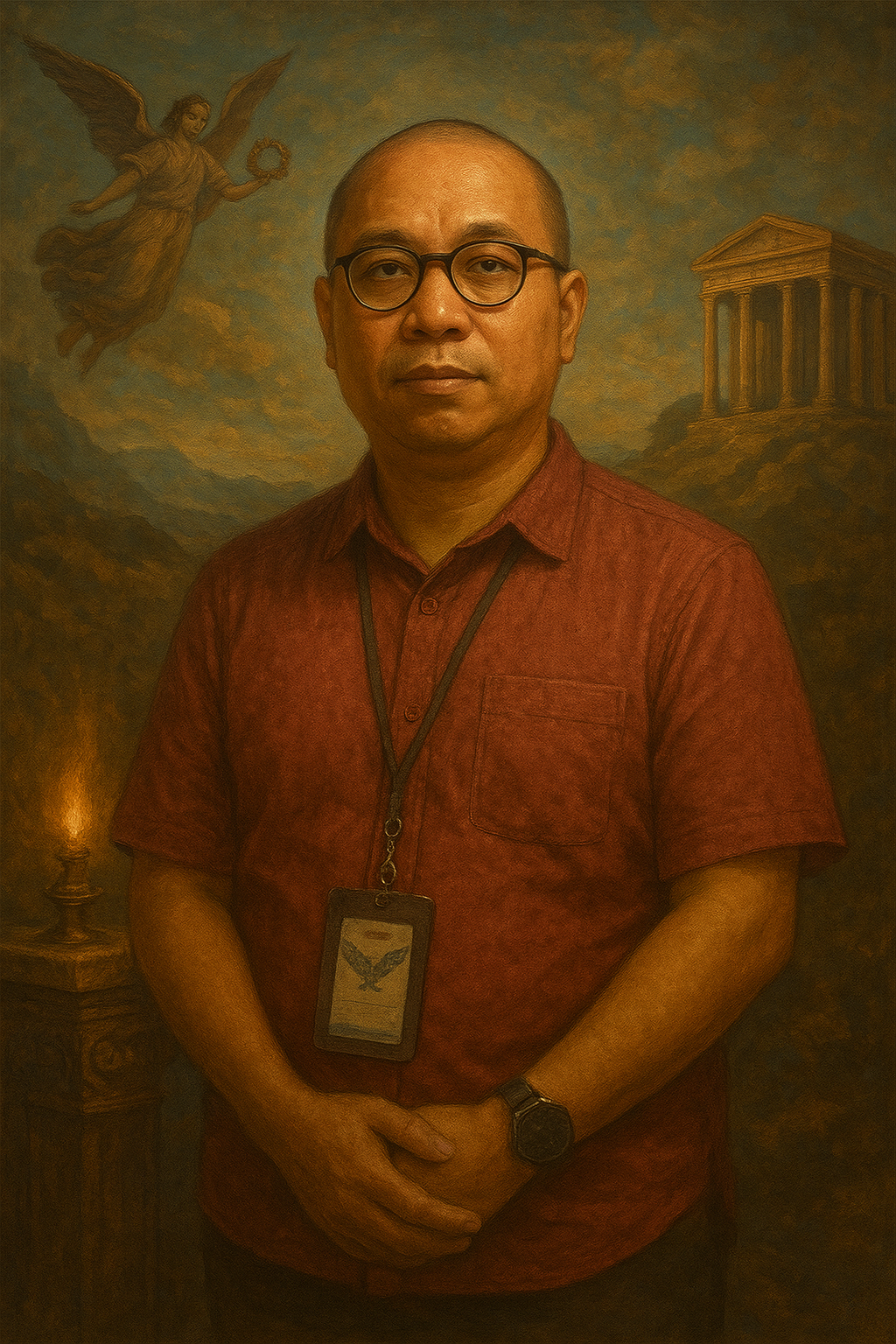Evolusi yurisprudensi global kontemporer secara konklusif menandai sebuah pergeseran epistemologis, dari paradigma retributif yang berpusat pada pelaku (offender centric) menuju model keadilan restoratif yang menempatkan viktimologi dan pemulihan korban (victim centric restoration) sebagai raison d'être dari sistem peradilan pidana.
Gerakan ini, yang diinspirasi oleh instrumen internasional seperti Deklarasi PBB tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan, menuntut reorientasi fundamental dalam praktik peradilan. Di Indonesia, legislasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan manifestasi normatif dari pergeseran paradigmatik tersebut.
Jantung dari spirit restoratif ini berdetak kencang dalam Pasal 16 ayat (1), yang mempostulatkan sebuah mandat imperatif: "hakim wajib menetapkan besarnya Restitusi". Norma substantif ini, dalam kemegahannya, merepresentasikan apa yang oleh Roscoe Pound disebut sebagai law in books, yakni hukum dalam idealitas teks.
Baca Juga: Menelusuri Akar Keadilan, Dialektika Sejarah dan Kausalitas dalam Sengketa Pajak
Namun, untuk mencegah idealisme ini menjadi sekadar utopia normatif yang tak tersentuh oleh realitas, dibutuhkan sebuah jembatan operasional menuju law in action, yakni hukum dalam implementasinya. Jembatan inilah yang secara presisi dibangun oleh Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.
Oleh karena itu,
sebuah analisis kritis harus melampaui pandangan simplistis yang membenturkan
keduanya, dan sebaliknya, menempatkan Perma ini sebagai artikulasi prosedural
yang esensial untuk mengaktualisasikan keadilan restitutif yang diamanatkan
oleh UU TPKS.
Dialektika antara keadilan prosedural dan keadilan substantif telah lama menjadi diskursus sentral dalam filsafat hukum. Keadilan prosedural, yang berakar pada teori procedural due process, mensyaratkan bahwa proses penegakan hukum harus dijalankan secara adil, transparan, dan dapat diprediksi (predictable) untuk melegitimasi hasilnya.
Tanpa kerangka kerja prosedural yang jelas, penegakan keadilan substantif akan rentan terperosok ke dalam lembah arbitrasi dan inkonsistensi yudisial. Dalam aras inilah Perma Nomor 1 Tahun 2022 tampil sebagai praesidium, sebuah benteng pelindung bagi integritas proses peradilan. Dengan merumuskan secara metodis syarat-syarat permohonan, mekanisme pembuktian kerugian, dan tahapan pemeriksaan.
Perma ini mentransformasikan konsep restitusi dari sebuah abstraksi menjadi sebuah proses hukum yang terukur, memastikan bahwa penetapan nilai kerugian tidak lahir dari intuisi atau simpati yang subjektif, melainkan dari sebuah proses adjudikasi yang didasarkan pada dalil-dalil yang didukung oleh alat bukti yang valid dan terverifikasi.
Dengan
demikian, prosedur yang digariskan oleh Perma bukanlah formalisme yang steril,
melainkan sebuah matriks prosedural yang menjamin bahwa fondasi bagi
terwujudnya keadilan substantif dibangun di atas pilar-pilar kepastian hukum (rechtszekerheid).
Kepastian prosedural ini tidak hanya memberikan perlindungan bagi korban untuk
mengajukan klaimnya secara terstruktur, tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa
dari tuntutan ganti rugi yang tidak berdasar, sehingga menjaga keseimbangan dan
kelayakan proses peradilan secara keseluruhan.
Lebih dari sekadar instrumen prosedural, Perma Nomor 1 Tahun 2022 secara inheren berfungsi sebagai katalisator untuk materialisasi keadilan substantif itu sendiri. Dengan menyediakan taksonomi kerugian yang dapat dimohonkan, mulai dari damnum emergens (kerugian nyata seperti biaya medis) hingga lucrum cessans (kehilangan keuntungan yang diharapkan seperti hilangnya penghasilan) dan kerugian imateriel, Perma ini memberikan sebuah kerangka kerja analitis yang komprehensif bagi yudikatif.
Tanpanya, Hakim akan menghadapi tugas herculean untuk mengkuantifikasi penderitaan korban dalam sebuah kevakuman normatif, yang berpotensi melahirkan disparitas putusan yang tajam. Prosedur yang mendorong penyertaan bukti-bukti pendukung, seperti visum et repertum psychiatricum atau laporan valuasi kerugian ekonomi, merupakan sebuah mekanisme yudisial untuk "menerjemahkan" trauma dan kerugian korban ke dalam postulat hukum yang dapat dijustifikasi secara rasional.
Instrumen ini memberdayakan
yudikatif untuk mengejawantahkan amanat UU TPKS dengan basis argumentasi dan
pembuktian yang solid, memastikan bahwa putusan yang dihasilkan tidak hanya
memuaskan rasa keadilan korban, tetapi juga memiliki resiliensi yuridis
terhadap pengujian di tingkat banding maupun kasasi. Hal ini sejalan dengan
teori "moralitas internal hukum" dari Lon Fuller, di mana kejelasan,
konsistensi, dan kemungkinan untuk dipatuhi yang ditawarkan oleh Perma
menjadikan norma restitusi dalam UU TPKS tidak hanya sebuah perintah, tetapi
sebuah aturan hukum yang fungsional dan efektif.
Simbiosis yuridis antara mandat substantif UU TPKS dan kerangka prosedural Perma Nomor 1 Tahun 2022 pada akhirnya berkonvergensi pada penguatan akuntabilitas dan transparansi peradilan. Dengan mewajibkan setiap tahapan, mulai dari pengajuan hingga eksekusi, untuk terdokumentasi, Perma ini menciptakan sebuah jejak audit (audit trail) yang memungkinkan pengawasan terhadap kinerja aparatur peradilan.
Putusan Hakim menjadi lebih transparan karena landasan pertimbangannya terartikulasi secara eksplisit, merujuk pada permohonan dan bukti-bukti yang telah diuji silang (cross examined) dalam persidangan. Ini adalah manifestasi dari prinsip peradilan yang akuntabel.
Dengan demikian, Perma Nomor 1 Tahun 2022 harus dibaca sebagai sebuah mahakarya regulasi yudisial, sebuah wujud kearifan institusional Mahkamah Agung dalam mengorkestrasi sebuah sintesis antara imperatif perlindungan korban yang termaktub dalam lex superior (UU TPKS) dengan kebutuhan akan sebuah proses peradilan yang tertib, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sebuah harmoni antara law in books dan law in action.
Pengaturan teknis ini mencegah potensi penyalahgunaan wewenang
dan memastikan bahwa diskresi hakim dalam menilai kerugian tetap berada dalam
koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, baik secara horizontal kepada
sesama penegak hukum maupun secara vertikal kepada publik dan pencari keadilan.
Sebagai kesimpulan, memposisikan UU TPKS dan Perma Nomor 1 Tahun 2022 dalam sebuah oposisi biner merupakan sebuah kekeliruan analitis. Keduanya berada dalam sebuah hubungan simbiosis mutualisme yang tak terpisahkan.
UU TPKS adalah tesis normatif yang menetapkan apa yang harus dicapai, yakni keadilan restitutif. Sementara itu, Perma Nomor 1 Tahun 2022 adalah antitesis prosedural yang menyediakan perangkat tentang bagaimana tujuan luhur tersebut dapat dicapai secara efektif dan berkeadilan.
Baca Juga: Dialektika Pendulum dan Yudisialisme: Menelusuri Dinamika Sumber Hukum Peradilan Pajak
Sintesis dari keduanya adalah terwujudnya sebuah sistem peradilan pidana yang tidak hanya kapabel dalam menghukum pelaku, tetapi juga kompeten dalam memulihkan korban. Melalui Perma ini, Mahkamah Agung telah menyediakan perangkat yudisial yang canggih bagi para hakim untuk menjadi agen transformasi, memimpin evolusi peradilan pidana Indonesia menuju sebuah cakrawala yang lebih humanis, restoratif, dan beradab.
Model sinergis antara legislasi substantif dan regulasi prosedural yudisial ini
berpotensi menjadi cetak biru bagi reformasi hukum di area lain, menunjukkan
bahwa pembaruan hukum yang paling efektif adalah yang mampu menyeimbangkan
antara grand design normatif dengan arsitektur implementasi yang cermat.
Pada akhirnya, harmoni inilah yang akan menentukan apakah keadilan bagi korban
kekerasan seksual akan menjadi realitas yang dirasakan atau sekadar janji yang
tertulis di atas kertas. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI