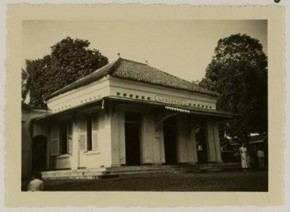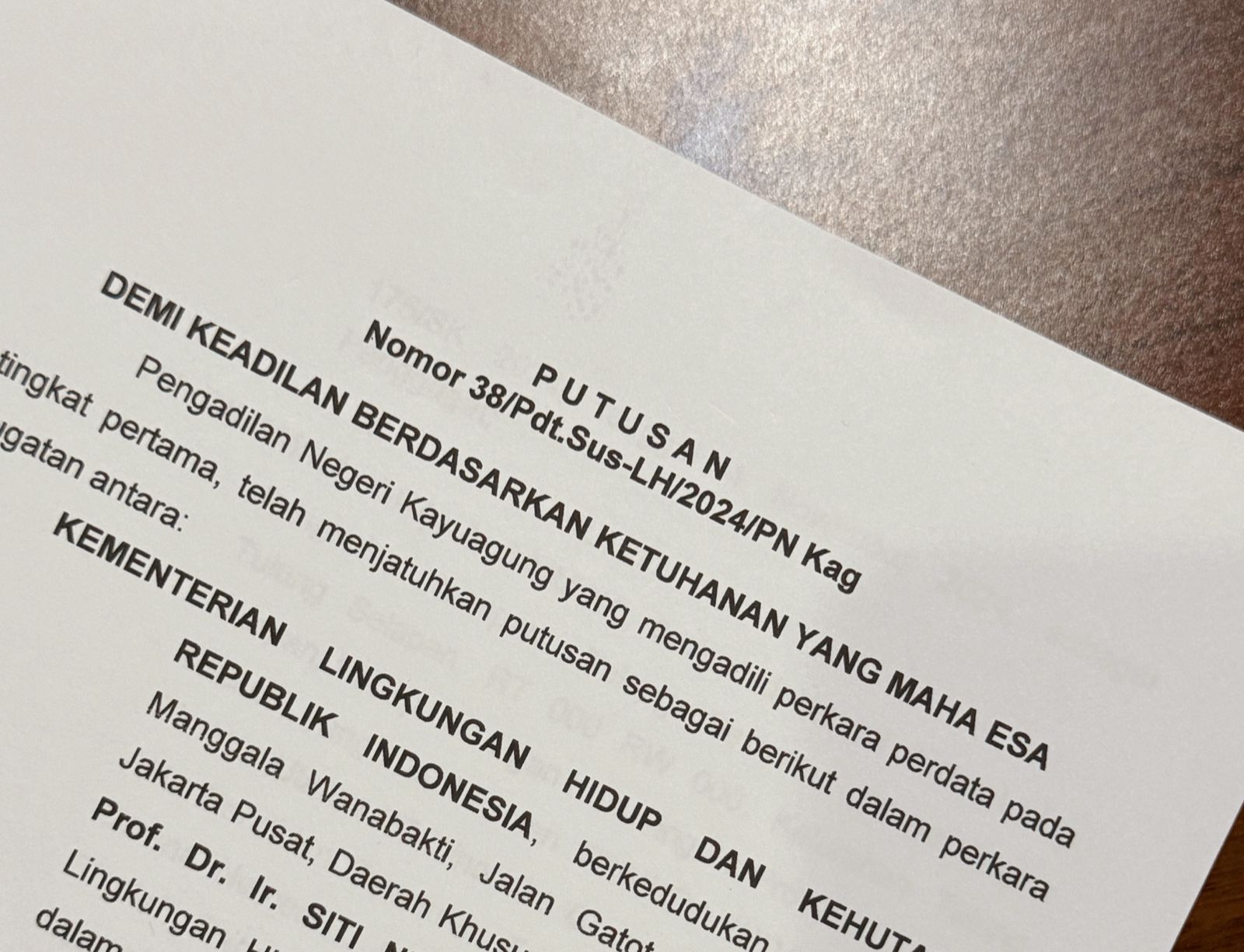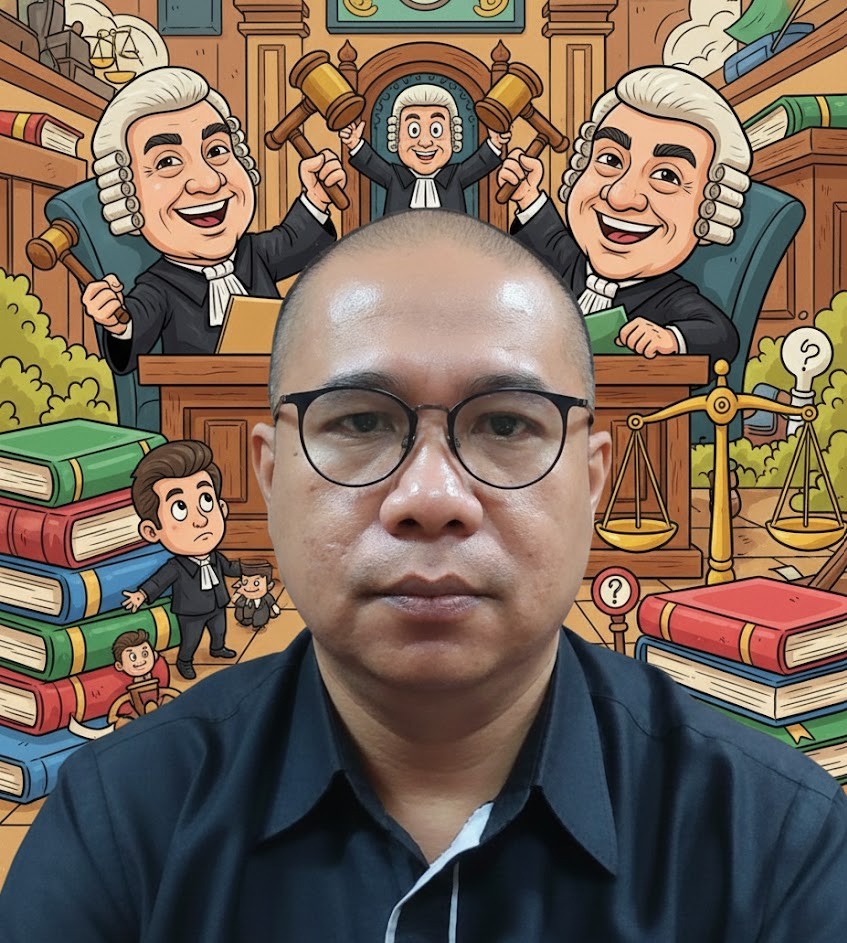Perkembangan sektor jasa
keuangan yang makin kompleks, cepat, dan terdigitalisasi memperlihatkan
paradoks klasik dalam hukum perdata, di mana hubungan yang secara doktrinal
dipahami sebagai relasi privat yang setara, dalam praktik justru bertumpu pada
asimetri informasi dan asimetri daya tawar. Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK)
mengoperasikan produk dan layanan yang sarat teknologi, klausula baku, serta
struktur risiko yang tidak mudah dibaca oleh konsumen.
Dalam situasi demikian,
mekanisme "gugat sendiri" yang menjadi nadi litigasi perdata
konvensional sering berakhir sebagai hak yang semu. Kerugian individual yang
relatif kecil, biaya berperkara yang tidak sedikit, dan ketakutan menghadapi
institusi besar menumbuhkan apatisme rasional, akhirnya konsumen memilih diam
karena menggugat terasa tidak sepadan.
Di titik itu intervensi
negara memperoleh justifikasi. Melalui mandat perlindungan konsumen, OJK diberi
kewenangan pembelaan hukum, termasuk secara eksplisit mengajukan gugatan untuk
pemulihan harta dan/atau ganti kerugian akibat pelanggaran ketentuan sektor
jasa keuangan, dengan penegasan bahwa ganti kerugian hanya dipergunakan untuk
membayar pihak yang dirugikan.
Baca Juga: PN Kayuagung: Negara Berwenang Ajukan Gugatan Kerusakan Lingkungan Lahan Privat
Namun kewenangan
substantif itu cukup lama berhadapan dengan problem prosedural, yakni bagaimana
gugatan yang mewakili banyak konsumen diletakkan dalam hukum acara perdata yang
dirancang untuk sengketa individual, bagaimana pengadilan mengelola pembuktian
massal, bagaimana menutup celah litigasi berulang, dan bagaimana mengeksekusi
putusan yang sasarannya menyentuh ribuan orang.
Jawaban prosedural
tersebut dihadirkan melalui PERMA 4/2025 yang mengatur tata cara mengadili
gugatan OJK sebagai upaya pelindungan konsumen. Pada tataran teori, PERMA ini
mencerminkan pergeseran dari litigasi privat individual menuju litigasi korektif
berbasis kepentingan publik dan keseimbangan, yakni model yang bertujuan
mengoreksi kegagalan pasar dan ketimpangan struktural dalam relasi konsumen -
pelaku usaha jasa keuangan. Karena itu, istilah "hegemoni negara"
perlu didefinisikan secara eksplisit.
Hegemoni dalam konteks
ini bukan dominasi negara yang meniadakan otonomi privat, melainkan perluasan
fungsi negara kesejahteraan sebagai koreksi struktural, di mana negara hadir
mengambil alih sebagian beban litigasi agar hak perdata yang secara teoritis ada
benar-benar efektif dijalankan dalam kenyataan, terutama ketika mekanisme
privat gagal menghasilkan pemulihan yang memadai. Catatan definisional ini
penting agar "hegemoni" tidak dibaca sebagai glorifikasi negara,
tetapi sebagai konsep kerja untuk menjelaskan pergeseran fungsi.
Konsekuensi pertama
tampak pada konstruksi kedudukan OJK di pengadilan. Ketika OJK mengajukan
gugatan, OJK tidak ditempatkan sebagai kuasa berdasarkan mandat individual
konsumen, melainkan sebagai pengampu kepentingan perlindungan konsumen
berdasarkan kewenangan undang-undang. Karena itu, PERMA menegaskan OJK dapat
mengajukan gugatan tanpa memerlukan surat kuasa khusus dari konsumen. Namun
frasa "tanpa kuasa dari konsumen" tidak berarti tanpa instrumen
representasi di persidangan, sebab OJK tetap dapat memberi surat tugas kepada
pegawainya atau memberikan surat kuasa khusus kepada pihak lain yang memenuhi
syarat sebagai kuasa. Dengan konstruksi demikian, legitimasi OJK sebagai
penggugat tidak dibangun dari kuasa individual, melainkan dari mandat
kelembagaan untuk melindungi kepentingan publik konsumen.
Pergeseran lain yang
tidak kalah penting adalah mekanisme opt out. Sebelum gugatan diajukan,
OJK wajib mengumumkan daftar konsumen yang akan dicantumkan dalam gugatan dan
memberi ruang bagi konsumen untuk menyatakan keluar dalam jangka waktu tertentu
melalui kanal pengumuman yang ditetapkan. Pernyataan keluar disampaikan kepada
OJK, dan konsumen yang memilih keluar tidak dimasukkan dalam daftar konsumen di
dalam gugatan.
Konsekuensi yuridisnya
tegas, yakni konsumen yang keluar dapat menggugat sendiri melalui hukum acara
perdata biasa, sedangkan konsumen yang tidak menyatakan keluar dan tercantum
dalam putusan yang berkekuatan hukum tetap tidak dapat mengajukan gugatan
kembali. Model ini menutup fragmentasi perkara dan mencegah gugatan ulang atas
pokok perkara yang sama, tetapi sekaligus menuntut kecermatan pada aspek
pemberitahuan agar "diam dianggap ikut" tidak berubah menjadi jebakan
prosedural bagi konsumen yang tidak terjangkau informasi.
PERMA juga merombak
arsitektur pemeriksaan perkara dengan cara yang sengaja dibuat ringkas. Proses
pemeriksaan gugatan tidak membuka ruang replik, duplik, rekonvensi, intervensi,
maupun kesimpulan. Secara kebijakan, ini diarahkan untuk memotong tahapan yang
sering memperpanjang proses, menekan biaya, dan mengurangi ruang manuver
menunda.
Namun percepatan tidak
boleh dibaca sebagai tujuan tunggal. Dari sudut due process, pemangkasan
tahapan menggeser beban artikulasi ke tahap awal, di mana penggugat harus
merumuskan dalil, petitum, dan konstruksi pembuktian secara matang sejak
gugatan, sementara tergugat harus menumpahkan bantahan dan bukti secara efektif
dalam jawaban. Di sini kualitas manajemen perkara oleh hakim menjadi faktor
kunci, di mana tanpa pengendalian sidang yang aktif dan tertib, desain ringkas
dapat kontraproduktif karena justru memperbesar kebingungan isu, melemahkan
pencarian kebenaran materiil, atau menimbulkan persepsi ketidakadilan
prosedural.
Dimensi "hegemoni
negara" makin jelas ketika melihat pilihan forum dan batas waktu. PERMA
menempatkan kewenangan mengadili gugatan terhadap PUJK konvensional pada
pengadilan niaga, dan terhadap pelaku usaha jasa keuangan syariah pada
pengadilan agama. Pengaturan ini bukan sekadar pembagian administratif,
melainkan penegasan yurisdiksi yang berkelindan dengan karakter produk dan
prinsip yang melandasinya.
Pada saat yang sama,
putusan tingkat pertama dibatasi tenggat pengucapannya, dan jika berlanjut ke
kasasi, terdapat tenggat yang ketat pula. Pesan normatifnya gamblang, yakni
perkara pelindungan konsumen tidak boleh dibiarkan menjadi sengketa
berkepanjangan yang menggerus nilai pemulihan.
Tetapi, konsekuensi
kelembagaannya perlu dibaca jernih, yakni pengadilan niaga maupun pengadilan
agama dituntut kesiapan mengelola pembuktian massal, penataan alat bukti, dan
manajemen perkara cepat agar tenggat tidak berubah menjadi tekanan formal yang
mengorbankan kualitas pemeriksaan.
Kontroversi terbesar
biasanya mengemuka pada rezim upaya hukum. PERMA menentukan bahwa terhadap
putusan, para pihak hanya dapat mengajukan kasasi. Pembatasan ini perlu
ditautkan langsung dengan due process, bukan semata-mata dipuji sebagai
efisiensi. Karena pemeriksaan fakta pada dasarnya berhenti di tingkat pertama,
standar kehati-hatian hakim tingkat pertama menjadi kompensasi utama, di mana
penilaian alat bukti harus cermat, pertimbangan harus runtut, dan rumusan amar
harus presisi.
Dengan kata lain,
pembatasan upaya hukum menuntut "penebalan" kualitas putusan tingkat
pertama agar risiko kekeliruan penilaian fakta, yang secara doktrin sulit
diperbaiki di tingkat kasasi, dapat ditekan semaksimal mungkin. Tanpa kesadaran
itu, desain kasasi sebagai satu-satunya upaya hukum dapat dipandang mengurangi
peluang koreksi, khususnya dalam perkara massal yang kompleks secara data.
Aspek eksekusi
menunjukkan bentuk paling konkret dari pergeseran peran negara. Jika putusan
tidak dilaksanakan secara sukarela, penggugat mengajukan permohonan pelaksanaan
putusan, dan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap pada prinsipnya
mengikuti ketentuan hukum acara perdata, kecuali ditentukan lain. Dalam hal gugatan
dikabulkan, pelaksanaan putusan dinyatakan selesai setelah pengadilan
menyerahkan hasil pelaksanaan eksekusi kepada OJK.
Mekanisme distribusi
pembayaran ganti rugi dilakukan oleh OJK setelah penyerahan hasil eksekusi
tersebut, dan OJK menyerahkan laporan pelaksanaan kepada pengadilan. Di sinilah
OJK tampil bukan hanya sebagai penggugat, tetapi juga sebagai pengelola
distribusi pemulihan.
Titik ini perlu
diperjelas dari sisi diskresi. Secara konseptual, peran OJK dalam distribusi
bersifat administratif karena melaksanakan amar dan mekanisme yang sudah
ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam praktik, distribusi hampir selalu
membutuhkan keputusan teknis yang berpotensi mengandung diskresi, misalnya
verifikasi identitas, pemadanan data, penanganan rekening tidak aktif, koreksi
duplikasi klaim, serta pembagian ketika dana hasil eksekusi tidak menutup
seluruh klaim.
Demi akuntabilitas,
desain pelaksanaan idealnya menyediakan mekanisme koreksi atau keberatan yang
proporsional, maka cukup untuk mengoreksi kekeliruan faktual dalam distribusi,
namun tidak membuka pintu bagi sengketa baru yang mengulang perkara pokok.
Dengan demikian, tujuan utama PERMA, pemulihan yang cepat dan efektif, tetap
terjaga, tetapi rasa keadilan konkret pada tahap distribusi juga terlindungi.
Pada akhirnya, PERMA
4/2025 memperlihatkan arah baru hukum acara perdata dalam konteks sektor jasa
keuangan, di mana negara tidak lagi sekadar menyediakan forum, melainkan ikut
memikul beban litigasi dan merancang jalan pemulihan kolektif. Kerangka ini
sejalan dengan mandat perlindungan konsumen, tetapi sekaligus menuntut
kedisiplinan institusional, yaitu kualitas seleksi kasus, ketepatan perumusan
gugatan, kehati-hatian pembuktian, kesiapan kelembagaan pengadilan, serta
akuntabilitas distribusi. Jika prasyarat itu dijaga, "hegemoni
negara" yang lahir dari PERMA tidak akan dibaca sebagai dominasi yang
menyingkirkan subjek privat, melainkan sebagai koreksi struktural yang
memulihkan keseimbangan di pasar keuangan yang sejak awal tidak benar-benar
setara. (asn/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI