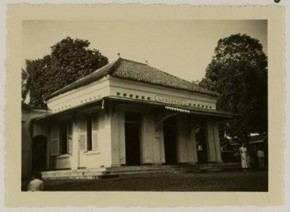Ketika mendengar istilah “Pelanggaran
Integritas”, tidak jarang hal-hal yang terlintas pertama kali dalam pikiran kita
adalah penerimaan suap, gratifikasi, pemerasan, dan perbuatan-perbuatan lain
yang berbau transaksional. Hal tersebut tidak sepenuhnya salah, karena memang
seringkali kita dipertontonkan persoalan nir-integritas yang cenderung memiliki
corak yang sama, yaitu kegiatan-kegiatan yang transaksional, baik itu mengenai
perkara, jabatan, kemudahan (privilege), dan masih banyak hal lainnya.
Namun, seringkali hal yang luput
disadari adalah integritas dapat tercoreng dari hal-hal yang terkecil sekalipun
yang sama sekali belum menyentuh pokok atau core business dari lingkup
kerja itu sendiri. Dalam praktik peradilan, tidak jarang persoalan integritas
itu muncul ketika batas kewenangan yang telah diatur dengan tegas mulai
dikaburkan oleh praktik-praktik informal yang tidak memiliki legitimasi
normatif, dan tanpa disadari, hal tersebut cukup berpengaruh dalam segala
urusan, termasuk di dalamnya berupa kelancaran proses persidangan.
Ancaman itu tidak selalu muncul secara
terbuka, ia muncul dengan cara yang halus, bahkan senyap, dengan cara
pembentukan persepsi bahwa proses peradilan dapat “diarahkan” oleh jalur di
luar mekanisme yang resmi. Beragam klaim mulai dari kedekatan, penggunaan nama
aparatur tertentu sebagai alat legitimasi semu, klaim palsu atas “pengaruh”
sangat sering digunakan sebagai senjata untuk memengaruhi pihak berperkara.
Perbuatan-perbuatan itulah yang akhirnya menimbulkan persepsi bahwa hukum
merupakan ruang negosiasi atas dasar kedekatan personal. Sayangnya, persepsi
itu seringkali dipercaya begitu saja.
Baca Juga: Hakim Tidak Boleh Flexing di Media Sosial, Perspektif Filosofis dan Etika
Persoalan itu akan menjadi semakin
serius ketika praktik semacam itu dilakukan oleh unsur yang berada dalam
struktur pengadilan. Semuanya memiliki potensi untuk melewati batas kewenangan
apabila kesadaran terhadap kode etik yang melekat tidak dipahami dan diresapi
dengan baik. Seluruh fungsi dalam struktur peradilan telah dirancang dengan
peran dan batas yang jelas. Ketika batas itu dilanggar, baik secara sadar
ataupun karena dibiarkan, maka integritas lembaga peradilan berada dalam posisi
yang rentan, tidak runtuh seketika, namun perlahan-lahan melemah.
Konkritnya, permasalahan akan muncul
ketika fungsi-fungsi yang sudah diatur dengan jelas melampaui kewenangannya dan
bergeser ke arah yang seharusnya bukan kewenangan dari fungsi tersebut.
Misalnya, dengan membentuk persepsi atau mengarahkan sikap pihak-pihak terhadap
tahapan proses persidangan. Sudah barang tentu, pergeseran fungsi ini
menciptakan “ilusi otoritas” yang sejatinya tidak pernah diberikan oleh aturan
manapun, dan hal itu berpotensi cukup kuat dalam merusak tertib peradilan.
Kerentanan makin terbuka ketika
dikaitkan dengan masih terbatasnya pemahaman publik mengenai struktur jabatan,
fungsi, dan batas kewenangan di lingkungan peradilan. Tidak semua pihak
mengetahui perbedaan peran yang ada dan apa yang menjadi kewenangan
masing-masing peran tersebut. Dalam kondisi demikian, klaim-klaim yang tidak
benar menjadi lebih mudah dipercaya. Pada tahap inilah, persoalan integritas
juga tidak lagi semata-mata muncul dari niat seorang individu, melainkan juga
karena lemahnya pemahaman publik yang belum terlindungi oleh sistem yang ada.
Pelanggaran-pelanggaran ini seringkali
tidak akan tercatat dalam dokumen resmi, karena pelanggaran ini terjadi dalam
ranah informal, melalui komunikasi di luar forum resmi, dan seringkali melalui
sugesti yang dibungkus dengan simbol institusi. Justru karena tidak tercatat
dan sulit dibuktikan, praktik demikian akan sangat berbahaya karena secara
terus-menerus akan menggerus proses peradilan dari dalam, tidak
menimbulkan kegaduhan, dan berdampak langsung pada keadilan prosedural yang
seharusnya dijamin oleh Pengadilan.
Persoalan ini menjadi makin nyata dan
mengkhawatirkan ketika telah sampai pada titik persidangan. Ruang sidang yang
seharusnya menjadi satu-satunya ruang otoritatif justru dipersepsikan sebagai
ruang tawar ketika pihak berperkara merasa memiliki legitimasi dengan
mengatasnamakan klaim otoritas di luar persidangan. Yang dipertaruhkan adalah
kewibawaan ruang sidang itu sendiri. Persoalan integritas kini bukanlah
persoalan yang abstrak, ia hadir secara nyata di hadapan Hakim dan para pihak.
Pada titik inilah, pesan dari Yang
Mulia Ketua Mahkamah Agung pada pembinaan bidang teknis dan administrasi
yudisial tanggal 10 Februari 2026 menjadi sangat relevan. Marwah peradilan
tidak dijaga oleh siapa yang paling keras bersuara, melainkan oleh siapa yang
paling mampu menjaga perilaku dan menata tutur kata. Pernyataan tersebut
menegaskan bahwa marwah peradilan bukan dijaga melalui simbol atau retorika,
melainkan melalui disiplin perilaku dalam praktik sehari-hari.
Integritas peradilan tidak dapat
dititikberatkan hanya pada putusan Hakim. Integritas peradilan secara
keseluruhan mencakup seluruh rangkaian proses dan melibatkan seluruh aparatur
yang ada di dalamnya. Ketika terdapat fungsi yang merasa berhak melampaui
perannya, maka akan tercipta ketidakteraturan yang tidak dapat dianggap sebagai
persoalan individu saja. Ini adalah masalah institusional, yang menunjukkan adanya
tantangan yang serius dalam penegakan disiplin terhadap perbuatan pelanggaran
integritas tersebut.
Seringkali, ketika proses persidangan
tetap berjalan dan prosedur formal telah dilalui, integritas dinilai telah
terjaga dengan baik. Pandangan ini menurut Penulis tidak sepenuhnya benar,
karena prosedur yang dijalankan secara formal akan kehilangan makna ketika di
baliknya terdapat intervensi informal yang membelokkan proses. Integritas bukan
hanya kepatuhan terhadap aturan, melainkan juga kesetiaan terhadap nilai yang
mendasari aturan.
Dalam konteks ini, Hakim merupakan
penjaga batas kewenangan dan ketertiban proses peradilan. Keteguhan Hakim dalam
menegakkan prosedur adalah bentuk perlindungan terhadap keadilan substantif dan
kepercayaan publik. Namun, apabila lingkungan institusionalnya belum sepenuhnya
memiliki komitmen yang sama dalam menjaga batas masing-masing, maka akan selalu
terdapat tantangan dalam menegakkan integritas secara utuh di lingkungan
peradilan.
Kepercayaan publik terhadap lembaga
Peradilan tidak dibangun melalui pernyataan normatif atau simbol-simbol
kampanye dan kelembagaan, tetapi dibentuk melalui konsistensi praktik
sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai dari integritas itu sendiri.
Praktik-praktik informal yang mengarah ke nir-integritas ini apabila dibiarkan
berlarut-larut, meski nampak kecil dan tidak berarti, dapat menimbulkan
persepsi bahwa hukum dapat dipengaruhi oleh cara-cara di luar mekanisme resmi.
Persepsi inilah yang kemudian perlahan mengikis legitimasi Pengadilan sebagai
lembaga penegak keadilan.
Baca Juga: Jalan Sunyi Hakim: Menggali Fakta, Memahat Kebijaksanaan
Pada akhirnya, menjaga integritas
peradilan sama artinya dengan menjaga kedisiplinan diri terhadap batas
kewenangan. Setiap aparatur, apapun fungsinya, memikul tanggung jawab untuk
tidak melampaui peran yang telah ditetapkan sedemikian rupa. Perlu diingat,
integritas bukanlah heroisme sesaat, melainkan kerja sunyi dengan tuntutan
konsisten dan keberanian dalam menahan diri. Proses peradilan hanya dapat
berjalan sebagaimana mestinya tanpa intervensi ketika batas kewenangan
dihormati. Namun ketika batas itu dilanggar, hal yang pertama kali dikorbankan
adalah keadilan. (rs/snr/ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI