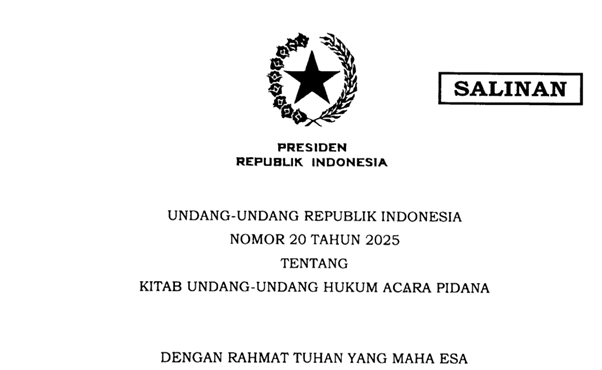Paradigma pemidanaan perikanan mesti berubah dari menghukum demi rupiah menjadi melindungi demi bumi.
Dari Laut yang Luka ke Hukum yang Bisu
Aktivitas illegal fishing, penangkapan destruktif, dan eksploitasi ikan dilindungi telah menyebabkan kerusakan ekologis dan ekonomi yang masif di Indonesia. Data KKP (2022-2023) menunjukkan 65% terumbu karang rusak akibat pengeboman ikan dan 1,2 juta hektar mangrove hilang setiap tahun, sementara LIPI (2023) mencatat 40% spesies dilindungi seperti penyu terancam punah akibat perdagangan ilegal.
Ironisnya, di tengah kerugian ekonomi Rp101 triliun per tahun dan dominasi 90% kapal asing ilegal, sanksi hukum masih sangat ringan-hanya denda Rp1-2 miliar atau kurungan 1-3 tahun, jauh di bawah ancaman maksimal 5 tahun penjara yang diatur UU.
Kondisi ini mempertanyakan urgensi peralihan paradigma hukum dari antroposentris ke ekosentris, di mana kerusakan lingkungan menjadi pertimbangan utama. Environmental ethic menawarkan solusi dengan memposisikan alam sebagai subjek hukum yang harus dilindungi.
Baca Juga: Perubahan Iklim, Yurisprudensi dan Hukum Lingkungan Pakistan
Konsep ini mengubah pendekatan pemidanaan dari sekadar menghukum pelaku menjadi memulihkan ekosistem, seperti mewajibkan rehabilitasi habitat atau pendanaan konservasi, sehingga menjamin keberlanjutan laut untuk generasi mendatang.
Hukum yang Terlambat: Lemahnya Efek Jera dalam Pemidanaan Kejahatan Perikanan
Sistem hukum kita masih beroperasi dalam kerangka berpikir antroposentris yang terbatas, di mana laut dan isinya lebih sering dipandang sebagai sumber daya ekonomi ketimbang sebagai bagian dari ekosistem yang memiliki hak untuk dilestarikan.
Prinsip etika lingkungan (environmental ethic) mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup, termasuk spesies seperti penyu, memiliki nilai intrinsik yang patut dihormati, bukan semata dinilai dari manfaat ekonominya.
Sayangnya, fakta di lapangan menunjukkan bahwa ancaman terhadap kelestarian spesies tersebut terus meningkat. Dalam beberapa kasus, ribuan telur penyu berhasil diselundupkan, mengindikasikan masih lemahnya pencegahan dan perlindungan terhadap satwa langka ini.
Penanganan hukum atas kasus-kasus seperti penyelundupan 1.500 telur penyu di Singkawang dan 2.000 telur di Ketapang pada tahun 2023 menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik yakni yang tidak hanya menindak secara pidana, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan, edukasi publik, dan kerja sama lintas batas negara untuk memberantas perdagangan ilegal satwa dilindungi.
Baru-baru ini, Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pontianak melakukan upaya nyata dalam pemberantasan kejahatan terhadap perdagangan ikan dilindungi (telur penyu) yang semakin marak terjadi di Kalimantan Barat.
Berdasarkan data berbagai sumber, tindak pidana penyelundupan atau eksploitasi telur penyu semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan kegagalan sistem pemidanaan dalam menerapkan prinsip environmental ethic.
Lemahnya penegakan hukum ini tidak hanya mengabaikan prinsip keadilan antar spesies, tetapi juga mengancam keberlanjutan ekosistem laut yang menjadi penopang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Oleh karena itu, pendekatan hukum harus beralih dari logika antroposentris menuju ekosentris, dimana kerusakan lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pemidanaan bukan sekadar pelanggaran administratif atau kerugian ekonomi.
Antroposentrisme yang Usang: Ketika Alam Sekadar Objek Eksploitasi
Sistem hukum Indonesia masih cenderung menggunakan pendekatan antroposentris yang sempit dalam menangani kasus-kasus perdagangan telur penyu, dengan fokus utama pada aspek ekonomi dan pelanggaran administratif, sementara dimensi ekologisnya sering diabaikan.
Padahal, secara ekologis, penyelundupan 2.000 butir telur penyu setara dengan potensi hilangnya sekitar 500 ekor penyu dewasa di masa depan yang masing-masingnya mampu menjaga produktivitas hingga 0,5 hektar padang lamun per hari.
Kerugian ekologis ini jauh lebih besar dibandingkan dengan sanksi ekonomi yang umumnya dijatuhkan, sehingga pendekatan hukum yang lebih berbasis pada etika lingkungan dan prinsip keberlanjutan menjadi sangat mendesak untuk diterapkan.
Pendekatan hukum seperti ini terbukti gagal menciptakan efek jera, hal ini terlihat dari lonjakan 60% kasus serupa pada 2024. Lebih memprihatinkan lagi, vonis ringan semacam ini mengabaikan dampak jangka panjang seperti ancaman kepunahan penyu hijau yang populasinya telah merosot 60% dalam satu dekade terakhir, serta kerugian ekonomi dari hilangnya jasa ekosistem yang mencapai Rp. 35 miliar per tahun.
Fakta-fakta ini menunjukkan urgensi untuk meninggalkan pendekatan antroposentris yang sudah usang dan beralih ke paradigma ekosentris yang memposisikan kerusakan lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam pemidanaan.
Ekosentrisme sebagai Paradigma Baru: Menempatkan Alam sebagai Subjek Hukum
Paradigma hukum ekosentris menawarkan pendekatan revolusioner dalam penegakan hukum perikanan, terutama dalam menangani kasus-kasus seperti perdagangan telur penyu yang semakin marak terjadi.
Pendekatan ini menggeser fokus dari kepentingan manusia semata (antroposentris) menuju perlindungan ekosistem sebagai subjek hukum yang utuh dan bernilai intrinsik. Dalam paradigma ini, ekosistem tidak lagi dipandang sebagai objek pasif yang dapat dieksploitasi, melainkan sebagai entitas yang memiliki hak untuk dilindungi demi kelangsungan kehidupan seluruh makhluk.
Perubahan paradigma ini menuntut penegak hukum untuk melihat setiap tindak pidana lingkungan bukan sekadar sebagai pelanggaran administratif atau ekonomi, tetapi sebagai serangan langsung terhadap keseimbangan ekologis yang menyokong kehidupan manusia itu sendiri.
Secara yuridis, penerapan paradigma ekosentris membutuhkan rekonstruksi sistem hukum pidana yang selama ini cenderung memarjinalkan aspek lingkungan. Selama ini, kerusakan lingkungan sering kali hanya dianggap sebagai akibat sampingan dari suatu tindak pidana, bukan sebagai unsur pokok delik yang harus dipertimbangkan secara serius dalam penjatuhan sanksi.
Dalam konteks penyelundupan telur penyu di Kalimantan Barat, misalnya, pendekatan ekosentris akan mengubah secara mendasar parameter pemidanaan. Jika sebelumnya sanksi hanya dihitung berdasarkan nilai ekonomi telur yang diperdagangkan, maka dalam paradigma baru ini hakim harus memperhitungkan dampak ekologis yang bersifat irreversibel, seperti terganggunya rantai makanan laut, hilangnya keanekaragaman hayati, serta kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem pesisir yang berfungsi sebagai penyangga kehidupan laut dan manusia di wilayah pesisir.
Tafsir Progresif UU Perikanan: Jalan Menuju Keadilan Ekologis
Secara normatif, penerapan paradigma ekosentris dalam UU Perikanan dapat dilakukan melalui penafsiran progresif terhadap beberapa ketentuan kunci, seperti:
- Pasal 1 Angka 1 tentang Definisi Sumber Daya Ikan: "Potensi semua jenis ikan" tidak hanya mencakup nilai ekonomi, tetapi juga peran ekologisnya dalam rantai makanan dan keseimbangan ekosistem laut.
- Pasal 6 ayat (2) tentang Pelestarian Lingkungan: Kewajiban pelestarian lingkungan harus mencakup perlindungan nilai intrinsik ekosistem, termasuk habitat dan spesies kunci seperti penyu.
- Pasal 26 tentang Larangan Penangkapan Ikan dengan Cara Merusak: Eksploitasi telur penyu termasuk "cara merusak" karena mengancam keberlangsungan spesies dan fungsi ekologisnya, terlepas dari metode penangkapan.
- Pasal 84 tentang Pidana Perikanan: "Kerugian negara" tidak hanya dihitung dari nilai ekonomi, tetapi juga kerusakan ekologis yang ditimbulkan.
- Pasal 93 tentang Tindakan Tata Tertib: Sanksi administratif dapat diperluas mencakup kewajiban restorasi ekosistem oleh pelaku.
Dalam menerapkan paradigma ekosentris, hakim dapat menggunakan metode “purposive interpretation” untuk membaca UU Perikanan secara progresif, dengan menekankan pada tiga aspek fundamental.
Pertama, penekanan pada tujuan ekologis di balik ketentuan larangan, seperti dalam Pasal 26 tentang penangkapan ikan dengan cara merusak. Pasal ini tidak hanya dimaknai secara sempit sebagai larangan terhadap metode destruktif (bom atau racun), tetapi juga mencakup aktivitas yang mengancam keberlangsungan ekosistem, termasuk perdagangan telur penyu yang berdampak pada kepunahan spesies.
Kedua, hakim perlu mengedepankan prinsip keberlanjutan dalam Pasal 6 ayat (2), yang mewajibkan pelestarian lingkungan. Prinsip ini harus ditafsirkan sebagai kewajiban untuk menjaga keseimbangan ekologis, bukan sekadar memastikan stok ikan tersedia untuk pemanfaatan ekonomi.
Ketiga, penafsiran harus mengacu pada nilai konstitusional perlindungan lingkungan hidup dalam Pasal 28H UUD 1945, yang menjamin hak warga negara atas lingkungan yang sehat. Dengan demikian, UU Perikanan tidak lagi dipandang sebagai instrumen pengaturan eksploitasi semata, tetapi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan ekologis, di mana kerusakan lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pemidanaan. Pendekatan ini memungkinkan hakim menjatuhkan sanksi yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan kerusakan ekosistem, seperti mewajibkan pelaku merehabilitasi habitat penyu atau membiayai program konservasi.
Belajar dari Dunia: Praktik Baik Penegakan Hukum Ekologis di Negara Lain
Beberapa negara telah membuktikan efektivitas pendekatan ekosentris dalam penegakan hukum perikanan. Kosta Rika, melalui Wildlife Conservation Law, tidak hanya menjatuhkan hukuman pidana bagi pelaku perdagangan telur penyu, tetapi juga mewajibkan restorasi ekologis seperti penanaman mangrove.
Filipina menerapkan model serupa dengan mewajibkan pelaku membiayai program penetasan buatan dan rehabilitasi habitat. Yang lebih visioner, Selandia Baru secara hukum mengakui ekosistem sebagai subjek berhak melalui Undang-Undang Sungai Whanganui, sementara Ekuador memasukkan hak alam dalam konstitusi. Australia bahkan menghitung sanksi berdasarkan nilai ekonomi jasa ekosistem yang hilang.
Menuju Rekonstruksi Hukum Perikanan: Tiga Pilar Transformatif untuk Indonesia
Pengalaman internasional tersebut menawarkan tiga prinsip utama bagi Indonesia: (1) sanksi harus mencakup biaya pemulihan ekologis, (2) pengakuan hak lingkungan dalam instrumen hukum, dan (3) sinergi antara penegak hukum dan ahli ekologi.
Sayangnya, Indonesia masih berkutat pada pendekatan usang, seperti terbukti dari vonis 6-8 bulan penjara untuk penyelundupan ribuan telur penyu, hukuman yang tidak sebanding dengan kerusakan ekologis yang ditimbulkan. Padahal, dengan mencontoh praktik terbaik dunia dan menafsirkan ulang UU Perikanan secara progresif, Indonesia bisa beralih dari paradigma eksploitasi menuju perlindungan ekosistem yang berkeadilan.
Penerapan paradigma ekosentris bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan sebuah keharusan yang mendesak. Kita perlu segera:
- Merekonstruksi UU Perikanan dengan menjadikan kerusakan ekologis sebagai unsur utama delik;
- Menerapkan sanksi restoratif yang memaksa pelaku memulihkan kerusakan yang ditimbulkan;
- Membangun sistem peradilan yang melibatkan ahli ekologi dalam setiap proses hukum.
Pengalaman negara-negara lain membuktikan bahwa pendekatan ini tidak hanya mungkin, tetapi juga efektif. Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar dengan keanekaragaman hayati laut yang luar biasa, harus segera berani mengambil langkah transformatif ini. Sudah waktunya kita berhenti memandang laut hanya sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi, dan mulai menghormatinya sebagai sistem kehidupan yang harus dilindungi. Paradigma ekosentris dalam penegakan hukum perikanan adalah langkah pertama yang penting untuk mewujudkan keadilan ekologis bagi generasi sekarang dan mendatang. Jika tidak sekarang, kapan lagi? Jika bukan kita, siapa lagi? (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI