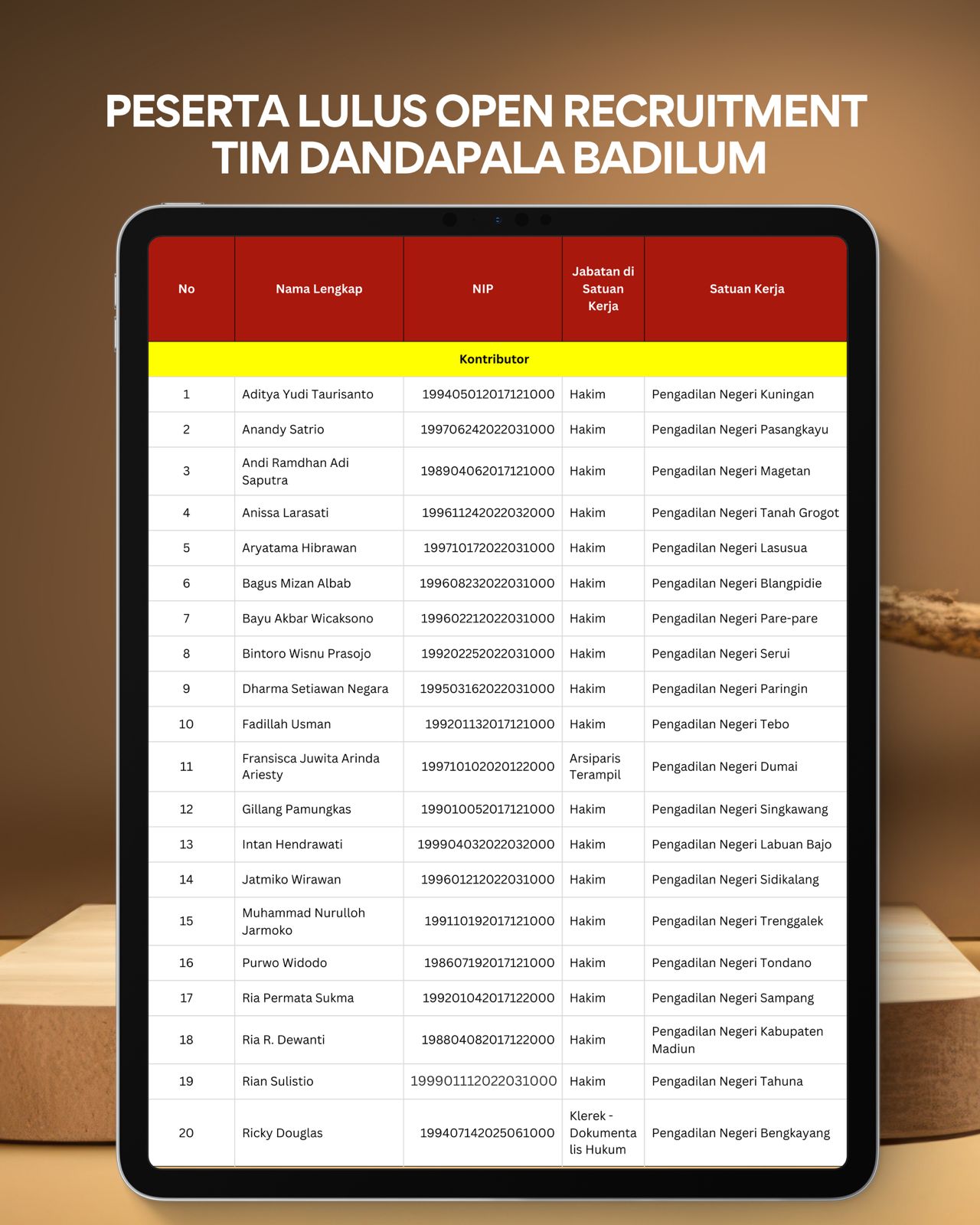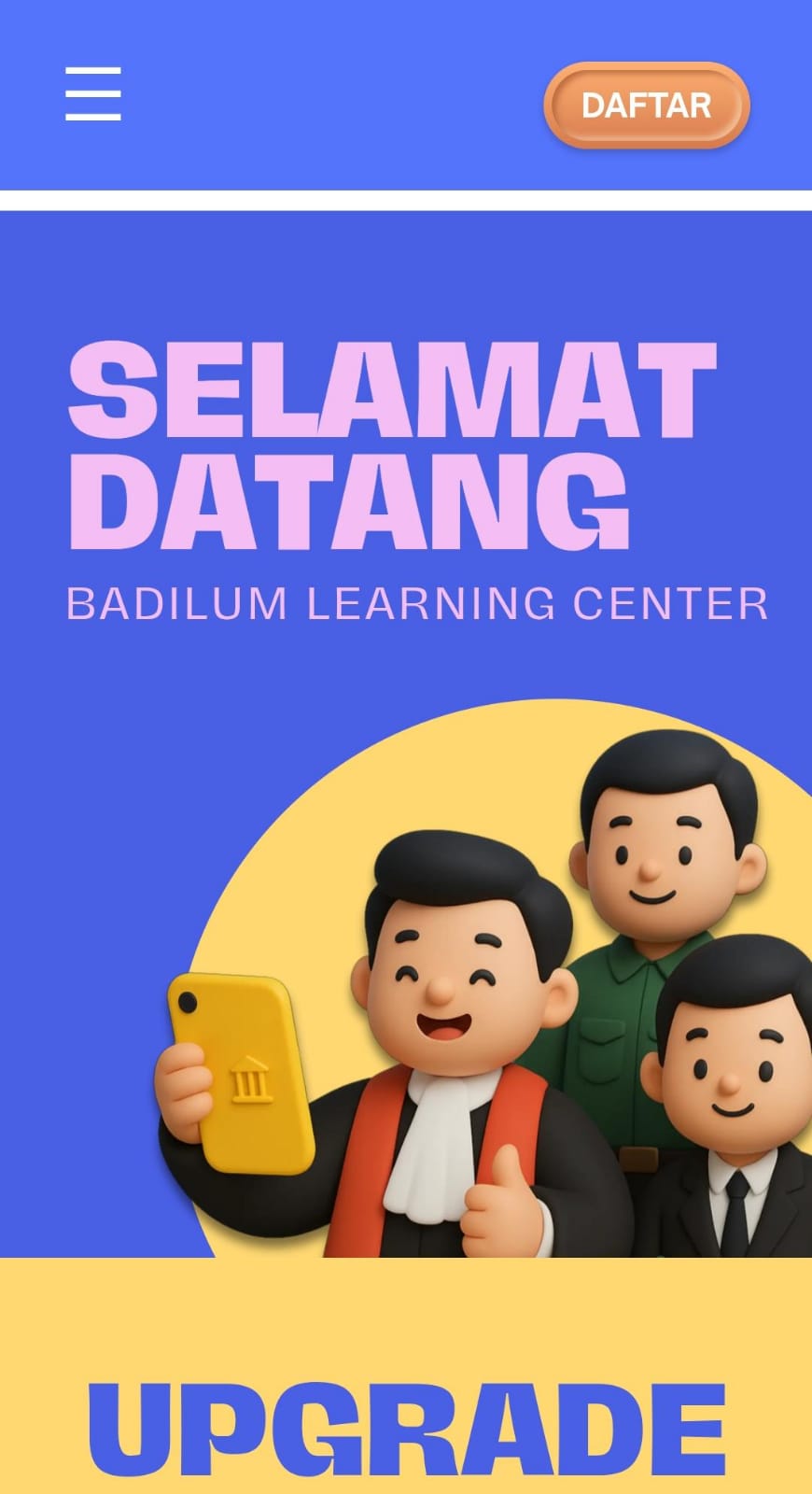Penggunaan analogi secara tegas telah dilarang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya, KUHP Baru). Analogi yang berasal dari
bahasa latin “analogia” yaitu “ana” (menurut) dan “logia”
(proporsi atau perbandingan), merupakan salah satu penemuan hukum yang
dilakukan dengan metode konstruksi hukum.
Konstruksi
hukum dalam analogi dilakukan dengan cara merangkum unsur-unsur yang terdapat
dalam teks undang-undang dan menggunakannya sebagai dasar logika untuk dianalisa
dan dibandingkan dengan perbuatan yang tidak diatur dalam undang-undang, dengan
tujuan untuk menemukan persamaan diantara keduanya sehingga makna dalam teks
undang-undang menjadi lebih luas.
Analogi
sebenarnya dapat membantu penegak hukum ketika menghadapi kekosongan hukum,
namun di sisi lain penerapannya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum karena
dapat memperluas ketentuan pidana terhadap perbuatan yang sebenarnya tidak
dilarang dalam undang-undang.
Baca Juga: Analogi Dalam Putusan Pidana, Apakah Terobosan Atau Kemunduran Hukum ?
Hal
tersebut tentunya bertentangan dengan prinsip hukum pidana nullum delictum,
nulla poena, sine praevia, lege poenali (tiada delik, tiada pidana, tanpa
adanya aturan hukum pidana), yang salah satu penerapannya mewajibkan penegak
hukum untuk menafsirkan hukum pidana secara ketat (lex stricta). Asas
inilah yang membuat analogi menjadi penemuan hukum yang dilarang dalam KUHP
Baru.
Seiring
berkembangnya teori penemuan hukum, terdapat penemuan hukum lain yang secara
praktis sangat sulit dibedakan dengan analogi, yaitu: penafsiran ekstensif. Secara
prinsip, penafsiran ekstensif berbeda dengan analogi karena metode penemuan
hukum yang digunakan adalah metode interpretasi.
Dalam
metode interpretasi, penafsiran dilakukan pada teks undang-undang dan hasil
penafsirannya tidak boleh keluar dari norma yang diatur dalam teks
undang-undang.
Meskipun
secara prinsip berbeda, penafsiran ekstensif memiliki tujuan yang sama dengan
analogi yaitu untuk memperluas cakupan ketentuan dalam undang-undang. Adanya kesamaan tujuan ini yang kemudian dalam
praktiknya sulit untuk membedakan analogi dengan penafsiran ekstensif.
Hal
ini lah yang kemudian menjadi dasar alasan Scholten mendukung penerapan analogi
dalam hukum pidana karena menurut Scholten, penafsiran ekstensif tidak memiliki
perbedaan dengan analogi.
Pendapat
yang sama juga disampaikan oleh Jonkers yang mengkritisi penerapan penafsiran
ekstensif dalam Putusan Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 dalam kasus tindak pidana
pencurian listrik yang menyamakan perbuatan menghidupkan listrik dengan
perbuatan mengambil barang atau Putusan Rechtbank Leeuwarden tanggal 10
Desember 1919 yang menyamakan perbuatan seseorang yang datang dan berdiri di
dekat sapi yang telah melepaskan diri sebagai perbuatan mengambil ternak.
Jonkers berpendapat bahwa sesungguhnya putusan-putusan tersebut tidak
menerapkan interpretasi, melainkan analogi.
Dalam
menjelaskan penerapan larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru, Eddy O.
S. Hiariej dan Topo Santoso membedakan antara analogi yang diperbolehkan yang
dan yang dilarang.
Menurutnya,
rechts analogie atau analogi hukum tidak boleh diterapkan, sedangkan gesetze
analogie atau analogi undang-undang masih boleh diterapkan sepanjang dimaksudkan
untuk menjelaskan unsur pasal. Berangkat dari pendapat tersebut, beliau menilai
bahwa Putusan Hoge Raad tanggal 23 Mei 1921 yang dikritisi Jonkers, sebenarnya
masih menggunakan gesetze analogie, sehingga penafsiran terhadap
perbuatan menghidupkan listrik sebagai tindak pidana pencurian adalah analogi
yang masih dapat dilakukan.
Terhadap
penjelasan tersebut, Penulis belum merasa cukup karena penjelasan tersebut
hanya akan menambah kerancuan dalam pemberlakuan larangan analogi pada KUHP
baru.
Di
satu sisi Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru telah melarang penerapan analogi, namun di
sisi lain terdapat pengecualian analogi yang lain. Hal ini akan menimbulkan
standar ganda dalam penerapan Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru karena pada prinsipnya
analogi bersandar pada metode konstruksi hukum.
Hal
tersebut akan memicu pertanyaan-pertanyaan mendasar mengapa KUHP Baru melarang
analogi jika terdapat bentuk analogi lain yang diperbolehkan? Oleh karenanya,
menurut penulis, sebaiknya larangan analogi dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru
diterapkan secara ketat dimana larangan penggunaan rechts analogie
berlaku pula bagi gesetze analogie.
Akan
tetapi, hal tersebut belum secara tuntas menjawab permasalahan utama mengenai
penerapan analogi yang sulit dibedakan dengan penafsiran ekstensif. Tentunya
penegak hukum khususnya hakim membutuhkan penemuan hukum yang tujuannya
memperluas cakupan ketentuan hukum manakala menghadapi kekosongan hukum, karena
hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih tidak ada hukumnya dan hakim
harus mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Oleh
karenanya, penafsiran ekstensif adalah penemuan hukum yang tetap diperlukan
jika KUHP Baru telah melarang secara tegas penggunaan analogi. Namun, jika
analogi dan penafsiran ekstensif sulit untuk dibedakan, maka larangan analogi
dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP Baru dapat berimplikasi pula pada larangan penafsiran
ekstensif.
Atau, sebaliknya,
larangan analogi dalam KUHP Baru akan menjadi pasal yang dapat disalahgunakan
karena analogi menjadi dapat secara bebas digunakan dengan dalih menggunakan
penafsiran ekstensif.
Terhadap
permasalahan tersebut, Penulis memandang penting adanya batasan yang tegas
dalam penerapan penafsiran ekstensif. Dalam penerapannya, penafsiran ekstensif
dapat digabungkan atau diterapkan secara bersamaan dengan penafsiran restriktif
menjadi penafsiran ekstensif-restriktif.
Penafsiran
restriktif adalah metode interpretasi yang bertujuan untuk membatasi makna
ketentuan hukum dengan mempertimbangkan ruang lingkup undang-undangnya.
Dengan
menggabungkan penafsiran ekstensif dan restriktif maka penafsirannya tetap
dapat memperluas cakupan ketentuan undang-undang dengan adanya batasan yang
tegas yang tidak dapat dilanggar sesuai dengan makna restriktif di dalamnya.
Hal ini akan menjadi titik pembeda dengan analogi sehingga larangan analogi
dalam KUHP Baru dapat diterapkan sepenuhnya.
Menurut
penulis, unsur restriktif dalam penafsiran ekstensif-restriktif dapat berfungsi
sebagai batasan agar penafsiran ekstensif tidak mengubah norma yang telah
diatur dalam undang-undang.
Misalnya,
dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan yang belum memberikan definisi terhadap
kendaraan listrik, penafsiran ekstensif-restriktif dapat diterapkan terhadapnya
dengan memperluas frasa kendaraan bermotor mencakup pula kendaraan listrik.
Meskipun
perluasan ini tidak sejalan dengan KBBI yang mendefinisikan mesin sebagai perkakas
yang meggunakan bahan bakar minyak atau tenaga lama, sedangkan motor sebagai tenaga
penggerak, namun tidak ada perubahan norma dalam undang-undang dalam
mendefinisikan kendaraan bermotor sehingga ketentuan ketentuan kendaraan
bermotor dalam undang-undang dapat diterapkan pula pada kendaraan listrik.
Baca Juga: Memahami Esensi Pidana Narkotika Dalam Kacamata Teleologis
Berbeda
halnya jika mendefinisikan kendaraan listrik sebagai kendaraan tidak bermotor,
maka makna restriktif dalam penafsiran ekstensif-restriktif akan melarangnya,
mengingat kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga
manusia dan/atau hewan.
Penggabungan penafsiran ekstensif dan restriktif sejatinya memang tidak dikenal dalam teori penemuan hukum karena dalam teori penemuan hukum, keduanya adalah penafsiran yang berdiri sendiri, namun hal ini dapat menjadi solusi praktis agar penerapan larangan analogi dalam KUHP Baru dapat diterapkan secara tegas tanpa mengurangi hak penegak hukum khususnya hakim untuk melakukan penemuan hukum. Pada akhirnya, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar hakim memiliki rambu yang jelas dalam membedakan analogi dan penafsiran ekstensif. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI