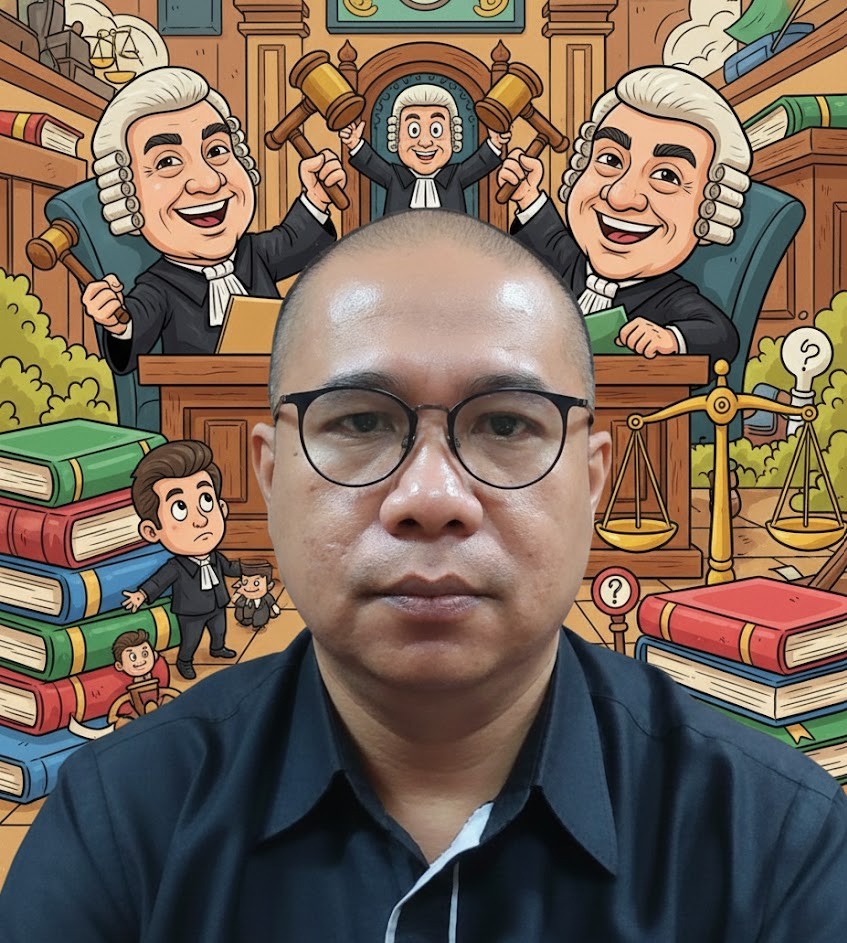Sejarah panjang hukum pidana di Indonesia memang sangat
dipengaruhi oleh kolonialisme Belanda. Sejak pemberlakuan WvS tahun 1918, wajah
hukum kita terpasung dalam kerangka berpikir positivistik serta retributif.
Sistem ini awalnya dibangun di atas fondasi diskriminatif yang menjadikan
penjara sebagai instrumen penaklukan dan pengasingan semata.
Sayangnya, filosofi pembalasan warisan kolonial ini
terus bertahan pasca kemerdekaan melalui asas konkordansi, sehingga sanksi
pidana penjara tetap menjadi primadona utama dalam penyelesaian perkara.
Kondisi ini membuat sistem peradilan terjebak, di mana
penjara justru gagal membina manusia dan malah melanggengkan residivisme.
Kini, momentum perubahan hadir lewat UU Nomor 1 Tahun
2023 yang membawa misi suci dekolonisasi dan demokratisasi. KUHP baru ini
merombak total filosofi pemidanaan, menggeser fokus dari orientasi perbuatan
menuju keseimbangan antara perbuatan dan pelakunya.
Di tengah transformasi agung ini, pidana kerja sosial
hadir sebagai inovasi revolusioner untuk mengakhiri hegemoni penjara,
menawarkan solusi yang jauh lebih bermartabat serta selaras dengan nilai luhur
bangsa.
Permasalahan krusial yang mendesak perlunya pergeseran
paradigma ini adalah kegagalan sistemik dari model pemidanaan berbasis penjara
dalam mewujudkan keadilan yang substansial dan kemanfaatan sosial.
Hegemoni "budaya penjara" warisan kolonial
telah menyeret Indonesia ke dalam krisis kemanusiaan yang akut di dalam Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas). Data terbaru menunjukkan kondisi kelebihan kapasitas (overcrowding)
yang sangat memprihatinkan, di mana tingkat hunian lapas di Indonesia telah
mencapai angka 93 persen di atas kapasitas normal pada tahun 2025, bahkan di
beberapa wilayah angkanya jauh melampaui itu.
Fenomena ini bukan sekadar statistik belaka, melainkan
cerminan dari penderitaan manusia yang dipaksa hidup berdesakan dalam ruang
yang tidak layak, kehilangan privasi, dan tergerus martabatnya, yang pada
akhirnya memicu dehumanisasi dan pelanggaran hak asasi manusia yang
sistematis.
Penjara penuh sesak tidak lagi mampu menjalankan
fungsi rehabilitasi dan reintegrasi sosial, melainkan hanya berfungsi sebagai
gudang penyimpanan manusia yang menunggu waktu untuk kembali ke masyarakat
dengan membawa trauma dan kemarahan baru.
Lebih dalam lagi, permasalahan ini berakar pada
ketidaksesuaian filosofis antara sistem hukum pidana warisan Barat yang individualistik
dan retributif dengan karakteristik sosiologis masyarakat Indonesia yang
komunal dan restoratif. Sistem kolonial memandang kejahatan sebagai
pelanggaran terhadap negara yang harus dibayar lunas dengan isolasi,
mengabaikan dimensi pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan
masyarakat.
Aparat penegak hukum sering kali terjebak dalam pola
pikir legalistik-formal yang kaku, di mana memenjarakan orang dianggap sebagai
satu-satunya parameter keberhasilan penegakan hukum, tanpa mempertimbangkan dampak
sosial ekonomi yang ditimbulkannya.
Ketiadaan alternatif sanksi yang efektif dalam KUHP
lama memaksa hakim untuk menjatuhkan pidana penjara pendek yang sejatinya tidak
efektif dan justru merusak.
Oleh karena itu, urgensi penerapan pidana kerja sosial
bukan hanya soal mengurangi kepadatan penjara, melainkan soal bagaimana
meruntuhkan tembok arogansi hukum kolonial yang telah lama membelenggu rasa
keadilan masyarakat dan menggantinya dengan pendekatan yang lebih humanis,
partisipatif, dan berkeadaban sesuai dengan Pancasila.
Pidana kerja sosial dalam KUHP Nasional
menyingkapkan bahwa sanksi ini adalah manifestasi nyata dari pergeseran
ontologis hukum pidana Indonesia. Berbeda dengan KUHP kolonial yang semata-mata
berorientasi pada pembalasan, KUHP Nasional mengadopsi paradigma keseimbangan
monodualistik yang menekankan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan
individu, serta antara unsur objektif dan unsur subjektif.
Dalam konteks ini, pidana kerja sosial
yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 85 UU Nomor 1 Tahun 2023 berfungsi
sebagai antitesis terhadap budaya penjara karena menolak isolasi sebagai metode
utama pemidanaan.
Jika penjara bekerja sebagai mekanisme
eksklusi sosial, maka pidana kerja sosial bekerja dengan cara sebaliknya:
mempertahankan pelaku di tengah masyarakat untuk memperbaiki diri melalui
kontribusi nyata, sebuah mekanisme inklusi dan reintegrasi sosial.
Secara yuridis, Pasal 85 memberikan
kerangka yang sangat progresif dengan menetapkan bahwa pidana kerja sosial
dapat dijatuhkan bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang
dari lima tahun dan hakim memvonis pidana penjara paling lama enam bulan atau
denda kategori II.
Persyaratan ini menegaskan bahwa pidana
kerja sosial didesain sebagai alternatif primary alternative untuk
menggantikan pidana penjara jangka pendek yang selama ini terbukti
destruktif. Yang paling menarik secara filosofis adalah adanya syarat
"persetujuan terdakwa" setelah dijelaskan mengenai tujuan dan tata
cara pelaksanaannya.
Hal ini menandakan penghormatan tinggi
terhadap otonomi individu dan hak asasi manusia, membedakan secara tegas antara
pidana kerja sosial dengan forced labour. Negara tidak lagi memposisikan
diri sebagai entitas otoriter, melainkan mengajak pelaku kejahatan untuk
berpartisipasi aktif dalam proses pemulihannya sendiri, membangun kembali harga
diri melalui karya yang bermanfaat.
Dari perspektif sosiologis dan kultural,
pidana kerja sosial memiliki resonansi yang kuat dengan nilai gotong royong
yang merupakan intisari dari Pancasila dan kearifan lokal nusantara. Dalam
masyarakat adat, sanksi sering kali berupa kewajiban untuk melakukan pelayanan
masyarakat atau pemulihan keseimbangan kosmis yang terganggu, bukan pengurungan
badan.
Dengan demikian, penerapan pidana kerja
sosial sejatinya adalah proses re-inventing the living law yang
selama ini tertimbun oleh positivisme hukum kolonial. Ketika seorang
terpidana membersihkan fasilitas umum atau terlibat dalam kegiatan sosial
lainnya, ia sedang melakukan ritual reintegrasi yang alami.
Masyarakat tidak lagi melihatnya sebagai
"penjahat" yang harus ditakuti dan dijauhi, melainkan sebagai anggota
komunitas yang sedang berusaha menebus kesalahan. Proses interaksi ini
memulihkan stigma, merajut kembali kohesi sosial yang retak, dan menghidupkan
kembali semangat kebersamaan yang menjadi ciri khas bangsa.
Lebih jauh, implementasi pidana kerja
sosial menuntut transformasi peran aparat penegak hukum menjadi fasilitator
pemulihan. Peran Bapas menjadi sangat sentral dalam melakukan penelitian
kemasyarakatan untuk menilai kelayakan terdakwa, sebuah proses yang
mengedepankan pendekatan personal dan humanis ketimbang pendekatan
formalistik.
Sinergi antara kejaksaan sebagai pengawas,
Bapas sebagai pembimbing, dan pemerintah daerah sebagai penyedia fasilitas
kerja sosial, mencerminkan sebuah ekosistem penegakan hukum yang integratif dan
berorientasi pada penal welfarism.
Kehadiran pidana kerja sosial dalam KUHP
Nasional bukan sekadar penambahan varian sanksi dalam katalog pemidanaan,
melainkan sebuah pernyataan sikap ideologis bangsa untuk mengakhiri dominasi
budaya penjara warisan kolonial.
Ini adalah antitesis yang tegas terhadap
paradigma retributif, menggantinya dengan paradigma restoratif yang memuliakan
pemulihan dan partisipasi. Secara filosofis, pidana kerja sosial mengembalikan
marwah hukum pidana ke tujuan hakikinya: bukan untuk membinasakan pelaku,
tetapi untuk memanusiakannya kembali sebagai subjek yang bermartabat dan
berguna.
Baca Juga: Penegakan Hukum Maritim Amanna Gappa yang Berkeadilan di era VOC
Dengan mengakar pada nilai gotong royong
dan berorientasi pada keseimbangan monodualistik, pidana kerja sosial
membuktikan bahwa keadilan tidak harus berwujud jeruji besi yang dingin, tetapi
bisa berupa keringat pengabdian yang hangat bagi sesama.
Implementasi sanksi ini mulai tahun 2026
akan menjadi tonggak sejarah peradaban hukum Indonesia, sebuah langkah maju
dekolonisasi yang mentransformasi sistem peradilan dari alat penindasan menjadi
sarana pengayoman.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI