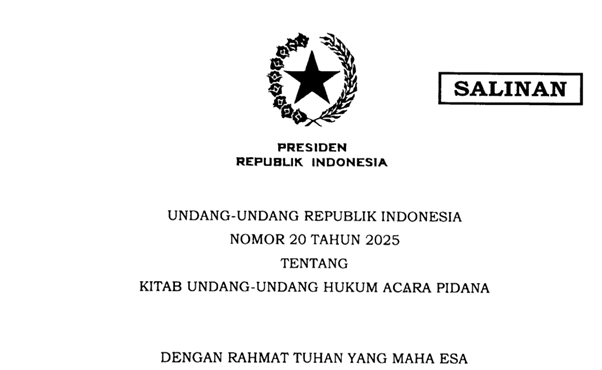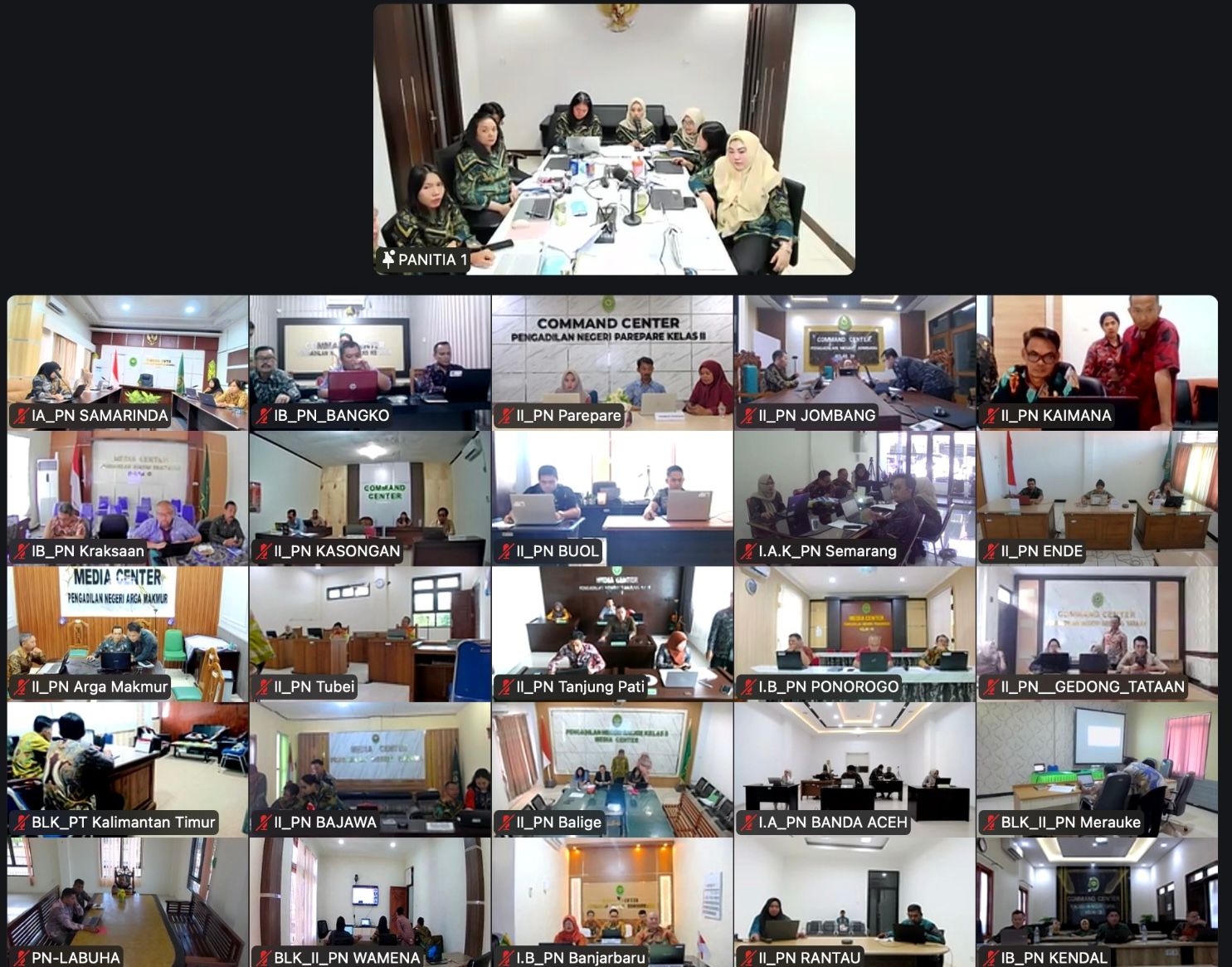Pendahuluan: Anatomi Sebuah Dilema
Dalam setiap ruang sidang, hampir selalu terdapat momen kritis ketika hakim menghadapi ketegangan fundamental antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Dilema ini bukan sekadar persoalan teknis yudisial, melainkan refleksi dari pertarungan filosofis yang sebenarnya telah berlangsung berabad-abad dalam tradisi pemikiran hukum. Di Indonesia, dengan warisan kolonial civil law yang dipadukan dengan nilai-nilai Pancasila, ketegangan ini memperoleh dimensi yang unik dan kompleks.
Baca Juga: Keadilan di Era Digital Nurani di Tengah Kemajuan Teknologi
Pertanyaan mendasar yang menghadang setiap hakim adalah: haruskah putusan hukum didasarkan pada kepatuhan rigid terhadap bunyi undang-undang (legal formalism), ataukah pada pencapaian keadilan substantif meski harus melampaui batas-batas tekstual peraturan? Dialektika ini mencerminkan konflik yang lebih dalam antara prinsip negara hukum yang menekankan kepastian hukum dengan aspirasi keadilan yang inheren dalam sistem hukum yang hidup.
Genealogi Formalisme vs Substansialisme
Tradisi formalisme hukum dalam konteks Indonesia tidak dapat dilepaskan dari warisan Eropa Kontinental yang mengutamakan kodifikasi dan hierarki norma. Formalisme, dalam esensinya, menawarkan prediktabilitas dan konsistensi—dua pilar yang menjadi prasyarat bagi stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.
Argumen pro-formalisme bermuara pada premis bahwa legitimasi yudisial terletak pada kapasitas hakim untuk menerapkan hukum yang telah ditetapkan oleh lembaga yang demokratis, bukan untuk menciptakan hukum baru (Ronald Dworkin, 1986). Dalam paradigma ini, hakim berfungsi sebagai "mulut undang-undang" (la bouche de la loi) yang tugasnya adalah menginterpretasi dan mengaplikasikan norma tanpa menambahkan preferensi subjektif.
Kekuatan formalisme terletak pada kemampuannya memberikan jawaban yang konsisten terhadap kasus-kasus serupa, menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "keadilan prosedural" (John Rawls,1971). Ketika hakim berpegang teguh pada bunyi undang-undang, maka tidak ada ruang untuk diskriminasi atau favoritisme, setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum yang sama.
Namun, kritik terhadap formalisme muncul dari kesadaran bahwa hukum positif tidak selalu mampu mengantisipasi kompleksitas realitas sosial (Roberto Mangabeira Unger, 1976). Substansialisme mengargumentasikan bahwa tujuan utama sistem hukum bukanlah kepatuhan buta terhadap aturan, melainkan pencapaian keadilan dalam arti yang substantif dan kontekstual.
Dalam tradisi pemikiran hukum Indonesia, substansialisme menemukan resonansinya dalam konsep "hukum yang hidup" dan prinsip-prinsip Pancasila yang menekankan keadilan sosial. Pendekatan ini mengakui bahwa undang-undang, sebagai produk manusia, memiliki keterbatasan inheren dan dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak adil jika diterapkan secara mekanis.
Hakim, dalam perspektif substansialis, tidak sekadar penerapan algoritma hukum, tetapi agen moral yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang dihasilkan mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dianut masyarakat. Ini mensyaratkan kemampuan untuk melakukan interpretasi kreatif, analogi hukum, dan bahkan judicial activism ketika diperlukan.
Sintesis dalam Konteks Indonesia: Menuju Pragmatisme Yudisial
Realitas sistem hukum Indonesia menunjukkan bahwa dikotomi rigid antara hakim formalisme dan substansialisme adalah oversimplifikasi yang sejujurnya kontraproduktif. Apa yang menurut penulis sebenarnya diperlukan adalah pendekatan yang lebih bernuansa—sebuah pragmatisme yudisial yang mengakui nilai dari kedua paradigma sambil menyadari konteks spesifik di mana keputusan hukum dibuat.
Dalam konteks ini, konsep "nurani hukum" tidak boleh dipahami sebagai lisensi subjektif untuk menciptakan keserampangan lembaga yudisial, melainkan sebagai kapasitas untuk melakukan penilaian moral yang terinformasi dalam kerangka sistem hukum yang ada (Benjamin Cardozo,1921). Hakim yang baik adalah hakim yang mampu mengidentifikasi kapan ketaatan pada bunyi undang-undang akan menghasilkan keadilan, dan kapan diperlukan interpretasi yang lebih fleksibel.
Kriteria untuk menentukan pendekatan yang tepat dapat dirumuskan dalam beberapa parameter: (1) kejelasan intensi pembuat undang-undang, (2) konsekuensi sosial dari penerapan secara literal, (3) konsistensi dengan prinsip-prinsip konstitusional, dan (4) preseden yudisial yang relevan (Frederick Schauer, 1991). Pendekatan ini mengakui bahwa kepastian hukum dan keadilan substantif bukanlah tujuan yang saling eksklusif, melainkan aspek komplementer dari sistem hukum yang sehat.
Sintesis ini mengimplikasikan redefinisi peran hakim dari eksekutor pasif undang-undang menjadi interpreter aktif yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Hal tersebut tentu mensyaratkan tidak hanya kompetensi teknis dalam interpretasi hukum, tetapi juga sensitivitas sosial dan kemampuan untuk memahami implikasi moral dari putusan yang diambil.
Dalam konteks praktis, hal ini berarti hakim harus mengembangkan metodologi yang memungkinkan mereka untuk melakukan interpretasi yang berprinsip dalam hal ini interpretasi yang sebagaimana disebutkan Aharon Barak, dapat dipertanggungjawabkan secara rasional dan konsisten dengan nilai-nilai fundamental sistem hukum (Aharon Barak, 2006). Transparansi dalam argumentasi hukum dalam setiap pertimbangan menjadi krusial untuk memastikan bahwa fleksibilitas interpretasi tidak berubah menjadi keserampangan.
Kesimpulan: Menuju Kearifan Lembaga Yudisial
Dilema antara formalitas dan substansi dalam praktik yudisial mencerminkan ketegangan yang lebih fundamental antara rule of law dan aspirasi keadilan. Dalam konteks Indonesia, resolusi terhadap ketegangan ini tidak dapat ditemukan melalui kecenderungan yang ekstrem pada salah satu paradigma, melainkan melalui pengembangan kearifan yudisial yang mampu mengintegrasikan kedua perspektif dalam kerangka yang koheren dan berprinsip.
Nurani hukum, dalam pengertian ini, bukanlah instrumen untuk mengesampingkan hukum positif, melainkan kapasitas untuk memahami dan mengaplikasikan hukum dalam cara yang mencerminkan tujuan tertinggi sistem hukum: penciptaan tatanan sosial yang adil, prediktabel, dan terlegitimasi. Hakim yang bijak adalah hakim yang mampu mengenali bahwa kekuatan sejati hukum terletak bukan pada rigiditas tekstualnya, melainkan pada kemampuannya untuk beradaptasi dengan tuntutan keadilan tanpa kehilangan integritas strukturalnya. (YPY/LDR)
Daftar Bacaan:
Ronald Dworkin, Law's Empire (Cambridge: Harvard University Press, 1986), hlm. 87-113.
John Rawls, A Theory of Justice (Cambridge: Harvard University Press, 1971), hlm. 85-90.
Roberto Mangabeira Unger, Law in Modern Society (New York: Free Press, 1976), hlm. 176-192.
Benjamin Cardozo, The Nature of the Judicial Process (New Haven: Yale University Press, 1921), hlm. 89-106.
Frederick Schauer, Playing by the Rules (Oxford: Oxford University Press, 1991), hlm. 149-166.
Baca Juga: Uji Substansi Panitera Muda: Badilum Dorong Budaya Kinerja Berbasis Merit
Aharon Barak, The Judge in a Democracy (Princeton: Princeton University Press, 2006), hlm. 116-135.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI