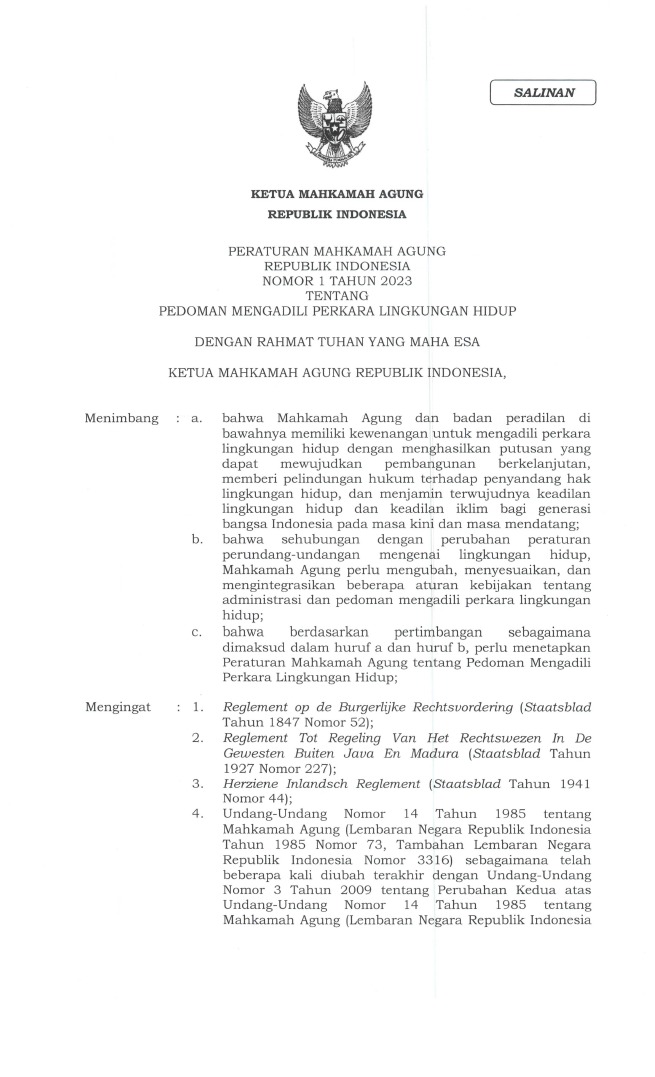Berlakunya KUHP Nasional merubah paradigma sistem pemidanaan dari retributif menuju sistem pemidanaan yang korektif dan restoratif. Pemidanaan tidak lagi berorientasi pada penderitaan pelaku semata, melainkan pada hasil yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.
Tujuan pemidanaan ini merupakan hal baru yang tidak
diatur dalam KUHP lama yang merupakan peninggalan kolonial, sehingga seorang
hakim harus merubah mindset nya
sebelum menjatuhkan pidana. Untuk mempermudah hakim dalam menjatuhkan pidana,
KUHP Nasional telah mengatur secara rinci pedoman pemidanaan, hal ini menjadikan
Hakim mempunyai peranan sebagai aktor sentral
dalam proses pemidanaan dan dalam menjatuhkan pidana. Pergeseran paradigma ini
bisa dipahami sebagai sarana pemulihan sosial bukan sekedar penderitaan yang di
jatuhkan Negara.
Keputusan
yang dibuat hakim adalah puncak dari integritas, keahlian, dan martabatnya
dimana penjatuhan pidana harus selalu berdasarkan pertimbangan yuridis (unsur-unsur tindak pidana, fakta
persidangan, bukti) dan non-yuridis (latar
belakang terdakwa, tujuan pemidanaan, keadilan bagi korban dan masyarakat), serta
tidak boleh subjektif atau semata-mata berdasarkan keinginan pribadi hakim yang
semuanya bertujuan mencapai keadilan. KUHP Nasional menyediakan pedoman
pemidanaan secara eksplisit yang diatur secara lengkap di Bab III.
Filosofi pemidanaan
oleh hakim merupakan manifestasi nilai keadilan subtantif yang tidak hanya
berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada perlindungan masyarakat,
perbaikan pelaku dan pemulihan keseimbangan sosial. Putusan hakim dapat
dianalogikan dengan pemberian resep oleh seorang dokter, karena keduanya
menuntut ketepatan diagnosis dan penentuan dosis yang proposional agar tujuan
pemidanaan dapat tercapai tanpa menimbulkan ketidak adilan baru. Analogi ini
memang tidak selalu dinyatakan secara harafiah, tetapi subtansinya diakui luas
dalam literatur hukum pidana dan filsafat hukum.
Keputusan hakim di buat oleh otoritas pofesional yang
berdasarkan konstitusi dan undang undang sebagaimana profesi seorang dokter
yang juga standar profesi dan ilmu kedokteran. Penanganan perkara juga case by case sesuai dengan pemeriksaan
individual di persidangan yang menghasilkan diagnosis individual bukan formula
seragam. Menilai tingkat kesalahan,
motif dan resiko residivisme untuk menentukan kadar pidana yang akan dijatuhkan
oleh hakim. Putusan hakim yang di jatuhkan kepada terdakwa bertujuan untuk memulihkan
keadaan yaitu pemulihan keadilan dan ketertiban hukum. Selain itu pemidanaan juga diarahkan pada
reintegrasi sosial yaitu menyembuhkan, memulihkan, dan
mencegah masalah mendasar.
Beberapa filsuf hukum seperti Marc Ancel menekankan bahwa pemidanaan harus bersifat individualized treatment (1) yang menentukan “perlakuan” yang tepat bagi pelaku, mirip dokter menentukan terapi bagi pasien. Filsuf hukum di Indonesia Sudarto menyampaikan bahwa pidana harus dijatuhkan secara proporsional dan manusiawi, serta disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. (2) Ini bermakna Konsep “menakar pidana” sejalan dengan menakar dosis obat dimana penakaran pidana (pidana tidak boleh terlalu berat atau terlalu ringan).
Putusan hakim yang berupa pidana penjara di
harapkan mampu untuk memperbaiki perilaku terdakwa, memulihkan hubungan social
serta mengembalikan keseimbangan yang terganggu. Diharapkan dapat memberikan
efek jera kepada pelaku serta mencegah orang lain melakukan perbuatan yang
sama.
Kesalahan dalam penjatuhan pidana dapat juga terjadi dalam hal hakim keliru dalam menilai tingkat kesalahan, mengabaikan peran pelaku yang minimal atau tidak mempertimbangkan kondisi social dan psikologis terdakwa. Kekeliruan ini merupakan bentuk kegagalan diagnosis dan terapi pidana yang berpotensi putusan menjadi tidak tepat sasaran karena terlalu berat (over punishment) atau terlalu ringan (under punishment) dan meniadakan tujuan rehabilitative dan restorative sebagaimana system pemidanaan modern dalam KUHP Nasional.
Dalam
masa transisi dari KUHP lama dengan KUHP Nasional saat ini, potensi kekeliruan
dapat terjadi karena mindset yang
mungkin belum berubah yaitu menggunakan pendekatan legalistik-formalistik,
tidak menggunakan pedoman pemidanaan dalam KUHP Nasional, orientasi retributif
yang masih dominan atau bahkan tekanan sosial atau opini publik.
Keputusan hakim mengandung perintah hukum sehingga harus dilaksanakan agar tidak menimbulkan akibat. Sebagaimana disebut dalam KUHAP, pelaksana keputusan hakim dalam perkara pidana adalah Jaksa Penuntut umum dan berdasarkan Undang Undang no 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan terpidana diserahkan ke Lapas/rutan sebagai tempat pembinaan narapidana selama menjalankan masa pidananya.
Bila hal ini dianalogikan dengan dunia medis maka lapas/rutan dapat di sebut sebagai apotekernya, sehingga jika apoteker yang dalam hal ini Lembaga pemasyarakatan tidak menjalankan pidana kepada terdakwa sesuai dengan amar putusan hakim maka pemberian treatment menjadi tidak optimal. Hal ini dapat terjadi ketika lembaga pemasyarakatan dalam memberikan remisi kepada narapidana tidak ada standar yang jelas dan tranparan serta tidak adanya kewajiban untuk meminta pertimbangan dari hakim.
Kritik pedas sering dilontarkan oleh masyarakat kepada
lembaga peradilan karena menjatuhkan pidana yang tidak memberikan efek jera
kepada terdakwa sehingga tidak memberi rasa keadilan terhadap korban maupun
masyarakat dan Negara. Hal ini tentunya tidak sepenuhnya benar karena Hakim
tentu telah berupaya semaksimal mungkin dalam memeriksa perkara serta telah
menjatuhkan pidana sebagai terapi bagi terdakwa. Sebagaimana yang dilakukan
oleh seorang dokter yang mendiagnosa pasien dan kemudian memberikan obat
sebagai terapi.
Dalam sistem hukum Indonesia, remisi merupakan hak administratif narapidana yang berada dalam ranah eksekutif bukan yudikatif, dengan demikian hakim tidak terlibat lagi setelah putusan pidana berkekuatan hukum tetap. Sebagai Negara hukum (rechtstaat) yang menganut asas trias politika, eksekutif tidak memiliki kewenangan korektif terhadap putusan hakim sebagai lembaga yudikatif. Oleh karena itu pemberian remisi merupakan tindakan yang kurang tepat karena putusan lembaga yudikatif di rubah/ dikorektif tanpa meminta pertimbangan lembaga yudikatif.
Bukan
hal yang asing bagi seorang hakim ketika memutus seorang terdakwa selama tujuh
tahun, akan tetapi dalam jangka waktu tiga tahun terdakwa sudah merada di luar
penjara. Sungguh sangat ironis pidana yang sudah dibuat oleh hakim dalam amar putusan
tidak dilaksanakan dengan semestinya.
Melalui analisis kritis terhadap praktik
diatas, diharapkan bisa memperkaya diskursus akademik dengan menawarkan
perspektif baru, kerangka analisis yang lebih komprehensif, serta pemetaan
masalah yang selama ini belum di bahas secara mendalam. Pada tataran nasional,
tulisan ini bermanfaat sebagai refleksi dan evaluasi praktik pemidanaan di
Indonesia. Perlu adanya pengaturan atau standar yang jelas dalam pemberian
remisi karena Ketidakpatuhan
terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap akan merusak wibawa
peradilan serta melanggar asas res
judicata pro veritate habetur atau bahkan masuk dalam katagori contempt of court. (zm/ldr)
Daftar Referensi
1.
Marc Ancel, Social Defence: A Modern Approach
to Criminal Problems (London: Routledge, 1965).
2.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung:
Alumni, 1986).
Baca Juga: Lagi! PN Belopa Sukses Menyelesaikan Perkara Anak Melalui Diversi
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI