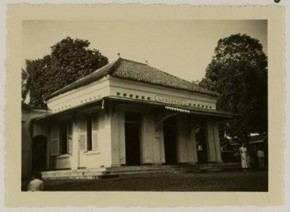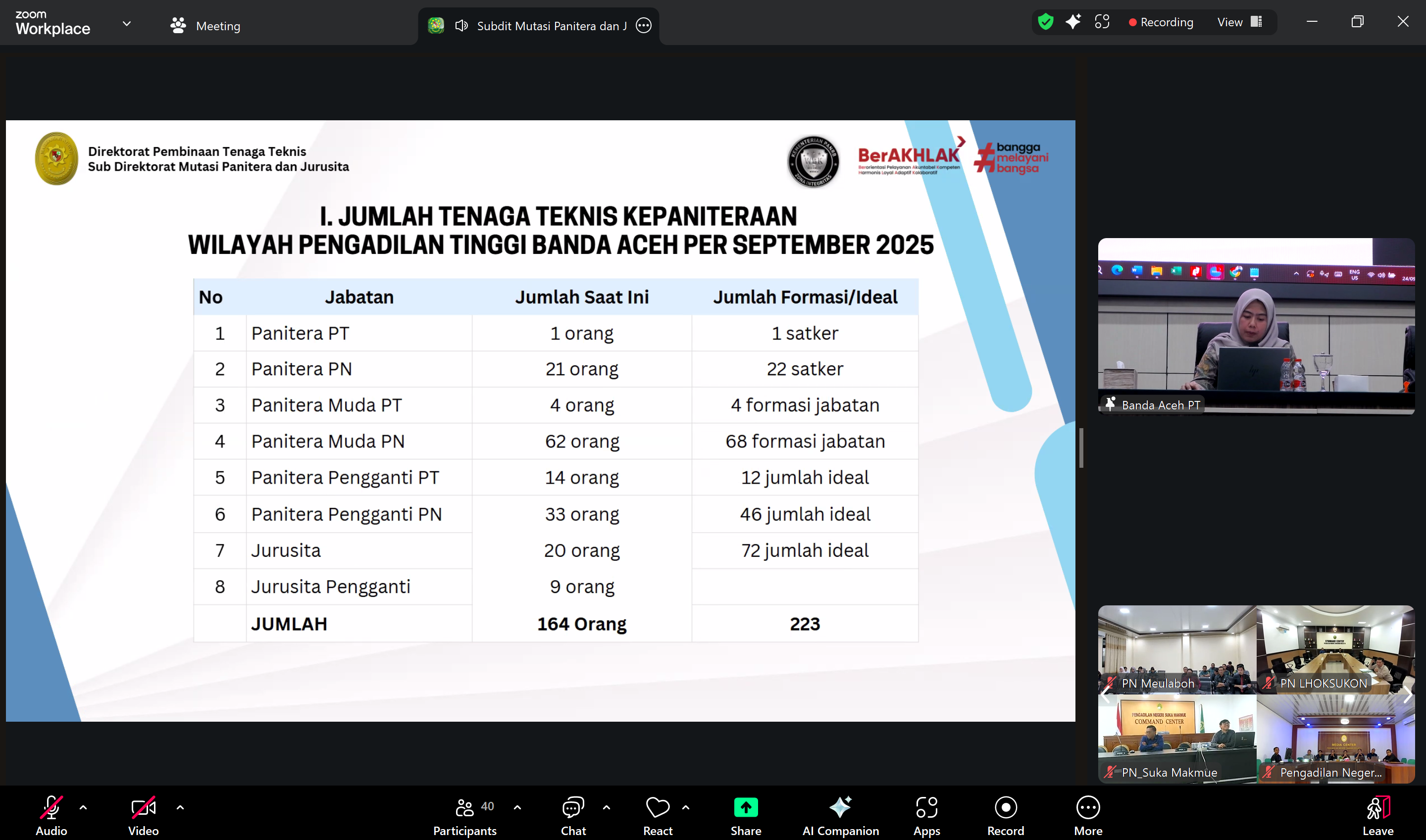Perkara pertanahan yang beririsan dengan penertiban tanah
telantar sering membawa dua cerita yang berlawanan. Di satu sisi ada penimbunan
tanah untuk spekulasi yang menutup akses publik dan menghambat tata ruang. Di
sisi lain ada warga yang membeli tanah dengan tabungan bertahap dan baru mampu
membangun sedikit demi sedikit. PP Nomor 48 Tahun 2025 hadir untuk menertibkan
tanah telantar, namun penerapannya menuntut kepekaan agar penertiban tetap
tepat sasaran tanpa mengubah keterbatasan ekonomi menjadi kesalahan hukum.
Analisis penulis menawarkan cara baca yang memudahkan hakim membedakan kedua
cerita itu.
Premis awal yang perlu dipegang ialah bahwa ketidakadaan
aktivitas fisik yang besar tidak identik dengan keterlantaran. Di dalam PP,
penertiban mengandaikan adanya kewajiban mengusahakan, mempergunakan,
memanfaatkan, atau memelihara tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak.
Rumusan itu mengarahkan penilaian pada relasi aktif pemegang hak dengan
tanahnya, bukan sekadar pada penampakan tanah pada satu waktu. Hakim sebaiknya
menolak penalaran instan yang hanya bertumpu pada kesan visual, dan lebih
menimbang apakah masih ada pemeliharaan, pengamanan, serta langkah yang masuk
akal menuju pemanfaatan.
Masalah paling tajam muncul ketika pembatasan perbuatan
hukum menutup jalan pembiayaan. PP mengatur bahwa sejak tanah diusulkan untuk
ditetapkan sebagai tanah telantar, perbuatan hukum atas bidang tersebut tidak
dapat dilakukan sampai terbit keputusan penetapan. Penguncian ini penting untuk
mencegah pengalihan yang menghindari penertiban, tetapi pada warga berdaya beli
terbatas ia dapat menutup akses terhadap agunan atau skema pembiayaan. Jika
akses modal tertutup, pemanfaatan menjadi makin tidak mungkin. Jika pemanfaatan
makin tidak mungkin, status telantar menjadi makin mudah dilekatkan. Hakim
perlu peka terhadap lingkaran ini karena berpotensi menciptakan kemustahilan
yang dibentuk oleh mekanisme administratif.
Baca Juga: Pembekuan Sejak Usulan Tanah Telantar: Uji Proses dan Proporsionalitas
Dengan background tersebut, hakim memerlukan pedoman
untuk menilai unsur kesengajaan secara adil. Penjelasan Pasal 6 ayat 2 PP
menempatkan kesengajaan sebagai tindakan sadar untuk tidak mengusahakan, tidak
mempergunakan, tidak memanfaatkan, atau tidak memelihara tanah sesuai sifat dan
tujuan pemberian hak. Penjelasan yang sama juga menyebut keadaan yang tidak
termasuk kesengajaan, antara lain ketika tanah menjadi objek perkara di
pengadilan, ketika pemanfaatan terhalang perubahan tata ruang, ketika tanah
diperuntukkan konservasi, serta ketika terjadi keadaan memaksa yang dinyatakan
instansi berwenang. Rujukan ini memberi kerangka pembuktian yang menuntut
rangkaian fakta yang stabil, bukan kesimpulan dari satu potret waktu.
Langkah pertama yang bersifat operasional adalah uji
kelayakan nyata. Hakim menanyakan apakah pada horizon waktu yang wajar,
pemegang hak memiliki akses pembiayaan yang lazim bagi kondisi sosial
ekonominya untuk memulai pemanfaatan. Uji ini tidak menuntut standar
kemakmuran, melainkan standar kewajaran. Dalam perkara, kelayakan nyata dapat
diuji melalui bukti sumber penghasilan, riwayat tabungan, upaya mengakses
kredit, serta skala rencana pemanfaatan. Uji kelayakan nyata membantu hakim
menilai apakah ketidakpemanfaatan adalah pilihan sadar atau fase yang wajar
pada pembangunan bertahap.
Langkah kedua adalah uji kesungguhan bertahap. Hakim menilai
apakah pemegang hak melakukan tindakan persiapan yang konsisten, meski kecil.
Tindakan itu dapat berupa pembersihan berkala, penataan batas, pemasangan tanda
kepemilikan, penjagaan akses, atau pengurusan dokumen yang relevan. Intinya
bukan besar kecilnya biaya, melainkan keberlanjutan relasi. Uji ini sekaligus
menutup ruang bagi spekulasi yang benar benar pasif, karena spekulasi lazimnya
tidak meninggalkan jejak relasi aktif selain tujuan menahan aset.
Langkah ketiga adalah uji hambatan objektif. Hakim menilai
apakah ada kondisi yang secara faktual menghalangi pemanfaatan, seperti konflik
penguasaan, sengketa batas, akses jalan yang tidak tersedia, atau perubahan
kebijakan ruang yang membatasi opsi. Pada tahap ini, rujukan Penjelasan Pasal 6
ayat 2 mengenai perubahan tata ruang dan keadaan memaksa membantu hakim menjaga
kausalitas. Hakim perlu memastikan hambatan tersebut relevan dengan bidang yang
sama dan berhubungan langsung dengan ketidakmungkinan memulai pemanfaatan. Jika
hambatan hanya menjadi alasan abstrak, hal itu tidak cukup. Jika hambatan
nyata, hal itu meniadakan asumsi kesengajaan.
Langkah keempat adalah uji kontribusi kebijakan. Hakim
menilai apakah tindakan administratif, termasuk pembatasan perbuatan hukum
sejak tahap usulan, ikut memperburuk ketidakmungkinan pemanfaatan. Di sini
hakim dapat menguji apakah pemberitahuan telah dilakukan secara patut, apakah
dasar data penertiban dapat diuji, dan apakah pemegang hak memiliki kesempatan
yang bermakna untuk menjelaskan rencana bertahapnya. Uji ini penting karena PP
memberikan konsekuensi serius sejak tahap awal. Ketika prosedur lemah atau data
tidak kokoh, pembatasan yang berdampak berat patut dipandang tidak sejalan
dengan asas kepatutan dan perlindungan yang wajar.
Langkah kelima adalah pengujian proporsionalitas terhadap
konsekuensi. Pengujian ini menilai kecocokan antara tujuan penertiban dan
instrumen yang digunakan, menilai ada tidaknya alternatif yang lebih ringan,
serta menilai keseimbangan dampak pada hak perorangan. PP memuat konsekuensi
lanjutan setelah penetapan, termasuk kewajiban pengosongan dalam tenggang waktu
tertentu dan konsekuensi terhadap benda di atas tanah jika tidak dikosongkan.
Karena dampaknya dapat menyerupai pemutusan relasi faktual atas tanah, hakim
perlu menakar apakah langkah tersebut benar benar diperlukan terhadap pemegang
hak yang menunjukkan relasi aktif dan rencana bertahap.
Langkah keenam menyangkut perlindungan pihak ketiga
beritikad baik. Dalam banyak perkara, tanah terkait dengan kreditor, pembeli,
penyewa, atau anggota keluarga. Pembatasan perbuatan hukum dapat memindahkan
risiko kepada pihak ketiga yang tidak berkontribusi pada dugaan keterlantaran.
Hakim perlu menilai hubungan hukum pihak ketiga dan memastikan bahwa putusan
tidak menciptakan beban yang tidak proporsional bagi mereka. Perspektif ini
menjaga agar penertiban tidak menimbulkan gelombang sengketa turunan yang
justru merusak kepastian hukum.
Langkah ketujuh adalah membangun struktur pembuktian yang
seimbang. Pemerintah tetap perlu menunjukkan dasar data yang dapat diuji
mengenai keadaan tanah dan kewajiban yang tidak dipenuhi, sedangkan pemegang
hak diberi ruang membuktikan relasi aktif, rencana, dan hambatan. Hakim dapat
menilai bukti sederhana sebagai bukti yang relevan, seperti foto berkala, kuitansi
perawatan, korespondensi perizinan, atau catatan upaya pembiayaan. Struktur ini
membuat pembuktian kesengajaan sesuai Penjelasan Pasal 6 ayat 2 tidak berubah
menjadi beban yang mustahil bagi warga yang bergerak bertahap.
Langkah kedelapan, Hakim dapat merumuskan ratio decidendi
dengan urutan yang jernih. Pertama uraikan tujuan penertiban dan risiko
spekulasi dalam kerangka PP. Kedua uraikan fakta relasi aktif atau pasif.
Ketiga uraikan kelayakan nyata dan kesungguhan bertahap. Keempat uraikan
hambatan objektif dan kontribusi kebijakan sejak tahap usulan pembatasan.
Kelima simpulkan proporsionalitas tindakan dan konsekuensi. Urutan ini membuat
putusan tajam namun tetap mudah diikuti, sekaligus memberi sinyal kepada
aparatur tentang batas penertiban yang adil.
Penertiban tanah telantar akan memperoleh legitimasi
ketika melindungi kepentingan umum tanpa menutup ruang bagi warga yang
membangun hidup secara bertahap. Hakim berada pada posisi kunci untuk
memastikan pembedaan yang disiplin antara spekulasi dan penundaan wajar. Dengan
memedomani Penjelasan Pasal 6 ayat 2 tentang kesengajaan dan pengecualian,
serta dengan memahami dampak pembatasan perbuatan hukum sejak tahap usulan,
hakim dapat memastikan bahwa keterbatasan modal tidak disulap menjadi kesalahan.
Putusan yang demikian tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga
mengarahkan praktik administrasi agar lebih manusiawi dan lebih taat asas.
Kerangka ini memberi hakim alat yang konkret karena setiap uji berangkat dari fakta yang dapat diverifikasi dan setiap kesimpulan ditarik melalui penalaran yang tertib.. (ldr)
Baca Juga: Eksistensi Alat Bukti Bekas Hak Milik Adat Dalam Sengketa Hak Atas Tanah
Tulisan merupakan pendapat pribadi dan tidak mewakili lembaga/institusi.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI