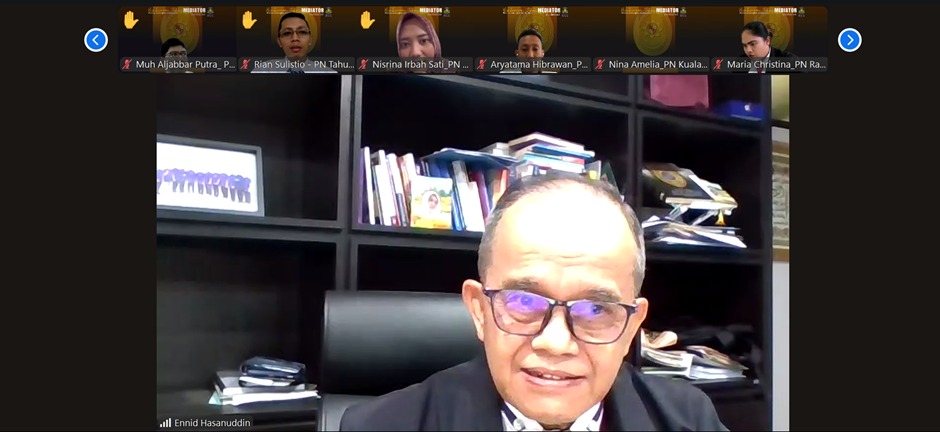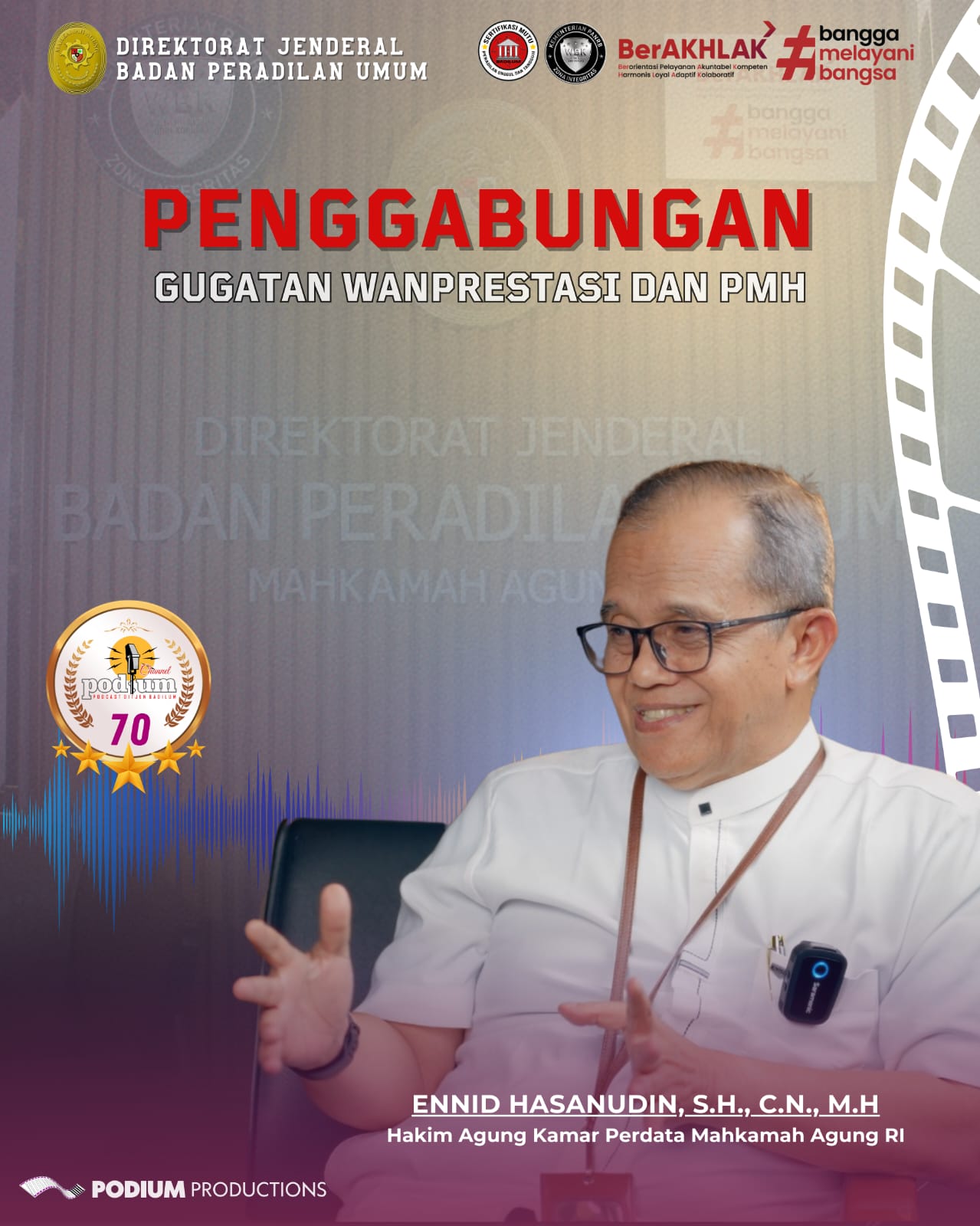Jakarta- Mediasi di pengadilan kembali menjadi bahan renungan serius di Mahkamah Agung. Sebab, keberhasilan mediasi baru 4 persen di Peradilan Umum.
Dalam dialog yang hangat dan sarat makna di kanal Podium (Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum), Mahkamah Agung, Hakim Agung Kamar Perdata, Ennid Hasanuddin, mengurai panjang-lebar ihwal perjalanan, tantangan, dan arah pembaruan sistem mediasi di lingkungan peradilan Indonesia, dari masa sebelum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 hingga ke rencana pembentukan mekanisme mediasi pra-litigasi yang lebih lentur dan manusiawi.
Sejak diatur secara formal dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi di pengadilan sejatinya dirancang sebagai upaya penyelesaian sengketa yang lebih cepat, sederhana, dan murah. Namun, sebagaimana disampaikan Ennid, realitasnya belum seindah harapan.
Baca Juga: Ennid Hasanuddin Usul Mediasi Jadi Prasyarat Pengajuan Gugatan Ke Pengadilan
“Tingkat keberhasilan mediasi di peradilan umum baru sekitar empat persen, sedangkan di peradilan agama bisa mencapai empat puluh persen,” ujarnya.
Menurut Ennid, salah satu faktor penyebab rendahnya efektivitas mediasi adalah ketidakseimbangan posisi para pihak. Di ruang mediasi, sering kali tergugat hadir dengan kuasa hukum, sementara penggugat datang sendiri tanpa pendamping. Di sinilah mediator harus hadir bukan sekadar sebagai penengah, tetapi sebagai penjaga keseimbangan.
“Mediator itu menyeimbangkan ruang pertemuan. Ketika satu pihak terlalu dominan, mediator harus bisa mengatur dinamika agar keadilan tetap hidup di meja mediasi,” jelasnya.
Ia juga menyinggung perlunya surat kuasa khusus bagi kuasa hukum dalam proses mediasi, agar benar-benar berwenang mengambil keputusan atas tawaran perdamaian,bukan sekadar hadir secara administratif.
Transformasi menuju mediasi elektronik, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022, diakui membuka peluang besar untuk mengatasi kendala kehadiran fisik para pihak. Namun, menurutnya, tantangan baru pun muncul yaitu kesenjangan teknologi.
“Tidak semua pihak technology friendly. Ada yang tidak punya perangkat, sinyal tidak stabil, atau bahkan hanya mengandalkan ponsel anaknya. Karena itu, mediasi elektronik harus diterapkan bertahap, mulai dari wilayah kota besar lebih dulu,” katanya.
Selain aspek teknis, Ennid menyoroti belum adanya petunjuk teknis khusus tentang kerahasiaan data dalam mediasi elektronik. Ia mengingatkan agar pengaturan tidak terlalu kaku sehingga pelaksanaannya tidak membuat masyarakat enggan berpartisipasi.
Salah satu gagasan besar yang muncul dari perbincangan ini adalah rencana mengeluarkan mediasi dari proses litigasi (court-annexed mediation). Dengan begitu, mediasi akan menjadi prasyarat sebelum gugatan diajukan ke pengadilan, sebagaimana praktik di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).
“Kalau di PHI, gugatan tidak bisa diterima tanpa melampirkan risalah mediasi. Kita bisa meniru pola itu, agar waktu mediasi tidak diburu-buru oleh jadwal persidangan,” ujarnya.
Dalam skema ini, bila mediasi berhasil, perjanjian damai dapat didaftarkan ke pengadilan agar memiliki kekuatan eksekutorial, setara dengan akta perdamaian. Jika gagal, berita acara mediator dapat menjadi lampiran gugatan sebagai bukti bahwa upaya damai telah dilakukan.
Menariknya, Ennid juga menegaskan pentingnya memperluas cakupan siapa yang dapat menjadi mediator. Ia mengusulkan agar mediator non-hakim, panitera, jurusita, hingga ketua adat dapat dilibatkan, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 2.161 komunitas adat yang eksis dan memiliki struktur hukum sendiri.
“Kita punya lebih dari enam belas undang-undang yang mengatur hukum adat, dan lebih dari dua puluh undang-undang yang memuat kewajiban mediasi. Jiwa musyawarah itu sebenarnya sudah hidup di masyarakat adat kita,” katanya.
Konsep ini sejalan dengan semangat KUHP Nasional yang baru, yang juga menghidupkan kembali nilai-nilai penyelesaian secara adat dan kekeluargaan.
Di penghujung diskusi, Ennid menyampaikan pesan menyentuh bagi para hakim mediator:
“Untuk menjadi hakim atau mediator, kuncinya tiga: bekerja dengan hati, bekerja sepenuh hati, dan bekerja dengan hati-hati.”
Baginya, keberhasilan mediasi bukan hanya soal prosedur, tapi soal jiwa, menghadirkan ruang dialog yang hangat, cair, dan jauh dari suasana formal persidangan.
Baca Juga: Hakim Agung Ennid: Penggabungan Gugatan PMH dengan Wanprestasi Tak Lagi Jadi Polemik
“Mediasi harus terasa kekeluargaan, bukan keterpaksaan. Kalau orang sudah nyaman, damai itu akan tumbuh sendiri,” tutupnya.
Dengan semangat itu, Mahkamah Agung terus berupaya menghidupkan kembali esensi mediasi sebagai jalan tengah hukum dan kemanusiaan, tempat di mana para pihak tak lagi bertanding, tetapi berdamai.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI