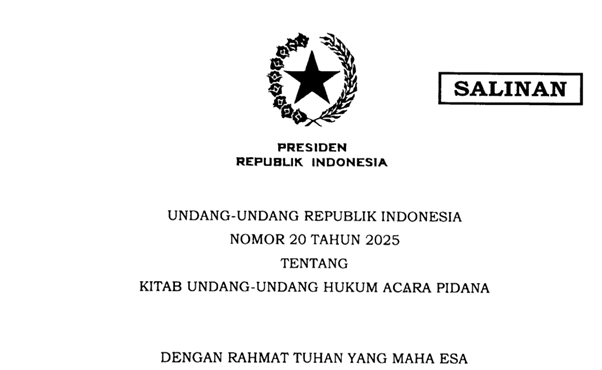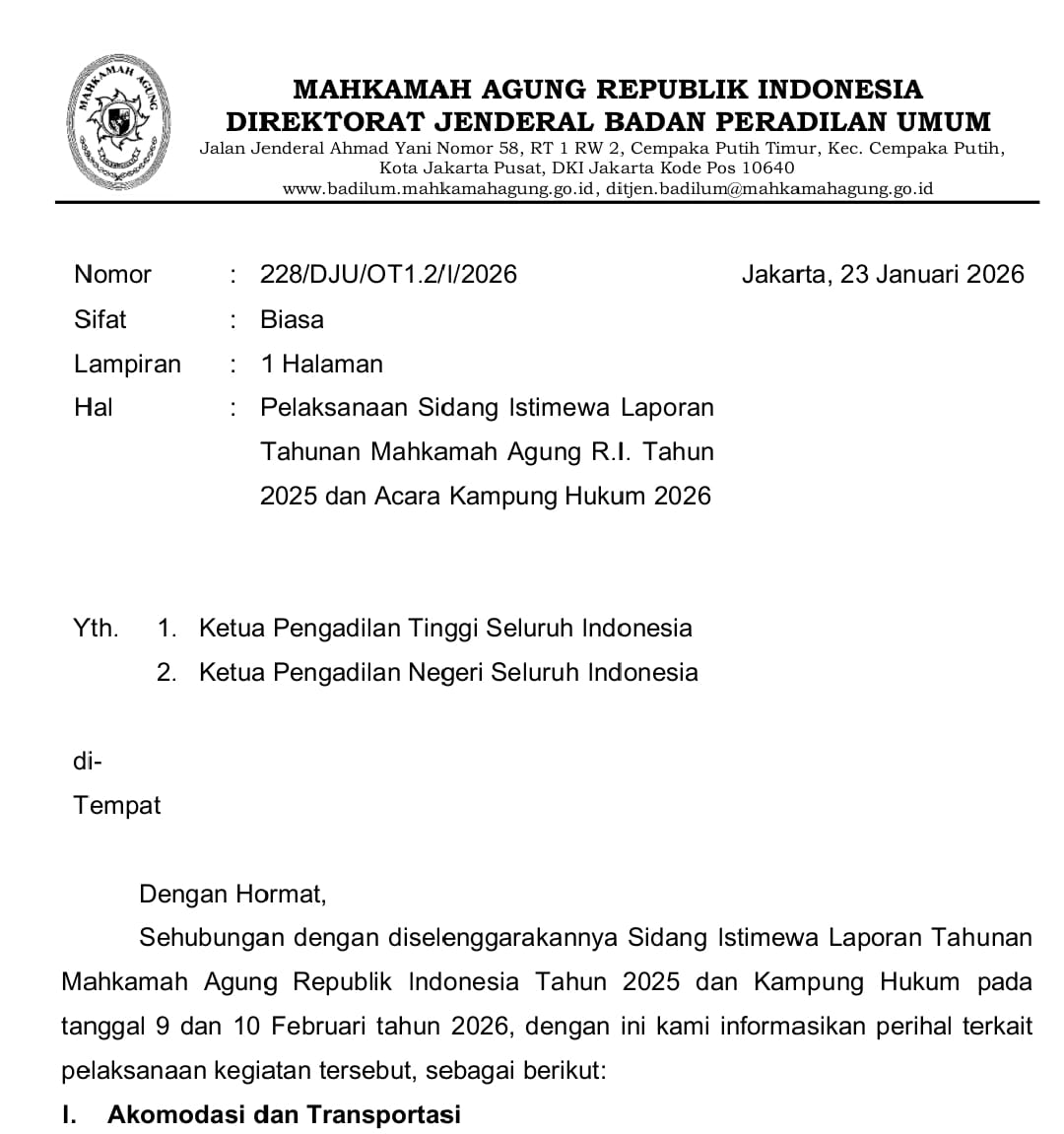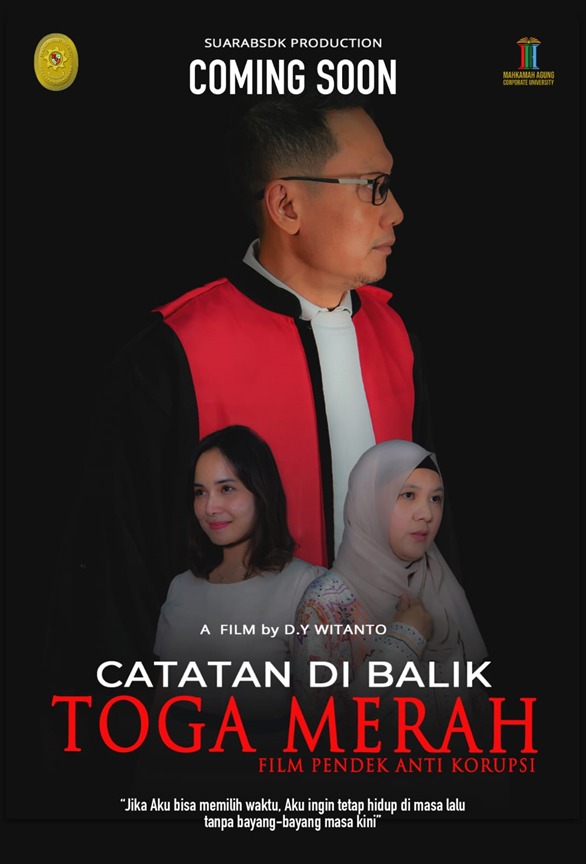Kata “toga” berasal dari bahasa Latin tego, yang berarti menutupi (to cover). Awalnya, pemakaian toga berasal dari kebiasaan bangsa Romawi untuk mencerminkan status sosialnya di masyarakat. Toga juga digunakan secara luas di berbagai seremoni seperti festival perayaan kedewasaan (toga virilis), pencalonan kandidat politik (toga candida), atau suasana berkabung (toga pulla) (ROM).
Sebagai agama resmi Kekaisaran Romawi, rohaniwan Kristen mengenakan jubah vestimentum untuk keperluan ibadah dan upacara keagamaan. Setelah Kekaisaran runtuh di awal abad pertengahan, gereja tetap melanjutkan tradisi pemakaian toga. Pada tahun 1215, Konsili Lateran Keempat memerintahkan agar para rohaniwan mengenakan jubah khusus.
Baca Juga: Begini Penampakan Toga Hakim di Era Penjajahan Belanda di Indonesia
Umumnya, rohaniwan Kristen mengenakan toga berwarna hitam. Terdapat dua alasan mengapa warna ini dipilih. Pertama, gereja melarang pendeta untuk mengejar kehidupan duniawi yang mencolok. Maka dari itu, mereka sengaja menghindari warna-warna populer, serta lebih memilih warna hitam yang tampak lebih sederhana dan khidmat.
Kedua, terdapat kisah dalam Keluaran 20:21, yakni “Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada.” Di samping itu, Mazmur 18:11 menyatakan: “Ia membuat kegelapan di sekeliling-Nya menjadi persembunyian-Nya, ya, menjadi pondok-Nya: air hujan yang gelap, awan yang tebal.” Karena “kegelapan” adalah tempat kediaman Allah, tak heran warna hitam dipilih untuk memberitakan Injil (Story Studio).
Di era abad pertengahan, sebagian besar hakim adalah pendeta, sehingga mereka kerap melaksanakan sidang dengan mengenakan jubah hitam (Sohu). Dari yang awalnya merupakan tradisi keagamaan, kebiasaan memakai toga berkembang menjadi atribut wajib dalam praktik persidangan modern.
Toga di Prancis dan Belanda
Menurut sejarawan Robert Sanders, pemerintah revolusioner Prancis mengakhiri profesi hukum dengan menghapuskan gelar profesional sekaligus hak untuk mengenakan toga pada tahun 1790. Gagasan awalnya adalah setiap warga negara harus mampu membela diri sendiri atau sesama warga negara di pengadilan. Dengan pemikiran semacam ini, fakultas hukum di universitas juga ditutup dan profesi hakim diberhentikan (Mvz).
Kekacauan hebat yang terjadi di ruang sidang membuat Napoleon tak punya pilihan selain membatalkan perubahan revolusioner tersebut. Undang-Undang Pendidikan tahun 1804 tidak hanya membuka kembali fakultas hukum, tetapi juga menandai kembalinya profesi pengacara dan toga.
Namun, Napoleon sebenarnya tidak menyukai independensi advokat. Ia menandatangani dekret 1810 “dengan berat hati” dan bahkan menyebut advokat sebagai “factieux, artisans de crimes et de trahisons (penghasut, pelaku kejahatan dan pengkhianatan).” Dalam dokumen Cambacérès, Napoleon bahkan menulis ingin “memotong lidah advokat yang menggunakannya melawan Pemerintah” (Lexbase).
Di Belanda, regulasi pemakaian toga diatur rinci dalam Dekrit Pakaian Resmi dan Tituler Badan Peradilan tanggal 22 Desember 1997: “Toga adalah mantel panjang dan lebar dengan kerah tegak setinggi kurang lebih 4 sentimeter. Toga seluruhnya terbuat dari kain hitam, menjuntai hingga kira-kira 10 sentimeter di atas tanah.” “Bef terdiri dari dua potongan kain baptis putih berlipat yang disatukan di bagian atas, memiliki panjang 30 sentimeter dan pada bagian bawah tidak boleh lebih lebar dari 15 sentimeter.”
Sejak era modern, warna hitam toga dianggap simbol untuk menghindarkan diri dari kesombongan, sedangkan kerah putih melambangkan netralitas (Mr.).
Pengaturan Toga di Indonesia
Baca Juga: Coming Soon! Laporan Tahunan MA dan Kampung Hukum 2026
Di zaman kolonial Hindia Belanda, hakim dan advokat sudah lazim mengenakan toga hitam dalam persidangan, berdasarkan Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren der Advokaten, Procureurs en Deuwaarders (Stb. 1848 Nr 8). Pasca kemerdekaan, regulasi ini tetap dipertahankan oleh Pasal 1 PP Nomor 2 Tahun 1945—menegaskan segala badan negara dan peraturan sebelum 17 Agustus 1945 tetap berlaku, selama belum diganti dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1966, Mahkamah Agung juga mewajibkan pemakaian toga bagi hakim, demi menciptakan suasana khidmat di persidangan.
Pemakaian toga baru diatur dalam hukum nasional melalui Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.07-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pakaian dan Atribut Pejabat Peradilan dan Penasehat Hukum. Regulasi ini menyatakan hakim, penuntut umum, dan advokat bersidang dengan toga hitam berlengan lebar, simare dan bef, dengan atau tanpa mengenakan peci.
Selain toga, hakim dan penuntut umum seharusnya juga mengenakan lencana di dada sebelah kiri. Namun pada praktiknya, penggunaan atribut lencana kini sangat jarang dikenakan, bahkan cenderung terabaikan.
Atribut toga di Indonesia sarat dengan makna filosofis yang mendalam. Sesuai ketentuan, kancing toga harus persis berjumlah 17 dan memiliki 8 lipatan pada pangkal lengan toga. Angka ini merujuk pada tanggal 17 dan bulan 8 (Agustus), sebagai hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Simbol ini menjadi pengingat agar hakim selalu teguh menegakkan keadilan, sejalan dengan cita-cita luhur Proklamasi 17 Agustus 1945. Sementara itu, warna hitam pada toga melambangkan kesederhanaan dan kerendahan hati, sedangkan bef putih melambangkan netralitas serta sikap imparsial dalam menjalankan tugas peradilan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI