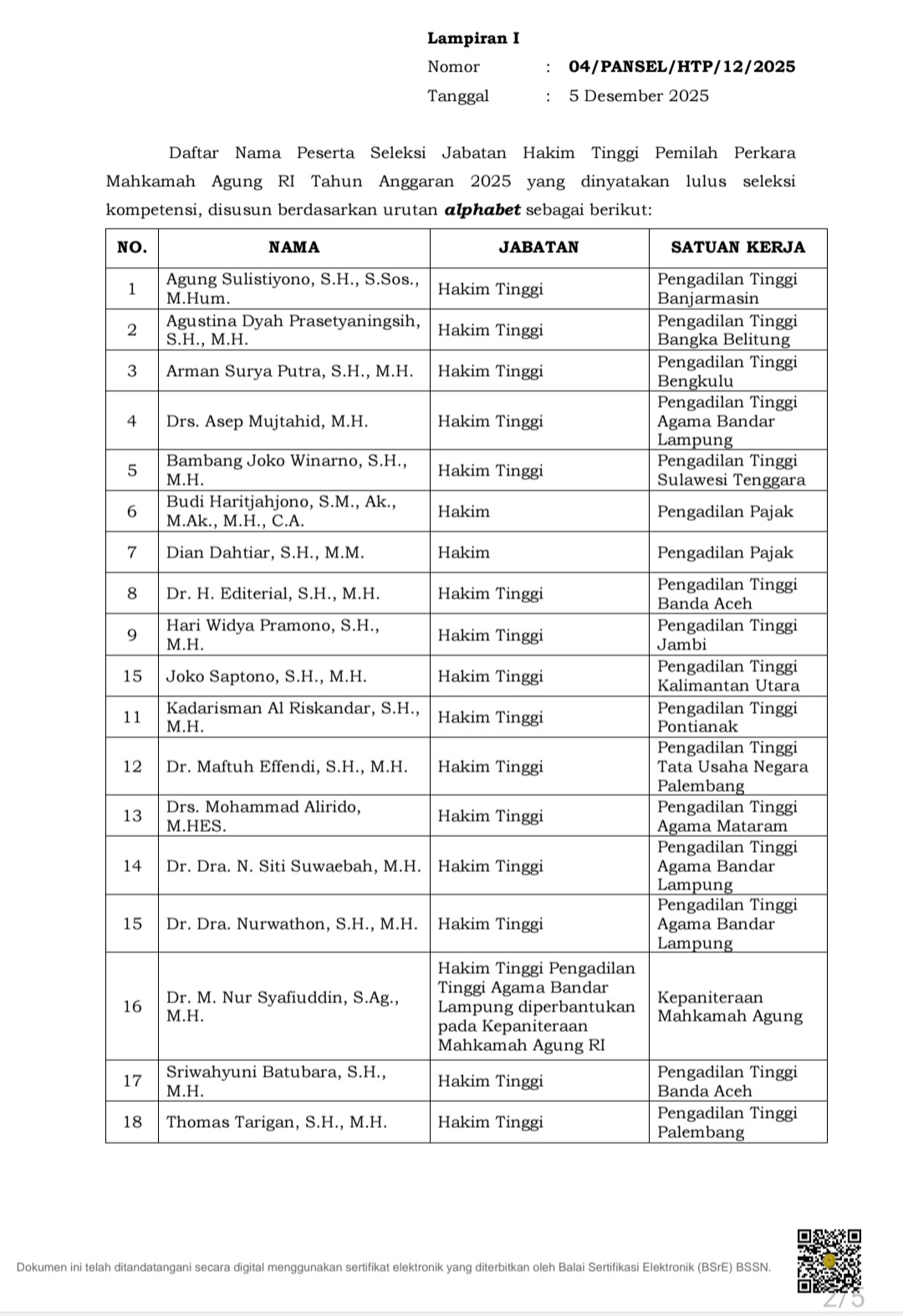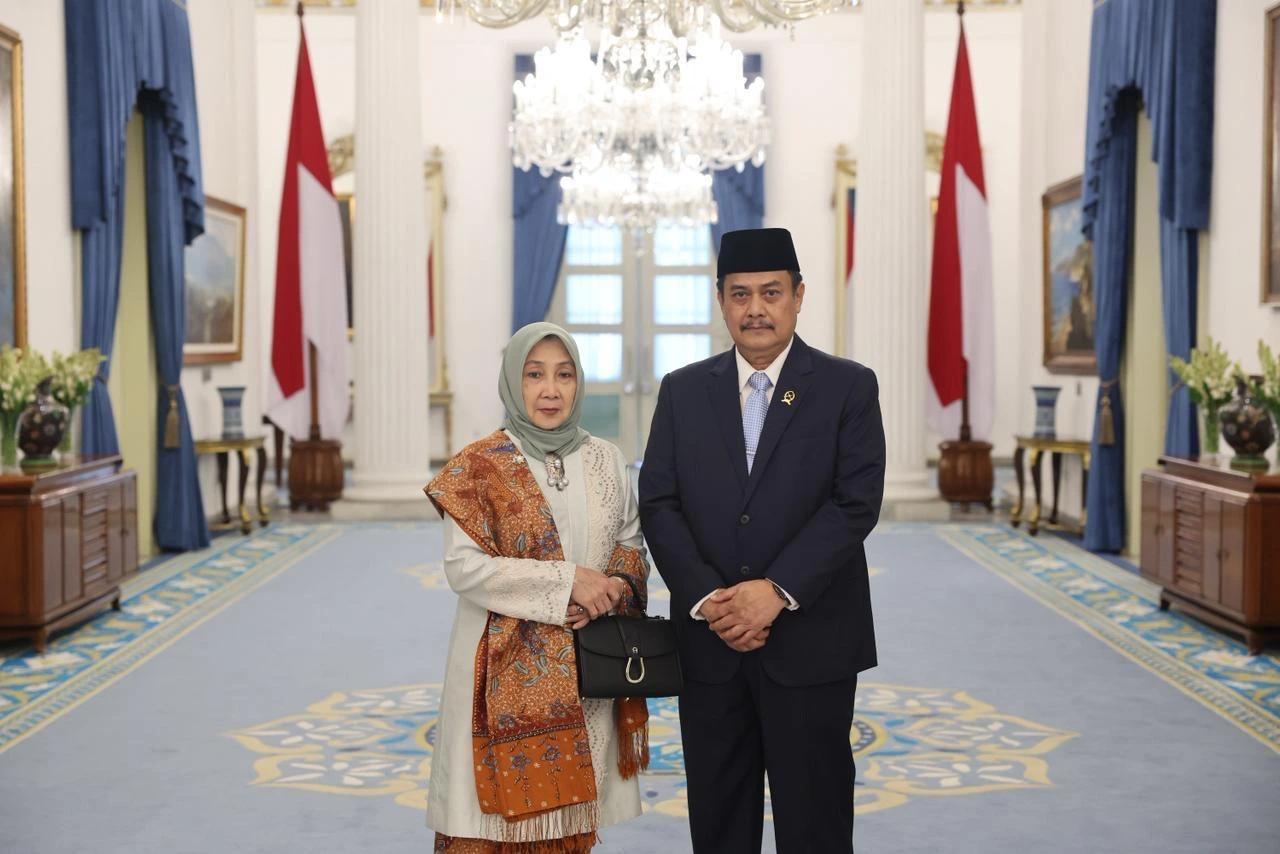Pada saat kita mendengar mengenai hukuman dalam konteks pemidanaan, yang
pertama kali terlintas dipikiran kita adalah rasa takut karena hukuman identik
dengan penderitaan yang harus dijalani seseorang sebagai konsekuensi dari
perbuatannya.
Hukuman pada hakikatnya dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan
efek jera dan memberikan keadilan, baik bagi korban, masyarakat, maupun pelaku,
sehingga kehadirannya selalu menyisakan ambivalensi dimana disatu sisi
menakutkan, namun di sisi lain dianggap perlu demi menjaga ketertiban dan
keseimbangan dalam kehidupan bersama.
Roscoe Pound dalam bukunya yang berjudul “An Introduction to the Philosophy of Law” pernah menyatakan bahwa
hukum adalah sarana untuk merekayasa masyarakat/sosial, dimana dalam konteks
penghukuman/pemidanaan yang menjadi tujuan utama dari “rekayasa” tersebut
adalah untuk menimbulkan ketertiban melalui pencegahan terjadinya tindak
pidana. Namun pada praktiknya, perimusan suatu instrumen penghukuman/pemidanaan
justru dapat menimbulkan suatu paradoks.
Baca Juga: Pidana Mati: Melawan Takdir Tuhan atau Menjalankan Takdir Tuhan?
Paradoks adalah pernyataan atau situasi yang tampak
bertentangan dengan logika atau akal sehat, tetapi bisa mengandung kebenaran
tertentu di dalamnya seperti “Semakin banyak yang saya tahu,
semakin saya sadar bahwa saya tidak tahu apa-apa” disatu sisi, mengetahui
lebih banyak seharusnya membuat kita merasa pintar, tapi justru menyadarkan
bahwa masih banyak hal yang belum kita ketahui.
Dalam filsafat, ilmu pengetahuan, bahkan kehidupan sehari-hari,
paradoks sering muncul untuk menunjukkan kerumitan realitas,
keterbatasan logika, atau cara berpikir yang perlu ditinjau ulang.
Instrumen penjeraan dalam hukum pidana merupakan sarana yang
dipergunakan negara melalui sistem peradilan pidana untuk menimbulkan efek
jera, baik bagi pelaku tindak pidana (special
deterrence) maupun masyarakat luas (general
deterrence).
Efek jera ini dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan
yang sama dan masyarakat terdorong untuk menghindari perilaku yang dilarang
oleh hukum. Instrumen yang digunakan cukup beragam, mulai dari pidana pokok,
pidana tambahan, tindakan, hingga mekanisme sosial hukum pidana.
Formulasi pidana mati dalam KUHP Nasional dapat kita temui dalam Pasal
98 yang pada pokoknya menyatakan Pidana mati diancamkan secara alternatif
sebagai upaya terakhir untuk mencegah dilakukannya Tindak Pidana dan mengayomi
masyarakat.
Namun tanpa disadari formulasi demikian justru dapat menimbulkan
suatu paradoks dimana alih-alih pidana mati dapat mencegah dilakukannya tindak
pidana, justru sebaliknya formulasi Pidana Mati tersebut dapat menjadi motivasi/dorongan
bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana.
John Stuart Mill
dalam pidatonya pada tanggal 21 April 1868 yang berjudul “A Bill to Provide for
Carrying out of Capital Punishment within Prisons” menyatakan bahwa:
“The failure of capital
punishment in cases of theft is easily accounted for: the thief did not believe
that it would be inflicted. He had learnt by experience that jurors would
perjure themselves rather than find him guilty; that Judges would seize any
excuse for not sentencing him to death, or for recommending him to mercy; and
that if neither jurors nor Judges were merciful, there were still hopes from an
authority above both.”
Dalam terjemahan bebas dapat memiliki arti kegagalan pidana mati
dalam kasus pencurian mudah dijelaskan: pencuri tidak percaya bahwa hukuman itu
benar-benar akan dijatuhkan. Dari pengalamannya, ia mengetahui bahwa para juri
lebih memilih bersumpah palsu daripada menyatakannya bersalah; bahwa hakim akan
mencari alasan apa pun untuk tidak menjatuhkan hukuman mati atau untuk
merekomendasikan pengampunan; dan bahwa jika baik juri maupun hakim tidak
menunjukkan belas kasihan, masih ada harapan dari otoritas yang lebih tinggi
dari keduanya.
Sehingga dapat ditarik dua unsur utama gagalnya pidana mati dalam
mencegah terjadinya tindak pidana adalah karena hukuman tersebut tidak pernah dijatuhkan
dan apabila hukuman tersebut dijatuhkan, ia tidak pernah dijalankan. Dengan
demikian timbul suatu pertanyaan bagaimana hubungan antara pendapat Mill dalam
pidatonya tersebut dengan formulasi pidana mati dalam KUHP Nasional yang dapat
mendorong/memotivasi terjadinya tindak pidana.
Dalam dunia bisnis dikenal suatu metode atau strategi penetapan
harga dengan nama Psychological Pricing.
Psychological Pricing adalah strategi
penetapan harga produk atau layanan yang disusun sedemikian rupa, sehingga bisa
memanipulasi persepsi pelanggan dan memengaruhi keputusan pembelian mereka.
Tujuan dari psychological
pricing adalah untuk menciptakan efek psikologis tertentu dalam pikiran
pelanggan. Salah satu penerapan strategi ini adalah dengan menggunakan Decoy pricing di mana
perusahaan menambahkan satu opsi produk (disebut decoy atau umpan)
yang sengaja dibuat kurang menarik, agar konsumen terdorong
memilih opsi lain yang sebenarnya lebih menguntungkan bagi perusahaan,
contohnya Bioskop menjual popcorn dalam 3 ukuran:
a.
Kecil: Rp20.000
b.
Sedang (decoy): Rp35.000
c.
Besar: Rp40.000
Di sini, harga popcorn sedang hanya sedikit lebih murah
dari besar, sehingga konsumen merasa pilihan besar jauh lebih
“worth it”. Tujuan decoy (popcorn sedang) bukan untuk laku, tapi untuk
membuat opsi besar terlihat sebagai keputusan paling rasional.
Psychological Pricing tersebut tidak hanya dapat diterapkan dalam dunia bisnis, melainkan
dapat pula diterapkan dalam menilai cost
and benefit dari suatu perbuatan pidana. Dalam kriminologi, hal tersebut
sangat dekat dengan teori rasional pilihan (rational
choice theory) dimana pelaku melakukan perhitungan sederhana seperti apakah
keuntungan dari kejahatan lebih besar dibanding risiko dan “harga” yang harus
dibayar (hukuman pidana).
KUHP Nasional menempatkan pidana mati sebagai pidana yang bersifat
khusus, sebagai upaya terakhir (ultimum
remedium) serta apabila dijatuhkan maka harus disertai masa percobaan
selama 10 (sepuluh) tahun dimana jika terpidana selama masa percobaan
menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah
menjadi pidana penjara seumur hidup.
Hal ini menunjukkan bahwa rumusan pidana mati dalam KUHP Nasional
memenuhi dua unsur utama gagalnya pidana mati dalam menimbulkan efek jera (baik
general deterrence maupun special deterrence).
Apabila kita memandang Pelaku sebagai konsumen/pembeli, sedangkan
hukuman/pidana dipandang sebagai harga yang harus dibayar (cost) dari keuntungan yang dapat diperoleh atas suatu perbuatan
atau tindak pidana (benefit), maka formulasi
pidana mati demikian dapat menjadikannya sebuah decoy atau umpan sehingga membentuk suatu rasio dimana hukuman
penjara seumur hidup, hukuman penjara waktu tertentu, dan hukuman-hukuman
lainnya menjadi sesuatu yang dapat dibayarkan/dianggap menguntungkan. Berikut skema
yang dapat digunakan untuk mengilustrasikan decoy
pricing dalam Pemidanaan:
Ancaman Tertinggi (Pidana Mati) → dianggap "decoy"
↓
Membuat Pidana Seumur Hidup tampak lebih rasional
↓
Membuat Pidana Penjara Waktu Tertentu tampak lebih
ringan
↓
Membuat Denda/Hukuman Tambahan terasa paling murah
Apabila skema tersebut kita terapkan dalam suatu
perkara seperti Penjual/Penyalur narkotika golongan I bukan tanaman yang
beratnya melebihi 5 (lima) gram maka dengan adanya ancaman pidana mati pada
pelaku peredaran narkotika tersebut, sistem hukum pidana memberi kesan bahwa pidana
mati adalah “harga tertinggi” untuk kejahatan narkotika.
Namun karena pidana mati sering dipandang sebagai upaya
terakhir/ultimum remedium dan meskipun
dijatuhkan ia tidak akan dilaksanakan, justru membuat pidana seumur hidup atau
20 tahun penjara tampak sebagai harga yang lebih masuk akal dan ringan. Efek
psikologisnya sama seperti decoy pricing:
ancaman paling ekstrem (pidana mati) berfungsi sebagai “umpan” sehingga pidana
di bawahnya dianggap lebih wajar untuk dijalani, dan bagi pelaku, masih ada
“perhitungan” bahwa manfaat ekonomi dari menjual narkotika bisa dianggap
sebanding dengan “harga” hukuman yang lebih ringan.
Formulasi pidana mati dalam KUHP Nasional yang
menempatkannya sebagai pidana khusus, bersifat ultimum remedium, dan disertai
masa percobaan 10 tahun justru melahirkan suatu paradoks penjeraan.
Alih-alih menimbulkan efek jera yang maksimal,
keberadaan pidana mati dalam bentuk demikian lebih berfungsi sebagai decoy yang membuat pidana lain (seumur
hidup, penjara waktu tertentu, dan jenis pidana pokok lainnya) tampak lebih
rasional dan ringan (mengakibatkan pidana penjara seumur hidup, pidana penjara
waktu tertentu, dan jenis pidana lainnya kehilangan efek deterrence-nya). Hal ini sejalan dengan pandangan John Stuart Mill
bahwa kegagalan pidana mati terletak pada kenyataan hukuman tersebut jarang
dijatuhkan dan sekalipun dijatuhkan sering tidak dijalankan. (ldr)
Referensi
Mill, J. S.
(1988). The collected works of John Stuart Mill, Volume XXVIII: Public and
parliamentary speeches, Part I, November 1850 – November 1868. J. M.
Robson (Ed.). University of Toronto Press; Routledge & Kegan Paul.
(Original work published 1850–1868).
Kubíčková, L.,
Veselá, L., Kormaňáková, M., & Veverková, E. (2023). How does decoy pricing
affect purchasing decisions? Studies in Business and Economics, 18(3), 176–197.
https://doi.org/10.2478/sbe-2023-0053
Baca Juga: Dari Tiang Eksekusi ke Meja Refleksi, Evolusi Pidana Mati dalam Reformasi Hukum Pidana
Akers, R.
L., & Sellers, C. S. (2012). Criminological theories: Introduction,
evaluation, and application (6th ed.). Oxford University Press.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI