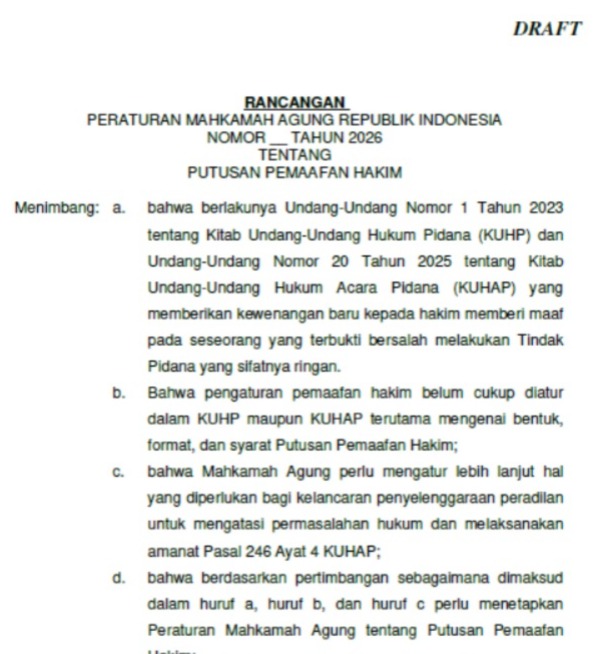Antara Belas Kasih dan Kepastian Hukum
Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2026, menandai babak baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia dengan mengintroduksi konsep judicial pardon atau pemaafan hakim.
Pasal 54 ayat (2) KUHP Baru
memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak
mengenakan tindakan meskipun terdakwa terbukti bersalah, dengan
mempertimbangkan "ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, keadaan
pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian" dengan
"mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.”
Baca Juga: Harmonisasi Konsep Pemaafan Hakim (Recterlijk Pardon) dalam Rancangan KUHAP
Konsep ini lahir dari keinginan menghumanisasi sistem peradilan pidana yang selama ini dianggap terlalu kaku dan berorientasi semata pada legal positivisme.
Dalam tradisi hukum kontinental,
khususnya Belanda, rechterlijk pardon telah lama dipraktikkan sebagai
jembatan antara kepastian hukum dan rasa keadilan. Namun, adopsi konsep ini
dalam konteks Indonesia perlu dievaluasi secara kritis, mengingat perbedaan
fundamental dalam struktur sosial, budaya hukum, dan kematangan institusi
peradilan.
Judicial pardon menawarkan solusi humanis
terhadap kasus-kasus yang secara teknis memenuhi unsur pidana namun tidak
proporsional jika dihukum penuh. Misalnya, pencurian sandal jepit senilai Rp.
10.000 oleh seorang gelandangan, atau pemukulan ringan akibat reaksi spontan
atas provokasi ekstrem. Dalam konteks seperti ini, penjara justru
kontraproduktif dan tidak mencerminkan nilai keadilan substantif.
Namun, ketiadaan kriteria
objektif dan mekanisme kontrol memadai dapat membuka ruang bagi bias kognitif
hakim. Frasa "mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan" dalam
Pasal 54 ayat (2) bersifat abstrak dan multi tafsir, sehingga berpotensi
menciptakan ketidakpastian hukum yang justru bertentangan dengan tujuan utama
sistem peradilan.
Potensi Risiko yang Perlu Diwaspadai
Risiko pertama yang mengancam implementasi judicial pardon adalah bias kognitif dan sosial hakim. Tanpa panduan objektif yang jelas, keputusan pemberian pemaafan sangat bergantung pada persepsi subjektif hakim terhadap pelaku dan perbuatannya.
Riset psikologi hukum menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti penampilan fisik,
ras, latar belakang sosial-ekonomi, dan kemampuan komunikasi terdakwa dapat
mempengaruhi penilaian hakim secara tidak sadar (Nicole Van Cleve, 2016)
Dalam konteks Indonesia yang
majemuk, bias ini dapat termanifestasi dalam diskriminasi terselubung
berdasarkan etnis, agama, kelas sosial, atau relasi kuasa. Seorang pelaku
dengan koneksi politik atau ekonomi yang kuat mungkin mendapat "keadilan
dan kemanusiaan" yang berbeda dengan rakyat biasa dalam perkara serupa.
Fenomena ini berpotensi mengukuhkan ketimpangan sosial yang sudah ada,
alih-alih mengatasinya.
Risiko kedua, keberadaan judicial pardon juga menciptakan moral hazard yang dapat mengikis efektivitas hukum pidana sebagai sarana pencegahan kejahatan. Ketika masyarakat mengetahui bahwa terdapat kemungkinan "dimaafkan" oleh hakim, kalkulasi rasional untuk melakukan tindak pidana dapat berubah.
Hal ini terutama berbahaya untuk
tindak pidana yang dipandang "ringan" namun memiliki dampak kumulatif
signifikan, seperti pelanggaran lalu lintas, pencemaran lingkungan skala kecil,
atau kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap "sepele."
Paradoks yang muncul adalah
bahwa semakin sering judicial pardon diterapkan, semakin berkurang pula
efek pencegahannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan angka kriminalitas
untuk kategori tertentu. Di beberapa negara Eropa, evaluasi jangka panjang
menunjukkan bahwa liberalisasi penghukuman tanpa disertai reformasi
sosial-ekonomi justru meningkatkan angka residivis. (United Nations Office On
Drugs And Crime, 2007)
Risiko ketiga dan yang paling fundamental adalah ancaman terhadap kepastian hukum sebagai salah satu pilar negara hukum. Pasal 54 ayat (2) KUHP yang abstrak dapat menciptakan disparitas putusan yang signifikan untuk kasus serupa, bergantung pada interpretasi dan preferensi personal hakim.
Sebagaimana dikhawatirkan Catur Alfath Satriya, salah seorang hakim yang pernyataannya
dimuat di kanal berita hukum online tahun 2024 lalu, "penerapan ketentuan judicial
pardon dinilai masih bersifat abstrak, sehingga dari satu kasus ke kasus
lainnya bisa saja penerapannya berbeda."
Ketidakpastian ini tidak hanya
merugikan tersangka yang tidak dapat memprediksi konsekuensi perbuatannya,
tetapi juga korban yang mungkin merasa dirugikan ketika pelaku
"dimaafkan" tanpa kriteria yang jelas. Dalam jangka panjang, hal ini
dapat menggerus kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mendorong main
hakim sendiri (vigilantism).
Mitigasi Risiko: Menuju Implementasi yang
Bertanggung Jawab
Seharusnya, sebelum KUHP baru di
berlakukan, langkah pertama yang urgen adalah penyusunan pedoman implementasi
yang komprehensif dan objektif. Pedoman ini harus mencakup kriteria kuantitatif
dan kualitatif yang jelas, seperti batasan nilai kerugian, kategori tindak
pidana yang eligible, kondisi sosial-ekonomi yang relevan, dan
faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara konsisten.
Pedoman tersebut perlu
mengadaptasi kearifan lokal dan nilai-nilai masyarakat Indonesia, namun tetap
mempertahankan objektivitas hukum. Misalnya, dengan mengintegrasikan konsep adat
tentang pemulihan keseimbangan sosial, namun dalam kerangka yang terukur dan
dapat dipertanggungjawabkan.
Kedua, Implementasi judicial
pardon harus disertai sistem pengawasan berlapis yang melibatkan tidak
hanya lembaga internal peradilan, tetapi juga elemen masyarakat sipil. Setiap
putusan judicial pardon harus disertai reasoning yang detail dan dapat
diakses publik untuk memastikan akuntabilitas. Selain itu, perlu dibentuk
mekanisme review berkala untuk mengevaluasi pola dan konsistensi penerapan.
Dalam tradisi Indonesia yang
menghargai musyawarah, dapat dikembangkan forum konsultasi antara hakim, tokoh
masyarakat, dan ahli hukum untuk kasus-kasus yang kompleks. Hal ini tidak
mengurangi independensi hakim, tetapi memperkaya perspektif pengambilan
keputusan.
Ketiga, investasi pada peningkatan
kapasitas hakim menjadi kunci keberhasilan implementasi. Pelatihan tidak hanya
mencakup aspek teknis hukum, tetapi juga sensitivitas sosial, psikologi
pengambilan keputusan, dan manajemen bias kognitif. Hakim perlu dibekali dengan
alat untuk mengenali dan mengatasi bias personal dalam pengambilan keputusan.
Penutup: Keseimbangan yang Dinamis
Judicial pardon dalam KUHP Baru merupakan
inovasi progresif yang mencerminkan evolusi pemikiran hukum pidana menuju
paradigma yang lebih humanis. Namun, progressivitas tanpa disertai safeguards
yang memadai dapat berubah menjadi regresivitas yang mengancam rule of law.
Tantangan ke depan adalah
bagaimana mengimplementasikan konsep ini secara bertanggung jawab, dengan
menyeimbangkan antara fleksibilitas yang diperlukan untuk keadilan substantif
dan kepastian hukum yang menjadi fondasi negara hukum. Keberhasilan
implementasi judicial pardon akan menjadi ujian bagi kematangan sistem
peradilan Indonesia dalam mengadaptasi perkembangan global tanpa kehilangan
jati diri dan prinsip-prinsip fundamental.
Pada akhirnya, palu hakim yang
dapat mengampuni harus tetap menjadi simbol keadilan yang berimbang, bukan alat
yang menciptakan ketidakadilan baru dalam kemasan humanisasi yang menyesatkan. (al/ldr)
Referensi
Jennifer K. Elek,
et al., "The Context of Procedural Justice: Bias and the Constitutional Minimum,"
Psychology, Public Policy, and Law, Vol. 24, No. 4 (2018), hlm. 456-470.
Baca Juga: Ingat! Beberapa Poin Penting Rancangan PERMA Putusan Pemaafan Hakim
United Nations
Office On Drugs And Crime, Handbook of basic principles and promising practices
on Alternatives to Imprisonment, Vienna, United Nations publication, 2007
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI