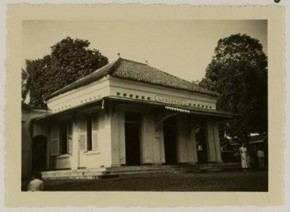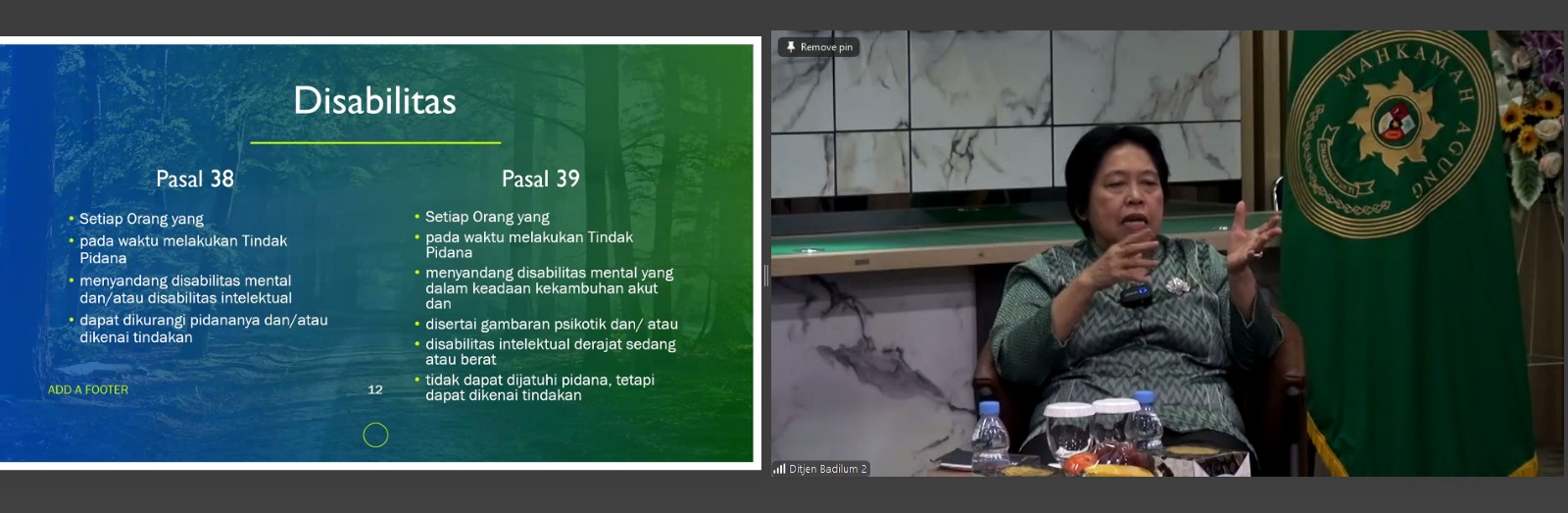Sore kemarin membaca berita tentang seseorang yang mengejar dan menabrak penjambret demi menyelamatkan tas istrinya. Saya langsung teringat dengan Guru Besar Hukum Pidana, Roeslan Saleh dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, saat itu beliau sudah mengingatkan akan pentingnya mengatur “daya memaksa” dalam KUHP baru. Saat itu Prof. Roeslan Saleh menhgatakan:
“Jadi, mengenai daya memaksa ini menurut hemat saya sebaiknya dirumuskanlah dengan jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana nasional kita yang akan datang”
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana sudah berlaku, dan
ini menandai berakhirnya era dominasi positivisme hukum yang kaku (legisme)
dalam sistem pemidanaan Indonesia.
Baca Juga: Menelisik Perbedaan Pengaturan Recidive dalam KUHP Lama dan KUHP Baru
Salah
satu pilar reformasi yang paling fundamental namun sering luput dari pembahasan
awam adalah rekonstruksi pengaturan tentang Alasan Pembenar (Rechtvaardigingsgronden).
Dalam KUHP lama (wetboek van strafrecht), alasan pembenar seringkali dipahami secara parsial dan sangat bergantung pada teks pasal. Namun, KUHP baru dalam Pasal 31 hingga Pasal 35 melakukan kodifikasi yang tidak hanya merapikan, tetapi juga mengubah paradigma penilaian sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dari yang semula formal menjadi materiil dalam fungsi negatif.
Dalam
KUHP lama, daya paksa (overmacht) dalam Pasal 48 seringkali
dicampuradukkan dengan keadaan darurat (noodtoestand). Padahal, secara
dogmatik, keduanya berbeda. Overmacht cenderung menyerang kehendak bebas
pelaku (alasan pemaaf), sedangkan noodtoestand berbicara tentang
benturan dua kepentingan hukum yang sama-sama sah (alasan pembenar).
KUHP
baru melalui Pasal 33 secara tegas memisahkan dan mengkodifikasi noodtoestand
sebagai alasan pembenar. Konstruksi pasal ini mengakui situasi dilematis dimana
seorang pelaku dihadapkan pada pertentangan kewajiban hukum atau pertentangan
kepentingan hukum.
Implikasi bagi hakim sangat jelas, Hakim tidak lagi perlu bersusah payah melakukan penemuan hukum (rechtsvinding) melalui yurisprudensi (seperti Opticien Arrest) untuk membenarkan tindakan darurat demi menyelamatkan kepentingan yang lebih besar. KUHP baru telah menyediakan "kamar" tersendiri bagi diskresi tersebut.
Lalu apa itu opticien arrest?
Mari
kita putar kembali waktu ke Amsterdam di tahun 1923. Ini adalah peristiwa yang
kemudian melahirkan doktrin hukum penting. Saat
itu, peraturan kota sangat kaku. Ketika jam menunjukkan waktu tutup, semua toko
wajib tutup tanpa terkecuali, sama sekali tidak ada toleransi.
Namun, di sebuah senja, seorang pemilik toko kacamata diuji integritas kemanusiaannya. Tepat saat ia hendak menutup pintu, muncul sosok pria tua bernama Tuan de Grooth. Wajahnya panik, kacamatanya jatuh dan hilang di jalanan. Tuan de Grooth meminta tolong kepada pemilik toko agar diperbolehkan membeli kacamata karena kacamata yang biasa dia pakai jatuh di jalan dan tak bisa ditemukan lagi. Tanpa alat bantu itu, dunia bagi de Grooth hanyalah buram, ia tak mungkin bisa menemukan jalan pulang dengan selamat.
Pemilik
toko optik dihadapkan pada dilema batin yang hebat. Di satu sisi pundaknya ada kewajiban
hukum (rechtsplicht) untuk patuh pada aturan jam operasional kota. Namun
di pundak lainnya, ada kepentingan hukum (rechtsbelang) untuk
menyelamatkan keselamatan seorang manusia yang tak berdaya.
Menurut anda, mana yang akan dipilih si pemilik toko? Ya, saat itu hati nuraninya menang. Ia memilih melanggar jam malam demi melayani de Grooth. Ironisnya, tindakan heroik ini justru menyeretnya ke meja hijau karena dianggap melanggar aturan jam malam toko.
Pengadilan
tingkat pertama Amsterdam membebaskan pemilik toko dengan pertimbangan ia
berada dalam suatu keadaan terpaksa atau in staat van nood. Kemudian
putusan ini dibatalkan pada tingkat banding, pemilik toko dinyatakan bersalah. Namun
pada tingkat kasasi, Hoge Raad membebaskan pemilik toko kacamata dengan alasan
yang bersangkutan berada dalam suatu noodtoestand.
Putusan ini kemudian disebut opticien arrest. Dalam arrestnya tertanggal 15 Oktober 1923, Hoge Raad membenarkan alasan overmacht yang digunakan pemilik toko. Menurut Hoge Raad, ada suatu noodtoestand yang terjadi karena adanya suatu pertentangan antara kewajiban hukum (rechtsplicht) dengan suatu kepentingan hukum (rechtsbelang). Mahkamah Agung Belanda bertitah:
“Inilah yang disebut Noodtoestand. Ketika aturan birokrasi berbenturan dengan keselamatan nyawa, hukum harus membungkuk untuk membenarkan penyelamatan nyawa tersebut"
Pada
Pasal 34, pengaturan pembelaan terpaksa mempertahankan esensi pelindungan
terhadap tubuh (lijf), kesusilaan (eerbaarheid), dan harta benda (goed).
Namun, pendalaman yang perlu dicermati adalah pada asas proporsionalitas dan
subsidiaritas. Serangan yang dilawan haruslah "seketika" dan
"melawan hukum".
KUHP
Nasional mempertegas bahwa pembelaan harus seimbang. Ini menjadi tantangan
pembuktian di persidangan, sejauh mana hakim dapat menilai
"keseimbangan" psikologis korban yang diserang? Di sinilah seni
memutus perkara diuji, memastikan bahwa alasan pembenar tidak menjadi lisensi
untuk main hakim sendiri (eigenrichting).
Sedangkan poin paling revolusioner dalam bab alasan pembenar adalah Pasal 35. Pasal ini menegaskan bahwa ketiadaan sifat melawan hukum materiil adalah alasan pembenar. Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana merupakan alasan pembenar. Secara teoritis, ini adalah pengakuan yuridis terhadap sifat melawan hukum materiil dalam fungsi negatif (Negatieve Functie van de Materiele Wederrechtelijkheid).
Selama
puluhan tahun, praktik peradilan kita terjebak dalam dialektika antara kaum
monistis dimana unsur melawan hukum selalu melekat pada delik dan dualistis.
Sejarah mencatat, yurisprudensi Mahkamah Agung melalui Putusan Machroes Effendi
(No. 42 K/Kr/1965) telah memberi sinyal progresif dengan menerapkan fungsi
negatif sifat melawan hukum materiil, membebaskan terdakwa karena perbuatannya
justru menguntungkan negara meski secara formal melanggar aturan.
Sinyal ini kemudian dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi meski dengan batasan, melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006 yang mengoreksi penerapan fungsi positif demi kepastian hukum. Kini, Pasal 35 hadir mematrikan norma tersebut. Bahwa ketiadaan sifat melawan hukum materiil adalah alasan pembenar yang sah menurut undang-undang.
Pasal
ini menjadi jembatan antara hukum negara (state law) dan hukum yang
hidup (living law). Hakim diwajibkan untuk menyelami nilai-nilai
keadilan masyarakat. Jika masyarakat adat atau kesadaran umum masyarakat tidak
menganggap perbuatan itu tercela, negara tidak boleh memidana.
Bagi penuntut umum, ini menambah lapisan beban pembuktian, Dimana penuntut umum tidak hanya harus membuktikan unsur pasal terpenuhi, tetapi juga harus siap berargumen bahwa perbuatan tersebut benar-benar "jahat" secara substansi. Di sisi lain bagi Penasihat Hukum dan Terdakwa, ini adalah amunisi pertahanan yang kuat untuk menggali motif dan konteks sosial perbuatan.
Baca Juga: Pergeseran Makna Putusan Lepas dalam RUU KUHAP dan Implikasinya
Ini
adalah tantangan bagi Hakim sebagai The Guardian of Justice. Rekonstruksi
alasan pembenar dalam KUHP Nasional kita saat ini menuntut perubahan pola pikir
penegak hukum. Kita tidak lagi bisa menjadi sekadar "mulut
undang-undang" (la bouche de la loi).
Dengan adanya Pasal 35, Hakim diberikan mandat besar sekaligus beban yang berat untuk menjadi penggali keadilan substantif. Hakim harus berani menyatakan "Lepas dari Segala Tuntutan Hukum" (onslag van alle rechtsvervolging) pada terdakwa yang secara teks bersalah, namun secara konteks sosial dan moralitas dapat dibenarkan. Inilah esensi dari hukum pidana modern, yaitu humanis, rasional, dan berkeadilan. Dengan Pasal 35, putusan lepas (onslag van alle rechtsvervolging) akan lebih sering mewarnai dinamika peradilan kita, menandakan bahwa hukum pidana Indonesia telah naik kelas dari sekadar menghukum raga, menjadi menguji rasa. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI