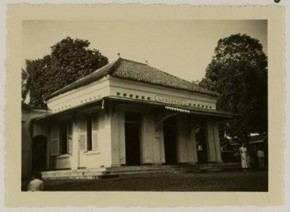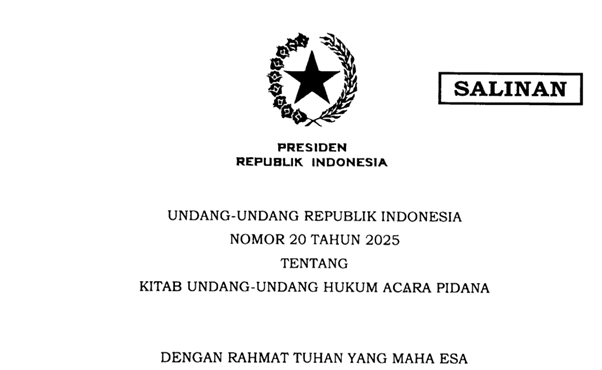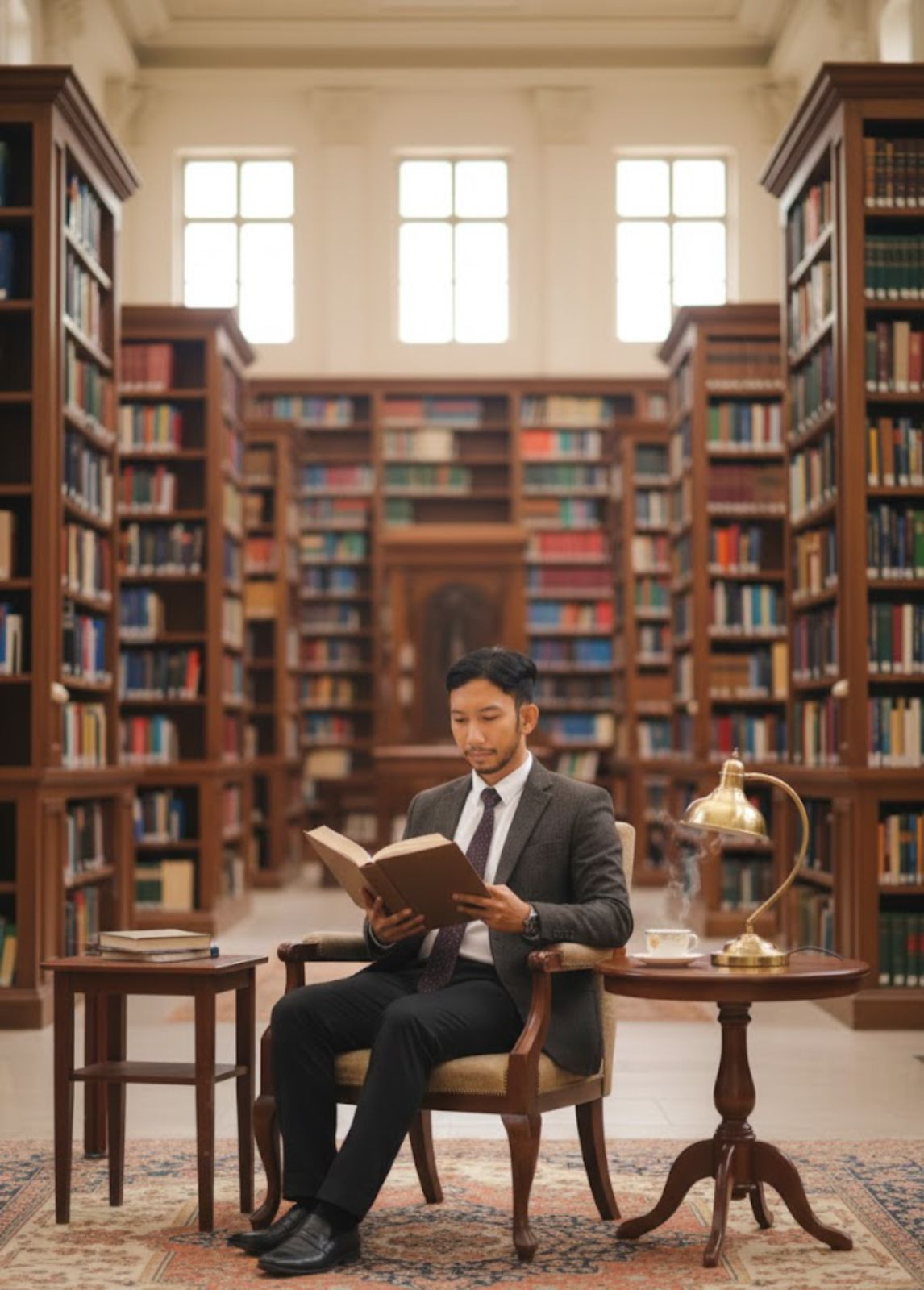Arsitektur hukum perkawinan nasional Indonesia didirikan di atas pilar filosofis yang luhur, sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan).
Pasal ini mendefinisikan perkawinan sebagai "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
Tujuan teleologis ini, pencapaian kebahagiaan dan keabadian (kekal), menjadi ratio legis utama pembentukan institusi keluarga.
Baca Juga: Memaknai Status “Kawin Belum Tercatat” pada Dokumen Kependudukan
Namun, UU Perkawinan secara pragmatis juga mengakui realitas kegagalan perkawinan. Pasal 39 ayat (1) dan (2) menetapkan bahwa perceraian, meskipun merupakan antitesis dari tujuan keabadian, dapat diakomodasi secara yuridis. Terdapat dua syarat imperatif: prosesnya harus dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah upaya mediasi gagal, dan harus didasarkan pada "cukup alasan" yang membuktikan bahwa "antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri".
Syarat "cukup alasan" ini kemudian dikodifikasi secara limitatif dan kaku oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan (PP Pelaksanaan). Pasal 19 PP Pelaksanaan merinci alasan-alasan tersebut, di antaranya adalah alasan yang sangat positivistik dan terukur secara kuantitatif, yakni Pasal 19 huruf (b): "Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah".
Di sinilah letak antinomi yuridis yang fundamental. Di satu sisi, hukum mendambakan tujuan substansial (kebahagiaan), di sisi lain, hukum menetapkan penghalang prosedural formalistik (limitasi waktu 2 tahun).
Dalam realitas sosiologis, hakim yang "terpenjara oleh belenggu positivisme hukum yang kaku" seringkali menolak gugatan perceraian yang diajukan oleh seorang istri yang terbukti menderita secara batin, menanggung beban ganda, dan hidup dalam perkawinan yang "mati suri", hanya karena Tergugat belum genap 2 tahun meninggalkannya. Kondisi ini menjebak Penggugat dalam hanging status secara de jure bersuami, namun secara de facto tidak, yang merupakan bentuk ketidakadilan gender dan mencederai rasa keadilan substantif.
Berdasarkan diskursus latar belakang mengenai antinomi antara idealisme UU Perkawinan dan rigiditas PP Pelaksanaannya, terdapat dua pertanyaan hukum fundamental yang harus dianalisis secara mendalam.
Pertama, apakah penafsiran tekstual positivistik terhadap alasan perceraian limitatif dalam Pasal 19 PP Nomor 9/1975, khususnya rigiditas tenggat waktu 2 tahun dalam Pasal 19 huruf (b), masih relevan dan mampu memberikan keadilan substansial dalam menghadapi realitas perkawinan yang telah pecah secara permanen (irreparable) dan berada dalam keadaan jeopardy?
Kedua, bagaimana penafsiran teleologis dan ekstensif terhadap Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9/1975 ("perselisihan dan pertengkaran terus menerus") dapat dikonstruksikan secara yuridis untuk mencakup konsep marriage breakdown, konflik batin yang permanen, dan hilangnya affectio maritalis sebagai dasar hukum yang sah untuk mengakhiri jeopardy perkawinan?
Kepatuhan mutlak terhadap tafsir literal Pasal 19 huruf (b) PP 9/1975 adalah bentuk manifestasi dari "positivisme hukum yang kaku". Pendekatan ini, yang mengutamakan kepastian hukum formal di atas keadilan substansial, gagal dalam mandat utamanya untuk "humanizing the law". Dalam menghadapi realitas sosiologis yang destruktif, penafsiran kaku ini justru "mencederai rasa keadilan" karena memaksa individu untuk tetap tersandera dalam penderitaan demi memenuhi tenggat waktu formal.
Kondisi inilah yang harus dielaborasi secara progresif oleh hakim sebagai konsep jeopardy (kemudaratan) dalam ranah hukum keluarga. Jeopardy adalah "suatu keadaan darurat di mana mempertahankan formalitas ikatan hukum justru mendatangkan kemudaratan (mudharat) yang jauh lebih besar daripada memutusnya".
Kemudaratan ini bukanlah sekadar ketidaknyamanan, melainkan ancaman nyata berupa "kerusakan kesehatan mental Penggugat" yang harus menanggung beban ganda, serta "distorsi perkembangan emosional anak-anak" yang hidup dalam "atmosfer rumah tangga yang 'mati suri'".
Dalam menghadapi jeopardy yang demikian, hakim tidak boleh terpenjara oleh positivisme.
Prinsip hukum tertinggi harus ditransplantasikan ke dalam hukum keluarga mikro: salus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi). Dalam konteks ini, contohnya, menyelamatkan Penggugat (istri) dan anak-anak dari lingkungan toxic marriage harus diprioritaskan di atas upaya mempertahankan status quo yang destruktif. Keselamatan psikologis dan emosional warga negara harus ditempatkan lebih tinggi daripada kepatuhan formalistik terhadap limitasi waktu 2 tahun.
Instrumen yuridis yang paling tepat untuk melakukan dekonstruksi positivisme tersebut adalah Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9/1975. Pasal ini memberikan alasan perceraian apabila "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Frasa kunci dalam pasal ini adalah "perselisihan dan pertengkaran" serta "tidak ada harapan".
Pertama, penafsiran teleologis mengharuskan hakim untuk menghubungkan Pasal 19(f) kembali dengan filosofi dasar Pasal 1 UU Perkawinan. Tujuan perkawinan adalah kebahagiaan. Ketika tujuan tersebut secara empiris telah mustahil dicapai dan perkawinan hanya menyisakan penderitaan batin, maka mempertahankan perkawinan tersebut justru bertentangan dengan filosofi dasar pembentukan hukum perkawinan itu sendiri. Frasa "tidak ada harapan" dalam Pasal 19(f) adalah penanda yuridis bahwa tujuan teleologis Pasal 1 UU Perkawinan telah sirna secara permanen.
Kedua, penafsiran ekstensif diperlukan untuk mendefinisikan ulang "perselisihan dan pertengkaran". Alasan ini "tidak harus selalu dimaknai sebagai konflik fisik atau verbal yang kasat mata". Dalam banyak perkawinan yang "mati suri", kehancuran justru terjadi dalam kebisuan. Oleh karena itu, penafsiran ekstensif harus mencakup pula keadaan "konflik batin yang permanen", yang termanifestasi dalam bentuk silent conflict, pengabaian total, dan hilangnya affectio maritalis (kasih sayang dan kehendak untuk hidup sebagai suami istri). Hilangnya affectio maritalis adalah bentuk "pertengkaran" batin yang paling fundamental dan permanen, yang membuktikan bahwa "tidak ada harapan" lagi untuk rukun.
Penafsiran progresif terhadap Pasal 19(f) ini didukung oleh perkembangan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Yurisprudensi telah berkembang ke arah pemikiran bahwa "pecahnya perkawinan" (marriage breakdown) dapat menjadi alasan perceraian yang berdiri sendiri.
Ketika fakta-fakta akumulatif, meliputi separasi, penghentian nafkah, masalah psikologis, dan adanya pihak ketiga, telah menunjukkan perkawinan itu irreparable, Pengadilan sejatinya tidak sedang memutuskan ikatan, melainkan hanya memberikan afirmasi hukum atas fakta sosiologis yang telah terjadi.
Secara prosedural, dalam kasus jeopardy, ketidakhadiran Tergugat harus dikonstruksikan secara yuridis. Itu adalah bentuk stilzwijgende erkenning (pengakuan diam-diam) atas dalil Penggugat, sekaligus manifestasi nyata pelepasan hak dan tanggung jawab mempertahankan rumah tangga.
Oleh karena itu, pengabulan gugatan adalah upaya legal protection yang diberikan negara. Ini adalah intervensi yudisial mendesak untuk mengakhiri "ketidakadilan" akibat hanging status, serta memberikan kepastian hukum untuk menata kembali masa depan para pihak dan/atau anak-anak yang lahir dalam perkawinan.
Alasan perceraian dalam Pasal 19 PP 9/1975 bukanlah "limitatif absolut", melainkan pedoman bagi hakim menilai apakah tujuan fundamental perkawinan (Pasal 1 UU Perkawinan) masih mungkin tercapai. Ketika perkawinan telah menjadi jeopardy, merusak kesehatan mental dan distorsi emosional anak, maka kepatuhan kaku pada positivisme (Pasal 19(b)) adalah denial of justice.
Baca Juga: Fenomena Dispensasi Kawin Pasca Perkawinan Terlaksana Secara Adat dan Agama di Bali
Penafsiran teleologis dan ekstensif terhadap Pasal 19(f) diperlukan untuk mencakup konflik batin permanen dan hilangnya affectio maritalis. Ini bukanlah untuk mempermudah perceraian, melainkan respon yudisial yang progresif dan bertanggung jawab. Ini adalah ultimum remedium untuk mencegah mudarat lebih besar, memastikan hukum keluarga tidak hanya formalistik, tapi adil dan berkemanusiaan. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI