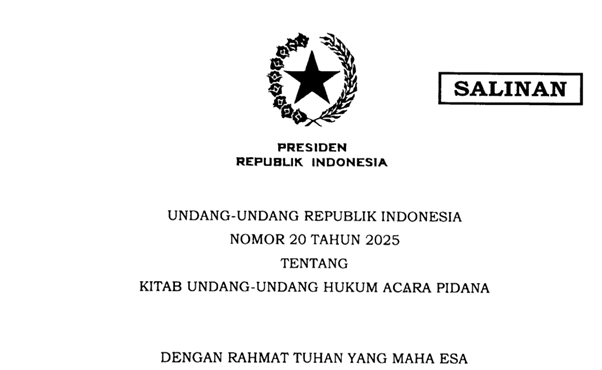Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa bahasa hukum terasa begitu "asing" dan sulit dipahami? Mengapa satu kata dalam konteks hukum bisa memiliki makna yang sangat berbeda dengan penggunaan sehari-hari? Di sinilah semiologi berperan sebagai kunci untuk membuka tabir kompleksitas bahasa hukum dalam sistem peradilan Indonesia.
Semiologi, sebagai ilmu yang mempelajari tanda dan makna (Saussure, 1916), menawarkan perspektif menarik untuk memahami bagaimana bahasa hukum bekerja dalam proses pembuktian di pengadilan. Bahasa hukum bukan sekadar rangkaian kata-kata formal, melainkan sistem komunikasi yang penuh dengan lapisan makna tersembunyi yang dapat menentukan nasib seseorang di hadapan hukum.
Anatomi Bahasa Hukum Indonesia: Warisan yang Membingungkan
Baca Juga: “Bahwa”: Kata Singkat Penata Keadilan
Bayangkan bahasa hukum sebagai sebuah kode rahasia yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu. Untuk membongkarnya, Ferdinand de Saussure mengajarkan bahwa setiap kata memiliki dua sisi: bentuk (signifier) dan makna (signified). Meskipun dalam konteks hukum Indonesia, fenomena ini menjadi semakin kompleks.
Ambil contoh sederhana kata "itikad baik" dalam hukum perdata. Secara harfiah, frasa ini mudah dipahami, namun dalam konteks hukum, makna "itikad baik" bisa sangat beragam tergantung pada kasus yang dihadapi. Seorang hakim mungkin menginterpretasikan "itikad baik" dalam kontrak jual beli berbeda dengan kasus perceraian. Inilah yang membuat bahasa hukum menjadi "hidup" dan dinamis namun sering membingungkan.
Charles Sanders Peirce memberikan sudut pandang lain yang menarik melalui konsep ikon, indeks, dan simbol (Peirce, 1931). Dalam ruang persidangan, kata "terdakwa" bukan sekadar label, melainkan simbol yang membawa serta seluruh konsep presumsi tidak bersalah. Dan setiap kali hakim menyebut "terdakwa", sebenarnya secara tidak langsung tercipta ekspektasi hukum yang kompleks.
Apa yang menarik adalah bagaimana bahasa hukum Indonesia menciptakan realitas tersendiri. Ketika seorang jaksa mengatakan "dakwaan" dalam persidangan, dia tidak hanya menyampaikan tuduhan, tetapi juga membangun narasi hukum yang akan menjadi dasar pembuktian. Karenanya, setiap pilihan kata menjadi strategi komunikasi yang dapat mempengaruhi persepsi hakim dan hasil putusan.
Bahasa hukum Indonesia sendiri memiliki DNA yang unik. Sebagai warisan dari sistem civil law Belanda, struktur bahasa hukum kita cenderung formal dan hierarkis. Terminologi seperti "perbuatan melawan hukum" atau "keadaan memaksa" telah menjadi bagian integral dari kosakata hukum Indonesia (Mertokusumo, 2014). Warisan yang kita adopsi tersebut pada prinsipnya menciptakan fenomena menarik di mana satu terminologi bisa memiliki interpretasi berbeda dalam konteks hukum pidana, perdata, atau administratif (Wignjosoebroto, 2013). Hal yang menunjukkan bahwa bahasa hukum Indonesia bukan monolitik, melainkan multidimensional.
Persidangan sebagai Teater Tanda dan Makna: Mengapa Semiotika Penting dalam Putusan
Ruang persidangan sesungguhnya adalah panggung di mana berbagai tanda dan makna saling berinteraksi. Setiap pernyataan saksi, setiap dokumen yang diajukan, setiap argumentasi pengacara adalah tanda yang harus "dibaca" dan diinterpretasikan oleh hakim. Proses pembuktian, dalam perspektif semiologis, adalah proses konstruksi makna yang sangat kompleks.
Hakim sendiri seharusnya berperan sebagai "penerjemah utama" yang mentransformasi berbagai tanda yang muncul dalam persidangan menjadi putusan yang memiliki kekuatan hukum. Proses ini jauh dari sederhana karena melibatkan seleksi, interpretasi, dan kombinasi berbagai elemen informasi yang tersedia (Eco, 1976).
Kualitas interpretasi hakim sendiri sangat bergantung pada pemahamannya terhadap "kode" semiologis yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia. Dimana seorang hakim yang memahami nuansa makna sebenarnya akan mampu menghasilkan putusan yang lebih adil dan komprehensif dibandingkan dengan yang hanya mengandalkan pendekatan tekstual semata.
Bagian yang paling menarik dan jarang dipahami adalah hakim tidak hanya bertugas memutus perkara, tetapi juga berkomunikasi dengan masyarakat melalui putusannya. Sebuah putusan pengadilan bukan hanya dokumen hukum internal, melainkan juga instrumen komunikasi publik yang harus dapat diakses dan dipahami oleh para pencari keadilan.
Bayangkan jika seorang hakim mampu menerapkan prinsip semiotika dengan baik dalam menyusun putusan. Dia akan memperhatikan tiga dimensi penting: bagaimana menyusun struktur kalimat yang sistematis dan logis (dimensi sintaksis), bagaimana memilih terminologi yang tepat dan konsisten (dimensi semantik), dan bagaimana mempertimbangkan konteks sosial serta dampak komunikatif putusan (dimensi pragmatik) (Morris, 1938).
Ketika hakim berhasil mengkomunikasikan alasan-alasan hukum dengan bahasa yang jelas namun tetap presisi, legitimasi putusan di mata masyarakat akan meningkat signifikan. Sebaliknya, putusan yang terlalu teknis dan sulit dipahami dapat menimbulkan skeptisisme dan mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan.
Untuk mengoptimalkan fungsi semiologis bahasa hukum di pengadilan, pengembangan kamus terminologi hukum yang komprehensif dan mudah diakses menjadi kebutuhan mendesak. Tentu kita bisa membayangkan bagaimana baiknya jika setiap praktisi hukum memiliki akses terhadap panduan yang jelas mengenai makna dan penggunaan terminologi hukum dalam berbagai konteks. Selain itu pelatihan semiologis bagi hakim juga dapat meningkatkan kesadaran terhadap dimensi makna dalam bahasa hukum. Pelatihan ini bukan hanya akan membantu mereka memahami nuansa makna, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi yang lebih efektif dengan masyarakat.
Terakhir, standardisasi penggunaan bahasa hukum dalam dokumen persidangan juga dapat mengurangi ambiguitas interpretasi dan meningkatkan konsistensi putusan. Standar ini harus fleksibel namun tetap mempertahankan presisi yang diperlukan dalam komunikasi hukum.
Semiologi memberikan lensa yang menarik untuk memahami kompleksitas bahasa hukum dan proses pembuktian di pengadilan Indonesia. Pendekatan semiologis membantu kita melihat bagaimana makna dikonstruksi, ditransmisikan, dan diinterpretasikan dalam konteks yuridis.
Pemahaman yang mendalam terhadap dimensi semiologis bahasa hukum bukan hanya memperkaya perspektif akademis, tetapi juga berkontribusi nyata pada peningkatan kualitas Putusan. Pada akhirnya, hal ini akan mendukung tercapainya keadilan yang substantif dalam sistem peradilan Indonesia. Karena secara universal salah satu indikator putusan yang baik adalah yang menggunakan bahasa hukum yang dapat menjembatani jurang antara kompleksitas hukum dan kebutuhan masyarakat untuk memahami keadilan, dan semiologi menawarkan jalan untuk mencapai keseimbangan tersebut. (YPY/LDR)
Daftar Bacaan
Umberto Eco, (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington: Indiana University Press.
Sudikno Mertokusumo, (2014). Teori Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
Charles W. Morris (1938). Foundations of the Theory of Signs. Chicago: University of Chicago Press.
Baca Juga: Sepeda Listrik dan Persoalan Hukumnya di Indonesia
Charles Sanders Peirce (1931). Collected Papers of Charles Sanders Peirce. Cambridge: Harvard University Press.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI