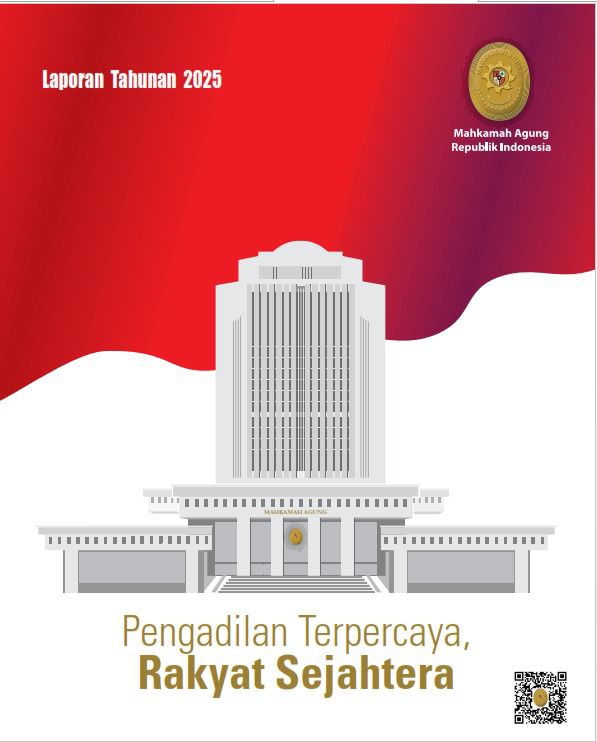MODUS suap korupsi ternyata tidak ada yang baru-baru amat. Sejak tahun 60-an, suap sudah diberikan lewat berbagai cara, salah satunya membelikan Vespa untuk keluarga, bukan pelaku langsung. Apakah si pelaku jadi bebas?
Berdasarkan berkas putusan yang didapat DANDAPALA, Jumat (14/11/2025), kasus itu dilakukan oleh Kepala Biro Umum Ditjen Pajak, R Soemarto Sumarjo pada Juni 1965. Kasus yang didakwakan kepada Soemarto yaitu membiarkan anak buahnya, Achmad Idris mengambil uang Rp 1,5 miliar dari brankas. Padahal, uang itu seharusnya untuk pembangunan rumah pegawai Ditjen Pajak di Kawasan Jakarta Barat.
Selidik punya selidik, Soemarto mendapatkan kickback Rp 25 juta dan pemberian barang. Di antaranya Vespa seharga Rp 2,5 juta, hingga barang elektronik yang semuanya diberikan lewat keluarga pelaku. Kasus ini terungkap dan diusut. Di persidangan, Soemarto beralibi aliran uang lewat keluarganya dan ia tidak tahu. Tapi apa kata majelis hakim?
Baca Juga: Akuntansi Forensik, Jurus Baru Pemberantasan Korupsi
Kasus ini diadili di Daerah Istimewa Jakarta. Pada 31 Maret 1970, pembelaan terdakwa ditolak dan ia dihukum 6 tahun penjara. Putusan ini dikuatkan hingga tingkat kasasi dengan nomor perkara 77 K/Kr/1973.
“1. Melakukan tindak pidana korupsi dengan jalan sebagai pegawai negeri dengan sengaja membiarkan uang yang ada padanya karena jabatannya digelapkan orang lain. 2. Melakukan tindak pidana korupsi dengan jalan sebagia pegawai negeri menerima hadiah/pemberian, sedang ia tahu atau patut dapat menduga bahwa apa yang dihadiahkannya itu berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang karena jabatannya,” demikian bunyi putusan tersebut.
Putusan itu diketok oleh Oemar Seno Adji dengan anggota Sri Widojati Wiratmo Soekito dan Indoharto. Belakangan, Oemar Seno Adji juga menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) 197401982. Pertimbangan putusan ini diikuti oleh para hakim lainnya sehingga menjadi yurisprudensi. Hingga 50 tahun berlalu, putusan pertimbangan Oemar Seno Adji dkk itu kerap dikutip dan dirujuk dalam berbagai kasus. Apa itu?
Pertama, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pembiaran aktif terhadap penggelapan dana negara merupakan bentuk korupsi. Artinya, seorang pejabat tetap dapat dipidana meskipun tidak menggelaplkan dana secara langsung tetapi membiarkan orang lain melakukannya dalam lingkup tanggungjawabnya.
Kedua, penerimaan hadiah tetap dipandang sebagai korupsi meskipun diberikan melalui perantara anak atau keluarga.
Yurisprudensi 77/1973 itu menunjukkan bahwa dua prinsip penting dalam hukum tipikor modern sejatinya telah hadir jauh sebelum lahirnya UU 31/1999. Pertama, pejabat dapat dimintai pertanggungjawaban atas pembiaran aktif terhadap korupsi yang dilakukan bawahannya. Kedua, penerimaan hadiah melalui keluarga atau perantara tetap dapat dipidana, sebuah konsep yang kini dikenal sebagai gratifikasi.
Kaidah hukum dalam yurisprudensi ini menjadi dasar awal pembeda antaragratifikasi yang dapat dibenarkan dan gratifikasi yang berimplikasi sebagai suap. Putusan ini memberi rambu yang jelas bagi aparat penegak hukum tentang kapan sebuah pemberian berubah menjadi tindak pidana, sehingga wajar jika preseden initerus dijadikan rujukan baik dalam putusan perkara tipikor masa kini maupun dalam Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang diterbitkan KPK.
Relevansinya yang bertahan hingga era regulasi modern menunjukkan bahwa warisan peradilan dapat menjadi fondasi bagi kebijakan integritas hari ini. Melalui preseden ini, terlihat bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia berakar pada gagasan hukum yang dirumuskan jauh sebelum hadirnya UU Tipikor modern.
Dari perkara inilah dasar- dasar penegakan hukum korupsi mulai terbentuk sebelum adanya lembaga modern seperti KPK, dan sebelum korupsi dipahami dalam kerangka “gratifikasi”, “kerugian negara”, dan “penyalahgunaan kewenangan” seperti sekarang.
Dalam putusan Pengadilan Negeri 1970, masih digunakan istilah “Vordering”, yang berasal dari sistem hukum Belanda. Kata ini berarti “tuntutan” atau “gugatan” dan digunakan sejak masa Wetboek van Strafrecht (KUHP) kolonial.
Baca Juga: 15 Tahun Pengadilan Tipikor, Saatnya Bangkit untuk Keadilan Substantif
Jejak ini menunjukkan bahwa pada 1950–1970-an, administrasi peradilan Indonesia masih banyak mempertahankan format kolonial. Kajian Hanifah dan Adil (2025), dalam artikel “Legal Culture and Law Enforcement in Indonesia: A Normative Juridical Perspective” yang dimuat di Eduvest – Journal of Universal Studies, mencatat bahwa budaya hukum pada masa awal kemerdekaan masih berakar pada tradisi Belanda. Baru setelah reorganisasi peradilan pada awal 1970-an, istilah-istilah tersebut mulai ditinggalkan dan diganti dengan terminologi Indonesia seperti “Nomor Perkara” dan “Register Pidana”.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI