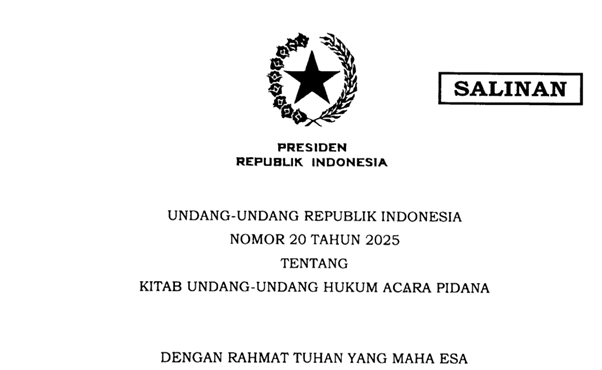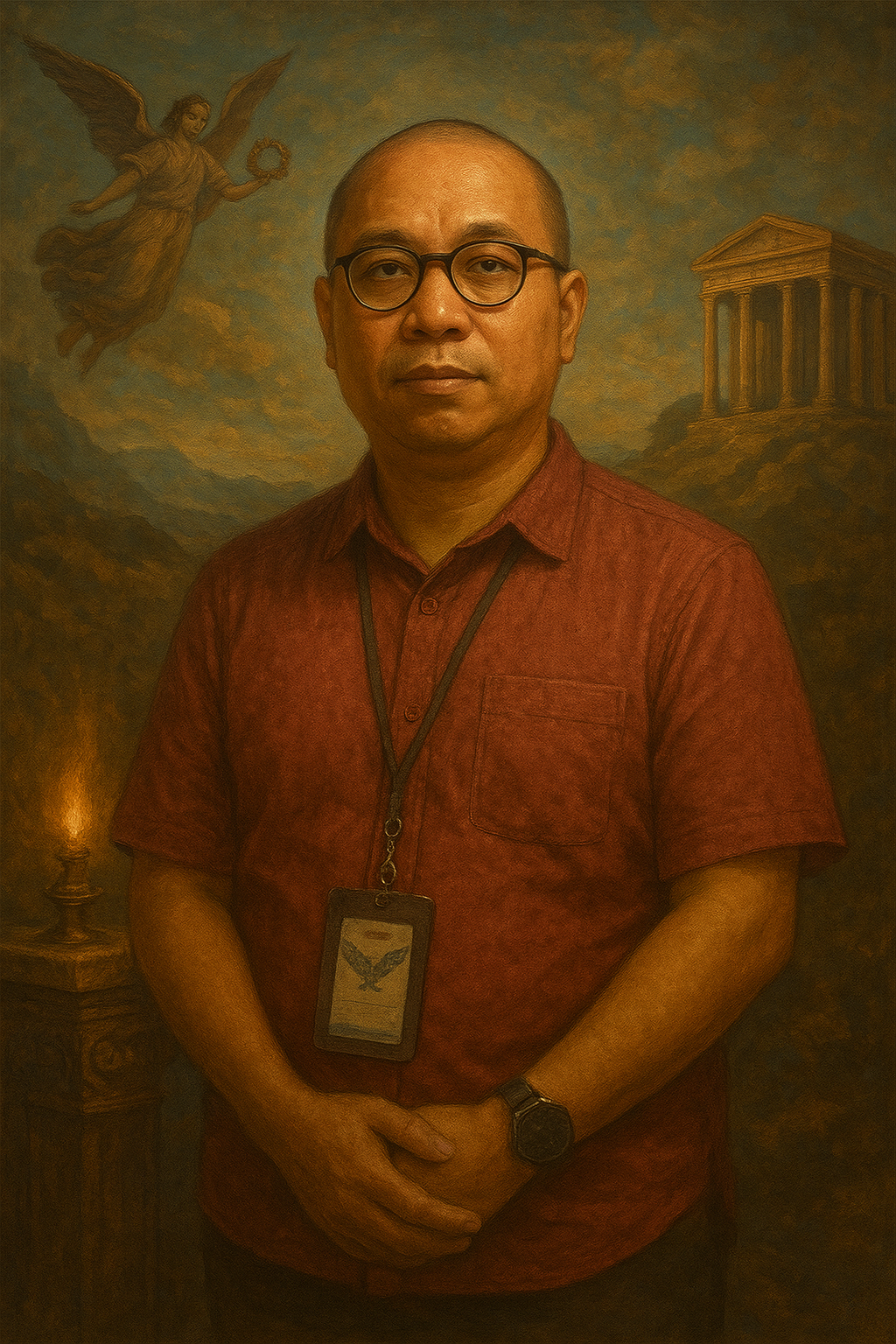“……the parable of the "boiled frog." If you place a frog in a pot of boiling water, it will immediately try to scramble out. But if you place the frog in room temperature water, and don't scare him, he'll stay put. Now, if the pot sits on a heat source, and if you gradually turn up the temperature, something very interesting happens. As the temperature rises from 70 to 80 degrees F., the frog will do nothing. In fact, he will show every sign of enjoying himself. As the temperature gradually increases, the frog will become groggier and groggier, until he is unable to climb out of the pot. Though there is nothing restraining him, the frog will sit there and boil. Why? Because the frog's internal apparatus for sensing threats to survival is geared to sudden changes in his environment, not to slow, gradual changes”.
Pendapat Peter M. Senge tersebut apabila diterjemahkan secara bebas kira-kira menjadi sebagai berikut, perumpamaan tentang “katak rebus”, seekor katak secara refleks akan melompat menyelamatkan diri jika si katak secara tiba-tiba dimasukkan ke dalam kuali yang berisi air mendidih.Namun, jika dari awal katak itu dimasukkan ke dalam kuali yang airnya bersuhu normal, ia akan diam karena berada dalam zona nyaman. Sekalipun air itu dipanaskan secara perlahan-lahan, si katak tetap akan diam. Bahkan, si katak terlelap tidur!, Dia tidak berusaha menyelamatkan diri karena menikmati hangatnya perpindahan suhu air. Ini berarti si katak sudah beradaptasi dengan panasnya air karena dari awal dia sudah beradaptasi dengan ”ancaman lambat”. Akibatnya, si katak tidak pernah menyadari adanya ancaman lambat hingga ia mati dalam air mendidih dan lebih celaka menikmatinya.
Begitu juga dengan eksplorasi besar-besaran terhadap kekayaan
sumberdaya alamnya melalui pembukaan areal pertambangan mineral bumi yang tak
terbarukan dengan hilirisasi dan sejenisnya yang masif akhir-akhir ini pasca
pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta
Kerja dan produk hukum turunannya berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional,
yang mengebiri Undang-Undang Nomr 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Baca Juga: Tips Memilih Klasifikasi Perkara Lingkungan Hidup di SIPP
Eksplorasi Pertambangan mineral bumi ini dilakukan dengan tujuan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi daerah dimana eksplorasi pertambangan itu didirikan dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah tujuan yang menggiurkan dan sekaligus melenakan ini apakah akan mengalami keadaan seperti balada ”katak rebus” sebagaimana alinea awal tulusan ini?, yakni sebuah proses yang dialami segenap warga negara yang kurang memiliki kepekaan terhadap ”ancaman lambat” dari degradasi kualitas lingkungan menuju kerusakan ekosistem yang tidak bisa dipulihkan setelah habis (tidak terbarukan) nanti, sebagai akibat eksplorasi besar-besaran terhadap kekayaan sumberdaya alam yang mengatasnamakan pertumbuhan dan kemakmuran ekonomi semata.
Dengan demikian dalam perspektif Socio-Legal Studies pemehaman terhadap Deep Ecology menjadi penting terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Yang Mengebiri Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Etnosentrisme dan deep ecology pada perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sebagaimana diketahui Undang-Undang tentang Cipta Kerja telah menghapus ketentuan penting terkait izin lingkungan dan sanksi pidana pengelolaan limbah B3 (Bahan, Berbahaya, Beracun) dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menjadikan menjadikan perizinan sebagai fokus pengawasan dan memindahkan penanganan pelanggaran lingkungan dari sanksi pidana menjadi sanksi administratif.
Penghapusan ini mengurangi hak partisipasi masyarakat dan
akses gugatan terhadap izin lingkungan, serta memberikan ruang lebih besar bagi
eksploitasi lingkungan.
Beberapa hal krusial yang diubah atau dihilangkan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terdiri dari Pencabutan Izin Lingkungan, Sanksi Pidana Terhadap Pengelolaan
Limbah B3, Pengurangan Partisipasi Masyarakat, Sentralisasi Kewenangan
Lingkungan, Pengabaian Kepatuhan terhadap Lingkungan,Potensi Eksploitasi dan
Kerusakan Lingkungan;
Dari pengebirian UUPPLH oleh UU Cipta Kerja tersebut, tampak bahwa orientasi hidup manusia modern yang cenderung materialistik dan hedonistik juga sangat berpengaruh. Kesalahan cara pandang atau pemahaman manusia tentang sistem lingkungannya, mempunyai andil yang sangat besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan yang terjadi dunia saat ini.
Cara pandang dikhotomis yang yang
dipengaruhi oleh paham antropoentrisme yang memandang bahwa alam
merupakan bagian terpisah dari manusia dan bahwa manusia adalah pusat
dari sistem alam mempunyai peran besar terhadap terjadinya kerusakan lingkungan.
Cara pandang demikian telah melahirkan perilaku yang eksploitatif dan tidak
bertanggung jawab terhadap kelestarian sumberdaya alam dan lingkungannya.
Antroposentrisme atau ada yang menyebut egosentrisme merupakan buah dari alam pikiran modern tersarikan dari esensialisme kesadaran akan kenyataan otonomi manusia di hadapan alam semesta, yang mulai muncul di bawah semboyan terkenal: Sapere Aude! (berpikirlah sendiri!) dan Cogito ergo sum (saya berpikir maka saya ada)-nya Rene Descartes.
Dengan semboyan kokoh ini, alam pikiran modern benar-benar menjadi masa di mana rasionalitas manusia muncul dan menggeser segala otoritas non-rasio, termasuk agama. Dari kesadaran essensialisme inilah embrio nalar antroposentrisme mulai nampak. Keyakinan akan rasionalitas manusia pada momen berikutnya mengejawantah dalam aktifitas kreatif, penciptaan, dan inovasi sains dan teknologi hingga munculnya masyarakat ekonomi global yang pada akhirnya membawa bencana yang maha dahsyat, yakni krisis lingkungan yang justru mewarnai optimisme modernitas ini.
Mula-mula secara embrional, masyarakat ekonomi global lahir dari rahim
revolusi industri dan revolusi hijau, yang telah menggeser masyarakat feodal
yang mapan. Masyarakat ekonomi baru ini senantiasa didominasi oleh keinginan
untuk memanfaatkan sebesar-besarnya potensi alam untuk kemakmuran dan
kesejahteraan manusia. Karena
motif ekonominya yang begitu dominan, pada akhirnya tidak ramah terhadap
lingkungan.
Menurut Hossein
Nasr, Manusia modern telah mendesakralisasi alam, meskipun proses ini sendiri
hanya di bawa ke kesimpulam logisnya oleh sekelompok minoritas. Apalagi alam telah dipandang sebagai sesuatu yang harus
digunakan dan dinikmati semaksimal mungkin
Pergeseran filsafati terhadap pelestarian
lingkungan ini bermuara pada diskursus deep
ecology yang dikemukakan oleh Arne
Naess seorang filsuf dari
Negara Norwegia yang didasari oleh pengalaman spiritualnya yang sangat mendalam
pada lingkungan hidup, sekitar tahun 1970 an. Diskursus ini di landasi dengan apa yang di
sebut dengan A platform of the deep
ecology movement.
Intisari dari deep ecology adalah untuk mengajak bertanya lebih dalam. Kata sifat ’dalam’ menekankan bahwa kita bertanya mengapa, di mana dan bagaimana jika yang lain tidak. Hal ini memerlukan perluasan pemikiran yang sangat luar biasa tentang ekologi dengan apa yang disebut ecosophy, dengan demikian ’deep’ identik dengan ’sophia’, atau ’dalam’ identik dengan ’kebijaksanaan’.
Sebagai contoh : kita harus mempertanyakan, mengapa berbicara
pertumbuhan ekonomi dengan tingkat konsumerisme menjadi sangat penting?, dan
jawaban konvensionalnya adalah bahwa hal ini dikarenakan konsekuensi ekonomi
itu sendiri. Tetapi apabila berbicaranya dengan mengunakan terminologi deep ecology maka pertanyaan yang mengemuka
menjadi : apakah masyarakat saat ini memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti
keamanan, cinta dan akses ke alam bersama dengan mahluk hidup yang lain.
Penutup
Terkait dengan pembangunan berkelanjutan (sustainable Development) maka pola
pikir etnosentrisme harus segera di tinggalkan dan beralih kepada sikap hidup
yang mengedepankan semangat deep ecology.
Dengan demikian desentralisasi sistem
pemerintahan sebagai konsekuensi otonomi daerah seharusnya tidak menjadi
hambatan tetapi menjadi tantangan untuk munculnya kearifan lokal (local wisdom) dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Roh yang meliputi deep ecology inilah yang
akan menentukan efektifitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (aar/ldr)
Penulis: R Moh Yakob Widodo-Hakim Adhoc Tipikor PN Ternate.
Baca Juga: Deepfake Dilema: Tantangan Hukum Pidana di Era Artificial Intelligence
Refrensi
- Peter M Senge, “The Fifth Discipline” Doubleday Publishing
New York,1990;
- Ben A. Minteer, “Anthropocentrism”, dalam J. Baird
Callicott and Robert Frodeman, Editors in Chief, Encyclopedia Of
Environmental Ethics And Philosophy, Gale Cengage Learning, Macmillan, 2009;
- Agus Rachmat W., “Etika Lingkungan
Hidup dan Pertentangan Politik”, dalam Bambang Sugiharto dan Agus rachmat W.
(ed), Wajah Baru Etika dan Agama,Kanisius, Jogjakarta,2000;
- Sayyed Hossen Nasr, Antara Tuhan,
Manusia dan Alam: Jembatan Filosofis dan Religius Menuju Puncak Spiritual,
(terj), Ali Noer Zaman, Ircisod, 2005, hal.28;
- Arne Naess,
“Ecology, community and lifestyle: Outline
of Ecosophy”, Cambridge University Press 1989;
- Lihat juga Fritjof Capra ”Kearifan Tak Biasa (Uncommon wisdom)” Bentang Budaya Jogjakarta 2002;
- R Moh Yakob Widodo-Hakim Adhoc Tipikor PN Ternate.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI