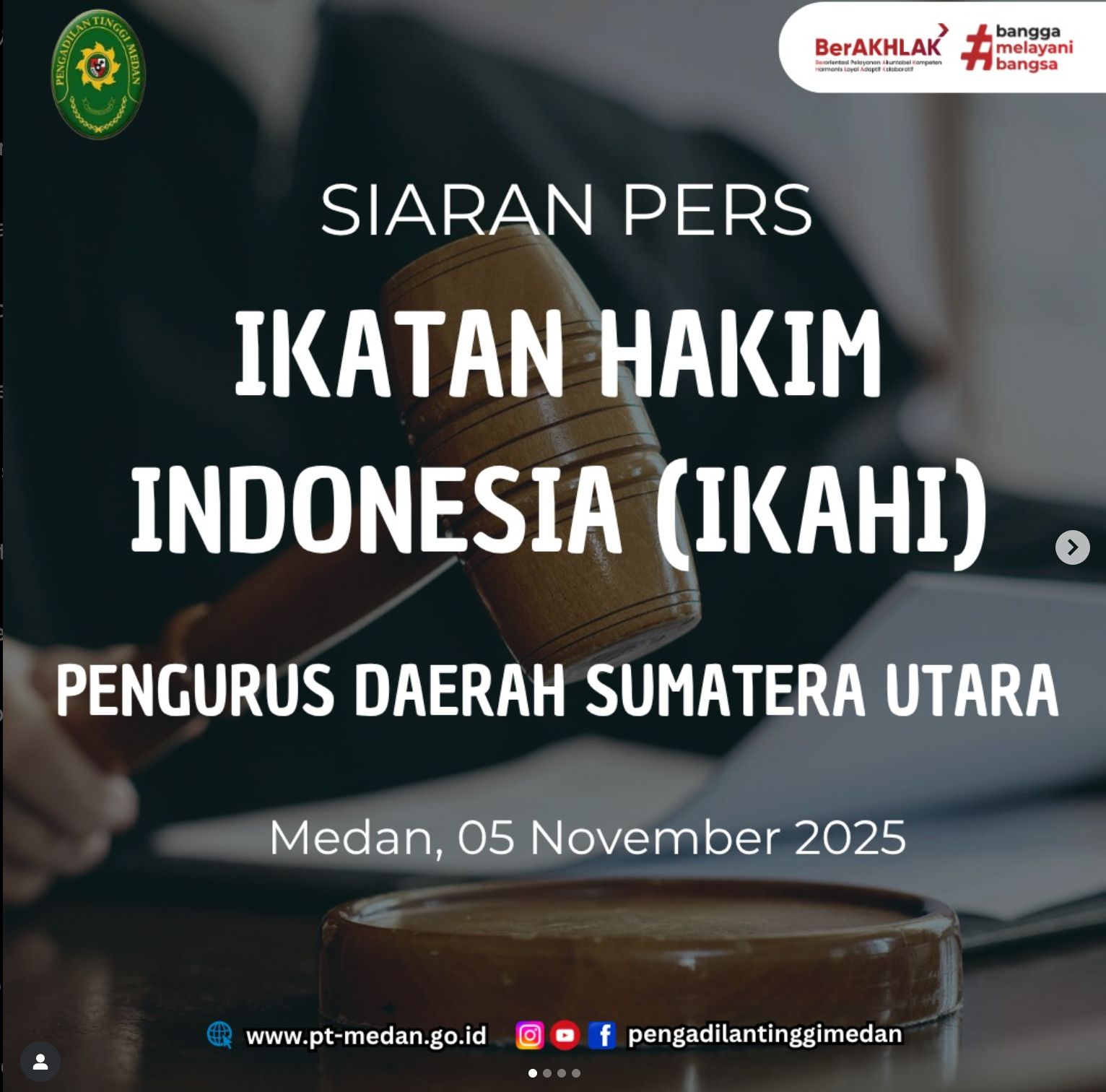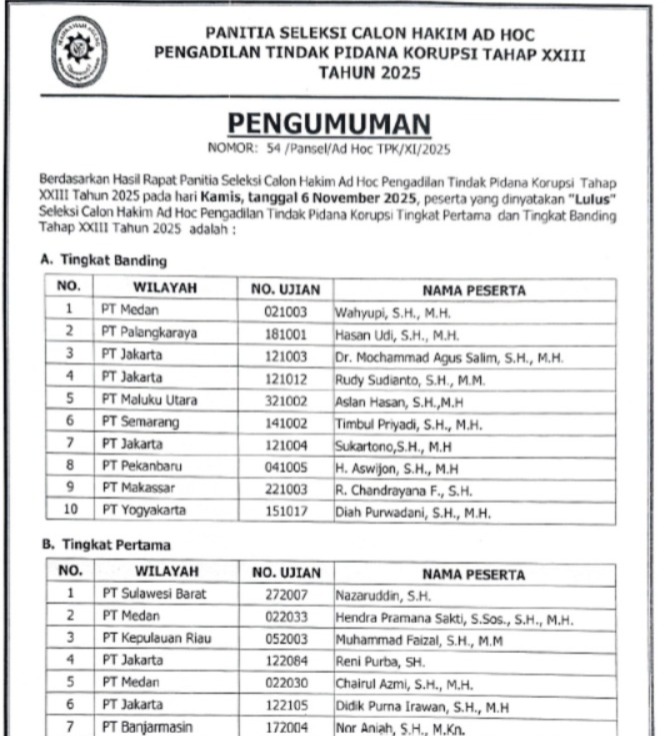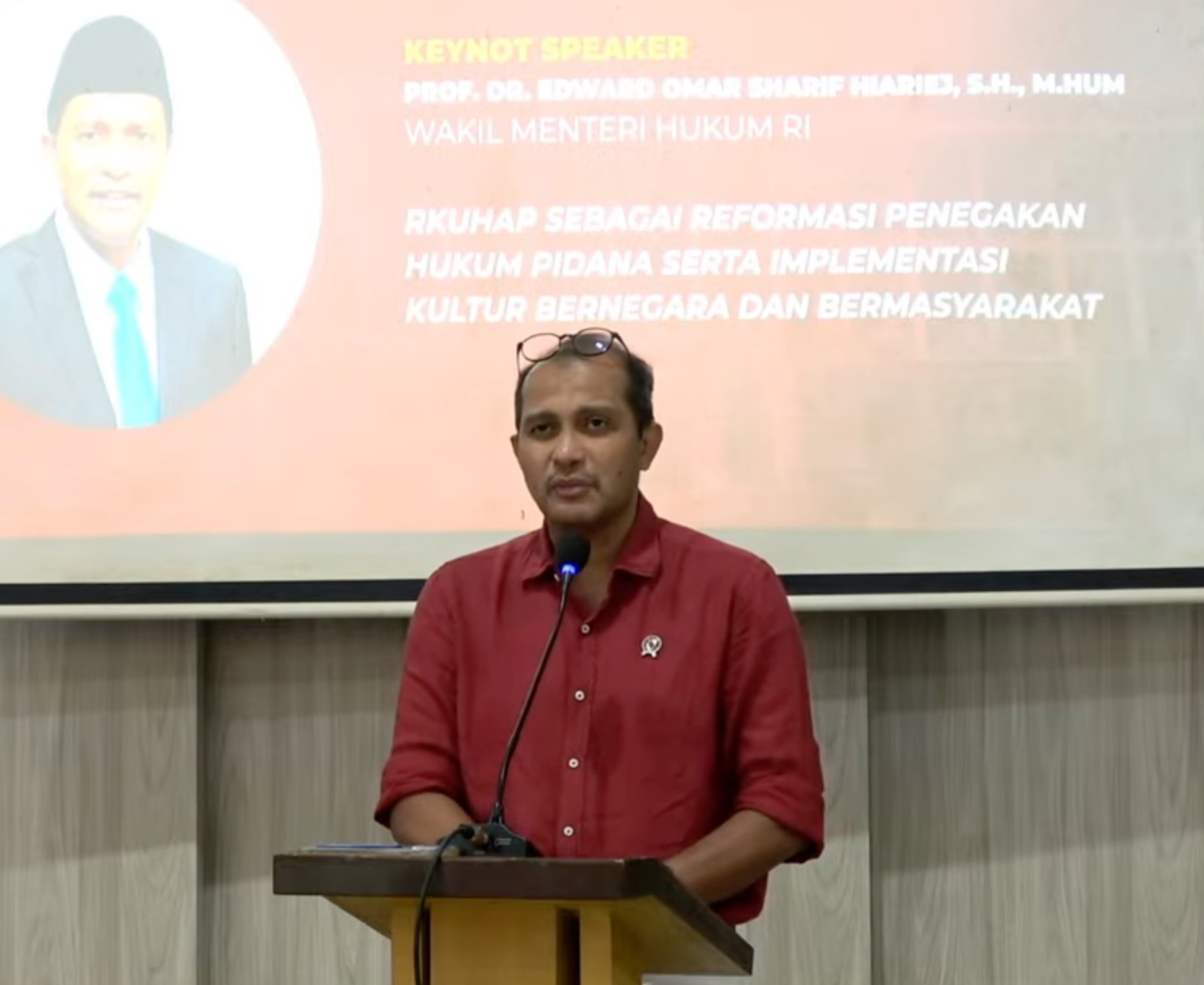Reformasi pemidanaan
melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 (KUHP Nasional) menghadirkan pembaruan
penting mengenai pedoman pemidanaan. Salah satu manifestasinya adalah pengakuan
kontribusi korban dalam tindak pidana sebagai faktor yang dapat menjadi alasan
tidak dijatuhkannya pidana penjara bagi terdakwa. Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP
Nasional mengatur bahwa “Pidana penjara sedapat mungkin tidak dijatuhkan jika
ditemukan keadaan bahwa korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan
terjadinya tindak pidana tersebut.”
Kebijakan ini dimaksudkan
untuk memperkuat prinsip proporsionalitas pemidanaan dan memberi ruang bagi hakim untuk menjatuhkan
pidana alternatif yang lebih konstruktif.
Namun demikian, penerapannya
menimbulkan pertanyaan serius: apakah kebijakan tersebut memperkuat keadilan restoratif
atau justru membuka peluang penyimpangan terhadap perlindungan korban?
Baca Juga: Family Courts And Restorative Justice For Children In Criminal Cases
Landasan
Viktimologi dan Teori Victim Precipitation
Hans von Hentig pertama
kali memperkenalkan teori bahwa ciri kepribadian dan perilaku tertentu membuat
beberapa individu lebih rentan menjadi korban. Lalu Marvin E. Wolfgang kemudian
mempopulerkan istilah victim precipitation dalam studinya bahwa
sekitar 26% kasus pembunuhan dipicu oleh korban. Akan tetapi, perkembangan
viktomologi kontemporer menjukkan bahwa teori ini kerap disalahgunakan untuk melegitimasi victim
blaming (menyalahkan korban atas kejadian yang dialaminya), khususnya dalam
kejahatan berbasis relasi kuasa seperti kekerasan seksual atau Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT).
Dalam
konteks hukum positif Indonesia, sistem peradilan pidana selama ini berfokus
pada pemulihan dan perlindungan hak korban, bukan menyudutkan. Mahkamah Agung
melalui Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman
Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum secara tegas melarang hakim
untuk menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan yang
menyalahkan, merendahkan, atau mengintimidasi perempuan.
Dengan
pergeseran paradigma ini perlu tinjauan lebih lanjut mengenai parameternya,
agar hakim tidak salah menjatuhkan putusan yang dapat merugikan korban. Oleh sebab itu, peran korban harus
dianalisis secara akurat dengan memeriksa hubungan kausal langsung, intensitas
tindakan korban, ketimpangan relasi atau kerentanan, serta konteks sosial dan
psikologis. Tanpa pendekatan menyeluruh, penerapan konsep ini berpotensi
menimbulkan ketidakadilan baru.
Ketiadaan
Kriteria dan Risiko Disparitas
Sebagai pedoman, Pasal 70 ayat
(1) huruf (h) KUHP Nasional masih menyisakan kekosongan pengaturan. Ketentuan
tersebut tidak mengatur secara rinci mengenai bentuk perilaku korban yang
dapat dikualifikasikan sebagai pendorong tindak pidana, kriteria
pembuktian keterlibatan korban dan mekanisme perlindungan hak
korban dalam proses yudisial. Dalam ayat (2) ketentuan tersebut pun hanya mengatur
ketidakberlakuan ayat (1) yakni apabila a) Tindak Pidana yang diancam dengan
pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b) Tindak Pidana yang diancam dengan
pidana minimum khusus; c) Tindak Pidana tertentu yang sangat membahayakan atau
merugikan masyarakat; atau d) Tindak Pidana yang merugikan keuangan atau perekonomian
negara. Ketiadaan aturan yang jelas ini berpotensi menimbulkan disparitas penerapan
dan ketidakpastian hukum.
Perbandingan
Hukum Internasional
Di Amerika Serikat konsep ini diatur
dalam Sentencing Guidelines for US Court §5K2.10 tentang Victim’s
Conduct (Policy Statement) bahwa jika korban berkontribusi secara
signifikan dalam memprovokasi terjadinya tindak pidana, pengadilan dapat
mengurangi pidana dengan mempertimbangkan karakteristik fisik korban,
persistensi provokasi, hingga proporsionalitas respons terdakwa. Pedoman
tersebut secara tegas dikecualikan untuk tindak pidana berbasis kekerasan
seksual, sehingga tetap menjaga perlindungan korban yang rentan. Formulasi yang
serupa penting untuk dipertimbangkan dalam konteks Indonesia.
Problematika
Penerapan Pasal 70 ayat (1) huruf (h) KUHP Nasional
Adapun dalam konteks hukum
Indonesia, penerapan pasal ini berpotensi menimbulkan beberapa tantangan,
diantaranya:
- Normalisasi pembenaran. Pelaku dapat berdalih “korban memicu tindakan” atau kerap disebut dengan victim blaming, terutama dalam kasus KDRT, kekerasan seksual, dan perundungan. Ketentuan ini menggeser pesan moral hukum pidana dengan mengevaluasi perilaku korban.
- Alat pembelaan yang eksploitatif. Advokat dapat menggunakan narasi stereotip terhadap korban untuk mengurangi pidana pelaku.
- Minimnya pedoman yudisial. Tanpa parameter baku, penilaian menjadi sangat subjektif dan rentan bias.
- Kontradiksi terhadap kerangka perlindungan korban. Berpotensi mengurangi akses korban terhadap pemulihan dan keadilan restoratif.
Rekomendasi
Penguatan Implementasi
Untuk mencegah
penyimpangan dalam penerapan, diperlukan pedoman teknis seperti perumusan Perma
atau SK KMA tentang pedoman penerapan Pasal 70 KUHP Nasional, yang memuat
setidaknya:
- Pembatasan eksplisit pengecualian pada kejahatan
berbasis gender, anak, dan relasi kuasa timpang;
- Kriteria baku dan terukur soal “mendorong” atau
“menggerakkan”, parameter objektif mengenai intensitas dan relevansi perilaku
korban terhadap terjadinya kejahatan;
- Ketentuan pembuktian kontribusi korban;
- Keterlibatan ahli psikologi forensik dalam
menilai relasi pelaku dan korban;
- Instrumen perlindungan hak korban sepanjang proses
peradilan, agar proses hukum tetap berprespektif pemulihan dan non- diskriminatif.
Penutup
Pasal 70 ayat (1) huruf
(h) KUHP Nasional memberikan peluang penting memperkuat proporsionalitas dalam
pemidanaan melalui perspektif viktimologi. Namun, tanpa pedoman penerapan yang
jelas dan terukur, konsep victim precipitation berpotensi menggeser
sebagian beban kesalahan pada korban serta bertentangan dengan prinsip
perlindungan korban, yang pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik
terhadap sistem peradilan pidana.
Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa perlindungan terhadap korban tidak dikompromikan oleh perluasan diskursus viktimologi. Kepentingan pemidanaan yang berimbang hanya dapat tercapai melalui kerangka normatif dan prosedural yang menjamin keadilan bagi semua pihak. (ikaw/ldr)
Baca Juga: Menelisik Perbedaan Pengaturan Recidive dalam KUHP Lama dan KUHP Baru
Referensi
- Eddy O.S. Hiariej, dkk. Anotasi KUHP Nasional, Rajawali
Pers, 2025
- Hans von Hentig. The
Criminal & His Victim. Yale University Press, 1948.
- Marvin E. Wolfgang. “Victim
Precipitated Criminal Homicide.” Journal of Criminal Law,
Criminology & Police Science 48(1), 1957.
- Sandra Walklate. Handbook
of Victims and Victimology. Routledge, 2011.
- UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum.
- Sentencing Guidelines
for US Court §5K2.10(https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/02/2024-31279/sentencing-guidelines-for-united-states-courts),
diakses pada 28 Oktober 2025 pukul 15.54 WITA
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI