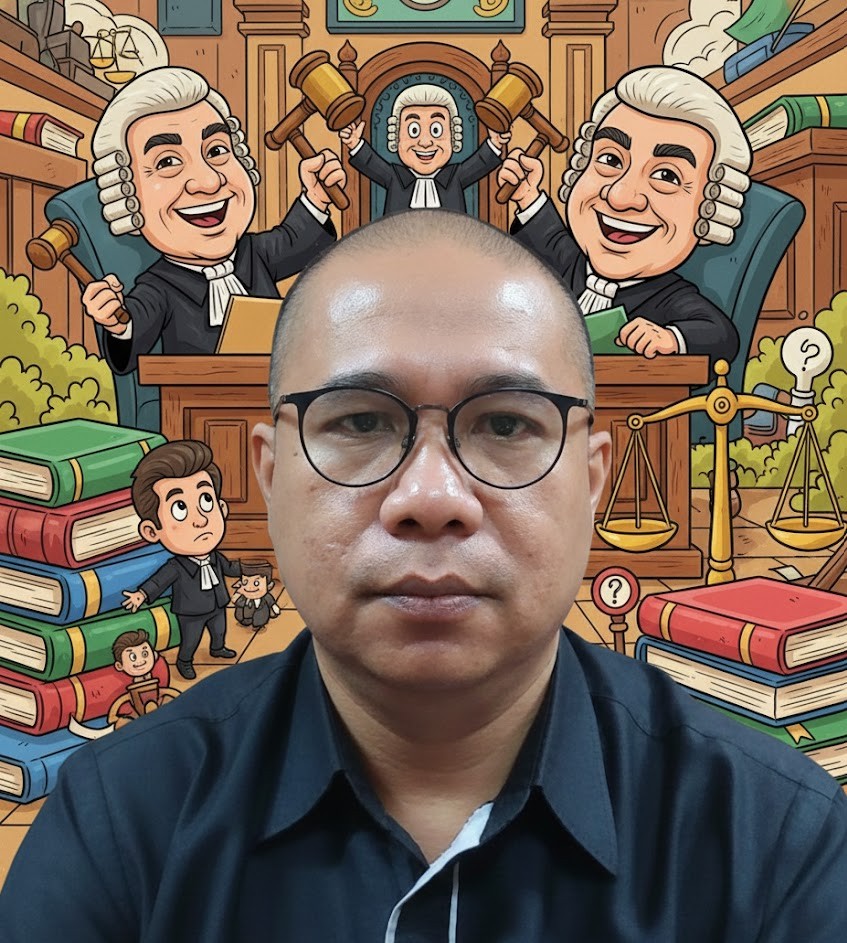Tradisi
hukum Indonesia yang mewarisi sistem Civil Law cenderung kaku dan
mengagungkan netralitas hakim. Padahal, Teori Hukum Feminis mengungkap bahwa
"netralitas" tersebut sering kali semu dan bias laki-laki. Akibatnya,
perempuan kerap menjadi korban ketidakadilan substantif dan reviktimisasi saat
berhadapan dengan hukum.
Untuk
mengatasi krisis ini, MA menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017. Aturan ini bukan
sekadar panduan teknis, melainkan sebuah revolusi cara pandang. Hakim kini
wajib menanggalkan netralitas pasif dan menggunakan perspektif gender untuk
memahami ketimpangan relasi kuasa, sejalan dengan prinsip HAM internasional.
Langkah
ini menandai pergeseran vital dari sekadar keadilan prosedural menuju keadilan
yang nyata bagi perempuan. Opini ini akan mengupas bagaimana regulasi tersebut
berupaya meruntuhkan mitos netralitas hukum di tengah tantangan budaya patriarki
yang masih kuat.
Baca Juga: Ilusi Netralitas Hakim: Ketika Independensi Formal Tak Menjamin Kebebasan Psikologis
Implementasi
Perma Nomor 3 Tahun 2017 menghadirkan dialektika filosofis serius dalam sistem
hukum positivistik Indonesia.
Pertama, muncul
ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, menuntut hakim
menyeimbangkan imparsialitas dengan diskresi untuk memulihkan ketimpangan
kuasa.
Kedua,
tantangan epistemologi pembuktian, di mana peradilan harus mendekonstruksi testimonial
injustice yang kerap menempatkan
kesaksian perempuan dalam defisit kredibilitas.
Ketiga,
urgensi pemahaman interseksionalitas agar hakim mampu membedah lapisan
penindasan yang majemuk (kelas, ras, dsb) demi menghindari elitisme hukum.
Keempat,
hambatan budaya hukum berupa resistensi internal hakim yang masih terikat nilai
patriarkis, yang mengancam konsistensi putusan. Intinya, regulasi ini menuntut
transformasi paradigma dari sekadar teknis yuridis menuju keadilan yang
responsif gender.
Analisis
mengenai epistemologi hukum baru yang berkeadilan gender dalam PERMA Nomor 3
Tahun 2017 menandai upaya fundamental untuk mendekonstruksi mitos netralitas
yang selama ini disakralkan dalam sistem peradilan modern.
Berpijak
pada kritik Feminist Legal Theory, regulasi ini menolak anggapan bahwa
hukum beroperasi di ruang hampa yang bebas nilai, melainkan mengakui bahwa
objektivitas semu sering kali hanyalah standar laki-laki yang dipaksakan.
Sebagai
solusinya, Perma ini mengadopsi pendekatan Standpoint Theory yang menegaskan
bahwa objektivitas hukum yang kuat justru hanya dapat dicapai ketika Hakim berani
menanggalkan posisi pasif dan secara aktif menyelami perspektif kelompok
rentan.
Pergeseran
ini menuntut Hakim untuk mempraktikkan empati yudisial, yakni sebuah kemampuan
kognitif untuk memahami realitas ketimpangan tanpa terjebak pada simpati emosional,
sekaligus berfungsi sebagai koreksi tegas terhadap praktik judicial
stereotyping yang kerap menyudutkan perempuan berdasarkan asumsi budaya patriarki
yang bias.
Pondasi
filosofis tersebut diperkuat secara signifikan dengan pengadopsian konsep relasi
kuasa yang membedah anatomi penindasan di ruang sidang. Hakim didorong untuk
memiliki kepekaan sosiologis yang tajam dalam mengidentifikasi bagaimana
ketimpangan status ekonomi, sosial, pendidikan, atau pengetahuan dapat
menciptakan kondisi ketidakberdayaan yang nyata, meskipun tidak selalu disertai
dengan kekerasan fisik.
Dalam
tatanan praktis, pemahaman mendalam ini memungkinkan hakim untuk menilai ketiadaan
perlawanan korban perkosaan, seperti kondisi kelumpuhan sementara atau freeze
response, sebagai akibat logis dari dominasi pelaku, bukan sebagai bentuk
persetujuan sukarela.
Lebih
jauh lagi, regulasi ini berupaya memulihkan ketidakadilan epistemik dengan
memberikan bobot kredibilitas yang layak pada kesaksian perempuan yang selama
ini sering mengalami defisit kepercayaan atau testimonial injustice,
serta menyediakan kosa kata hukum baru untuk menamai pengalaman diskriminasi
yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam bahasa hukum formal, sebuah langkah
yang dikenal sebagai pemulihan hermeneutik.
Di sisi
lain, penerapan prinsip negara yang responsif melalui lensa Vulnerability
Theory menegaskan bahwa kenetralan negara tidak boleh lagi diartikan
sebagai sikap pasif, melainkan sebuah kewajiban etis dan yuridis untuk hadir
secara afirmatif.
Negara,
melalui perpanjangan tangan hakim, harus secara aktif menyeimbangkan kerentanan
yang terdistribusi tidak merata akibat struktur sosial yang timpang, memastikan
bahwa mereka yang "terlempar" dalam posisi lemah mendapatkan pijakan
yang setara di hadapan hukum.
Kendati
demikian, analisis kritis yang lebih tajam menyingkap celah epistimologis dalam
regulasi ini, terutama terkait kompleksitas irisan penindasan atau
interseksionalitas. Definisi gender yang diadopsi hukum Indonesia masih
cenderung terpaku pada binerisme biologis, sehingga gagal memotret realitas
kelompok minoritas seksual atau perempuan adat miskin yang mengalami penindasan
berlapis. Bagi mereka, perlindungan hukum sering kali menjadi elitis dan sulit
dijangkau karena identitas mereka tidak sepenuhnya "terbaca" oleh
teks regulasi yang kaku.
Tantangan
yang lebih pragmatis namun krusial justru terletak pada realitas implementasi
di lapangan yang memperlihatkan disparitas mencolok antara visi MA dengan
praktik di pengadilan tingkat pertama.
Meskipun
MA secara konsisten menunjukkan tren putusan yang progresif dan korektif di
tingkat kasasi, sering kali membatalkan putusan yang bias gender, resistensi
budaya hukum di level judex facti masih sangat tangguh.
Di
tingkat akar rumput ini, banyak hakim yang belum sepenuhnya mampu melepaskan
diri dari nilai-nilai konservatif dan patriarkis yang bersumber dari
interpretasi tekstual agama atau adat, sehingga masih kerap menyalahkan korban
atau meremehkan dampak psikologis kekerasan domestik.
Kondisi
paradoksal ini menempatkan Indonesia pada posisi yang unik sekaligus dinamis
dalam peta hukum global. Secara normatif, Indonesia telah sejajar dengan
negara-negara progresif seperti Meksiko yang memiliki protokol peradilan
canggih, namun secara sosiologis, peradilan Indonesia masih harus bertarung
keras melawan inersia budaya internal demi memastikan bahwa keadilan substantif
benar-benar mewujud dalam setiap palu yang diketuk, dan tidak berakhir sekadar
sebagai retorika indah di atas kertas kebijakan.
Perma Nomor
3 Tahun 2017 adalah sebuah magnum opus dalam reformasi hukum di
Indonesia. Ia merepresentasikan keberanian Mahkamah Agung untuk melakukan
"pembangkangan" terhadap tradisi positivisme kaku demi mencapai keadilan
substantif.
Melalui
kacamata Feminist Legal Theory, Perma ini memvalidasi pandangan
bahwa hukum harus berpihak pada yang lemah untuk menjadi adil. Konsep
"Relasi Kuasa" dan larangan "Stereotip Gender" adalah
instrumen epistemologis yang ampuh untuk membongkar bias yang selama ini
tersembunyi di balik palu hakim.
Namun,
revolusi ini belum selesai. Teks yang progresif tidak akan bermakna jika
dibacakan oleh hakim yang masih berpikir konservatif. Kesimpulan utama dari
analisis ini adalah bahwa perubahan hukum (legal reform) harus
diikuti oleh perubahan budaya hukum (legal culture reform). Hakim
Indonesia harus bertransformasi dari sekadar corong undang-undang menjadi social
engineer yang sadar gender.
Ke
depan, konsep Pemulihan Epistemik (Epistemic Reparation) harus
menjadi tujuan akhir dari penerapan Perma ini. Putusan hakim tidak boleh hanya
menghukum pelaku, tetapi juga harus memulihkan narasi kebenaran korban yang
selama ini dirusak oleh stigma. Hakim harus menggunakan putusannya untuk
menulis ulang sejarah penindasan perempuan, memberikan pengakuan resmi bahwa
pengalaman mereka nyata, valid, dan bernilai di mata hukum.
Baca Juga: Part 3. Plea Bergain: Dekonstruksi Paradigma Berbasis Kesepakatan, Prosedural & Pembuktian
Rekomendasi
strategis dalam opini ini meliputi: integrasi materi Feminist
Jurisprudence dan Critical Legal Studies dalam
kurikulum pendidikan dan pelatihan Hakim, penguatan mekanisme eksaminasi publik
terhadap putusan-putusan yang bias gender sebagai bentuk kontrol sosial, perluasan
tafsir "Perempuan" dalam Perma untuk mencakup kerentanan
interseksional yang lebih luas, dan institusionalisasi prinsip "Hakim
Aktif" dalam hukum acara perdata nasional yang baru untuk memberikan
landasan yang lebih kuat bagi intervensi yudisial demi keadilan substantif.
Perma Nomor 3 Tahun 2017 adalah pelita di lorong gelap peradilan. Sudah menjadi tugas bersama, akademisi, praktisi, dan masyarakat sipil, untuk menjaga agar pelita ini tidak padam tertiup angin resistensi, melainkan semakin terang menyinari jalan menuju Indonesia yang berkeadilan gender. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI