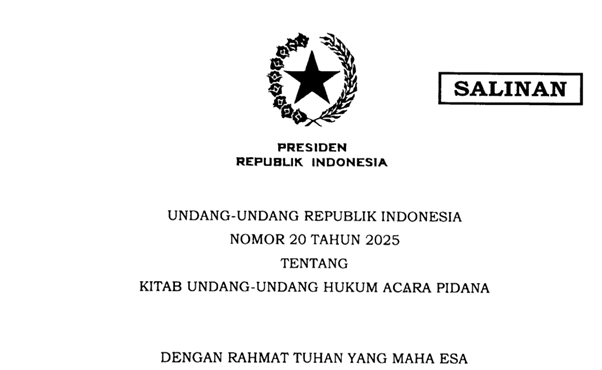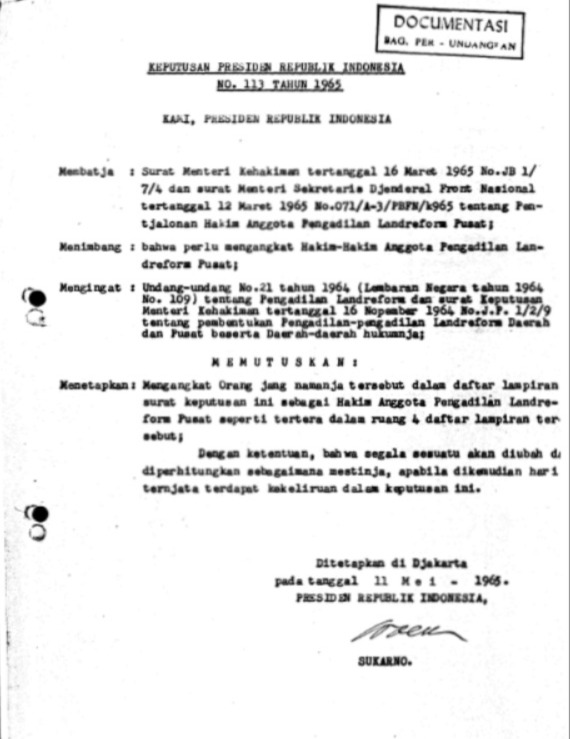Pembangunan
hukum nasional Indonesia bersemayam dalam dualitas
antara kepastian hukum (ius constitutum) dan keadilan sosial (ius
constituendum). Dalam konteks agraria, polaritas ini direpresentasikan
secara distingtif oleh dua agenda. Di satu kutub, berdiri rezim Penataan Ruang
sebagai instrumen ius constitutum yang dirancang untuk mewujudkan
pemanfaatan ruang yang tertib dan berkelanjutan. Fondasinya adalah Rencana Tata
Ruang (RTR), produk hukum yang diposisikan sebagai referensi imperatif. Untuk
menjamin ketertiban ini, rezim tata ruang dibekali aparatus sanksi
komprehensif, yang secara tegas memisahkan hak kepemilikan
(property right) dari hak membangun (development right).
Di kutub diametral, bersemayam spirit
Reforma Agraria (RA/land reform)
sebagai manifestasi ius constituendum yang berfokus pada keadilan dan
kesejahteraan. Dalam kerangka ini, Penataan Aset (legalisasi aset) bukanlah tujuan akhir, melainkan instrumen modal
dasar untuk menggapai tujuan luhur, yakni Penataan Akses. Penataan Akses didesain secara eksplisit
untuk memberdayakan subjek RA agar menjadi produktif. Ironisnya, kedua agenda
strategis ini seringkali berjalan dalam silo regulasi yang terpisah, membawa
imperatif teleologis yang bertentangan pada sebidang tanah yang sama. Rezim
tata ruang menuntut kepatuhan statis, sementara RA menuntut produktivitas
dinamis. Antinomi norma ini bermuara di ruang sidang, menempatkan hakim dalam
dilema yuridis antara kepastian hukum positivistik
dan keadilan substantif.
Permasalahan
hukum fundamental yang mengemuka adalah bagaimana hakim, dalam kapasitasnya
sebagai corong keadilan, harus memosisikan diri ketika mengadili
sengketa di mana seorang subjek penerima Redistribusi Tanah, yang didorong oleh mandat negara untuk
produktif melalui Penataan
Akses, dihadapkan pada ancaman sanksi administratif maupun pidana akibat aktivitas produktifnya (misalnya,
mendirikan unit usaha skala kecil) dianggap melanggar ius constitutum
berupa RTR yang berlaku, seperti zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B).
Baca Juga: Menelisik Eksistensi Sanksi Tindakan dalam KUHP Nasional
Apakah penegakan sanksi tata ruang secara
kaku demi kepastian hukum dapat dibenarkan, sekalipun tindakan tersebut secara
simultan mendelegitimasi dan menggagalkan esensi program Penataan Akses RA?
Sebaliknya,
apakah spirit keadilan sosial RA dapat serta merta menganulir kekuatan mengikat RTR dan memberikan imunitas hukum bagi subjeknya? Di sinilah letak
dialektika yuridis yang mendesak untuk ditemukan titik temunya.
Analisis
rigiditas ius constitutum dalam rezim penataan ruang menunjukkan
paradigma pengendalian mutlak. Dokumen tata ruang memanifestasikan kehendak negara dalam
alokasi spasial, di mana setiap jengkal tanah
ditentukan peruntukannya. Instrumen sentralnya
adalah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). KKPR menjadi tiket yuridis bagi pemegang property right
untuk memperoleh development right. Tanpa
KKPR, pemanfaatan ruang, meski di atas tanah hak milik, adalah ilegalitas.
Konsekuensinya, regulasi penataan ruang menggariskan
sanksi berlapis, dari administratif hingga pidana. Paradigma ini relevan dalam kawasan lindung seperti LP2B.
Secara tekstual, pendirian bangunan non pertanian di
zona LP2B oleh subjek RA adalah pelanggaran yang memenuhi unsur sanksi.
Pada kutub
diametral, analisis teleologis ius constituendum dalam kerangka Reforma
Agraria (RA) menyajikan imperatif berbeda. Program ini tidak berhenti pada Penataan Aset, melainkan membebankan positive
obligation (kewajiban positif) negara untuk menjamin suksesnya Penataan Akses. Arahan kebijakan ini menuntut agar subjek
penerima manfaat difasilitasi, melalui modal, bibit, pelatihan, untuk mencapai
produktivitas lahan lebih tinggi. Sertifikat hak
atas tanah didesain sebagai collateral bankabel, memungkinkannya
dibebani Hak Tanggungan guna mengakses modal usaha.
Di sinilah antinomi norma (benturan
kaidah) mengemuka. Aktivitas produktif yang didorong
mandat Reforma Agraria dihadapkan pada kewajiban imperatif Pemerintah Daerah
sebagai penegak ius constitutum penataan ruang. Pemerintah Daerah wajib menertibkan pemanfaatan ruang yang
tidak selaras dengan RTR. Konsekuensinya,
wirausaha yang sama, implementasi Penataan Akses, secara yuridis formal dapat
dikualifikasikan sebagai pelanggaran tata ruang
karena tidak sesuai zonasi. Pelanggaran ini,
dalam optik rezim tata ruang, membuka ruang sanksi administratif hingga pidana.
Subjek RA, esensinya kelompok rentan,
terperangkap dalam kontradiksi kebijakan negara: satu instrumen negara
memberi mandat pemberdayaan, sementara instrumen lainnya menyediakan aparatus
sanksi atas pelaksanaan mandat tersebut.
Hakim yang dihadapkan pada antinomi ini
tidak dapat berlindung di balik adagium lex dura sed tamen scripta
(undang-undang itu keras, tetapi sudah tertulis). Menerapkan sanksi tata ruang
secara membabi buta berarti hakim telah mengingkari tujuan sosial dari
penerbitan sertipikat RA. Ini adalah praktik summum ius, summa injuria, keadilan
tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi. Di sinilah hakim wajib melakukan rechtsvinding,
bergerak dari positivisme yuridis menuju realisme hukum yang sosiologis.
Pertama, hakim harus menguji proporsionalitas pelanggaran. Apakah
pelanggaran yang dilakukan subjek RA bersifat substansial dan merusak ekosistem
(misalnya, membangun pabrik di zona lindung), ataukah bersifat subsisten dan
produktif (membangun warung untuk menopang hidup)? Skala pelanggaran harus
menjadi pertimbangan utama.
Kedua, hakim wajib menginterogasi penerapan asas ultimum remedium
(pidana sebagai upaya terakhir). Dokumen tata ruang
sendiri menyebutkan sanksi pidana, namun juga
mengutamakan sanksi administratif. Apakah
Pemerintah Daerah telah menempuh jalur pembinaan terlebih dahulu,
sebagaimana diamanatkan pula oleh rezim penataan ruang? Jika pembinaan
tidak dilakukan, penjatuhan sanksi adalah sebuah cacat prosedural.
Ketiga, hakim dapat
menggali fakta koordinasi kelembagaan. Kerangka kerja Penataan Akses itu
sendiri secara normatif mengamanatkan adanya 'Hubungan Kelembagaan' antar pemangku
kepentingan yang menuntut sinkronisasi kebijakan. Pada saat yang sama, regulasi
penataan ruang menegaskan peran sentral Kementerian ATR/BPN, instansi yang
notabene juga menjadi pelaksana Reforma Agraria, dalam proses pembahasan lintas
sektor dan penerbitan persetujuan substansi RTR. Hakim dapat mempertanyakan
apakah dalam proses penyusunan RTR tersebut, Pemerintah Daerah telah secara ex
officio mengintegrasikan dan memetakan lokasi-lokasi obyek Reforma Agraria
sebagai zona dengan perlakuan khusus yang mengakomodasi kebutuhan produktif Penataan
Akses.
Putusan hakim yang adil bukanlah yang
memenangkan satu rezim hukum atas rezim lainnya. Putusan yang progresif adalah
yang mampu memaksa kedua rezim tersebut untuk berdamai. Hakim dapat, misalnya,
menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran tata ruang secara de jure,
namun menyatakan sanksi (terutama pidana atau pembongkaran) tidak proporsional
dan tidak dapat dieksekusi (unexecutable), mengingat adanya mandat
kontradiktif dari program Penataan Akses.
Sebagai
gantinya, putusan dapat bersifat korektif: memerintahkan Pemerintah Daerah
untuk melakukan pembinaan dan memfasilitasi subjek RA tersebut untuk mendapatkan KKPR melalui mekanisme dispensasi atau memerintahkan dilakukannya revisi
RTR parsial yang mengakomodasi kebutuhan produktif skala kecil bagi subjek RA.
Dialektika
antara ius constitutum yang diwakili oleh kepastian hukum sanksi tata
ruang dan ius
constituendum yang diwakili oleh keadilan sosial Penataan Akses Reforma Agraria menuntut hakim untuk
tidak sekadar menjadi bouche de la loi (mulut undang-undang). Titik temu
antara keduanya tidak terletak pada penerapan teks hukum secara literal,
melainkan pada interpretasi teleologis dan uji proporsionalitas. Hakim harus
memosisikan diri sebagai penjaga harmoni antara ketertiban dan keadilan.
Putusan yang dihasilkan harus mampu mengakui validitas RTR namun sekaligus melindungi hak subsisten dan produktif subjek RA yang lahir dari mandat negara. Dengan demikian, putusan hakim tidak hanya menyelesaikan sengketa in concreto, tetapi juga berkontribusi pada sinkronisasi kebijakan nasional, memastikan bahwa kepastian hukum tidak menindas keadilan sosial, dan program kesejahteraan tidak menjelma menjadi jebakan yuridis bagi rakyat kecil. (ldr)
Baca Juga: Mengenal Jenis Sanksi Hukum di Jawa Abad ke-18, dari Cambuk hingga Dibuang
Penulis Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. adalah Hakim PN Serang
Tulisan ini pendapat pribadi penulis yang tidak mewakili pendapat lembaga.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI