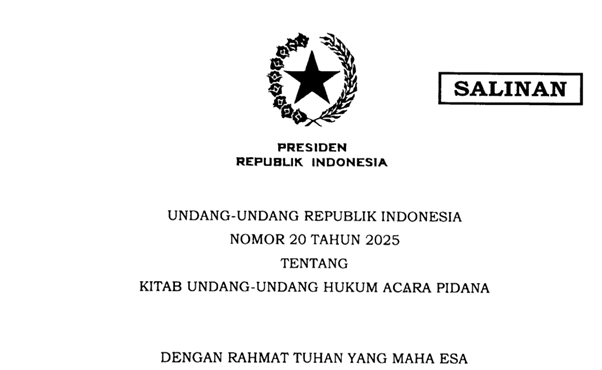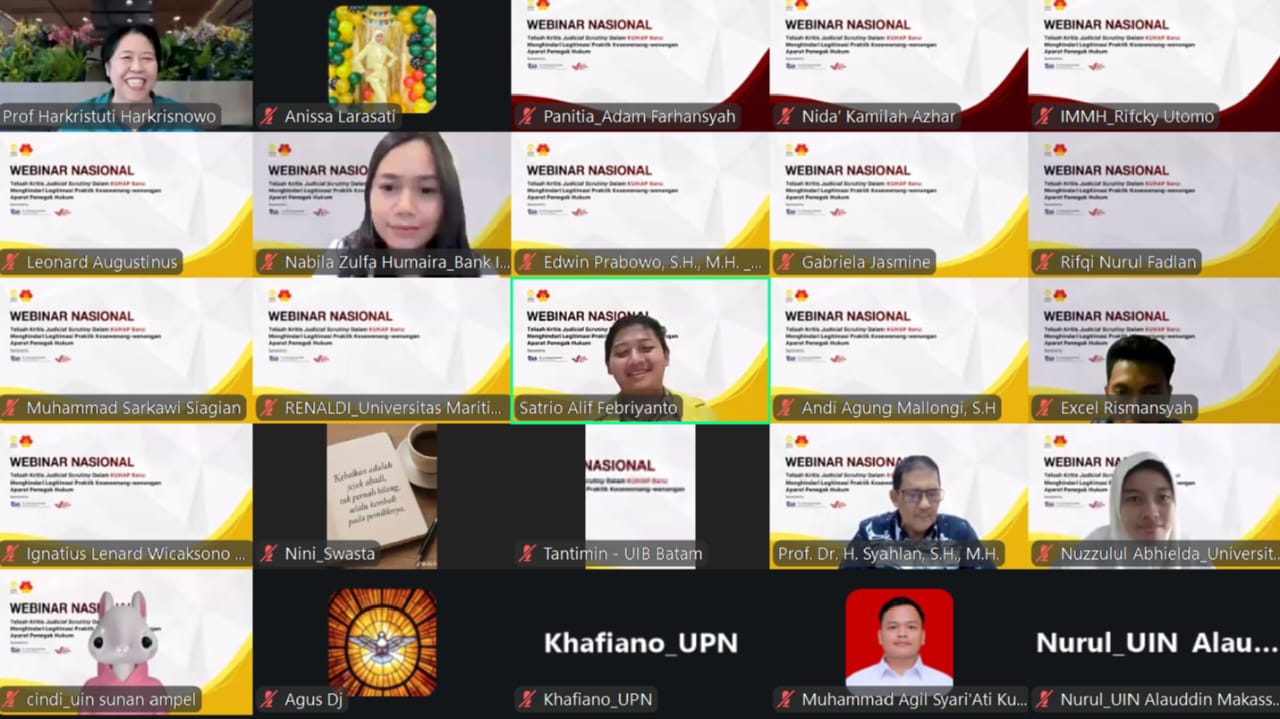Bab XXX UU No. 1/2023 (“KUHP Nasional”) mengatur tindak pidana jabatan sebagai wujud perlindungan terhadap akuntabilitas aparatur negara. Pasal 529–539 KUHP memberikan ketentuan rinci mengenai larangan prosedur pelaksanaan upaya paksa, meliputi penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, yang wajib dilaksanakan berdasarkan alasan hukum yang sah, proporsional, serta melindungi hak dasar tersangka.
Ketentuan ini membuka ruang bagi pengadilan untuk melakukan judicial scrutiny, yaitu pengawasan substantif terhadap tindakan aparat penegak hukum sejak tahap penyidikan hingga penuntutan. Pengawasan ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, memastikan due process of law, dan menjaga keseimbangan kekuasaan (checks and balances) antar lembaga penegak hukum.
Perbandingan Konsep Pengawasan Pengadilan Judicial Scrutiny di berbagai Negara
Baca Juga: Menjamin Independensi Hakim: Urgensi Pengaturan Gaji dalam UUD 1945
Amerika Serikat menggunakan konsep pengawasan peradilan yang dikembangkan melalui Habeas Corpus Act. Hebeas Corpus Act sendiri lahir atas adanya Miranda Rules yang dikenal atas kasus Miranda v. Arizona pada tahun 1966 Dalam kasus tersebut, Miranda dituduh melakukan penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang remaja yang memiliki keterbelakangan mental.
Selama dua jam diperiksa oleh penyidik, akhirnya ia mengaku dan kasus ini kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung AS, dan pada putusannya MA memutuskan bahwa pengakuan Miranda diperoleh tanpa adanya perlindungan terhadap hak-haknya. Inti dari putusan tersebut adalah bahwa pengakuan tersangka tidak boleh diperoleh melalui paksaan, kekerasan, atau tekanan. [1]
Proses koreksi atas upaya paksa di Amerika tersebut diajukan ke pengadilan yang dipimpin oleh hakim pemeriksa pendahuluan atau biasa dikenal sebagai Magistrat, Magistrat biasanya sudah terlibat sejak proses sebelum persidangan utama dijalankan (pre-trial) mulai dari preliminary hearing, arraignment, dan pretrial confrence. [2]
Preliminary hearing merupakan dengar pendapat antara polisi, jaksa dan Magistrat dalam tahap ini Magistrat meneliti apakah upaya paksa yang dilakukan penyidik tersebut didasarkan pada alasan-alasan yang sah sehingga penelitian tersebut tidak hanya sebatas formalitas dan menyentuh materi alasan dilakukannya upaya paksa tersebut kepada tersangka, dalam hal terdapat keraguan mengenai hal upaya paksa tersebut maka perkara dapat dihentikan sebelum memasuki proses persidangan. [3]
Selanjutnya negara-negara di Eropa yang tidak menerapkan Habeas Corpus Act, mereka juga menekankan pentingnya pengawasan pengadilan terhadap upaya paksa yang merampas hak seseorang. Di Perancis, hakim pemeriksa pendahuluannya dikenal dengan istilah Judge d’Instruction dan Procureur, sedangkan di Indonesia konsep pengawasan ini melalui lembaga Praperadilan.
Praperadilan berfungsi sebagai instrumen bagi tersangka maupun pihak lain untuk menilai keabsahan suatu tindakan upaya paksa. Namun, karakter pemeriksaan praperadilan yang berlangsung cepat seringkali membatasi ruang bagi tersangka dalam menyusun bukti-bukti. Padahal, sebagian besar perkara pidana di Indonesia melibatkan penggunaan upaya paksa, kondisi tersangka yang terpisah dari dunia luar membuatnya sulit menggunakan hak-haknya. Bahkan, meskipun telah mengajukan permohonan praperadilan, pemeriksaan dapat terhenti di tengah jalan ketika perkara telah dilimpahkan dan diregister di Pengadilan.
Dapatkah Pengaturan Tindak Pidana atas Jabatan sebagai Judicial Scrutiny?
KUHP Nasional mengatur mengenai Tindak Pidana Jabatan, khususnya pada bagian kedua dalam Pasal 529-539 mengatur mengenai tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan, dimana dalam ketentuan tersebut mengatur terhadap pejabat dalam perkara pidana yang melakukan upaya paksa berlebih dapat dipidana. Lebih lanjut dalam konteks ini penyidik dalam ranah upaya melaksanakan hukum acara pidana dapat dikenai hukuman pidana apabila melakukan penggeledahan, penyitaan, serta tidak memberitahukan kepada penyidik atas perampasan kemerdakaan bagi diri Terdakwa.
Ketentuan Tindak Pidana atas Jabatan tersebut bukanlah hal yang baru diterapkan, mengingat dalam Bab 28 UU No. 1/1946 (“KUHP Lama”) juga mengatur mengenai tindak pidana paksaan dan tindak pidana penyiksaan dalam rangka penegakan hukum pidana selain itu KUHP Lama juga memberikan ancaman terhadap upaya penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum acara.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa norma mengenai Tindak Pidana Jabatan dalam KUHP Nasional bukanlah suatu kebaharuan ataupun penyempurnaan mengingat dalam praktik ketentuan tersebut tidak pernah diterapkan satu kalipun dalam hal tersangka maupun keluarganya melaporkan kepada pihak kepolisian yang kedapatan melakukan tidakan abusive kepada tersangka.
Bahwa koreksi atas tindakan upaya paksa dalam hukum acara pidana menurut penulis terdapat 2 mekanisme, yakni:
Pertama, melalui mekanisme Praperadilan, dan Kedua, melalui pelaporan atas Tindak Pidana Jabatan dengan pasal-pasal yang diduga dilanggar tersebut. Adapun mekanisme Praperadilan dalam praktiknya menemui kendala sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dimana pemeriksaan Praperadilan hanya mencakup aspek formalitas atau keabsahan atas suatu upaya paksa, sedangkan pengusutan tindak pidana jabatan belum pernah terjadi di Indonesia, mengingat pelanggaran atas upaya paksa yang dialami oleh tersangka harus dilaporkan kepada tersangka ke pihak kepolisian sedangkan yang menjadi ojek pemeriksaan disini adalah penyidik yang sudah barang tentu merupakan pihak anggota polri.
Mengenai tata cara pemeriksa anggota Polri yang melakukan tindak pidana dapat merujuk dalam ketentuan PP No. 3/2023. Pada prinsipnya, proses peradilan pidana bagi anggota kepolisian secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum, dalam Pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana di wilayahnya dapat disidik oleh kesatuan yang lebih atas dari kesatuan ia bertugas.
Kemudian untuk penuntutan dilakukan di lingkungan peradilan umum oleh penuntut umum sesuai peraturan yang berlaku. Begitu pula dengan pemeriksaan sidang pengadilan oleh hakim peradilan umum. Selanjutnya, jika sudah didakwa dan dijatuhi vonis, pembinaan narapidana anggota kepolisian dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan.
Anggota polisi yang melakukan tindak pidana diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah dan menurut pertimbangan pejabat berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam kepolisian melalui sidang Komisi Etik Profesi Polri yaitu komisi yang dibentuk di lingkungan Polri berdasarkan Perkap No. 7/2022. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh tersangka anggota Polri dilakukan sendiri oleh Polri sehingga proses penegakan hukum yang berorientasi pada kepentingan due process of law, tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Kesimpulan
Pasal 529–539 KUHP Nasional yang mengatur tindak pidana jabatan, khususnya terkait penyalahgunaan upaya paksa merupakan norma lama yang diwariskan dari KUHP kolonial. Meskipun secara materi ketentuan ini memberikan dasar untuk menghukum aparat penegak hukum yang menyalahgunakan wewenang, dalam praktiknya ketentuan ini belum pernah diterapkan sehingga praktik cenderung mengupayakan permohonan Praperadilan.
Namun kendala yang didapati pemeriksaan Praperadilan ini bersifat formalistik, dan sifatnya relatif cepat serta tidak diakomodirnya akses bagi tersangka terhadap bukti sehingga permohonan cenderung ditolak. Selain itu mekanisme pelaporan atas Tindak Pidana Jabatan yang masih mengadopsi norma warisan dari KUHP Lama yang tidak pernah sekalipun muncul hingga KUHP Nasional disahkan, sehingga apabila Indonesia tidak berkeinginan menerapkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan sudah barang tentu aturan khusus mengenai Tindak Pidana Jabatan perlu dibuat agar tidak menjadi norma kosong dan wujud keseimbangan pembagian kekuasaan (checks and balances) antar lembaga penegak hukum berjalan sebagaimana mestinya. (ypy, ldr)
Referensi
(1) Sustira Dirga, dkk, Judicial Scrutiny Melalui Hakim Pemeriksa Pendahuluan dalam RKUHAP, ICJR, 2022, hlm. 5.
(2) Daniel E. Hall, Criminal Law and Procedure, Fifth Edition, New York: Maxwell, 2009, hlm. 446-447.
Baca Juga: Judicial Scrutiny sebagai Upaya Reintegrasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu
(3) Ibid.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI