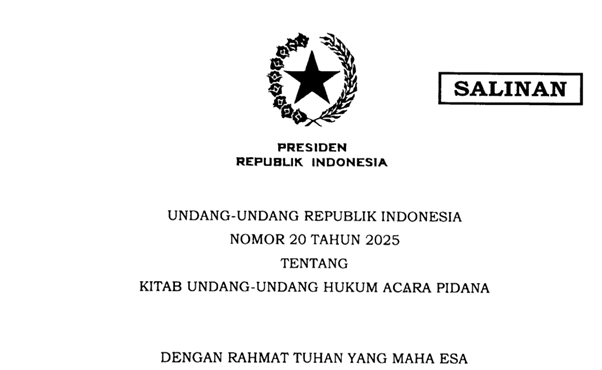Bagi masyarakat banyak, peristiwa mobil ditarik leasing di tengah jalan sangat sering terjadi, bahkan jadi hal yang dianggap wajar. Hal ini terjadi karena pihak perusahaan pembiayaan sebagai Kreditor berpegang pada Pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menegaskan bahwa sertifikat fidusia memiliki kekuatan eksekutorial langsung sama dengan putusan pengadilan yang inkracht.
Padahal, sejak Putusan No. 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan No. 2/PUU-XIX/2021 diucapkan oleh Mahkamah Konstitusi, praktik penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan tidak lagi sesederhana “kredit macet, mobil ditarik”.
Dua putusan Mahkamah Konstitusi ini telah merekonstruksikan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Mahkamah Konstitusi menegaskan, sertifikat jaminan fidusia memang memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi pelaksanaannya tidak bisa dilakukan secara sepihak. Eksekusi sah bila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan kendaraan secara sukarela. Jika tidak, kreditur harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri.
Baca Juga: Perlindungan Hukum Penyewa Benda Bergerak Objek Jaminan Fidusia
Dalam konteks ini, eksekusi jaminan fidusia yang selama ini dianggap perkara perdata, kini bisa berimplikasi pidana, bila dijalankan dengan cara paksa dan diluar koridor hukum.
Dari Wanprestasi ke Pidana
Dalam hukum perdata, jaminan fidusia adalah perjanjian tambahan (accessoir) dari perjanjian pokok utang piutang. Hubungan antara kreditor dengan debitor adalah murni kontraktual dan asas pacta sunt servanda menjadi dasar bahwa debitur wajib melunasi utangnya, dan kreditur berhak mengeksekusi jaminan bila terjadi wanprestasi.
Namun, UU Jaminan Fidusia memuat klausul khusus yakni kreditor memiliki hak menjual sendiri barang jaminan jika debitor wanprestasi. Akibatnya kreditor dapat menafsirkan sendiri kapan debitor wanprestasi.
Praktik ini yang dapat memunculkan kesewenangan-wenangan, begitu cicilan macet sebulan, kreditor dengan menggunakan jasa debt collector turun tangan, terkadang dengan nada keras dan kasar bahkan sampai dengan tindakan memaksa dibarengi ancaman kekerasan. Barang jaminan pun akhirnya dirampas tanpa ijin, kadang di rumah dan tak jarang di jalanan.
Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/2019, hak menentukan siapa dan kapan telah terjadi wanprestasi diserahkan kepada otoritas peradilan. Hal ini membuat debitor justru berhak mempertahankan barang jaminan sampai ada putusan pengadilan. Artinya, jika ada pihak yang memaksa mengambil barang jaminan tanpa putusan pengadilan adalah perbuatan pidana.
Potensi pidana bagi kreditor bisa saja terjadi ketika eksekusi dilakukan tanpa alasan yang sah, misalnya penarikan dilakukan dengan cara paksa, mengancam atau merampas barang dijalan maka perbuatan tersebut tidak lagi perkara perdata tetapi sudah dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Berikut beberapa pasal yang dapat digunakan antara lain:
- Pasal 368 KUHP - Pasal 482 KUHP Nasional : Pemerasan – jika penarikan dilakukan dengan ancaman kekerasan untuk memaksa debitor menyerahkan barang.
- Pasal 365 KUHP – Pasal 479 KUHP Nasional : Pencurian dengan kekerasan – jika barang diambil paksa tanpa seijin debitor.
- Pasal 406 KUHP – Pasal 521 KUHP Nasional : Perusakan barang – jika terjadi kerusakan saat penarikan barang.
Inilah yang menjadi titik singgungnya. Ketika kreditor melakukan penarikan tanpa ada pengakuan wanprestasi dari debitor, apalagi disertai ancaman atau kekerasan maka perbuatan tersebut bergeser dari ranah perdata ke pidana.
Dari Lex Certa ke Lex Humana
Perubahan tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap eksekusi jaminan fidusia dapat diartikan sebagai penegasan prinsip konstitusionalitas dalam hukum privat. Hukum perdata tidak lagi semata-mata menegakan kepastian (lex certa) bagi kreditor, tetapi juga kemanusiaan dan keadilan substansial (lex humana) bagi debitor.
Mahkamah Konstitusi menempatkan eksekusi sebagai bagian dari due process of law yang memastikan semua pihak diperlakukan setara dan mematuhi aturan serta prinsip hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan yang bisa menghilangkan hak seseorang harus melalui mekanisme peradilan. Prinsip ini tampak jelas dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak kekuasaan sepihak oleh kreditor dan mengembalikan kontrol ke pengadilan sang penjaga keadilan.
Dari perspektif teori hukum progresif, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk menggerakkan hukum untuk melindungi manusia, bukan sebaliknya. Penegasan tentang eksekusi jaminan fidusia sepihak tidak boleh dilakukan tanpa pengakuan wanprestasi menandakan peralihan menuju hukum yang lebih humanistik.
Antara Hak Kreditor dan Hak Debitor
Secara filosofis, putusan Mahkamah Konstitusi bukan sebagai bentuk pelemahan terhadap kreditor, tetapi menjadi penyeimbang posisi hukum antara kreditor dan debitor yang cenderung kreditor menjadi pihak yang lebih superior.
Dalam konteks hubungan perjanjian pembiayaan, terdapat kesenjangan antara kedudukan kreditor dengan debitor. Kreditor berada pada posisi yang lebih kuat karena didukung sumber daya ekonomi yang besar dan kelengkapan dokumen hukum mengikat. Sebaliknya, debitor sering kali hanya mengandalkan aset fisik, seperti barang-barang keperluan sehari-hari, sebagai jaminan. Maka hukum hadir untuk menjaga agar kekuatan yang dimiliki kreditur tidak menjadi kesewenang-wenangan.
Sebagaimana dikatakan Prof. Satjipto Rahardjo “Hukum yang baik adalah hukum yang melindungi manusia”. Maka menagih hak tidak boleh dilakukan dengan cara melanggar hak orang lain.
Penutup
Dua Putusan Mahkamah Konstitusi tentang eksekusi jaminan fidusia mengarahkan pada suatu hal yang sederhana tapi fundamental yakni, hukum perdata dan pidana tidak pernah benar-benar terpisah. Keduanya bertemu ketika keadilan menjadi korban dari prosedur hukum yang diabaikan.
Bagi lembaga pembiayaan, kepastian hukum sangat penting. Bagi debitor, perlindungan hak sangat mutlak. Namun di atas kepastian dan perlindungan itu ada nilai yang lebih tinggi yakni kemanusiaan dan keadilan.
Eksekusi harus dijalankan, tetapi melalui prosedur hukum yang sah. Karena di negara hukum, hak tidak boleh ditegakkan dengan kekerasan, melainkan harus dengan keadilan. (asn/ldr)
Baca Juga: Arsip Pengadilan 1932 : Cikal Bakal Lahirnya Fidusia Di Indonesia
Refrensi:
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021
- M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta : Genta Publishing, 2009
Tulisan ini pendapat pribadi penulis yang tidak mewakili pendapat lembaga.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI