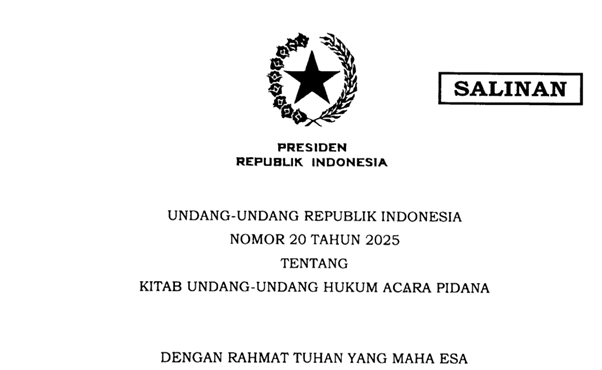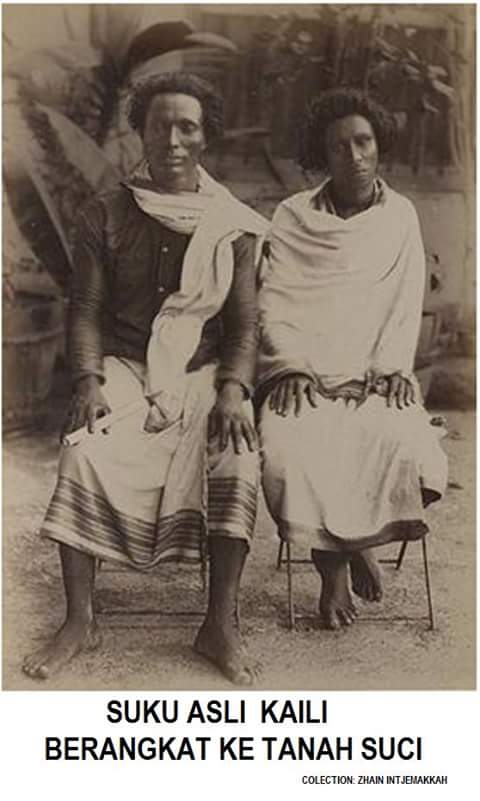Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan hanya dikenal karena keindahan alamnya, namun juga karena kekayaan budaya serta kearifan lokal yang tetap lestari hingga saat ini. Salah satu praktik hukum adat yang relevan dan menarik untuk dikaji adalah Kiu Muke, sebuah mekanisme penyelesaian sengketa lewat denda adat. Tradisi ini memperlihatkan bagaimana masyarakat setempat menjaga ketertiban sosial tanpa sepenuhnya bergantung pada instrumen hukum formal negara.
Kiu Muke, secara garis besar, adalah bentuk denda adat yang dikenakan kepada individu yang melanggar norma, dengan satu syarat utama, pelaku harus mau mengakui kesalahannya terlebih dahulu. Tanpa pengakuan, proses penyelesaian pun biasanya berhenti di situ saja. Justru pengakuan inilah yang jadi pintu masuk menuju penyelesaian dan pemulihan relasi sosial di tengah masyarakat.¹
Seorang
tokoh adat dari Amanuban pernah menyampaikan pandangan yang cukup jelas:
Baca Juga: Nilai Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Minangkabau
“Kalau ada orang salah, terus dia datang mengaku, adat tidak serta merta menjatuhkan hukuman. Tapi kewajibannya adalah membayar Kiu Muke, supaya relasi kita bisa kembali baik. Intinya, dendam jangan disimpan.”
Dari sini terlihat bahwa esensi utama Kiu Muke bukan semata-mata soal hukuman, melainkan penekanan pada rekonsiliasi dan pemulihan harmoni sosial. Mekanisme ini menempatkan pengakuan kesalahan sebagai fondasi, sehingga Kiu Muke berperan sebagai jembatan menuju kebersamaan dan perdamaian dalam komunitas.
Praktik
Kiu Muke dalam Kehidupan Sosial
Kiu
Muke merupakan mekanisme penyelesaian pelanggaran sosial yang masih ditemukan
dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai daerah. Contoh nyata dapat dilihat
pada kasus pencurian ternak di SoE, di mana penyelesaian persoalan tidak
semata-mata melalui jalur hukum negara, melainkan dengan pendekatan adat.
Pelaku diharuskan mengganti kerugian sekaligus memenuhi kewajiban membayar Kiu
Muke.²
Kasus
serupa terjadi pula di Desa Hane, Amanuban Barat, saat seekor sapi milik warga
merusak kebun masyarakat. Sesuai keputusan adat, sapi tersebut dipotong dan
dagingnya didistribusikan kepada pemilik kebun serta masyarakat, sementara
pemilik ternak tetap dibebani tanggung jawab membayar Kiu Muke.³
Kedua contoh di atas memperlihatkan bahwa inti dari penerapan Kiu Muke terletak pada upayanya memulihkan relasi sosial, sehingga proses yang terjadi lebih bersifat rekonsiliatif ketimbang represif semata.
Fleksibilitas
Bentuk Denda
Perlu dicatat bahwa Kiu Muke tidak mutlak diwujudkan dalam bentuk uang tunai. Dalam praktiknya, jenis denda dapat berupa hewan, hasil pertanian, atau benda berharga lain yang dinilai pantas menurut adat setempat. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa aspek material bukanlah esensi utama; pengakuan atas kesalahan dan pemenuhan tanggung jawab moral dianggap jauh lebih penting dalam konteks ini.⁴
Fungsi
Sosial Kiu Muke
Secara fungsional, Kiu Muke tak hanya berperan sebagai sanksi. Instrumen ini memuat nilai restoratif, preventif, sekaligus integratif di tengah masyarakat.⁵ Dengan demikian, Kiu Muke dapat dipahami sebagai praktik keadilan restoratif, yang menitikberatkan pada pemulihan hubungan sosial dibanding pembalasan.⁶
Relasi
dengan Hukum Formal
Dalam
kerangka hukum nasional Indonesia, keberadaan Kiu Muke menjadi bukti nyata
pluralisme hukum yang berlangsung di masyarakat, mekanisme adat dan hukum
negara berjalan berdampingan.⁷
Akan tetapi, realitanya sering dijumpai tumpang tindih antara keduanya. Sebagai contoh, kasus pencurian yang telah selesai melalui jalur adat tetap dapat berlanjut ke ranah hukum formal, sehingga pelaku harus menerima dua jenis sanksi sekaligus: denda adat dan hukuman pidana. Meski konstitusi negara telah mengakui hukum adat,⁸ sinkronisasi antara perangkat hukum adat dan negara masih menghadapi tantangan tersendiri.
Tantangan
di Era Modern
Adapun permasalahan utama yang kini dihadapi praktik Kiu Muke antara lain perbedaan penafsiran antar kelompok masyarakat adat, potensi konflik atau tumpang tindih dengan hukum nasional, serta minimnya dokumentasi tertulis yang dapat mengancam kelestarian tradisi ini di kalangan generasi muda. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya dokumentasi yang memadai, penelitian lanjutan, dan penguatan pengakuan formal terhadap hukum adat. Hal ini penting agar praktik seperti Kiu Muke tetap relevan dalam dinamika masyarakat modern. ⁹
Penutup
Kiu
Muke merupakan salah satu contoh nyata kearifan lokal masyarakat Nusa Tenggara
Timur yang berfokus pada pemulihan dan perbaikan hubungan sosial. Tradisi ini
menekankan pentingnya pengakuan kesalahan, tanggung jawab moral, serta
pencapaian perdamaian sebagai fondasi utama kehidupan bermasyarakat.
Dari
perspektif hukum, Kiu Muke dapat dikategorikan sebagai praktik keadilan
restoratif berbasis adat, yang relevansinya masih terasa hingga era modern saat
ini.
Walaupun dihadapkan dengan berbagai tantangan terkait perkembangan zaman serta dinamika globalisasi, eksistensi Kiu Muke membuktikan bahwa nilai-nilai lokal tetap memiliki peranan penting dalam menjaga harmoni sosial di tengah masyarakat. (ldr)
Referensi
T.O. Ihromi, Pokok-Pokok Antropologi Budaya, Jakarta: Yayasan Obor, 2006, hlm. 88.
W. Bayo, “Penerapan Sanksi Adat dalam Penyelesaian Konflik Sosial di Timor Tengah Selatan,” Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 39, No. 2, 2018, hlm. 102.
R. Liunokas, Hukum Adat dan Resolusi Konflik di Amanuban, Timor Tengah Selatan, Kupang: Pustaka NTT, 2015, hlm. 56-57.
Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 243.
Howard Zehr, The Little Book of Restorative Justice, Pennsylvania: Good Books, 2002, hlm. 21-23.
Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 134.
Baca Juga: Interpretasi Pengadilan Atas Hak Tradisional Masyarakat Adat Timor Tengah Selatan
Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Maria S.W. Sumardjono, “Hukum Adat dalam Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 19, No. 4, 2012, hlm. 567-568.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI