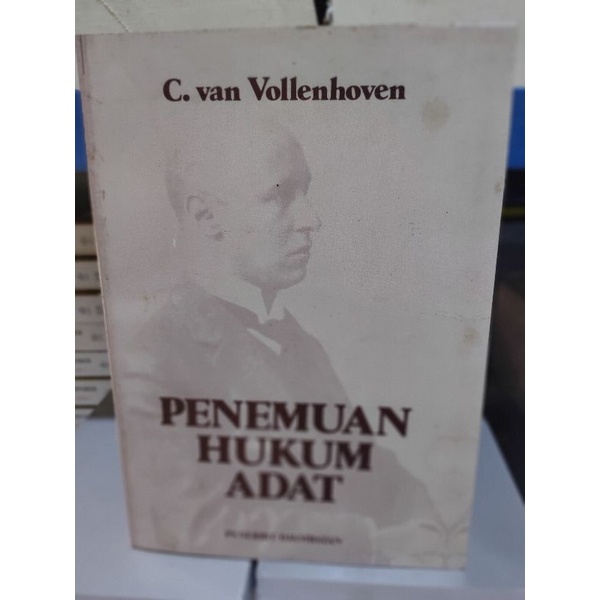Masyarakat adat di Timor
Tengah Selatan (TTS), Nusa Tenggara Timur telah menikmati hak-hak tradisional
mereka sejak sebelum kemerdekaan. Salah satu dari sekian banyak kategori hak
masyarakat adat adalah hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan sistem
kepengurusan/kelembagaan adat serta hak untuk menguasai dan mengelola tanah dan
sumber daya alam di wilayah adatnya.
Sayangnya, hak tradisional tersebut kerap terabaikan dalam berbagai kebijakan negara. Misalnya kebijakan dalam pembentukan Daerah Tingkat II TTS berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958.
Pembentukan Daerah Tingkat II TTS ini juga diikuti dengan pemekaran wilayah yang menimbulkan pergeseran wilayah-wilayah kerajaan yang kemudian terbagi menjadi tiga daerah swapraja: Daerah Swapraja Mollo, Amanuban, dan Amanatun.
Baca Juga: Nilai Keadilan Restoratif dalam Hukum Adat Minangkabau
Dampaknya, batas wilayah
kerajaan di TTS tidak memiliki kejelasan sehingga banyak menimbulkan masalah
penguasaan tanah antar persekutuan adat.
Selain itu, kebijakan
yang berdampak pada hak masyarakat adat adalah tentang pengorganisasian
masyarakat desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan
Desa. Undang-Undang ini menyeragamkan administrasi pemerintahan di level
terbawah. Penyeragaman ini berpotensi mengikis tatanan masyarakat adat dalam
kaitannya dengan hak untuk mengurus diri sendiri berdasarkan kelembagaan adat.
Meski secara
administratif desa di TTS tunduk pada aturan organisasi pemerintah, kelembagaan
adat yang masih kuat membuat struktur dan kewenangan masyarakat adat tetap
dipertahankan dan dihormati oleh warganya. Akibat dari kondisi ini, sering
muncul sengketa tanah yang diajukan ke pengadilan negara untuk memperoleh
kepastian hukum mengenai status penguasaan tanah yang diberikan oleh
fungsionaris adat.
Berdasarkan
hal-hal tersebut, selanjutnya dalam tulisan ini akan dibahas mengenai struktur
kelembagaan masyarakat adat di TTS dan bagaimana hakim
mengadili perkara yang berkaitan dengan struktur kelembagaan masyarakat adat di
TTS.
Struktur Kelembagaan Masyarakat Adat TTS
Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di Pulau Timor, NTT, adalah salah satu masyarakat hukum adat/jural communities/rechtgemeensschappen yang dikenal dalam literatur yang ditulis oleh Van Vollenhoven. Masyarakat hukum adat yang tinggal di Pulau Timor merupakan masyarakat hukum adat berdasarkan ikatan genealogis[1].
Kerajaan-kerajaan diatur berdasarkan semacam persekutuan pemerintahan adat di mana masing-masing kesatuan di bawahnya tetap menjalankan pemerintahan secara adat yang dikepalai oleh amaf-amaf besar yang kemudian juga menjadi semacam raja yang bergelar usif. Di bawahnya terdapat kefetoran yang dikepalai oleh fetor dan di bawah kefetoran adalah ketemukungan yang dikepalai oleh temukung.
Untuk bidang
keamanan terdapat panglima-panglima yang disebut meo naok yang merupakan
prajurit pilihan[2]. Ketemukungan tersebut
selanjutnya dibagi lagi menjadi temukung besar dan temukung kecil.
Dengan diadopsinya desa
gaya baru, temukung besar dan temukung kecil
sebagai dua kesatuan terkecil masyarakat hukum adat Mollo berubah menjadi rukun
warga dan rukun tetangga. Gabungan dari rukun
tetangga membentuk rukun warga; gabungan dari rukun warga membentuk dusun; dan
gabungan dusun membentuk desa[3]. Perubahan
pemerintahan adat ke dalam desa gaya baru ini menunjukkan masyarakat hukum adat
TTS berusaha untuk tetap bertahan dan beradaptasi di bidang hukum dan
pemerintahan.
Membaca Hak Tradisional Masyarakat Adat TTS
dalam Putusan Hakim
Para ahli hukum adat telah menyampaikan bahwa hukum adat dapat ditemukan dalam putusan-putusan hakim[4]. Pada tahun 2017, di Soe terjadi sengketa pertanahan yang diajukan di pengadilan. Penggugat mendalilkan mendapatkan tanah dari Usif Mella (Raja di kerajaan Mollo), sedangkan Tergugat mengklaim ia adalah seorang keturunan dari Temukung yang mendapatkan tanah dari dari Usif Nope (Raja di kerajaan Amanuban).
Dualisme tatanan organisasi masyarakat adat dan organisasi desa pemerintah yang berlaku di TTS membuat hakim harus menemukan titik temu yang ideal diantara keduanya. Oleh karena itu Hakim melakukan penemuan hukum untuk menyetarakan tatanan organisasi masyarakat adat ke dalam kerangka desa gaya baru. Dari hasil penemuan hukum oleh hakim, didapati bahwa usif adalah raja yang menguasai wilayah suku tertentu, di bawah Usif terdapat Fetor yang setara dengan Camat, dan di bawahnya adalah Temukung yang setara dengan Kepala Desa.
Usif
berwenang mengelola sumber daya alam di wilayahnya secara adat, namun Fetor
dan Temukung inilah yang memiliki kewenangan langsung dalam mengatur
pemanfaatan lahan bagi warga adatnya. Karena perannya yang strategis, Temukung
haruslah diangkat dari anggota masyarakat adat, dan tidak mungkin
seorang pendatang menduduki jabatan Temukung[5].
Ketentuan hukum adat yang bersifat umum tersebut digunakan hakim untuk menyelesaikan peristiwa konkrit. Dalam proses pembuktian diketahui bahwa tergugat adalah seorang pendatang yang datang ke TTS pada tahun 1930an.
Selain itu, diketahui pula bahwa pada tahun tersebut tanah sengketa berada pada Kefetoran Bijeli yang merupakan wilayah kerajaan Mollo yang dipimpin oleh Usif Mella, baru kemudian setelah tahun 1958 lokasi tanah sengketa masuk ke dalam wilayah Daerah Swapraja Amanuban.
Dari fakta tersebut maka Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dalil
Tergugat yang mengatakan bahwa ia adalah keturunan seorang temukung yang
mendapat tanah dari Usif Nope tidaklah terbukti. Selanjutnya dalil
gugatan Penggugat dibenarkan dan pengadilan menyatakan tanah sengketa adalah
milik Penggugat[5].
Pada perkara yang lain, di tahun 2019 terjadi sengketa tanah di Kolbano yang timbul dari konflik antar persekutuan adat berkepanjangan yang merugikan Penggugat dan Tergugat. Sengketa pertanahan yang terjadi saat itu muncul dari konflik persekutuan adat Pene Selatan dengan persekutuan adat Kolbano.
Masing-masing persekutuan adat menyatakan memiliki Usif masing-masing. Dalam mengadili perkara ini, Hakim kembali menggali dan menemukan ketentuan hukum adat TTS, selanjutnya hakim menerapkan hukum adat yang bersifat umum tersebut ke dalam peristiwa konkrit.
Pada tahap selanjutnya hakim menggali hubungan tanah sengketa dengan para pihak dengan menggunakan alat bukti yang disajikan di persidangan. Fakta hukum yang didapat ialah bahwa Penggugat merupakan keturunan seorang Meo yang telah terlebih dahulu menguasai tanah sengketa. Dalam hal ini Meo adalah suatu jabatan khusus dalam sistem pemerintahan adat di TTS yang bertindak sebagai panglima perang. Atas jabatan tersebut, seorang Meo diberikan tanah oleh Usif. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat memiliki hak untuk menguasai tanah sengketa[6].
Penutup
Meskipun beberapa kebijakan negara berpotensi mengikis hak-hak masyarakat adat, namun hukum tidak tertulis yang hidup terkait kelembagaan adat masih ada dan dihormati oleh warga masyarakat adat TTS. Hukum yang tidak tertulis tersebut digunakan oleh hakim untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
Dua kasus posisi di atas
menunjukkan bahwa hakim dalam mengadili perkara yang berkaitan dengan
kelembagaan adat di TTS telah melakukan penemuan hukum dengan cara menggali,
memahami, dan mengikuti rasa keadilan yang hidup di masyarakat serta
menggunakan asas-asas hukum adat yang bersifat umum ke dalam peristiwa konkrit. (ikaw/ldr)
Daftar Pustaka
[1] J. F. Holleman, Van Vollenhoven on
Indonesian Adat Law. Leiden: KITLV, 1981.
[2] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Sejarah
Daerah Nusa Tenggara Timur. Jakarta, 1984.
[3] S. I. Pradhani, “Konsepsi
Pengorganisasi Keberagaman Indonesia: Studi Kasus Sejarah Hukum Pemerintahan
Masyarakat Hukum Adat Mollo”, dalam HUKUM DAN POLITIK: Regulasi yang
Memuliakan Martabat Manusia, Yogyakarta: Sanggar Inovasi Desa, 2020, hlm.
61–114.
[4] A. C. L. Hakim dan S. I. Pradhani, “Penerapan
Pendekatan Formalistik dalam Penemuan Hukum Adat Oleh Hakim: Studi Kasus
Sengketa Surat Keterangan Tanah Adat di Kalimantan Tengah”, Bhumi, Jurnal
Agraria dan Pertanahan, vol. 7, no. 1, hlm. 96–111, 2021.
[5] Putusan 2370 K/Pdt/2018 jo.
163/Pdt/2017/PT KPG jo. 11/Pdt.G/2017/PN Soe.
Baca Juga: Menguak Misteri Suku Boti: Masyarakat Hukum Adat Pulau Timor
[6] Putusan 116/Pdt/2019/PT KPG jo.
10/Pdt.G/2019/PN Soe.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI