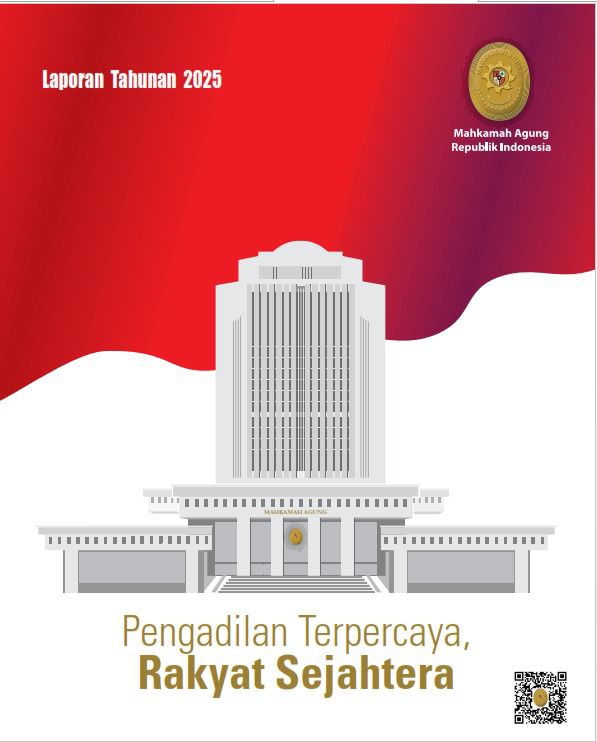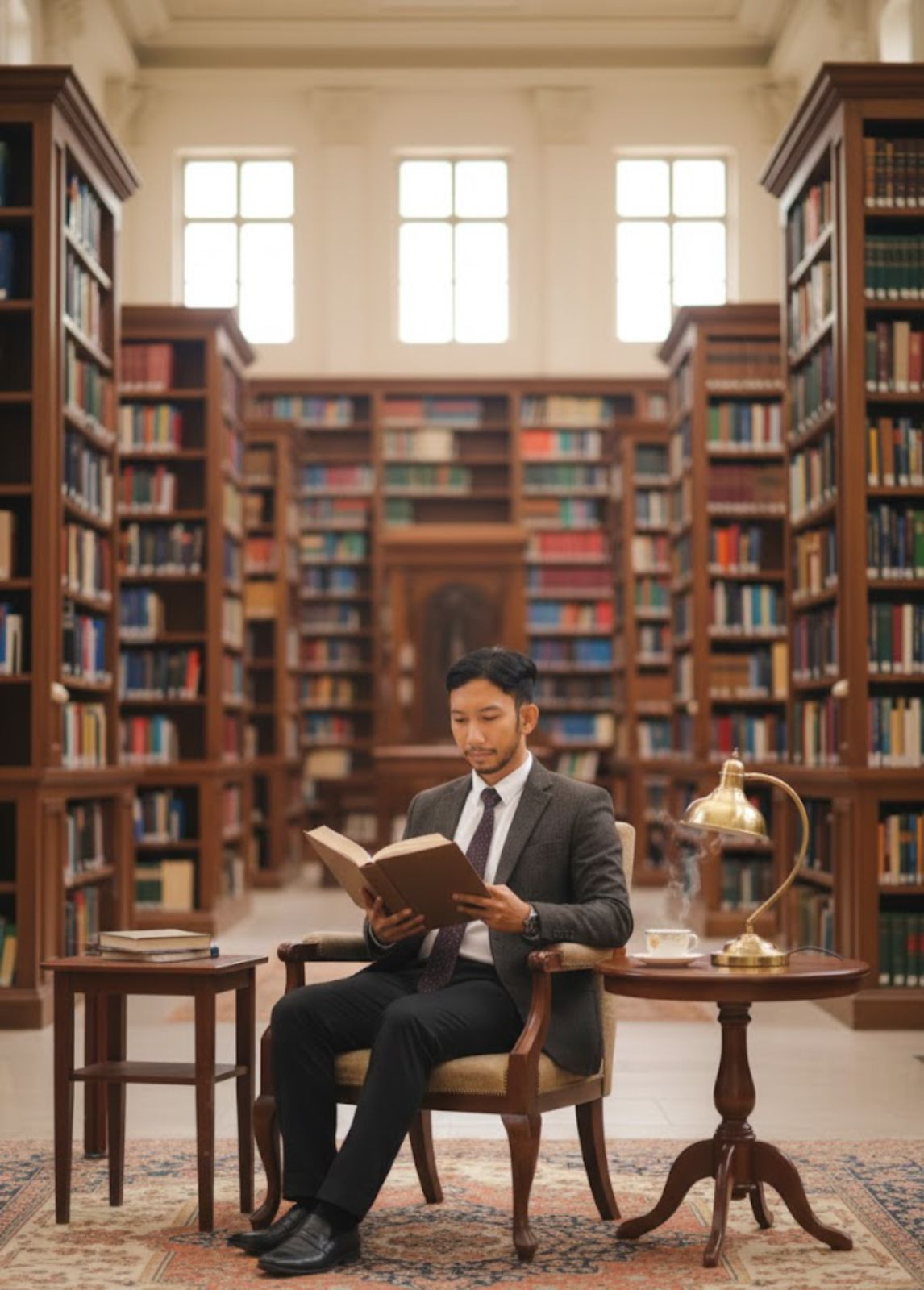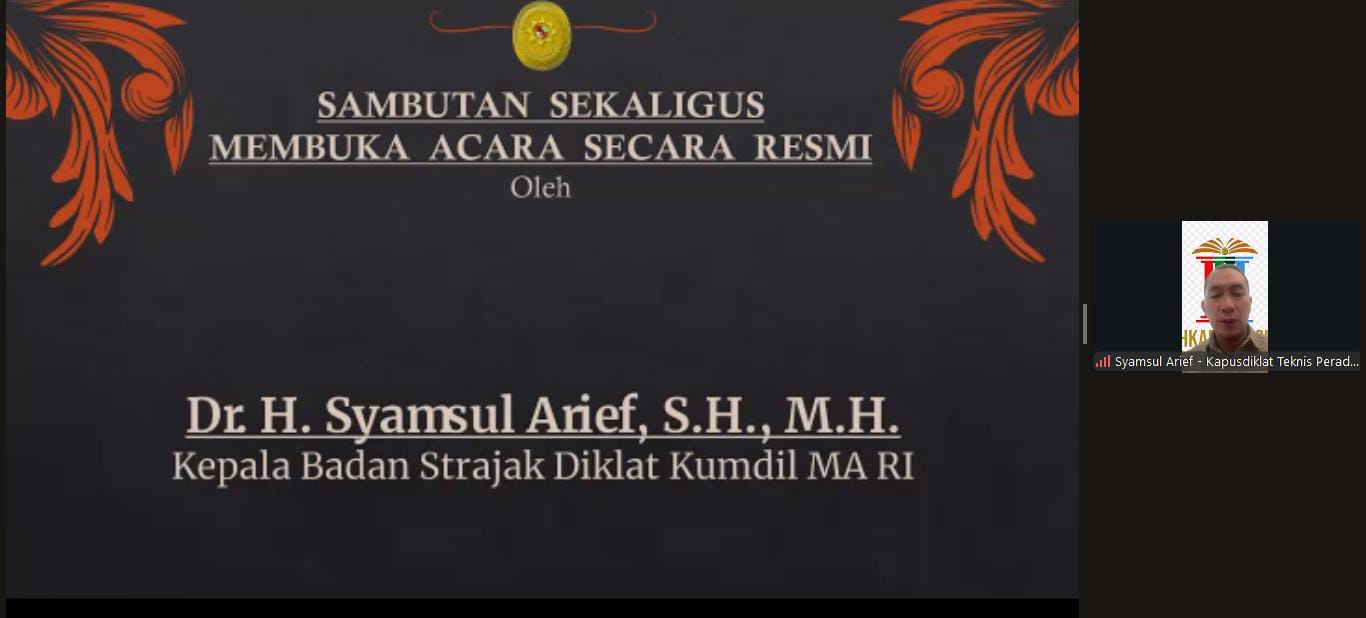Jakarta – Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Ditjen Badilum) kembali menggelar Podcast Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (Podium) dengan menghadirkan perbincangan mendalam terkait isu strategis di dunia peradilan. Kali ini, Lucas Prakoso, Hakim Agung pada Kamar Perdata Mahkamah Agung sekaligus pengajar dalam sertifikasi hakim lingkungan hidup di BSDK, hadir membahas tema Judicial Activism dalam Penanganan Perkara Lingkungan Hidup pada Senin (17/11).
Dalam pembukaannya, Lucas menegaskan bahwa kerusakan ekosistem, perubahan iklim, serta pencemaran lingkungan kini telah menimbulkan ancaman serius terhadap hak asasi manusia dan keberlanjutan hidup. Lembaga peradilan, menurut beliau, tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai benteng terakhir perlindungan lingkungan.
Menjawab pertanyaan mengenai definisi judicial activism dalam konteks lingkungan hidup, Lukas menekankan bahwa peran hakim justru diuji ketika menemukan aturan yang kabur atau kosong. Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan tegas mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dan tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum belum lengkap.
Baca Juga: Tips Memilih Klasifikasi Perkara Lingkungan Hidup di SIPP
“Perkara lingkungan hidup tidak bisa diselesaikan hanya dengan pendekatan yuridis. Ia harus dibaca melalui perspektif ekologi, sosial, dan filsafat. Ketika undang-undang belum bicara, di situlah hakim masuk,” tegasnya.
Judicial Activism Bukan Tindakan Tanpa Dasar
Lucas menegaskan bahwa judicial activism bukanlah langkah subjektif tanpa batas. Penemuan hukum harus tetap berdasar pada sumber hukum yang sah, mulai dari undang-undang, yurisprudensi, doktrin, hingga konvensi internasional. Beliau mencontohkan putusan-putusan penting seperti:
• Hak gugat organisasi lingkungan dalam putusan WALHI vs. PT Inti Indorayon Utama di PN Jakarta Pusat, terdapat konsep legal standing organisasi meski belum diatur undang-undang.
• Penerapan asas precautionary principle dan strict liability pada perkara Mandalawangi di PN Bandung, jauh sebelum asas itu diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Menurutnya, tindakan hakim dalam dua perkara tersebut merupakan judicial activism karena berangkat dari kebutuhan keadilan ekologis, tanpa mengabaikan dasar hukum yang tersedia.
Dalam proses sertifikasi hakim lingkungan hidup, para peserta dibimbing untuk menggunakan instrumen interpretasi dan rekonstruksi hukum secara bertanggung jawab, bukan sekadar berdasarkan intuisi atau kontemplasi pribadi.
“Subjektivitas hakim pasti hadir, tetapi subjektivitas yang positif, yang bekerja dengan metodologi,” jelasnya.
Terkait penerapan tanggung jawab mutlak (strict liability), Lukas menjelaskan bahwa konsep tersebut telah diakui melalui putusan-putusan pengadilan bahkan sebelum dicantumkan dalam Pasal 88 UU 32/2009. Ia menekankan bahwa dalam doktrin ini, penggugat tidak wajib membuktikan kesalahan pelaku, melainkan cukup menunjukkan hubungan kausal antara kegiatan berisiko dan kerugian yang timbul.
“Dalam banyak kasus, masyarakat tidak mampu membuktikan teknis kesalahan perusahaan. Tetapi kerugiannya nyata. Di situlah strict liability memberi keadilan,” ujarnya.
Baca Juga: Hukum Progresif dan Konstelasi Filsafat Timur: Menemukan Keadilan Substantif dalam Harmoni Kosmos
Lukas juga menegaskan bahwa hakim dapat menafsirkan kerugian lingkungan secara luas, termasuk kerugian ekologis dan non-ekonomi. Saat ini telah tersedia instrumen penilaian kerugian lingkungan, mulai dari valuasi ekologis hingga pedoman pemerintah, yang menjadi dasar objektif bagi hakim untuk mempertimbangkan besaran kerusakan.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI