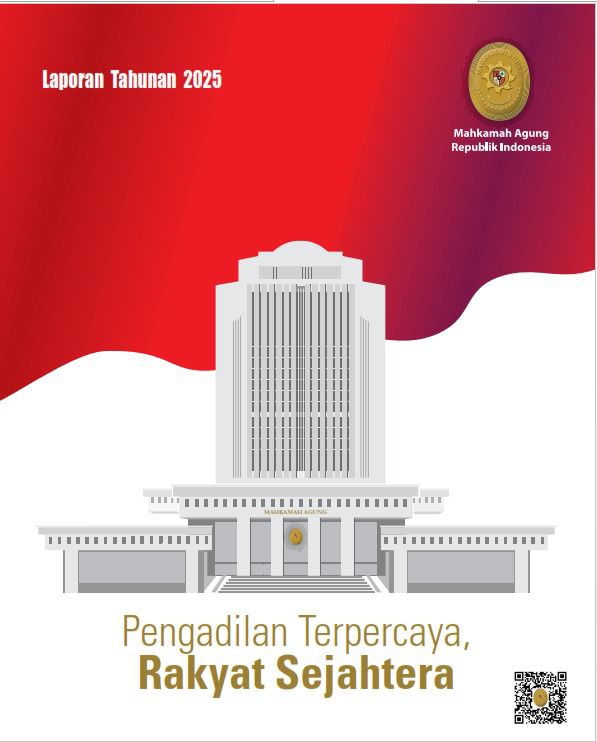Hakim adalah pilar terakhir yang menopang berdirinya keadilan secara tegak. Dalam sistem penegakan hukum secara terpadu (integrated criminal justice system), penetuan penegakan hukum, baik hukum formil maupun hukum materil berada di tangan hakim yang dimanifestasikan melalui produk hukum yang disebut putusan hakim. Sejalan dengan peran hakim tersebut, tidak salah jika kita menggunakan slogan yang diucapkan oleh Paman Peter Parker dalam Film Spiderman, “with a great power, comes great responsibilities”.
Untuk itu putusan hakim yang sejatinya adalah mahkota seorang hakim menjadi suatu barang sakral yang harus dihasilkan dari suatu proses kognitif-objektif yang dalam. Menurut Yahya Harahap (2017:166) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai, serta Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman. Selain itu putusan Hakim dituntut sesuai dengan hukum dan rasa keadilan Masyarakat.
Baca Juga: Meninjau Peradilan Pajak Indonesia Melalui Lensa "Kebingungan Teori Hukum" H.L.A. Hart
Putusan hakim yang diberikan kepada pencari keadilan haruslah timbul dari nilai-nilai arif dan bijaksana, dan bukan dari ketentuan undang-undang semata, untuk itulah pentingnya ditekankan elemen “keyakinan hakim” dalam suatu putusan yang dihasilkan. Lantas darimana nilai arif dan bijaksana itu dapat dipenuhi? Berbagai metode dapat digunakan untuk menggugah intuisi seorang hakim. Dari mempelajari berbagai teknik penafsiran hingga pendekatan filosofis yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan.
Salah satu aliran filsafat yang bersinggungan dengan proses berpikir adalah Skeptisime oleh seorang Filsuf asal Skotlandia, David Hume. Fondasi epistemologi dari putusan hakim, terutama klaimnya terhadap objektivitas dan kepastian, dapat dipertanyakan melalui lensa skeptisisme filosofis. Hume dalam pemikirannya mengenai keterbatasan akal budi manusia, kausalitas, dan induksi menawarkan perspektif yang menarik untuk menelaah bagaimana kita dapat meyakini validitas dan eksistensi "kebenaran" dalam putusan hakim.
Hukum
bukan merupakan suatu aturan tunggal, hukum adalah tata aturan (order)
sebagai suatu sistem aturan-aturan (rules) tentang perilaku manusia.
Dengan demikian hukum tidak menunjuk pada satu aturan tunggal, tetapi
seperangkat aturan yang memiliki kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu
sistem. Konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum, jika hanya
memperhatikan satu aturan saja (Jimly Asshiddiqie, 2021:13). Hakim sebagai
seorang penegak keadilan tidak dapat memberikan keadilan jika hanya menggunakan
kacamata kuda yang memandang hukum hanya sebagai aturan tertulis.
Demikian pula telah termaktub di dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim dalam memeriksa suatu perkara, bukan hanya berpatokan kepada undang-undang semata, namun harus menyelami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Untuk dapat berpikir secara objektif dan radikal, hakim tentu memerlukan tools untuk membantunya melakukan suatu proses kognitif. Filsafat Skeptisime oleh David Hume merupakan salah satu sarana untuk membantu hakim melaksanakan tugas tersebut.
Menurut Amzulian Rifa’I, dkk., (2012:73). Putusan hakim merupakan refleksi dari kinerja seorang hakim. Melalui putusan-putusan yang dibuatnya, kinerja seorang hakim dapat dinilai dan dievaluasi. Penilaian dan evaluasi dapat dilakukan melalui eksaminasi dan putusan hakim. Menurut Yusti Probowati, ada beberapa hal dalam diri hakim yang berpengaruh dalam pembuatan putusan, yakni:
1. Kemampuan berpikir logis;
2. Kepribadian;
3. Jenis kelamin;
4. Usia;
5. Pengalaman kerja.
Menempatkan kemampuan berpikir logis sebagai faktor utama memang sebuah hal yang wajar. Logika berpikir hakim dituntut sempurna karena seorang hakim harus bisa menyelesaikan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya yang tidak jarang perkara tersebut layaknya teka-teki dengan sedikit petunjuk melalui alat bukti yang disodorkan di hadapan meja yang mulia. Dalam persoalan berpikir secara logis, hakim dapat melakukan 3 (tiga) langkah merumuskan suatu masalah yang dihadapkan kepadanya melalui proses Konstatir, Kualifisir dan Konstituir.
Pada tahap Konstatir, hakim memeriksa dan menentukan kebenaran atau keabsahan peristiwa yang diajukan. Melibatkan pengumpulan dan analisis bukti untuk memastikan fakta yang menjadi dasar perkara. Dalam tahap kualifisir, hakim mengidentifikasi jenis hubungan hukum yang berlaku. Ini berarti hakim menentukan apakah peristiwa tersebut termasuk dalam kategori hukum tertentu, seperti perbuatan melawan hukum, atau delik pidana. Proses terakhir adalah tahap konstituir. Tahap ini melibatkan penetapan atau penerapan hukum yang sesuai dengan fakta yang dikonstatir dan jenis hubungan hukum yang sudah dikualifisir. Hakim menggunakan silogisme untuk menyimpulkan putusan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentu saja semua ini dapat dilakukan jika seorang hakim memiliki logika yang runut dan fasih.
Tentu kerunutan logika seorang hakim tidak dapat dibangun dalam semalam, jarang juga merupakan bakat bawaan seorang hakim. Logika harus ditempa sedemikian rupa, diasah, dan dipoles sehingga tajam dalam memandang sebuah permasalahan. Untuk itu filsafat empirisme dalam wujud skeptisime lahir dari dalam zaman pencerahan (reinessance) dan menjadi salah satu perangkat yang digunakan untuk mengasah logika berpikir seseorang. Filsafat skeptisisme dapat sangat berguna bagi seorang hakim dalam membuat keputusan, meskipun penerapannya perlu dilakukan secara hati-hati. Skeptisime adalah cara berpikir yang tidak menerima mentah-mentah suatu peristiwa yang dihadapkan kepadanya. Filsafat ini mendorong setiap orang untuk dapat melihat peristiwa tersebut secara utuh, faktor apa saja yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa tersebut, siapa saja yang turut andil, dan implikasi yang mungkin ditimbulkan.
Sejalan dengan hal tersebut, hakim pun dituntut untuk dapat melihat suatu perkara secara keseluruhan dan bukan merupakan fragmen semata. Untuk itulah dapat kita sandingkan filosofi skeptisime dengan peran hakim dalam pengambilan keputusan, yang mana tentu saja dapat memberikan banyak manfaat bukan hanya kepada hakim, maupun institusi peradilan itu sendiri. Manfaat skeptisisme bagi hakim menurut pendapat penulis dapat dijabarkan sebagai berikut
1. Mendorong Evaluasi Bukti yang Lebih Mendalam
Seorang hakim yang memiliki pandangan skeptis akan cenderung tidak mudah menerima begitu saja setiap bukti atau argumen yang diajukan. Mereka akan mempertanyakan keabsahan, keandalan, dan relevansi bukti tersebut secara lebih kritis.
2. Mengurangi Risiko Prasangka dan Bias
Skeptisisme mendorong hakim untuk meragukan asumsi dan keyakinan awal mereka sendiri. Dengan bersikap skeptis terhadap diri sendiri, hakim dapat lebih waspada terhadap potensi prasangka pribadi atau bias sistemik yang mungkin memengaruhi penilaian mereka.
3. Meningkatkan Kehati-hatian dalam Interpretasi Hukum
Hukum sering kali terbuka untuk interpretasi yang beragam. Sikap skeptis membantu hakim untuk tidak terpaku pada satu-satunya interpretasi yang mungkin, tetapi mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi dari setiap interpretasi sebelum membuat putusan.
4. Mendorong Pencarian Kebenaran yang Lebih Objektif
Dengan meragukan klaim yang diajukan dan mencari bukti yang kuat dan terverifikasi, hakim yang skeptis berusaha untuk mendekati kebenaran faktual dalam kasus yang mereka tangani seobjektif mungkin.
5. Meningkatkan Kualitas Argumentasi dalam Putusan
Proses skeptis yang dilakukan hakim dalam mengevaluasi kasus akan tercermin dalam putusan mereka. Putusan yang didasarkan pada analisis yang cermat dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang akan menjadi lebih kuat dan argumentatif.
Namun hal tersebut juga harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai bagi hakim. Untuk dapat meningkatkan pengetahuan terhadap nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat misalnya, hakim harus mengetahui kearifan lokal dari daerah tersebut. Namun kita ketahui dewasa ini sangat sedikit literatur yang menulis tentang kearifan lokal suatu daerah. Belum lagi Ketika hakim diperhadapkan dengan suatu kasus terbaru yang belum pernah terjadi sebelumnya, dalam situasi semacam ini tentu yang dapat diandalkan hanyalah prinsip preseden, yaitu mengikuti putusan-putusan terdahulu. Sekali lagi terjadi hambatan pada akses informasi (putusan) yang telah ada karena kurang mutakhirnya portal direktori putusan mahkamah agung. Padahal kita tahu bersama bahwa portal direktori mahkamah agung merupakan episentrum pengetahuan berbasis putusan hakim yang telah menjadi yurisprudensi.
Menjadi Hakim yang ideal dan profesional berarti mampu menciptakan putusan yang dapat memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Ideal sejatinya dapat menempatkan diri dan memberikan ilmu dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan yang dicitakan atau diidamkan Masyarakat. Sedangkan profesional berarti memiliki pengetahuan yang mumpuni, memiliki standar moral dan etika yang tinggi. Tidak dapat dipengaruhi oleh subjektifitas dan cenderung melihat suatu hal secara kognitif-objektif.
Filsafat Skeptisisme dapat membantu hakim mencapai 2 (dua) titel Ideal-Profesional tersebut dengan cara memberikan konsep berpikir secara mendalam, melalui penalaran-penalaran secara radikal seorang hakim akan mampu menghasilkan putusan yang tidak mustahil dapat menjadi pembaharuan hukum tanah air. (ZM/LDR)
Daftar Referensi :
1. Yahya Harahap. (2017). Hukum Acara Perdata. Sinar Grafika;
2. Prof. Amzulian Rifa’I, Dkk. (2012). Wajah Hakim Dalam Putusan. Pusham UII;
3. David Hume, (2023). Sebuah Penyelidikan Tentang Pemahaman Manusia. PT. Anak Hebat Indonesia;
Baca Juga: Semiologi Penggunaan Bahasa Hukum di Pengadilan: Mengapa Hakim Perlu Mempelajari Semiologi?
4. Prof. Dr. Jimly Ashiddiqie & Dr. M. Ali Safaat (2022). Konstitusi Pres
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI