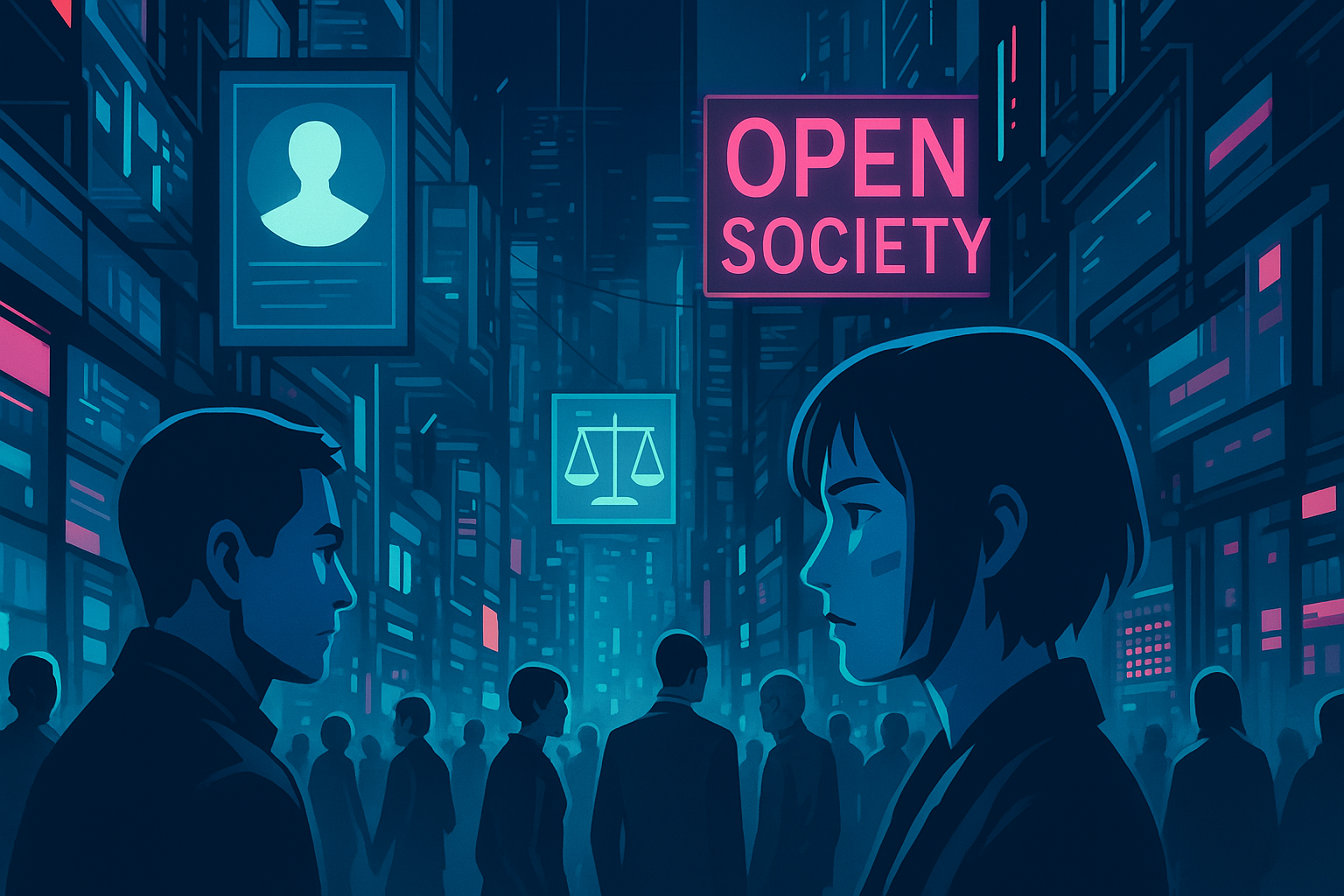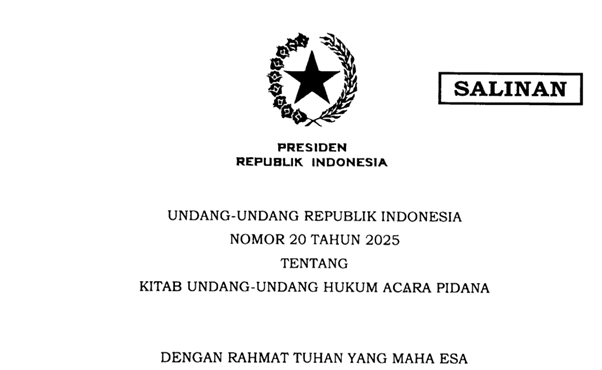Ketika
George Soros memperkenalkan gagasan "masyarakat terbuka" pada dekade
1990-an, ia seolah menawarkan sebuah mimpi yang nyaris sempurna: sebuah ruang
di mana perbedaan hidup berdampingan, dialog meredam konflik, dan pluralisme
menjadi fondasi stabilitas.
Siapa yang
tidak tertarik dengan visi dunia yang inklusif dan adil ini? Namun, saat
idealisme tersebut dibawa ke dalam praktik, realitas sering kali menunjukkan
jurang yang menganga. Alih-alih meredakan ketegangan, banyak negara yang
mengadopsi prinsip ini justru menghadapi polarisasi dan menguatnya identitas
primordial.
Mengapa visi
ini seringkali gagal di lapangan? Masalahnya terletak pada kecenderungan untuk
melihat manusia semata-mata sebagai makhluk rasional. Soros, yang terinspirasi
dari Karl Popper, meyakini bahwa dengan kebebasan berekspresi dan akses
informasi, manusia akan secara otomatis bergerak menuju moderasi.
Baca Juga: Menelusuri Akar Keadilan, Dialektika Sejarah dan Kausalitas dalam Sengketa Pajak
Namun,
pengalaman sejarah menunjukkan bahwa selain rasional, manusia juga makhluk
tribal. Rasa kebersamaan yang berbasis etnis, ideologi, agama, atau bahkan gaya
hidup, sering kali lebih kuat dari logika.
Di ruang
yang terbuka, identitas-identitas ini tidak mencair, melainkan justru semakin
mengeras dan bersaing, diantaranya misalnya karena adanya rasa iri ataupun
tendensi untuk bersikap kompetitif antar individu.
Lebih dari
itu, gagasan ini juga seringkali abai terhadap faktor lingkungan dan biologi
yang membentuk karakter manusia. Perbedaan sosial tidak hanya soal "warna
kulit" atau simbol budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh tempat kita
tumbuh, iklim, dan bahkan variasi biologis.
Menafikan
aspek ini hanya akan membuat masyarakat terbuka kehilangan realisme.
Keterbukaan menjadi paradoks: ia adalah kekuatan sekaligus kerentanan. Sistem
yang mengandaikan semua pihak bermain adil dan berkompromi akan runtuh jika ada
kelompok yang memanfaatkan keterbukaan untuk mendominasi dan menguatkan benteng
eksklusifnya.
Gagasan ini
juga bermasalah karena seringkali memperlakukan masyarakat sebagai
"laboratorium sosial," seakan manusia adalah objek pasif yang tidak
dapat memberikan consent dalam eksperimen ideologis.
Ini adalah
pandangan yang naif dan berbahaya. Dalam hukum internasional, percobaan
terhadap manusia tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius. Pasal 7 Kovenan
Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) misalnya, pada pokoknya
melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan martabat.
Eksperimen
sosial yang memperlakukan manusia sebagai objek, tanpa persetujuan dan tanpa
perlindungan, jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip ini. Lebih jauh, secara
lebih spesifik dalam Pasal 3 (1) pada EU Charter of Fundamental Rights pada
pokoknya mengatur bahwasanya setiap orang berhak atas penghormatan terhadap
integritas fisik dan mentalnya.
Adapun
eksperimentasi terhadap kondisi psikologis manusia, misalnya dengan menggunakan
algoritma sosial media, jelas saja bertentangan dengan prinsip ini. Setiap
orang berhak diperlakukan sebagai subjek yang bermartabat, bukan sebagai alat
untuk tujuan politik atau ideologis.
Dengan
demikian, mendorong masyarakat untuk dijadikan “laboratorium sosial” bukan
hanya persoalan akademis, melainkan berpotensi melanggar norma dasar hukum
internasional. Visi ini berisiko melukai martabat manusia, sebab warga negara
adalah subjek yang berdaulat, bukan objek penelitian.
Lantas, haruskah
kita meninggalkan ide "masyarakat terbuka" sepenuhnya? Boleh jadi tidak
juga. Sebagai cita-cita, ia tetap memiliki peranan setidaknya sebagai penangkal
otoritarianisme. Yang kita butuhkan adalah versi yang lebih realistis, yaitu
model keterbukaan yang mengakui tribalitas manusia dan menghormati martabatnya.
Untuk itu,
diperlukan beberapa syarat:
pertama,
mengakui dan mengelola perbedaan alih-alih mencoba meniadakannya.
Kedua,
adanya distribusi keadilan yang merata untuk meredam rasa iri dan kompetisi.
Ketiga,
institusi yang kuat untuk mengelola ketegangan.
Dan keempat,
kebijaksanaan budaya, seperti filosofi Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, yang
dapat menjadi jembatan lokal untuk mewujudkan keterbukaan yang membumi.
Bagi
Indonesia, keragaman yang luar biasa bukanlah bahan eksperimen, melainkan rumah
bersama yang harus dirawat. Menyebutnya "laboratorium sosial"
terdengar akademis, tetapi bagi warganya, itu terasa menyakitkan.
Masyarakat
terbuka yang realistis bukanlah tentang menghapus perbedaan, melainkan tentang
mengelolanya agar tidak berujung pada dominasi. Ini tentang memastikan bahwa
identitas apa pun dapat hidup tanpa menindas yang lain, lahir dari penghormatan
tulus terhadap martabat setiap individu.
Baca Juga: Hakim Dalam Perspektif Epistemologi Hukum: Klaim Kebenaran dalam Proses Peradilan
Idealisme
Soros hanya akan menjadi utopia jika tidak dikaitkan dengan sifat dasar
manusia, realitas lingkungan, dan martabat yang menolak untuk dijadikan bahan
eksperimen. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI