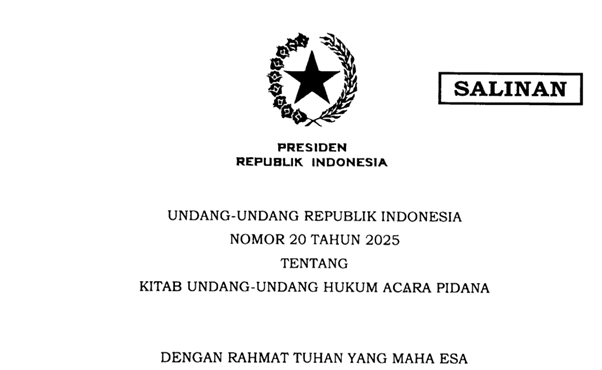Narkotika merupakan persoalan multidimensi di Indonesia, melibatkan aspek hukum, kesehatan, sosial, ekonomi, hingga keamanan nasional. Data Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri mencatat sejak 1 Januari hingga 17 April 2025 terdapat 13.142 kasus narkotika, terdiri atas 5.386 kasus penyalahgunaan (40,98%) dan 5.325 kasus peredaran gelap (40,51%).
Angka ini menunjukkan bahwa penyalahguna lebih dominan dibandingkan pengedar, sehingga kebijakan pemenjaraan terhadap pengguna narkotika belum efektif. Lembaga pemasyarakatan bahkan sering menjadi tempat berkembangnya jaringan kejahatan baru dan tidak menyentuh akar persoalan, yaitu kecanduan sebagai penyakit kronis yang membutuhkan penanganan medis.
Fakta tersebut menuntut perubahan paradigma hukum dalam memandang pengguna narkotika. Mereka bukan hanya pelaku tindak pidana, tetapi juga korban yang mengalami penderitaan fisik dan psikologis. Pidana penjara semata tidak menyelesaikan persoalan, justru meningkatkan potensi pengulangan.
Baca Juga: Memahami Esensi Pidana Narkotika Dalam Kacamata Teleologis
Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan kesempatan untuk pulih melalui pendekatan rehabilitatif, yang lebih tepat dibandingkan dengan pemidanaan berbasis pemenjaraan karena memungkinkan pemulihan kesehatan, pemutusan ketergantungan, dan reintegrasi sosial.
Apakah Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Masih Relevan?
Penerapan pidana penjara bagi pengguna narkotika masih menimbulkan perdebatan dalam hukum pidana Indonesia. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memang memungkinkan penyalahguna dijatuhi pidana penjara, tetapi juga memberi ruang bagi rehabilitasi medis dan sosial.
KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023) menegaskan pergeseran paradigma pemidanaan, dari sekadar pembalasan menuju perlindungan masyarakat, pemulihan, dan rehabilitasi pelaku. Orientasi ini sejalan dengan pemikiran Sahardjo pada 1963 yang menekankan bahwa narapidana tetap manusia yang dapat diperbaiki.
Secara teori, tujuan pemidanaan tidak tunggal. Doktrin klasik menekankan pembalasan, sedangkan teori modern menekankan pencegahan, perlindungan, dan perbaikan pelaku.
Dalam konteks penyalahguna narkotika, paradigma rehabilitasi lebih sesuai dengan teori proporsionalitas yang menuntut keseimbangan antara tingkat kesalahan, bahaya yang ditimbulkan, dan sanksi yang dijatuhkan. Karena penyalahguna sejatinya adalah korban ketergantungan, maka pemulihan melalui rehabilitasi lebih tepat dibandingkan pemenjaraan. Rehabilitasi tetap mengandung unsur pembatasan kebebasan, tetapi tujuannya pemulihan, bukan pembalasan.
Meskipun secara normatif rehabilitasi diakui, praktik peradilan menunjukkan dominasi pemenjaraan. Di lembaga pemasyarakatan, pembinaan dilakukan melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pembinaan kerohanian, namun pola ini tidak menyentuh akar persoalan pengguna, yakni kecanduan medis dan psikologis.
Sebaliknya, panti rehabilitasi memberikan pendekatan multidimensi berupa terapi medis, konseling psikososial, pendampingan spiritual, dan reintegrasi sosial. Orientasi ini lebih relevan bagi pengguna narkotika karena memulihkan kapasitas personal dan sosial.
Jika ditinjau dari nilai proporsionalitas, kebermanfaatan, dan keadilan, pidana penjara bagi pengguna narkotika semakin sulit dipertahankan.
Pertama, dari segi proporsionalitas, memenjarakan pecandu yang secara medis dikategorikan sebagai individu dengan gangguan kesehatan tidak seimbang dengan hakikat kesalahannya.
Kedua, dari segi kebermanfaatan, penjara tidak terbukti mengurangi ketergantungan, bahkan berpotensi memperburuk kondisi dengan menempatkan pecandu dalam lingkungan yang rawan memicu kejahatan.
Ketiga, dari segi keadilan, pemidanaan retributif cenderung mengabaikan kemanusiaan dengan memandang pecandu semata sebagai pelaku kejahatan, bukan sebagai individu yang perlu diselamatkan.
Rehabilitasi menawarkan pendekatan lebih humanis sekaligus normatif sesuai dengan tujuan hukum pidana modern. Melalui metode medis, psikologis, dan sosial, rehabilitasi diarahkan pada pemulihan perilaku serta pemulihan fungsi sosial pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang sehat.
Rehabilitasi tidak hanya menunda hukuman, melainkan perwujudan keadilan substantif dengan memperbaiki pelaku, melindungi masyarakat, dan memulihkan keseimbangan sosial.
Secara psikologis, rehabilitasi membantu individu mengatasi ketergantungan, stigma, dan menumbuhkan motivasi hidup sehat. Dari sisi sosial, rehabilitasi memulihkan peran individu agar mampu berinteraksi wajar di tengah masyarakat melalui konseling, pelatihan keterampilan, dan pembinaan spiritual.
Upaya komprehensif ini tidak dapat dicapai melalui pemenjaraan yang lebih menekankan pengendalian ketertiban dibanding pemulihan perilaku.
Dengan demikian, penjara bagi penyalahguna narkotika selayaknya diposisikan sebagai ultimum remedium, bukan primum remedium. Hakim dituntut tidak hanya menegakkan teks hukum, melainkan juga menimbang proporsionalitas, kebermanfaatan, dan keadilan substantif.
Rehabilitasi harus dipandang sebagai strategi utama, sejalan dengan pembaruan hukum pidana Indonesia dan prinsip perlindungan hak asasi manusia.
Lantas, Bagaimana Cara Mengidentifikasi Penyalahguna Narkotika?
UU No. 35 Tahun 2009 menghadirkan mekanisme tes asesmen terpadu melalui Tim Asesmen Terpadu (TAT) yang menilai status hukum pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika. Secara konseptual, pecandu adalah individu yang bergantung, penyalahguna adalah mereka yang menggunakan tanpa izin, sedangkan korban biasanya terjerumus karena dibujuk atau dipaksa.
TAT terdiri dari unsur hukum (penyidik, jaksa, petugas Kemenkumham) dan unsur medis (dokter dan psikolog). Tim hukum menilai aspek yuridis, sementara tim medis menilai kondisi medis dan psikososial untuk menyusun rekomendasi rehabilitasi. Hasil asesmen ini menjadi dasar pertimbangan apakah penyalahguna layak ditempatkan dalam program rehabilitasi.
Mekanisme ini diperkuat melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010, SEMA No. 3 Tahun 2015, dan SEMA No. 1 Tahun 2017 yang memberikan tentang petunjuk dalam menentukan penyalahguna narkotika dari tiga aspek utama yaitu jumlah barang bukti, adanya pengulangan tindak pidana, dan kondisi pelaku serta ruang bagi hakim untuk menyelisihi pidana minimum sebagaimana termuat dalam Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 meskipun tidak tercantum dalam dakwaan jaksa.
Namun, implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Penelitian Indonesia Judicial Research Society (IJRS) 2016–2020 menunjukkan dari 745 terdakwa penyalahgunaan narkotika, 92,3% dijatuhi hukuman penjara, hanya 3,2% dijatuhi rehabilitasi murni, 3,1% kombinasi, dan 1,3% hukuman lain. Data ini menunjukkan paradigma pemenjaraan masih sangat dominan, sementara paradigma pemulihan belum terinternalisasi.
Meski rehabilitasi dinilai lebih sesuai, penerapannya tidak dapat diberlakukan mutlak. Penolakan rehabilitasi oleh TAT menunjukkan bahwa tidak semua penyalahguna memenuhi syarat, khususnya jika hasil asesmen menunjukkan keterlibatan dalam peredaran gelap. Dalam situasi demikian, jalur pidana tetap diperlukan. Hal ini menegaskan perlunya kehati-hatian, proporsionalitas, dan pembedaan tegas antara pengguna murni dengan pengedar atau bandar narkotika.
Kesimpulan
Permasalahan narkotika di Indonesia bersifat kompleks dan multidimensi. Data kasus menunjukkan dominasi penyalahguna dibanding pengedar, yang menegaskan bahwa kebijakan pemenjaraan tidak efektif sebagai strategi utama. Secara normatif, hukum Indonesia telah menyediakan ruang rehabilitasi melalui UU Narkotika, KUHP baru, dan regulasi Mahkamah Agung. Rehabilitasi dinilai lebih proporsional karena memulihkan pengguna dari penyakit ketergantungan sekaligus mengembalikan fungsi sosialnya.
Namun, praktik peradilan masih menempatkan penjara sebagai pilihan utama, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian IJRS yang mencatat 92,3% pengguna dijatuhi pidana penjara. Oleh karena itu, paradigma pemulihan melalui rehabilitasi harus lebih dikedepankan, dengan menempatkan pemenjaraan sebagai ultimum remedium. Penerapan rehabilitasi harus selektif, berdasarkan asesmen terpadu yang membedakan pengguna murni dengan pengedar. Dengan demikian, kebijakan narkotika di Indonesia dapat lebih humanis, efektif, dan berkeadilan, sejalan dengan arah pembaruan hukum pidana nasional.
Daftar Pustaka
1. Muhammad Naim, “Proposionalitas dalam Penjatuhan Pidana Terkait Adanya Disparitas Pidana dalam Perkara Narkotika”, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol. 2, No. 1, Maret (2018).
2. Nurwana Abubakar, La Ode Husen dan Sri Lesatri Poernomo, “Efektivitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Rehabilitasi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dan Psiktropika: Studi kasus di Lapas Narkotika Klas II A Sunguminasa”, Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 3, No. 9, September (2022).
3. Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri, “ Jumlah Kasus Menyalahgunakan Narkoba Lebih Banyak ketimbang Mengedarkan”, diakses pada tanggal 17 November 2025, https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/jumlah_kasus_menyalahgunakan_narkoba_lebih_banyak_ketimbang_mengedarkan.
Baca Juga: Rehabilitasi dalam Hukum Pidana
4. Reza Pahlevi, Penyalahguna Narkoba di RI Umumnya Dipenjara, Bukan Diobati, diakses pada tanggal 20 September 2025, https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/301f17f097c29de/penyalahguna-narkoba-di-ri-umumnya-dipenjara-bukan-diobati#:~:text=%22Kritik%20terhadap%20pandangan%20ini%20adalah,crime%29%2C%22%20pungkas%20IJRS
Wawancara dengan Saferinus Juliono, Program Manager di Pusat Rehabilitasi Narkoba Galilea Palangkaraya pada tanggal 19 November 2025.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI