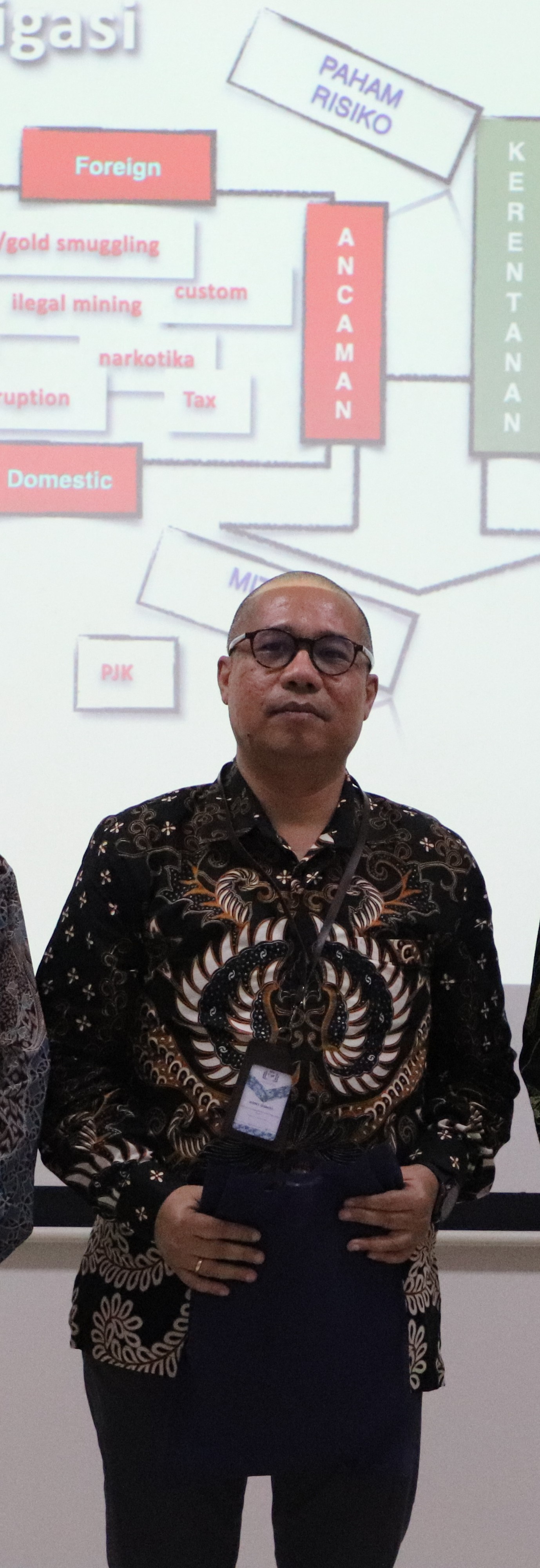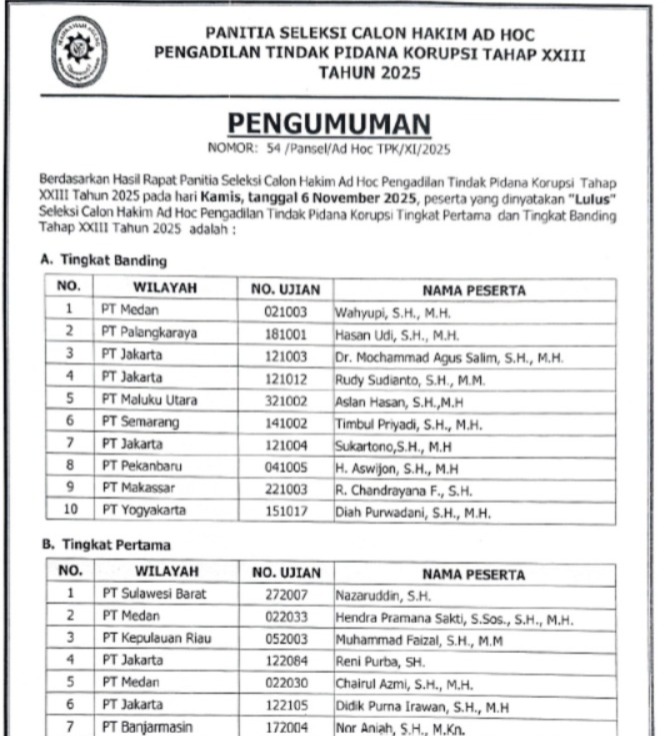UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika)
berlandaskan filosofi dualistik inheren, memposisikan narkotika sebagai pharmakon,
esensial secara medis namun ancaman eksistensial jika sirkulasinya ilegal.
Dualisme
ini mengamanatkan implementasi rezim hukum bifurkatif: pendekatan
represif retributif terhadap peredaran gelap (illicit trafficking) dan
pendekatan humanis restoratif terhadap penyalahgunaan.
Kompleksitas
tersebut memicu tensi paradigmatik dalam praktis yudisial, menuntut penalaran
kognitif superior untuk menentukan differentia specifica antara pengedar
dan pecandu/penyalah guna.
Baca Juga: Memahami Esensi Pidana Narkotika Dalam Kacamata Teleologis
Akurasi
kualifikasi yuridis menjadi imperatif krusial, mengingat implikasi hukum yang
diametral, pemidanaan minimum khusus versus intervensi rehabilitasi.
Inkonsistensi
putusan kerap bersumber dari kegagalan epistemologis dalam mendefinisikan
peredaran gelap atau interpretasi mekanistik terhadap beleidsregel
(SEMA). Risiko fundamentalnya adalah terjadinya error in judicando;
mengkriminalisasi korban murni atau mengekskulpasi pengedar.
Guna
mengatasi vacuum normatif terkait batasan kuantitatif, SEMA Nomor 4
Tahun 2010 menginstitusionalisasi parameter objektif "pemakaian
sehari". Ini memicu diskursus epistemologis fundamental mengenai
kualifikasi yuridis penguasaan narkotika yang eksesif di tengah ketiadaan bukti
langsung aktivitas distribusi, sehingga memerlukan formulasi presumsi hukum
kuantitatif (quantitative legal presumption).
Analisis
demarkasi konseptual mensyaratkan dekonstruksi definisi autentik legislator.
Peredaran gelap (Pasal 1 angka 6 UU Narkotika) bersifat lato sensu,
mencakup segala aktivitas melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana
narkotika. Interpretasi sistematis dengan Pasal 35 adalah imperatif.
Pasal ini
mendefinisikan peredaran sebagai penyaluran atau penyerahan, secara eksplisit
mencakup aktivitas "bukan perdagangan". Signifikansi krusialnya
adalah penegasan bahwa motif ekonomis bukanlah conditio sine qua non.
Penyerahan non komersial tetap terkualifikasi sebagai peredaran gelap, ratio
legis-nya adalah interupsi rantai distribusi ilegal secara komprehensif.
Secara
diametral, penyalah guna (Pasal 127 ayat 1) dicirikan oleh orientasi konsumtif
internal, yakni penggunaan "bagi diri sendiri" sebagai end user.
Perbedaan fundamental antara keduanya terletak pada orientasi actus reus:
sirkulasi eksternal versus konsumsi personal. Analisis ini
mengeksplorasi cakupan ekstensif Pasal 35 dan justifikasi Presumsi Kuantitatif
dalam menentukan kualifikasi delik.
Demarkasi
fundamental antara peredaran gelap dan penyalahgunaan terletak pada orientasi actus
reus dan mens rea: sirkulasi eksternal versus konsumsi
internal. Problematika yuridis mengemuka pada kualifikasi delik penguasaan
(Pasal 112), yang inheren dalam penggunaan (Pasal 127), menciptakan potensi concursus
idealis. Resolusi atas ambiguitas ini mensyaratkan determinasi niat batin
pelaku di muka persidangan.
Dalam
konteks ini, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 berfungsi sebagai kebijakan (beleidsregel)
interpretatif untuk penerapan Pasal 103, menetapkan kriteria kumulatif
identifikasi penyalah guna murni. Klausula esensialnya adalah ketiadaan bukti
keterlibatan dalam peredaran gelap. Ini menegaskan supremasi pembuktian
materiil di atas parameter kuantitatif.
Konsekuensinya,
apabila actus reus peredaran gelap terbukti, termasuk penyerahan non komersial
sebagaimana cakupan ekstensif Pasal 35, kualifikasi delik wajib mengikuti rezim
peredaran gelap (misalnya Pasal 114). Fakta materiil sirkulasi ilegal secara
imperatif menganulir relevansi kuantitas barang bukti dalam kualifikasi
penyalahgunaan.
Kompleksitas
yuridis mengemuka dalam skenario di mana seorang Terdakwa didapati menguasai
narkotika dalam kuantitas yang melampaui ambang batas kewajaran konsumsi
pribadi (sebagaimana diatur dalam SEMA), namun dalam proses pembuktian, tidak
ditemukan bukti langsung yang mengindikasikan aktivitas peredaran gelap
(misalnya, absensi saksi pembeli atau bukti transaksi). Terdakwa, dalam kondisi
ini, lazimnya berdalih bahwa jumlah tersebut merupakan stok untuk konsumsi
pribadi.
Dalam
menghadapi fakta hukum demikian, berlaku sebuah konstruksi logika yang dapat
dijustifikasi sebagai presumsi hukum kuantitatif (quantitative legal
presumption), atau dalam terminologi lain, sebuah fiksi hukum (legal
fiction). Presumsi ini dioperasikan melalui interpretasi sistematis dan
teleologis terhadap UU Narkotika dan SEMA, yang esensinya berfungsi sebagai
instrumen kebijakan kriminal (criminal policy tool).
Formulasi
logika hukum atas presumsi ini dapat dibangun melalui penalaran silogistik yang
terstruktur. Landasan utamanya adalah premis mayor (norma primer), di mana rezim
peredaran gelap, melalui pasal-pasal terkaitnya dalam UU Narkotika, secara
tegas melarang dan mengancam pidana berat atas setiap perbuatan memiliki,
menyimpan, atau menguasai Narkotika tanpa hak.
Hal ini
dikontraskan dengan premis minor (lex specialis), yaitu rezim
penyalahgunaan melalui pasal mengenai penyalah guna, yang merupakan
pengecualian spesifik bagi penyalah guna yang penguasaannya semata-mata untuk
konsumsi pribadi, dengan potensi penerapan rehabilitasi sebagaimana diatur
dalam pasal terkaitnya.
Kunci
penalaran ini terletak pada standar objektif kewajaran, yang ditetapkan oleh SEMA
yang relevan sebagai tolok ukur yuridis kuantitatif (misalnya, batasan spesifik
untuk jenis metamfetamina) untuk menilai kredibilitas klaim penggunaan pribadi.
Apabila
fakta hukum menunjukkan Terdakwa menguasai Narkotika dalam jumlah yang secara
signifikan melampaui standar objektif kewajaran SEMA tersebut, maka terjadi negasi
negation of the exception. Konsekuensinya, Terdakwa gagal memenuhi
syarat kumulatif untuk dikualifikasikan sebagai penyalah guna murni dalam
konteks rezim penyalahgunaan. Klaim Terdakwa bahwa penguasaan tersebut
semata-mata untuk penggunaan pribadi menjadi tidak kredibel secara yuridis.
Pada
titik inilah presumsi hukum kuantitatif aktif. Dengan gugurnya kualifikasi rezim
penyalahgunaan, perbuatan Terdakwa secara otomatis kembali tunduk pada norma
primer (rezim peredaran gelap). Hukum mempresumsikan bahwa penguasaan dalam
jumlah eksesif tersebut telah memenuhi unsur delik dalam ranah peredaran gelap.
Kuantitas eksesif berfungsi sebagai bukti sirkumstansial (circumstantial
evidence atau indicium) yang sangat kuat, yang melahirkan inferensi
logis mengenai adanya niat selain konsumsi pribadi, setidaknya niat untuk
"menyediakan" (providing) atau menyimpan stok yang
memfasilitasi sirkulasi ilegal.
Konstruksi
ini tidak mencederai asas praduga tak bersalah, sebab unsur inti penguasaan
tanpa hak telah terbukti secara faktual. Presumsi ini idealnya bersifat rebuttable
presumption (dapat dibantah), namun beban argumentasi (burden of
argument) untuk membuktikan bahwa kuantitas eksesif tersebut murni akibat
kondisi ketergantungan ekstrem, secara wajar bergeser kepada Terdakwa melalui
pembuktian ahli yang kredibel.
Penanganan
perkara narkotika menuntut kecermatan epistemologis dan kebijaksanaan yudisial
yang paripurna. Polarisasi antara peredaran gelap dan penyalahgunaan bukanlah
sekadar pilihan teknis pasal, melainkan penentuan fundamental antara pendekatan
punitif dan rehabilitatif.
Pemahaman
yang mendalam terhadap Pasal 35 UU Narkotika adalah imperatif. Peredaran gelap
mencakup spektrum aktivitas sirkulasi ilegal yang sangat luas, termasuk
penyaluran, penyerahan, dan pemindahtanganan tanpa motif ekonomis.
Ketiadaan
bukti transaksi komersial tidak serta merta meniadakan kualifikasi peredaran
gelap jika terbukti adanya penyerahan kepada pihak lain. SEMA Nomor 4 Tahun 2010
harus diposisikan secara proporsional sebagai pedoman interpretatif, bukan
norma absolut. Parameter kuantitatif hanyalah salah satu syarat kumulatif.
Syarat ketiadaan bukti keterlibatan dalam peredaran gelap tetap superior.
Fakta materiil keterlibatan dalam peredaran gelap akan menganulir klaim penyalah guna, meskipun kuantitas barang bukti berada di bawah ambang batas yang ditentukan. Sebaliknya, dalam menghadapi situasi di mana barang bukti melampaui ambang batas SEMA namun bukti langsung peredaran gelap tidak ditemukan, penerapan presumsi hukum kuantitatif adalah sebuah keniscayaan yuridis yang logis dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui konstruksi logika yang sistematis, kegagalan memenuhi standar objektif kewajaran konsumsi pribadi mengakibatkan perbuatan tersebut harus dikualifikasikan dalam rezim peredaran gelap. Konstruksi ini memastikan bahwa hukum ditegakkan secara efektif untuk memberantas peredaran gelap, sembari tetap menjaga keseimbangan dan proporsionalitas dalam pemidanaan. (ldr)
Baca Juga: KUHP Baru, Masalah Lama: Pasal (Keranjang Sampah) Narkotika Kembali Menghantui
Penulis Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. adalah Hakim PN Serang
Tulisan ini pendapat pribadi penulis yang tidak mewakili pendapat lembaga.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI