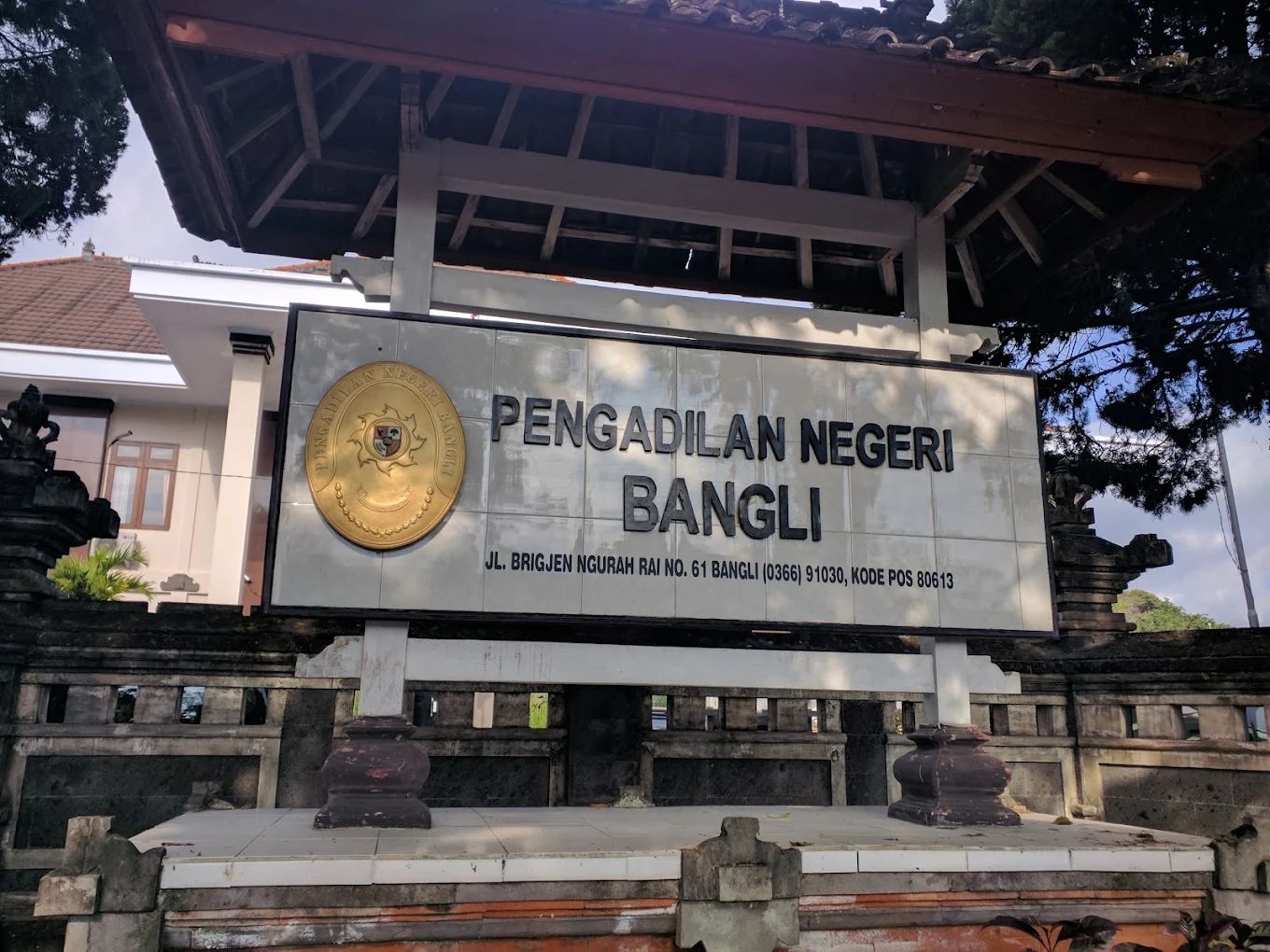Iftitah
Jaminan akan
pemenuhan perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang esenssial dan
substansi dalam negara hukum modern, yang secara Internasional telah
mendapatkan pengakuan dalam sebagian besar negara-negara di dunia.
Di Indonesia sendiri
jaminan akan hak asasi manusia telah mendapat pengakuan yang diatur secara
nyata dalam konstitusi meskipun pada awalnya belum secara spesifik dan tekstual
tertuang dalam konstitusi, dan mencapai puncaknya bahwa pengaturan Hak Asasi
Manusia secara tekstual masuk di dalam konstitusi perubahan, yang berlaku sejak
Amandemen selesai sampai saat sekarang ini.
Dengan diatur lebih luas
lagi dalam UUD Negara Republik Indonesia pada BAB X A, Tentang Hak Asasi
Manusia, mulai dari pasal 28 A sampai dengan pasal 28 J, dengan begitu memberikan
landasan yang kuat dalam ketata negaraan Negara Republik, dan menjadikan
patokan utama bagi seluruh Rakyat, Bangsa dan Negara Republik Indonesia dalam menjalankan
tugas dan kewajiban masing-masing sesuai dengan profesinya.
Baca Juga: Hukuman Mati, Perspektif Perbandingan UUD 1945 dan UU HAM
Setiap orang yang
berada di wilayah Republik Indonesia wajib patuh pada peraturan
perundang-undangan, hukum tidak tertulis dan hukum Internasional mengenai Hak
Asasi Manusia yang telah iterima oleh Negara Republik Indonesia (lihat pasal 67
UU 39/1999).
Demikian juga
Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan
memajukan Hak asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan
perundang-undangan lain, dan hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia yang
diterima oleh Negara Republik Indonesia. Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah
sebagai mana dimaksud diatas meliputi langkah implementasi yang efektifdalam
bidang hukum, politik, ekonomi sosial budaya, pertahanan keamanan negara dan
bidang lain. (lihat pasal 71 dan pasal 72 UU Nomor 39/1999).
Secara aturan memang
sudah secara jelas diatur dalam peratururan perundang-undangan yang memberikan
legitimasi yang kuat bagi Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penegakkan
hukum, namun dalam inplemantasinaya masih banyak terjadi pelanggran-pelanggraan
termasuk didalamnya pelanggaran HAM
berat yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat hukum, yang menurut Komnas HAM
setidaknya diduga melakukan pelanggara HAM berat (setidaknya terdapat 12 kasus
yang terjadi, lihat rilis Komnas HAM), yaitu:
1.
Peristiwa
1965/1966
2.
Peristiwa
Penembakan Misterius (1982-1985)
3.
Peristiwa
Tanjung Priok (1984-1985);
4.
Peristiwa
Talangsari (1989)
5.
Peristiwa
Kerusuhan Mei (1998);
6.
Peristiwa
Trisakti dan Semanggi (1998) dan Semanggi 2 (1999)
7.
Peristiwa
Penculikan dan Penghilangan Paksa Aktivis (1997-1998)
8.
Peristiwa
Timor Timur (1999)
9.
Peristiwa
Abepura (2000)
10. Peristiwa Wasior (2001) dan
Wamena (2003)
11. Peristiwa Jambu Keupok (2003)
12. Peristiwa Rumoh Geudong Pidie
(1989-1998)
Pelanggaran
HAM berat juga sudah diatur dalam Undang-undang, yaitu UU Nomor 26 Tahun 2000
Tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, yang dalam pasal 7 disebutkan,
Pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi: a. Kejahatan Genosida dan b.
Kejahatan terhadap Kemanusiaan.
Pasal 8 : Kejahatan Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.
Pasal
9: Kejahatan terhadap kemanusiaan
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf
b adalah salah satu
perbuatan yang dilakukan
sebagai bagian dari
serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung
terhadap penduduk sipil.
Dengan
telah diaturnya secara terperinci dalam bentuk UU
memberikan pedoman yang kuat kepada aparat penegak hukum dalam melakukan tugas
dan taggung jawabnya dalam melaksanakan penegakan hukum manakala terjadi suatu
peristiwa yang masuk dalam delik HAM berat dimaksud.
Penegakkan
hukum yang telah dilakukan oleh aparat dan berujung pada persidangan
Pelanggaran HAM berat secara empiris telah membuktikan bahwa perbuatan yang
dimaknai sebagai pelanggaran HAM berat tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi
sejak awal, artinya bahwa dari 4 peristiwa yang disidangkan pada Pengadilan HAM
Berat, baik pengadilan HAM Ad hoc untuk kasus Timor Timur dan Kasus Tanjung
Priok, maupun Pengadilan HAM permanen, yaitu untuk kasus Abepura dan Paniai,
sebagian besar terdakwa tidak terbukti di persdiangan melakukan Delik HAM,
sehingga konsekwensinya adalah putusan bebas atau setidaknya putusan lepas.
(Lihat pasal 191 UU Nomor 8/1981 Tentang Hukum Acara Pidana).
Menjadi pertanyaan besar, yang
merupakan permasalahan yang akan diangkat dalam pembahasan yang singkat ini,
diantaranya adalah Siapakah yang sesungguhnya harus bertanggung jawab dalam hal
terjadinya pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia, sedangkan permasalahn kedua
adalah bagaimanakah peran negara dalam menyikapi terjadinya pelanggaran berat
Hak Asasi Manusia.
Tanggung Jawab Pidana Pelanggaran Berat
HAM
Pengadilan
HAM di Indonesia merupakan salah satu bagian dari Sistem Peradilan di
Indonesia. Pengadilan HAM memiliki tugas penting untuk membangun rasa
kepercayaan rakyat Indonesia dan komunitas Internasional tentang kedaulatan dan
kepastian hukum di Indonesia saat ini.
Eksistensi
dan peran pengadilan HAM adalah menghargai nilai kemanusiaan, hak-hak korban,
hak-hak pelaku, sensitifitas sosial dan moralitas universal. (1)
Dalam
kekuasaan yudikatif di Indonesia, dimana kekuasaan kehakiman merupakan
kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan, dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dari semua
lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh
pemerintahan dan pengaruh-pengaruh lainnya, karenanya suatu kekuasaan
yudikatif haruslah independen. Karena
putusan yang telah diambil oleh majelis
hakim dalam perkara pelanggaran berat HAM terhadap kasus yang dirasa berada
diluar expektasi penuntut umum, haruslah dihargai dengan menggunakan prinsip Rex
Yudicata Pro Feritate Habituer
Pertanggung
jawaban kekuasaan kehakiman dibangun diatas prinsip yang merupakan perpaduan antara tanggung jawab politik
dan kemasyarakatan dengan tanggung jawab hukum. Diatas prinsip itulah kekuasaan
kehakiman dapat bersikap responsive terhadap perkembangan masyarakat. (2)
Pertanggung jawaban dalam
pelanggaran HAM Berat mempunyai karakteristik tersendiri, dalam artian
pelanggaran HAM berat bisa diklasifikasikan adanya tanggung jawab pribadi, juga
adanya tanggung jawab komando. Dalam Pertanggungjawaban pribadi seseorang yang
melakukan pelanggaran berat HAM apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran HAM
Berat dan tindakan yang dilakukan merupakan rumusan dari Tindak Pidana
Pelanggaran Berat HAM sebagaimana ditentukan secara limitatif dalam
undang-undang, maka memberikan konsekwensi kepada pelakunya untuk bertangung
jawab.
Lebih luas lagi ada jenis
pertanggungjawaban komando, yang bisa membebaskan seseorang pelaku pelanggaran
HAM Berat manakala ada komando dalam perbuatan yang dilakukannya, artinya
tanggung jawab pelanggaran berat HAM berat tersebut beralih kepada komandan,
yang tentunya hal ini harus dibuktikan dengan pembuktian yang akurat terhadap
sistem komando yang telah dilaksanakan, dengan tetap memperhatikan sistem
pertanggung jawaban pidana.
Dengan pemikiran yang demikian juga bisa
dipakai sebagai upaya untuk menjadikan pelaku dan juga juga komandan yang
melakukan tindak pidana termasuk didalamnya adalah pelanggaran berat HAM untuk
tidak bisa mengelak terhadap pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang
dilakukannya, sehingga keduanya harus bertanggungjawab.
Sebagai bahan rujukan terhadap pertanggung
jawaban komando ini bisa dirujuk pada Yurisprudensi Internasional dalam
beberapa kasus yang pernah terjadi diantaranya adalah kejahatan perang pada
Mahkamah Nurenberg dan juga Mahkamah Tokyo, yang kesemuanya itu adalah untuk
memenuhi prinsip fundamental yang berlaku universal dalam hukum pidana yaitu
prinsip aut punere aut dedere tidak boleh ada kejahatan yang berlalu
tanpa hukuman.(3)
Hal mana berkesesuaian antara beberapa kasus dalam pelanggaran berat dengan teori Tanggung
jawab multlak atau tanggungjawab
Absolud/retributif yang dikemukakan oleh Imanuel Kant dan Hegel, (4) yang
berpandangan bahwa setiap yang melakukan kejahatan harus bertanggung jawab,
menjadi sebuah teori yang relevan dalam menangani pelanggaran berat Hak Asasi
Manusia.
Peran Negara dalam Pelangaran HAM Berat
Berdasarkan komparansi di beberapa negara sejatinya banyak varian
cara-cara yang digunakan dalam menangani pelanggaran HAM berat ini, yang hingga
saat ini ada beberapa model (5) dalam upaya menuntut dan mengadili pelanggaran HAM berat, yaitu:
- Penuntutan
dan Pengadilan Reguler, seperti penuntutan terhadap Pinoched di Chilli, John
Walker Lind di Amerika Serikat.
- Internasional
atau Extra-teritorial, seperti tuntutan Spanyol untuk mengekstradisi Phinoched
dari Inggris.
- Nasional
tapi spesial, sperti pengadilan HAM ad hoc di Indonesia dalam kasu pelanggaran
HAM di Timor Timor, dan/atau (yad) Tanjung Priok.
- Mix model
seperti dicontohkan di Sierra Lione dan Kamboja, dimana mayoritas hakimnya dari
kamboja dan selebihnya dari negara lain yang difasilitasi PBB, atau sebaliknya.
Dan di Kamboja ini belum terlaksana karena PBB keberatan untuk bergabung karena
Pemerintahan Kamboja cenderung akan melindungi kroni Pol Pot, sehingga
pengadilannya diprediksi akan menjadi sandiwara hukum.
- Internasional
ad hoc, seperti dicontohkan dalam ICTY dan ICTR.
- Pengadilan
yang administrasinya dilakukan oleh PBB seperti yang dilakukan di Kosovo dan
Timor Timur selama berada dalam kekuasaan UNTAET, karena di daerah tersebut
belum ada pemerintahan.
- Pengadilan
Internasional yang permanen, yang otoritasnya global seperti halnya ICC (the
International Criminal Court).
- Pengadilan
Militer regular yang mengadili tentara dan musuh tentara.
- Pengadilan Militer Khusus.
Dengan
mendasarkan pada hukum positif di Indonesia, dalam beberapa kasus yang telah
dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM terhadap dugaan telah terjadi Tindak
Pidana Pelanggaran HAM Berat, penyelidikan yang secara menyeluruh dan detail,
serta dakwaan maupun tuntutan telah
dilakukan secara komprehensif oleh Jaksa Agung, namun demikian dengan
persidangan yang terbuka untuk umum yang akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan, pada akhirnya
dakwaan yang telah disusun dengan sesuai kaedah yang ada, dinilai oleh oleh
majelis hakim belum dapat membuktikan terjadinya delik tersebut sehingga harus
dibebaskan, serta kalaupun bisa dibuktikan tetapi oleh Majelis hakim dimaknai
bahwa perbuatan tersebut bukan masuk kualifikasi pelanggaran berat HAM. Inilah
yang terjadi dalam persidangan yang telah dilakukan pada Pengadilan HAM Ad Hoc
maupun pengadilan HAM permanen yang sudah diuraikan diatas.
Problematika
yang demikian seharusnya menjadi
pelajaran yang berharga bagi Aparat Penegak Hukum untuk lebih menerapkan unsur
kehati-hatian dan kecermatan yang tinggi dalam menyikapi suatu peristiwa yang
terjadi, apalagi rentang waktu kejadian yang sudah lama, dan tentunya lebih
mempersulit pengumpulan barang bukti, serta menjadikan perkara tersebut sulit
untuk dilacak. Hal mana juga sudah disinyalir oleh Undang-undang yang
menetapkan bahwa pelanggaran HAM Berat itu merupakan perkara yang tergolong Extra Ordinary Crime yang tentu sangat
rumit dan membutuhkan cara cara yang Extra Ordinary Measures.
Sejatinya
UUm juga sudah mebuka peluang penyelesaian
pelanggaran HAM berat menggunakan jalur lainnya, yaitu jalur Non Penal, hal
mana dituangkan dalam BAB X Ketentuan Penutup, Pasal
47 UU 26/2000, yaitu 1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi
sebelum berlakunya Undang-undang ini, tidak menutup kemungkinan penyelesaiannya
dilakukan oleh Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. 2) Komisi Kebenaran dan
rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam
ayat 1 dibentuk dengan Undang-undang.
Dengan
berpedoman pada ketentuan pasal 47 Undang-undang tersebut, maka lahirlah
Undang-undang Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi,
yang didalamnya mengatur beberapa hal diantaranya:
1. Menyelidiki
dan mengungkapkan pelanggaran HAM Berat
2. Menyelesaikan
kasus-kasus pelanggaran HAM
3. Meningkatkan
Kesadaran dan Pendidikan HAM
4. Meningkatkan
Rekonsoliasi Nasional.
Pada intinya
Undang-undang ini mencoba mengakomodir cara-cara penyelesaian yang dilakukan
dengan mekanisme non penal, artinya lebih kepada alternatif penyelesaian di
luar pengadilan HAM dengan maksud dan tujuan akhir untuk meningkatkan
rekonsoliasi Nasional dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini
bermakna bahwa pembuat undang-undang rupanya juga menyadari bahwa perkara
pelanggaran HAM berat ini merupakan perkara yang banyak bersinggungan dengan
berbagai dimensi dalam kehidupan bernegara baik secara sosial politik, juga
berhubungan dengan pandangan dunia Internasional yang masih mempunyai persepsi
berbeda dengan pandangan Nasional, tentunya dengan banyaknya dimensi yang
mempengaruhi tersebut menjadi perkara ini merupakan perkara yang tidak
sederhana dan memerlukan cara-cara yang tepat dalam menyelesaikannya, tidak
hanya berimplikasi pada faktor yudisial semata.
Dalam perkembangannya setelah melaui mekanisme Judicial Review, UU Nomor 27 Tahun 2004
Tentang KKR tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi yang amarnya :
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Undang undang Nomor 27 Tahun
2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsoliasi bertentangan dengan Undang
undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.
Untuk
memahami peran negara dalam menangani
kasus pelanggaran HAM Berat ini, digunakan teori Kedaulatan Negara Menurut Jean
Bodin dan Georg Jelinek, yaitu
: Negaralah yang menciptakan hukum, jadi segala seuatu harus tunduk kepada
negara, negara disini dianggap sebagai suatu keutuhan yang menciptakan
peraturan-peraturan hukum, jadi adanya hukum karena adanya negara, dan tiada
satu hukum pun yang berlaku jika tidak dikehendaki suatu negara. (6)
Demikian juga mengenai peran negara ini juga bisa disandarkan pada teori
hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo (7) bahwa pemaknaan aturan-aturan hukum yang bersifat abstrak haruslah
disandarkan pada kepentingan manusia sebagai subyek dari hukum tersebut, hal
mana membawa konsekwensi bahwa aturan-aturan hukum lebih mengedepankan pada
pada perasaan keadilan yang dianut oleh rakyat banyak.
Karena itu hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan
manusia/rakyat sebagai titik orientasinya, maka harus memiliki kepekaan pada
persoalan-persolana yang timbul dalam hubungan antar manusia, yang salah satu
persoalan krusial dalam hubungan-hubungan sosial adalah keterbelengguan manusia
pada struktur yang menindas, baik ekonomi politik, maupun sosail dan budaya.
Maka hukum progresif harus tampil sebagai institusi yang emansipatoris atau
yang membebaskan.
Berkesesuaian
antara teori kedaulatan negara tersebut dengan teori hukum progresif yang kedua
teori tersebut memberikan jalan yang lapang kepada negara dalam menyelesaikan
pelanggaran berat HAM yang terjadi dalam negara tersebut, artinya negera
mempunyai bebrapa alternatif cara-cara yang dipakai yang sejalan dengan
penafsiran didirikannya negara tersebut, yang kesemuanya bermuara pada tujuan
lahirnya suatu negara.
Khatimah
Peran negara dalam penegakan hukum utamanya dalam
pelanggaran Hak Asasi Manusia semuanya tertuang dalam aturan-aturan yang ada
yang merupakan regulasi yang dibuat oleh negara melalui aparatnya agar terjadi keseimbangan
antara upaya yang dilakukan oleh masyarakat dengan masyarakat yang lain, hal
mana sebagai suatau pedoman yang dilakukan oleh negara terutama apabila terjadi
pelanggaran yang terjadi.
Disamping itu negara juga mempunyai seperangkat alat yang digunakan,
demikian juga negara berhak untuk melakukan cara-cara tersendiri dalam upaya
untuk menjadikan terjadi keseimbangan yang ada dalam masyarakat.
Keseimbangan tersebut dimaknai sebagai upaya untuk
mewujudkan kebahagiaan bersama yang dirancang oleh negara sebagaimana ternyata
dalam rumusan cita-cita bangsa Indonesia dalam membentuk masyarakat yang adil dan makmur.
Sebagai pihak yang mempunyai segala fasilitas yang ada dan
juga sebagai pihak yang mendapatkan amanat konstitusi, maka negara haruslah menjamin
akan terjadinya kebersamaan dalam naungan masyarakat yang dicita-citakan oleh
konstitusi, sebagaiman tertuang dalam Mukadimah UUD 1945 dan lebih operasional
lagi dalam pasal-pasal UUD 1945.
Upaya pemerintah untuk mencari jalan lain agar beberapa pelanggaran
HAM berat yang sudah dilakukan penyelidikan oleh Komnas HAM mendapatkan saluran yang tepat merupakan
suatu cara jalan tengah untuk mengatasi terjadinya pelanggaran HAM berat,
tentunya dengan memperhatikan cara-cara yang yang manusiawi dan bermartabat
terutama untuk korban dan para ahli warisnya, dengan demikian juga tetap
mengedepankan prinsip pertanggung jawaban pidana serta, bukanlah pembenaran dan
juga impunitas terhadap pelaku yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM
Berat. Negara dengan demikian hadir untuk mengatasi problematika yang terjadi
dalam masyarakat dengan mengedepankan solusi jalan tengah dalam menyelesaiakn
problematika yang ada. (ldr/wi)
LITES FINIRI OPORTET
....
Penulis: Dr.H. Moh.Puguh Haryogi, SH, Sp.N,M.H adalah Hakim Ad Hoc HAM pada Mahkamah
Agung Republik Indonesia.
Tulisan merupakan pendapat pribadi, tidak mewakili
pendapat lembaga.
REFRENSI
(1) Artijo Alkostar,
Peradilan HAM di Indonesia Dan Peradaban, Makalah Disampaikan dalam
diskusi HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UI, Yogyakarta, 15 Juni 2002.
(2) Sarwata, Kebijaksanaan dan strategi Penegakan
Sistem Peradilan di Indonesia, Lemhanas Jakarta,
1997, Hal. 3.
(3) Joko Sasmito, Konsep
Asas Retroaktif Dalam Pidana, Pemberlakuan Asas Retroaktif pada Tindak Pidana
Pelanggaran HAM di Indonesia, Setara Press, Malang, 2017, Hal.
132.
(4) Moh.Puguh
Haryogi, Peran Dan Tanggung Jawab Dalam Pelanggaran HAM oleh
Organisasi/Korporasi, Makalah
disampaikan pada Diskusi HAM, tanggal 16 September 2025, Hal.5.
(5) Artijo Alkostar,
Peradilan HAM di Indonesia Dan Peradaban, Makalah Disampaikan dalam diskusi
HAM yang diselenggarakan oleh PUSHAM UI, Yogyakarta, 15 Juni 2002.
(6) Soehino,
Ilmu Negara, Penerbit Liberty, Yogjakarta, 1998, Hal. 155.
Baca Juga: Komnas HAM : Restorative Justice Bukan Celah Transaksi Hukum
(7) Bernard L Tanya
Dkk, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi, 2006,
CV.Kita Surabaya, hal. 175.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI