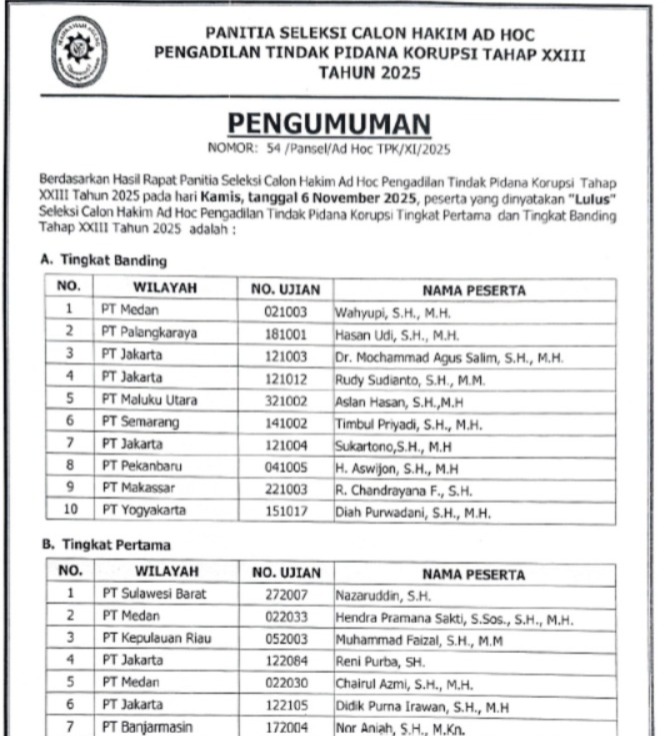Dalam lanskap praktik peradilan perdata Indonesia, diskursus mengenai kemungkinan penggabungan (kumulasi) gugatan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu proses litigasi merupakan salah satu episentrum doktrinal yang paling fundamental dan persisten.
Problematika ini berakar dari sebuah fenomena yuridis yang dikenal sebagai samenloop van vorderingen atau konkurensi tuntutan, di mana satu perbuatan faktual (een feitelijke handeling) yang dilakukan oleh tergugat secara simultan diduga melanggar dua sumber perikatan yang berbeda.
Perbuatan tersebut, di satu sisi, mencederai janji kontraktual yang melahirkan pertanggungjawaban ex contractu (wanprestasi), dan pada saat yang bersamaan, melanggar norma kepatutan atau kaidah hukum objektif yang melahirkan pertanggungjawaban ex delicto (PMH).
Baca Juga: Jalan Keadilan Itu Bernama Harmonisasi Yurisprudensi dan SEMA Perdata
Justifikasi atas penggabungan ini ditopang oleh dua pilar: pilar hukum acara formil yang menganut asas ekonomi prosesual (proces economie) demi peradilan yang efisien, yang spiritnya dapat ditarik secara analogis dari Pasal 158 RBg dan Pasal 132b HIR, serta pilar hukum perdata materiil yang mengakui dualisme sumber perikatan sebagaimana termaktub dalam postulat fundamental Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Namun, praktik peradilan diwarnai oleh antagonisme semu dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, di mana sebagian putusan (seperti Putusan MA Nomor 1875 K/Pdt/1984) seolah melarang penggabungan secara mutlak, sementara lini putusan lainnya (seperti Putusan MA Nomor 2686 K/Pdt/1985) justru mengizinkan hakim melakukan kualifikasi ulang.
Artikel ini akan mendemonstrasikan bahwa pertentangan tersebut sesungguhnya ilusi, dan bahwa Mahkamah Agung secara konsisten menerapkan sebuah doktrin tunggal yang koheren, yang bertujuan untuk purifikasi dogmatis dan penegakan disiplin hukum acara.
Sikap Mahkamah Agung yang tampak fluktuatif sesungguhnya berangkat dari satu aksioma yang tidak tergoyahkan: demarkasi absolut antara wanprestasi dan PMH berdasarkan sumber perikatannya sebagaimana digariskan secara definitif oleh legislator dalam Pasal 1233 KUH Perdata.
Perbedaan fundamental ini melahirkan dua rezim pertanggungjawaban yang secara diametral berlainan, mulai dari unsur-unsur konstitutif, alokasi beban pembuktian (bewijslast), hingga remedi hukum yang tersedia. Lini yurisprudensi pertama yang menyatakan gugatan kumulatif tidak dapat diterima harus dipahami bukan sebagai larangan terhadap kumulasi itu sendiri, melainkan sebagai sanksi prosedural terhadap surat gugatan yang secara formil cacat karena kabur (obscuur libel).
Dalam kasus-kasus tersebut, penggugat secara serampangan mengamalgamasikan dalil-dalil faktual (posita) dan tuntutan (petitum) dari kedua rezim dalam satu narasi tunggal yang tidak terpilah. Kekaburan ini menciptakan paradoks prosedural yang fatal, terutama terkait pembuktian unsur "kesalahan" (schuld). Dalam wanprestasi, kesalahan debitur dipresumsikan ada setelah ia dinyatakan lalai melalui somasi (Pasal 1238 KUH Perdata), sehingga beban pembuktian beralih kepada debitur untuk membuktikan adanya keadaan memaksa (overmacht).
Sebaliknya, dalam PMH, penggugat memikul beban penuh untuk membuktikan secara aktif adanya kesalahan pada diri tergugat sesuai asas umum dalam Pasal 1865 KUH Perdata atau Pasal 163 HIR. Gugatan yang kabur menempatkan hakim dalam posisi mustahil untuk menerapkan hukum pembuktian secara adil dan mencederai hak esensial tergugat untuk membela diri (audi et alteram partem), sehingga secara tepat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).
Di sisi lain, lini yurisprudensi kedua yang mengizinkan hakim melakukan intervensi, yang kini dikodifikasi dalam SEMA Nomor 01 Tahun 2022, merespons situasi prosedural yang sama sekali berbeda: yakni kasus miskwalificatie (kesalahan kualifikasi hukum) murni.
Dalam skenario ini, posita gugatan disusun secara jernih, konsisten, dan lengkap yang secara eksklusif mendalilkan fakta-fakta wanprestasi, namun penggugat secara keliru memberinya label PMH dalam petitum. Gugatan semacam ini secara faktual tidak kabur.
Oleh karena itu, hakim, berdasarkan kewajiban jabatannya yang termaktub dalam adagium ius curia novit (hakim dianggap mengetahui hukumnya) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 178 ayat (1) HIR, wajib mengabaikan label hukum yang keliru dan menerapkan hukum yang benar (rezim kontraktual) terhadap fakta-fakta yang telah didalilkan secara jelas.
Kedua lini yurisprudensi ini, jika dibaca secara dialektis, justru saling meneguhkan sebuah prinsip agung: hakim terikat pada fakta yang didalilkan para pihak (lijdelijkheid van de rechter), namun hakim adalah penguasa hukum.
Jika fakta yang disajikan kabur, hakim tidak dapat memperbaikinya, namun jika fakta yang disajikan jernih, hakim wajib menerapkan hukum yang benar. Ini bukan sekadar adjudikasi, melainkan sebuah bentuk pedagogi yudisial dari Mahkamah Agung untuk mendisiplinkan praktik beracara.
Konsekuensi logis dari rekonsiliasi doktrinal ini adalah bahwa satu-satunya jalan prosedural yang sah untuk mengajukan kedua landasan hukum adalah melalui struktur gugatan yang bersifat hirarkis (primair-subsidair) atau alternatif.
Penggugat wajib menyusun dua rangkaian posita dan petitum yang terpisah dan otonom. Struktur yang presisi ini berfungsi sebagai gerbang prosedural yang sekaligus menjadi filter kompetensi yuridis, ia menuntut seorang praktisi hukum untuk memahami secara mendalam perbedaan dogmatis antara kedua rezim.
Struktur ini pula yang memandu hakim untuk melakukan ajudikasi secara berjenjang: menguji dalil primair terlebih dahulu, dan hanya jika dalil primair gagal terbukti, barulah beralih memeriksa dalil subsidair dengan perangkat pembuktian dan remedi yang sepenuhnya berbeda.
Implikasi lebih lanjut yang tak terhindarkan adalah terkait pembatasan remedi. Sebagaimana ditegaskan dalam SEMA 01/2022, apabila hakim merekualifikasi suatu gugatan menjadi wanprestasi, maka petitum ganti rugi immateriil mutlak harus ditolak.
Penolakan ini bukanlah pelanggaran terhadap hukum pembuktian, sekalipun penggugat berhasil membuktikan penderitaan batinnya.
Ini adalah persoalan relevansi hukum (quaestio juris), bukan pembuktian fakta (quaestio facti). Sekali perkara diadili dalam koridor wanprestasi, maka hukum materiil yang berlaku adalah Pasal 1247 KUH Perdata yang secara limitatif membatasi ganti rugi hanya pada kerugian yang dapat diduga (foreseeability) saat kontrak dibuat, di mana kerugian immateriil pada umumnya berada di luar cakupan tersebut.
Ketegasan doktrinal ini, meskipun tampak kaku, sesungguhnya melayani tujuan efisiensi jangka panjang yang lebih luhur, yakni menciptakan kepastian hukum dan prediktabilitas, terutama dalam lalu lintas hubungan kontraktual.
Antagonisme yang tampak dalam yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kumulasi gugatan wanprestasi dan PMH pada hakikatnya adalah sebuah ilusi. Analisis yang mendalam menunjukkan adanya sebuah doktrin tunggal yang koheren dan konsisten, yang berpusat pada satu kriteria fundamental: kejernihan dan ketegasan dalil-dalil faktual (posita) dalam surat gugatan.
Mahkamah Agung secara tegas membedakan antara gugatan yang secara substansial kabur (obscuur libel) akibat amalgamasi fakta yang serampangan, yang harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan gugatan yang faktanya jernih namun hanya mengalami kesalahan kualifikasi hukum (miskwalificatie), di mana hakim wajib menerapkan asas ius curia novit.
Rekonsiliasi ini memberikan kepastian hukum dengan menawarkan sebuah jalur prosedural yang jelas, meskipun menuntut, bagi para pencari keadilan, yakni melalui formulasi gugatan yang terstruktur secara hirarkis (primair-subsidair).
Baca Juga: Dari Wanprestasi ke Pidana: Titik Singgung Eksekusi Jaminan Fidusia
Pada akhirnya, purifikasi dogmatis yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini bukan hanya menyelesaikan sebuah perdebatan yuridis, tetapi juga menetapkan standar profesionalisme dan kecermatan yang tinggi, menegaskan bahwa kemampuan untuk menavigasi persimpangan antara hukum kontrak dan hukum delik adalah cerminan dari kematangan dan keahlian seorang jurist modern di Indonesia. (ldr)
Penulis Dr. Bony Daniel, S.H., M.H. adalah Hakim PN Serang
Tulisan ini pendapat pribadi penulis yang tidak mewakili pendapat lembaga.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI