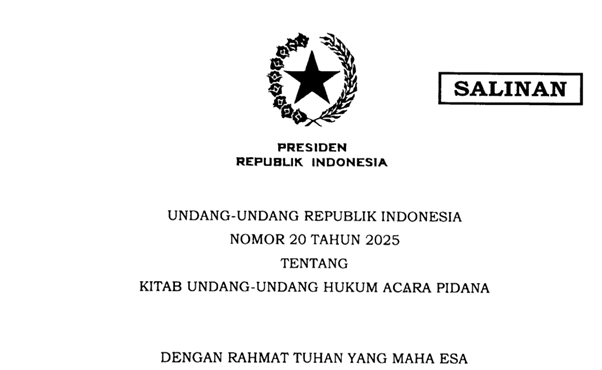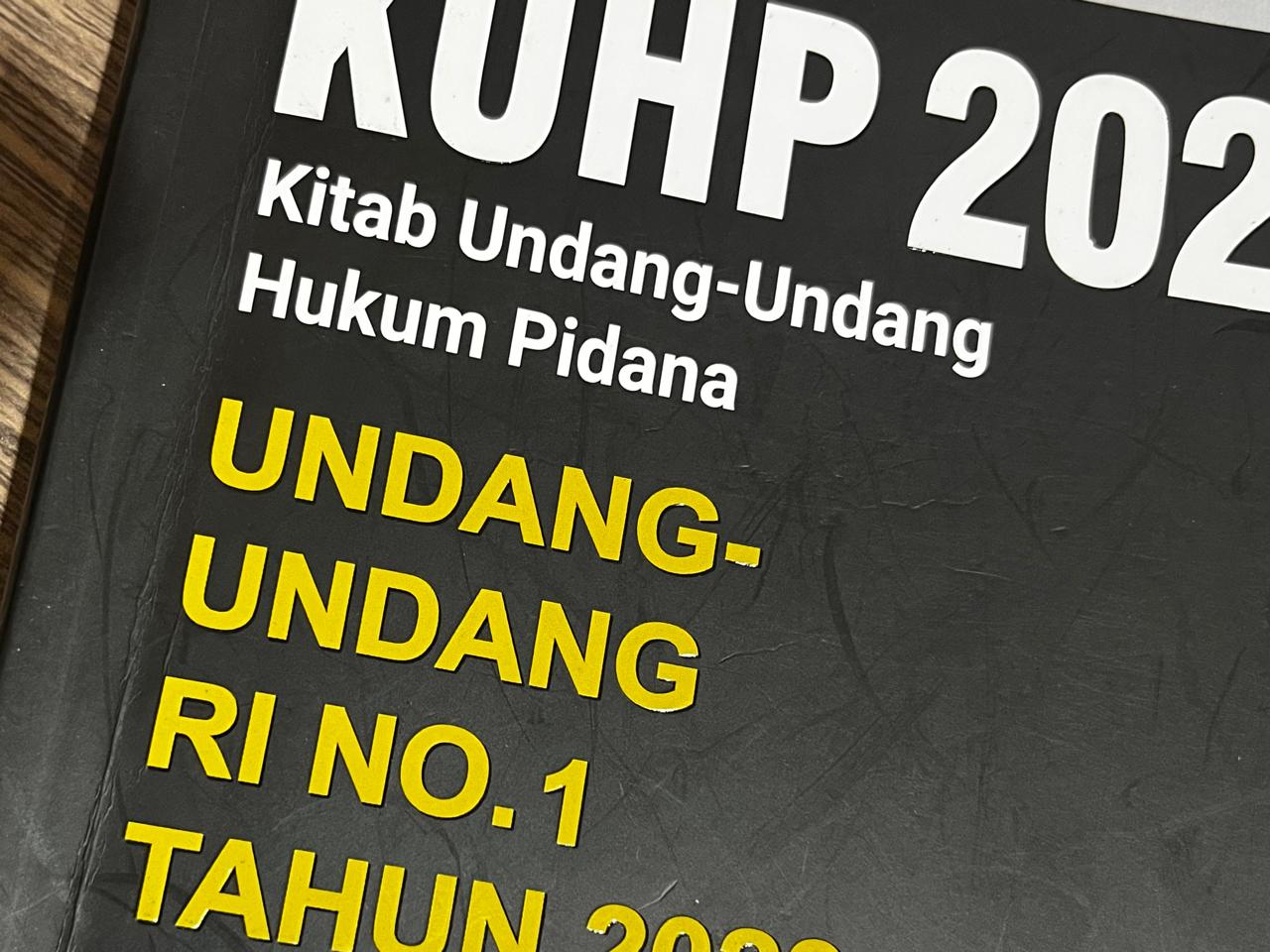Krisis sosial sering
merobek sendi-sendi kehidupan bersama. Jalanan dipenuhi suara protes, air mata
keluarga korban menetes, dan institusi negara ditantang mempertahankan
legitimasinya. Namun di tengah hiruk pikuk itu, ada satu kebutuhan yang tidak
boleh hilang: keadilan.
Tanpanya,
darurat hanya akan melahirkan kekerasan yang dilegalkan. Realitas ini kembali
mengemuka dalam gelombang demonstrasi Agustus 2025 yang melanda berbagai kota
di Indonesia.
Aksi yang
bermula dari protes terhadap kebijakan kontroversial berakhir tragis dengan
jatuhnya korban jiwa, mulai dari Affan Kurniawan, pengemudi ojek online yang
tewas dilindas kendaraan taktis Brimob, hingga empat korban di Makassar yang
meliputi petugas dan warga sipil.
Peristiwa ini
mengingatkan pada pola berulang dalam sejarah Indonesia: kerusuhan Mei 1998
yang berakar pada krisis ekonomi-politik, konflik Aceh dengan basis separatisme
bersenjata, dinamika Papua yang kompleks dengan isu identitas dan pembangunan,
hingga demonstrasi-demonstrasi kontemporer yang lebih sering berfokus pada
kebijakan pemerintah.
Masing-masing
krisis memiliki karakter yang berbeda, tetapi benang merahnya sama: selalu
muncul dilema antara menjaga stabilitas negara dan menegakkan hak asasi manusia.
Di tengah
situasi seperti ini, pengadilan tidak boleh berhenti beroperasi, justru diuji:
apakah masih mampu menghadirkan rasa keadilan, atau tenggelam dalam logika
darurat yang serba represif?
Dalam menjawab
tantangan tersebut, kita perlu kembali pada fondasi filosofis keadilan itu
sendiri.
Plato dalam Republic
menggambarkan keadilan sebagai harmoni di mana setiap elemen menjalankan
fungsinya dengan baik.
John Rawls
melalui teori justice as fairness-nya juga menekankan bahwa keadilan
harus dipahami dalam posisi asali (original position) di mana setiap
orang tidak mengetahui posisi sosialnya, sehingga prinsip-prinsip yang dipilih
akan adil bagi semua.
Sementara itu,
Pancasila mengajarkan keadilan sosial sebagai cita-cita bangsa yang harus
diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan bernegara.
Dari perspektif
manapun, keadilan bukan boleh absen saat krisis, melainkan harus menjadi
jangkar yang mencegah negara tergelincir pada otoritarianisme. Bahkan dalam
kondisi darurat sekalipun, prinsip salus populi suprema lex esto
(keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi) tidak boleh diartikan sebagai
pembenaran untuk mengorbankan hak-hak dasar warga negara tanpa prosedur yang
adil dan proporsional.
Paradoks utama
yang dihadapi hakim dalam situasi darurat sosial terletak pada tekanan ganda
yang sulit direkonsiliasi. Di satu sisi, ada desakan dari aparatur negara untuk
memberikan putusan yang cepat dan memberikan efek jera, sesuai dengan logika law
and order yang mengutamakan stabilitas.
Tekanan ini
sering kali disertai dengan argumen bahwa situasi luar biasa memerlukan
langkah-langkah luar biasa pula (exceptio facit legem). Di sisi lain,
terdapat hak-hak dasar warga negara yang berisiko dikorbankan, mulai dari hak
atas due process, presumption of innocence, hingga
proporsionalitas hukuman.
Tanpa pedoman
yang jelas, hakim dapat terjebak pada dua ekstrem yang sama-sama berbahaya:
tunduk sepenuhnya pada logika darurat sehingga mengabaikan prinsip-prinsip
hukum fundamental, atau sebaliknya, dianggap mengabaikan kepentingan stabilitas
negara sehingga dinilai tidak responsif terhadap krisis.
Pengalaman
internasional menunjukkan bahwa ketiadaan pedoman ini dapat berujung pada erosi
kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, sebagaimana terjadi dalam
berbagai kasus di negara-negara yang mengalami transisi demokrasi.
Perbandingan
dengan praktik negara lain menunjukkan pentingnya keberadaan pedoman khusus
untuk situasi darurat.
Amerika Serikat,
melalui Emergency Court Administration guidelines yang
dikembangkan pasca-9/11, memberikan kerangka kerja bagi pengadilan untuk tetap
beroperasi dalam situasi krisis sambil mempertahankan due process.
Jerman memiliki
konsep Wehrverfassung yang mengatur bagaimana sistem peradilan harus
beroperasi dalam situasi darurat sambil tetap menjaga prinsip-prinsip negara
hukum.
Bahkan Inggris,
yang tidak memiliki konstitusi tertulis, mengembangkan Civil Contingencies
Act 2004 yang memberikan panduan tentang bagaimana sistem hukum harus beroperasi
dalam kondisi darurat.
Indonesia,
dengan kompleksitas geografis dan sosio-politiknya, membutuhkan adaptasi
prinsip-prinsip tersebut dalam konteks Pancasila dan sistem hukum nasional.
Pengalaman masa lalu Indonesia dengan berbagai bentuk darurat, mulai dari
darurat militer di Aceh, status keadaan bahaya di berbagai daerah, hingga
darurat kesehatan masyarakat saat COVID-19, menunjukkan perlunya standardisasi
pendekatan yudisial yang dapat menjamin konsistensi dan akuntabilitas.
Karena itulah
pedoman mengadili dalam situasi darurat diperlukan bukan untuk membatasi
independensi hakim, melainkan untuk menjaga agar setiap putusan tetap berpijak
pada prinsip keadilan, bahkan ketika jalan negara penuh gejolak.
Menurut penulis,
pedoman ini harus mencakup beberapa elemen kunci:
Pertama, kriteria objektif untuk mengidentifikasi situasi darurat, meliputi
gangguan ketertiban umum yang meluas di berbagai lokasi, ancaman signifikan
terhadap keselamatan publik, dan ketidakmampuan aparatur normal mengatasi
situasi.
Kedua, prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan sanksi, di mana tingkat
pembatasan hak harus sebanding dengan tingkat ancaman aktual, dengan prioritas
rehabilitasi untuk pelaku anak di bawah umur dan pembedaan perlakuan antara
provokator dan peserta pasif.
Ketiga, mekanisme pemeriksaan yang dipercepat namun tetap menghormati due process, termasuk batas waktu
maksimal 1x24 jam untuk pemeriksaan pendahuluan, hak atas bantuan hukum sejak
penangkapan, dan akses keluarga dalam batas wajar.
Keempat, standar pembuktian yang ketat untuk kasus-kasus terkait kerusuhan,
dengan kewajiban verifikasi rekaman video/foto dan larangan penggunaan pengakuan
di bawah tekanan.
Kelima, prosedur khusus untuk perlindungan kelompok rentan seperti diversi
wajib untuk anak di bawah 18 tahun, asesmen kesehatan mental untuk terduga
pelaku, dan proteksi khusus untuk jurnalis.
Keenam, mekanisme oversight dan review berkala setiap 30
hari dengan keterlibatan ombudsman dan Komnas HAM, termasuk sunset clause
untuk pedoman darurat. Implementasi pedoman ini harus disertai dengan pelatihan
khusus bagi para hakim dan aparatur peradilan, serta sistem monitoring yang
melibatkan masyarakat sipil untuk menjaga akuntabilitas.
Pedoman
mengadili dalam situasi darurat pada akhirnya bukan sekadar aturan prosedural,
melainkan janji moral negara bahwa bahkan ketika jalanan penuh asap dan tangis,
hukum tetap berpijak pada keadilan. Dengan pedoman itu, pengadilan dapat
menjaga agar martabat manusia tidak dikorbankan atas nama stabilitas, dan cita
keadilan bangsa tetap bersinar bahkan di tengah gelapnya krisis. (ldr)
Daftar bacaan
Plato, The
Republic, trans. Benjamin Jowett (Moscow: Roman Roads Media, 2013) John
Rawls, A Theory of Justice, revised edition (Cambridge: Harvard
University Press, 1999), 11-15.
Administrative
Office of the US Courts, "Emergency Guidelines for Court Operations,"
Federal Judicial Center
Christoph
Möllers, "The Three Branches: A Comparative Model of Separation of
Powers" (Oxford: Oxford University Press, 2013), 187-210.
Baca Juga: Potensi Konflik Internasional dan Pengaruhnya terhadap Proses Penegakan Hukum di Indonesia
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2004/36/contents.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI