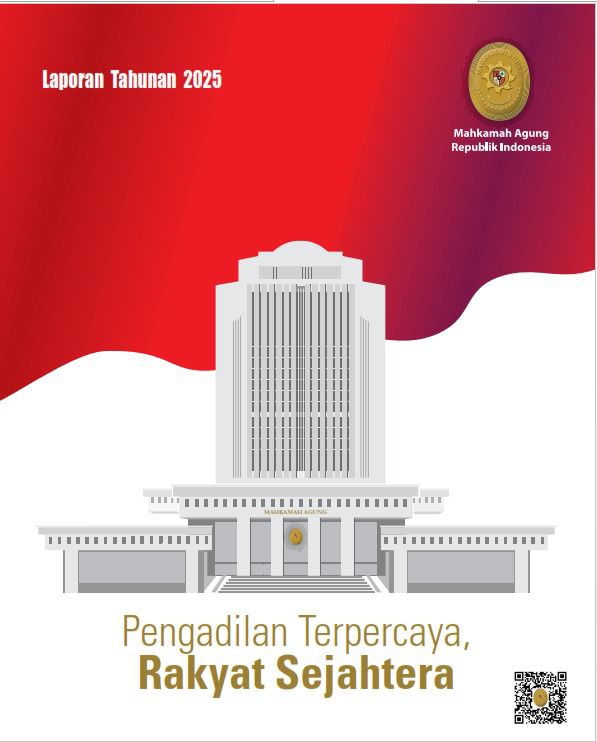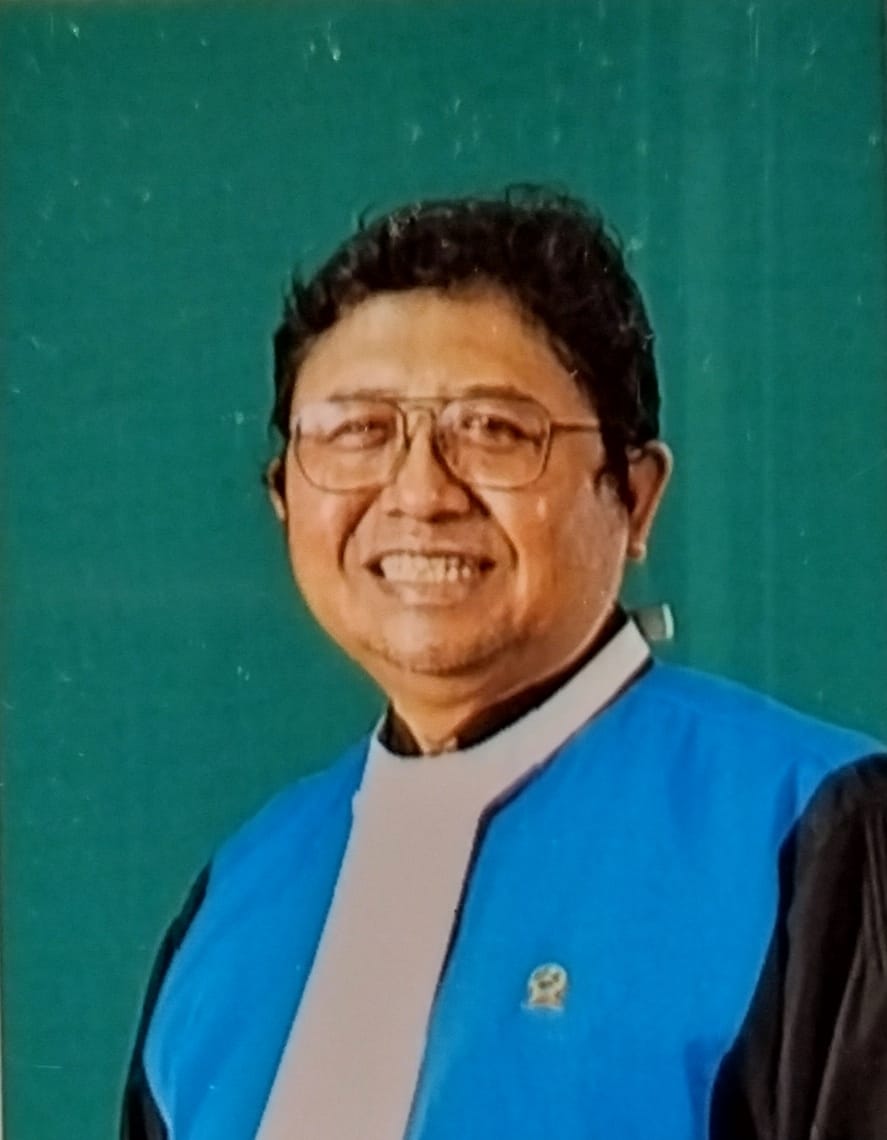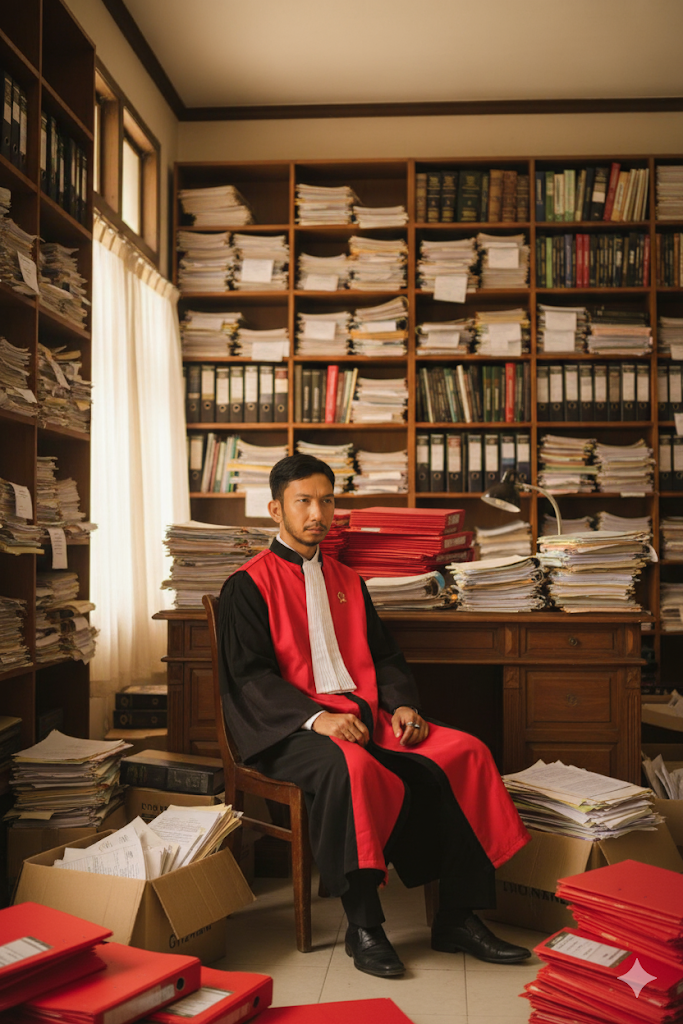Pertanyaan tentang bagaimana negara seharusnya menegakkan hukum pidana sering kali dianggap sebagai persoalan teknis semata. Padahal, cara negara mengelola proses penegakan hukum yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan bahkan hingga pelaksanaan putusan, akan menentukan sejauh mana keadilan dapat dirasakan warga negaranya.
Di ruang sidang, sebagai Hakim, kita semua barangkali pernah melihat
bagaimana prosedur hukum yang longgar memberi ruang bagi penyalahgunaan
kewenangan oleh Aparat Penegak Hukum (APH), sementara prosedur yang terlalu
kaku boleh jadi menghambat usaha mendapatkan kebenaran materiil perkara pidana.
Saat ini Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) hadir sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk menata ulang keseimbangan itu. KUHAP lama, yang telah berlaku lebih dari empat dekade, memang pernah menjadi tonggak reformasi.
Baca Juga: Integrasi Pengadilan Pajak ke MA: Dinamika, Tantangan dan Arah Reformasi Hukum
Namun, perubahan struktur
sosial, kemajuan teknologi informasi, dan perkembangan prinsip hak asasi
manusia menuntut pembaruan mendasar. Reformasi ini bukan hanya soal mengubah
pasal, tetapi juga menyempurnakan mekanisme agar due process of law
berjalan berdampingan dengan fair trial.
Menurut hemat penulis, salah satu fokus utama pembaruan yang penting segera diwujudkan adalah pengawasan yudisial (judicial scrutiny) terhadap penggunaan upaya paksa.
Besar harapan penulis, upaya seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan kini harus diatur dengan alasan yang lebih jelas dan terukur serta diawasi secara periodik oleh Hakim.
Tujuannya jelas, untuk memastikan pembatasan kebebasan hak individu atau warga
negara hanya dapat dilakukan dengan dasar hukum yang sahih, proporsional, dan bertanggung
jawab.
Selain itu, perlu adanya redefinisi pengaturan mengenai mekanisme restorative justice (RJ) di dalam RUU KUHAP agar tidak menjadi salah kaprah yang berujung pada atribusi kewenangan kepada masing-masing pejabat dalam setiap tingkatan sistem peradilan pidana.
Bagaimana mungkin RJ terhadap tindak pidana dapat dilakukan di tingkat penyelidikan. Padahal kita tahu semua bahwa di tingkat penyelidikan, suatu peristiwa yang terjadi belum jelas disebut tindak pidana.
Lebih lanjut, meskipun setiap tahap sistem peradilan pidana diberi kewenangan untuk menerapkan RJ, namun pada akhirnya, hakimlah sebagai pemegang kuasa yudisial yang berhak menilai layak atau tidaknya produk dari RJ tersebut diterbitkan.
Sebab, nantinya pendekatan ini akan
menjadi bingkai untuk mengakomodir norma-norma dalam KUHP Nasional yang kini
lebih mengedepankan pemulihan, menghindarkan stigmatisasi, dan menekankan
reintegrasi sosial daripada sekadar penghukuman.
Tak lupa, besar harapan penulis RUU KUHAP juga mengatur larangan membentuk opini bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Pembatasan pengumuman penetapan tersangka secara berlebihan atau penggunaan atribut yang menimbulkan stigma tertentu yang merupakan perlindungan konkret terhadap asas praduga tak bersalah (presumption of innocence).
Dalam lanskap hukum Indonesia yang sudah kadung terpapar arus informasi instan,
langkah ini berfungsi sebagai penahan derasnya vonis sosial (trial by the
press) yang kerap mendahului putusan pengadilan.
Namun di sisi lain, RUU KUHAP juga tampaknya akan memperkenalkan prosedur baru. Perluasan kewenangan upaya paksa terhadap kejahatan tertentu, termasuk kejahatan berbasis teknologi informasi yang merupakan respons terhadap kompleksitas tindak pidana kontemporer.
Demikian pula, pengaturan
sanksi pidana terhadap pelanggaran prosedural yang sebelumnya tidak diatur
secara eksplisit dapat menunjukkan komitmen peningkatan efektivitas dalam penegakan
hukum. Meski demikian, langkah-langkah ini memerlukan pengawasan ketat agar
tidak berubah menjadi instrumen penindasan atau ekstensi kekuasaan yang tidak
proporsional.
Sebagai seorang Hakim, penulis memandang RUU KUHAP ini seperti sebuah peta baru yang akan memandu perjalanan peradilan pidana kita.
Tetapi peta yang baik tak hanya menggambarkan jalan menuju tujuan (baca:
keadilan), ia juga harus menandai potensi bahaya atau bahkan jalan buntu
yang mungkin saja terjadi. Pengaturan prosedur yang berlebihan boleh jadi akan membuat
jalan menjadi penuh rintangan, sementara absennya
prosedur justru akan meninggalkan jalur rawan tanpa penerangan.
Sejatinya, reformasi hukum acara pidana tidak akan begitu tampak dan terasa ketika sedang diuji di ruang sidang DPR atau meja para akademisi, namun implementasi semua ini justru akan lebih terasa ketika pasal demi pasal dalam KUHAP yang baru nantinya menyambangi lorong-lorong kantor polisi, meja para jaksa, kursi-kursi saksi, bangku terdakwa, dan tentu saja meja Majelis Hakim.
Di sanalah kita akan tahu, apakah reformasi hukum acara
pidana dalam RUU KUHAP benar-benar bisa menjemput ‘keadilan baru’, atau hanya
mengganti seragam lama dengan potongan kain baru.
Baca Juga: Sebuah Harapan kepada Ketua PN Jakpus yang Baru
Reformasi penegakan hukum acara pidana melalui RUU KUHAP adalah momentum penting untuk menata ulang hubungan antara kekuasaan negara dan hak warga negara dalam proses peradilan pidana. Dengan pembatasan penggunaan upaya paksa, redefinisi keadilan restoratif, penguatan perlindungan asas praduga tak bersalah, serta reformulasi sanksi prosedural, pembaruan ini berupaya membangun sistem yang lebih proporsional, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.
Keberhasilannya akan sangat bergantung pada konsistensi
penerapan norma, pengawasan yang memastikan hukum tetap menjadi pelindung,
bukan alat penindasan, dan yang tak kalah penting adalah integritas para APHnya. (IKAW/LDR)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI