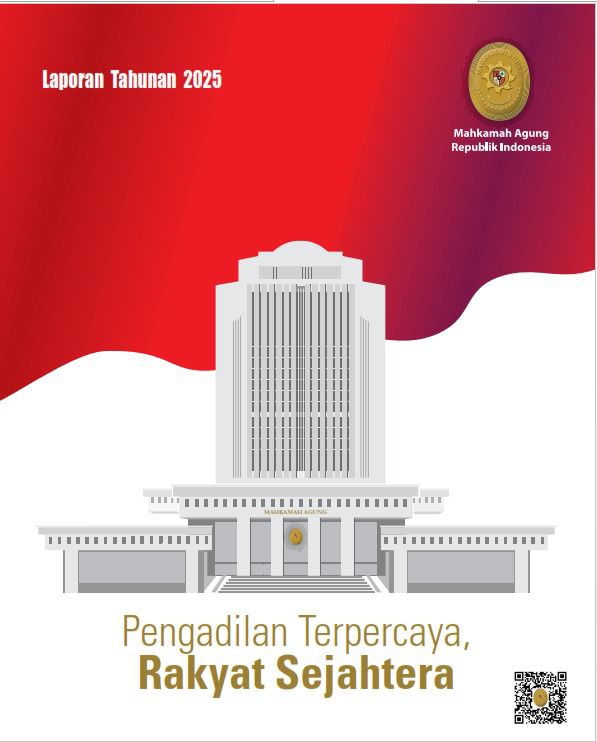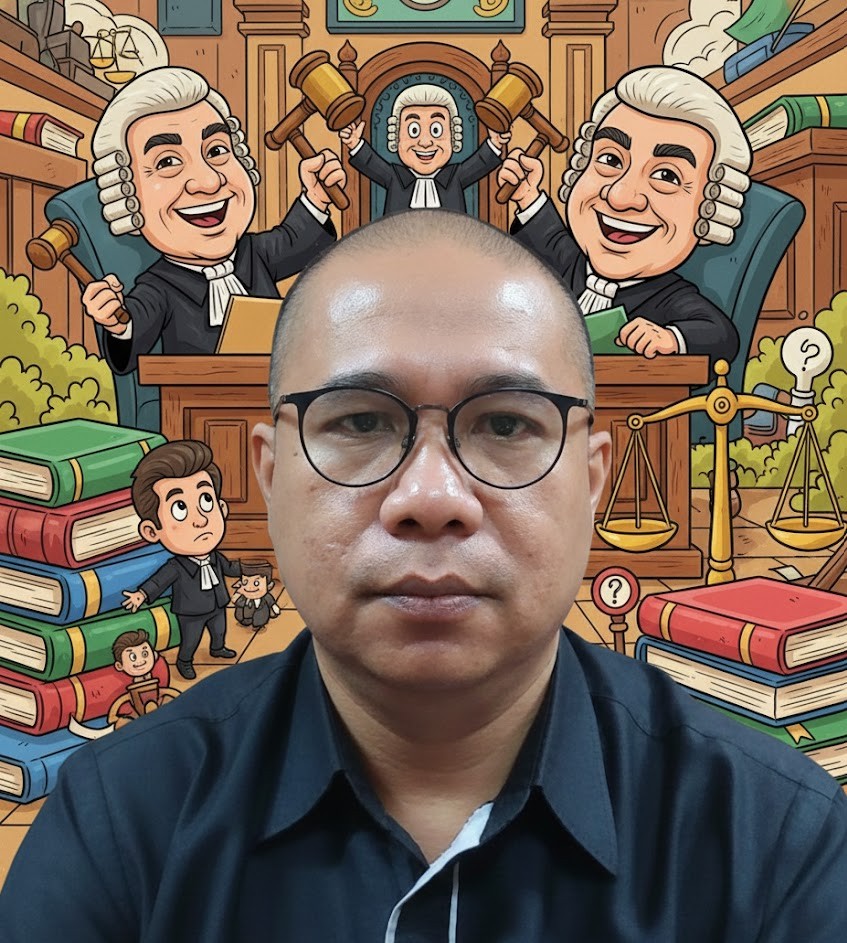Sekitar tiga tahun pasca lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XX/2022 mengenai uji materiil terhadap ketentuan norma Pasal 143 ayat (3) KUHAP, masih meninggalkan diskursus di kalangan praktisi maupun akademisi yang belum kunjung menemukan titik terang.
Putusan tersebut secara eksplisit telah menyatakan frasa “batal demi hukum” dalam Pasal 143 ayat 3 KUHAP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum yang telah dinyatakan batal atau batal demi hukum oleh hakim dapat diperbaiki dan diajukan kembali dalam persidangan sebanyak 1 (satu) kali, dan apabila masih diajukan keberatan oleh terdakwa/penasihat hukum, hakim langsung memeriksa, mempertimbangkan, dan memutusnya bersama-sama dengan materi pokok perkara dalam putusan akhir”.
Berlakunya norma tersebut memungkinkan Hakim menemui kondisi nyata di mana surat dakwaan yang sebelumnya dinyatakan batal demi hukum yang kemudian dilimpahkan lagi untuk kedua kalinya dan diajukan keberatan kembali oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya namun saat ditelaah, Majelis Hakim menilai surat dakwaan itu masih tidak disusun secara lengkap, cermat dan jelas sebagaimana Pasal 143 ayat 2 KUHAP akan tetapi, Majelis Hakim menilai berdasarkan fakta persidangan menunjukkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan dan Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana.
Baca Juga: Dialektika Norma dan Prosedur Perma 1/2022: Wujud Artikulasi Keadilan Restitutif
Kemudian, dalam situasi demikian, apa langkah yang harus dipilih oleh Majelis Hakim? Apakah membatalkan dakwaan Penuntut Umum untuk yang kedua kalinya dengan mengabaikan fakta bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal yang didakwakan, atau “menutup mata” atas kecacatan dakwaan Penuntut Umum dan memutus Terdakwa terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah?
Pilihan pertama, Majelis Hakim dapat menyatakan dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum untuk kedua kalinya, maka amar pada putusan akhir hanya sebatas menyatakan dakwaan batal demi hukum dengan konsekuensi perkara a quo tidak dapat diperiksa dan diadili untuk ke tiga kalinya.
Pilihan ini bertitik berat pada keadilan prosedural bahwa dalam memutus perkara, Majelis Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan (vide Pasal 182 ayat 4 KUHAP). Apabila dakwaannya saja cacat karena tidak disusun secara cermat, maka sudah seharusnya dakwaan dinyatakan batal demi hukum (vide Pasal 143 ayat 3 KUHAP), lantas atas dasar apa Majelis Hakim menjatuhkan putusan akhir sedangkan dakwaan batal demi hukum?
Akibatnya, putusan tersebut tidak memberikan kepastian apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atau tidak, tidak juga memberi manfaat ataupun keadilan bagi Korban dan Terdakwa. Sedangkan, dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim sudah memeriksa Saksi-saksi dan alat bukti lainnya sehingga sejatinya bisa menyimpulkan apakah Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana atau tidak.
Pilihan kedua, Majelis Hakim “pura-pura” tidak melihat kecacatan yang termuat dalam surat dakwaan tersebut dan menentukan apakah Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana atau tidak dengan tujuan memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi Korban maupun Terdakwa. Pilihan ini akan dinilai tidak berpedoman pada Pasal 143 juncto Pasal 182 ayat 4 KUHAP sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan hukum selurus-lurusnya dan mengesampingkan keadilan prosedural.
Mengutip pendapat beberapa sarjana hukum, keadilan sering kali diklasifikasikan menjadi keadilan prosedural/formil yaitu adil dalam prosedur demi menegakkan hukum acara (Scheuerman dkk. 2020) dan keadilan substantif/materiil yaitu adil dalam menerapkan norma hukum yang berlaku. Menelisik teori keadilan prosedural Miller, bahwa keadilan prosedural merupakan suatu ide keadilan yang mengacu pada aturan dasar dan pengaturan prosedural.
Keadilan prosedural menekankan bahwa pelaksanaan proses dalam aturan tertulis itu sendiri haruslah adil, jaminan atas pelaksanaan aturan perundang-undangan yang adil merupakan harga mati yang harus selalu dipegang oleh para penegak hukum (Miller 1999). Sehingga, dalam teori keadilan prosedural murni, tidak ada standar yang dapat memutuskan apa yang “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri (Lebaqcqz 1986).
Dalam perkembangannya, menegakkan keadilan prosedural tidak jarang menemui kebuntuan ketika ada aturan dan prosedur yang malah menimbulkan ketidakadilan akibat relasi yang tidak setara (Suhartono 2019) ataupun situasi dimana adanya kekosongan hukum. Penegakkan hukum yang terlalu kaku/formalist, tidak jarang bertemu dengan jebakan formalisme dalam memutus perkara (Rahardjo 2009).
Pemikiran ini juga selaras dengan pendapat Friedrich Carl von Savigny yang dikutip oleh Lilik Mulyadi menyatakan bahwa ada konsekuensi negatif akibat pemikiran kaku yang cenderung positivisme, yaitu dapat memunculkan kesenjangan/gap antara semangat/jiwa bangsa (volkgeist) dengan hukum yang berlaku sehingga terciptanya disharmoni dan jarak antara keadilan dalam diri masyarakat dan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum yang dibuat oleh Negara (Mulyadi 2019).
Keadilan prosedural sejatinya ditegakkan semata-mata untuk menciptakan keadilan materiil dengan memberikan kesempatan, akses dan perlakuan yang sama bagi setiap orang, demi menemukan kebenaran dengan cara yang sah sehingga terciptalah kebenaran yang sebenarnya (Hamzah 2014). Dalam hukum acara pidana, Hakim dituntut bersifat aktif dalam membuka tabir kebenaran seterang-terangnya.
Melalui metode pembuktian Negatif Wettelijke Bewijstheorie, Hakim diwajibkan menilai kebenaran dari minimal dua alat bukti dan dari situ ia memperoleh keyakinannya. Sehingga, beberapa sarjana hukum sepakat bahwa apa yang hendak diungkap dalam perkara pidana ialah kebenaran materiil/substantif (Mochtar dan Hiariej 2021; Hamzah 2014; Gulo dan Gulo 2024)
Berkaca pada perubahan paradigma hukum di Indonesia, dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP menentukan “dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan” yang selanjutnya pada ayat ke-2 ditentukan bahwa “Jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan”. Apabila merujuk pada anotasi Prof Topo Santoso dan Prof Eddy Hiariej sebagai anggota perumus Undang-undang a quo, bahwa semangat yang dibangun oleh perumus undang-undang adalah Hakim harus berani dan mampu menegakkan keadilan di atas kepastian hukum (Hiariej dan Santoso 2025).
Traksi antara nilai keadilan prosedural dan substantif memang tidak jarang ditemui, sehingga saat berhadapan pada masalah di atas, kembali kepada asas kebebasan Hakim untuk memutuskan langkah apa yang akan diambil dalam situasi tersebut. Masing-masing pilihan memiliki pembenaran dan akibatnya tersendiri. Namun hal yang harus selalu disadari adalah Hakim merupakan penulis ulang makna hukum agar ia hidup senafas dengan nilai di masyarakat (Arief 2025).
Kepastian, kemanfaatan dan keadilan, ketiga tujuan hukum itu pada dasarnya memiliki nilai yang berkontradiksi (semisal kepastian dan keadilan), bagaimana menyeimbangkan ketiganya, menurut Gustav Radbruch, itu ditentukan oleh kreatifitas dan intuisi sang Hakim (Spaak 2009). Lantas, sesungguhnya Hakim bukanlah pelaksana mekanik, melainkan penafsir dan penerjemah keadilan (Arief 2025).
Demi mewujudkannya Hakim tidaklah kaku pada prosedur dalam teks hukum (Rahardjo 2009). Sebagaimana pesan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof Sunarto bahwa seorang Hakim tidak hanya berkutat pada aturan, melainkan harus juga mengandalkan rasa dan nurani, sebab itulah yang menjadikan peran seorang Hakim tak bisa digantikan oleh mesin dan artificial intellegence di masa depan. (ypy)
Daftar Pustaka
Arief, Syamsul. 2025.
“Hakim Sebagai Subjek Sintesis: Dari
Kepastian ke Kebijaksanaan.” Pelatihan
Teknis Yudisial Filsafat Hukum Untuk Keadilan Lingkungan Peradilan Umum Seluruh
Indonesia, November 17.
Gulo,
Nimerodi, dan Cornelius Dikae Zolohefona Gulo. 2024. “Timbulnya Keyakinan Hakim
dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana di Peradilan Indonesia.” UNES Law
Review 6 (3): 8115–22. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1672.
Hamzah,
Andi. 2014. Hukum Acara Pidana Indonesia. Sinar Grafika.
Hiariej,
Eddy O.S., dan Topo Santoso. 2025. Anotasi KUHP Nasional. Rajawali Pers.
Lebaqcqz,
Karen. 1986. Six Theories of Justice. Augsbung Publishing House. diterjemahkan oleh Yudi Santoso, 2015, Penerbit Nusa Media, Bandung
Miller,
David. 1999. Principles of Social Justice. Harvard University Press.
Mochtar,
Zainal Arifin, dan Eddy O.S. Hiariej. 2021. Dasar-Dasar Ilmu Hukum.
Rajawali Pers.
Mulyadi,
Lilik. 2019. “Interpretation Of Judges In Representing The Dynamics Of Religion
Of Indigenous Legal Inheritance Of Bali.” Jurnal Hukum Dan Peradilan 8
(2): 214. https://doi.org/10.25216/jhp.8.2.2019.214-227.
Rahardjo,
Satjipto. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta
Pengalaman-pengalaman di Indonesia. Genta Publishing.
Scheuerman,
Heather L, Talia N Gilbert, Shelley Keith, dan Karen A Hegtvedt. 2020.
“Discerning Justice: Clarifying The Role Of Procedural And Interactional Justice
In Restorative Conferencing.” Contemporary Justice Review 24 (1): 4–23.
Spaak,
Torben. 2009. “Meta-Ethic and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch.” Journal
Law and Philosophy 28 (3): 261–90.
Baca Juga: Pembaharuan Fungsi Hakim Pada Proses Pembuktian dalam KUHAP Baru
Suhartono,
Slamet. 2019. “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya.” DiH:
Jurnal Ilmu Hukum 15 (2): 201–11.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI