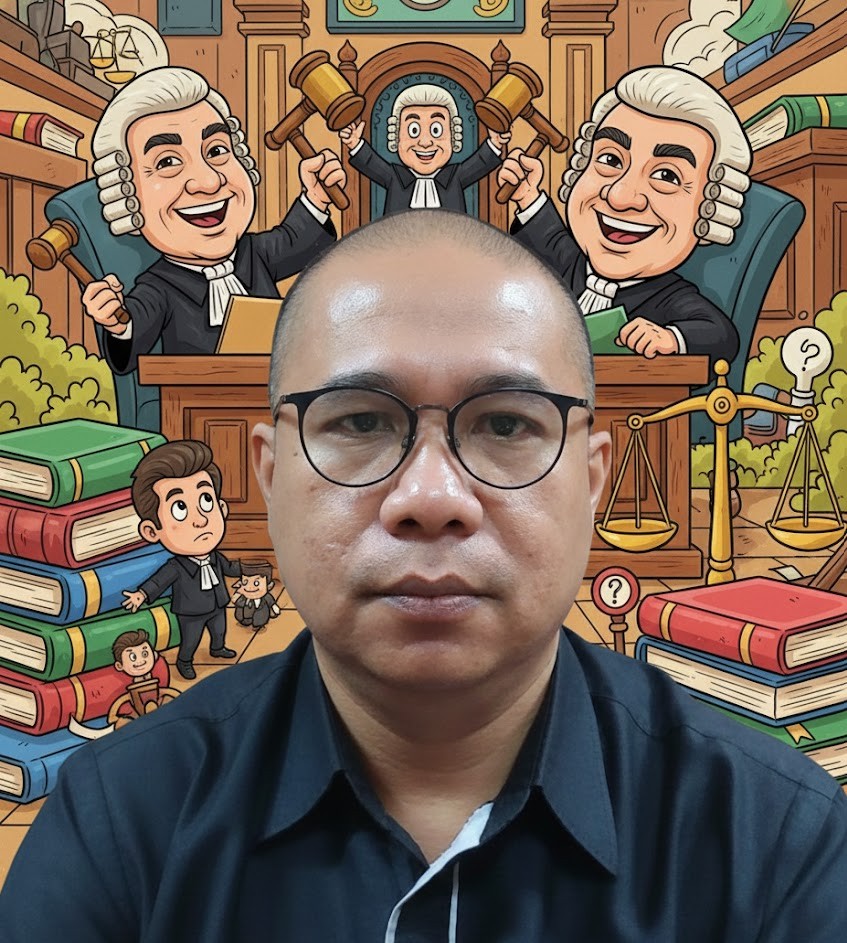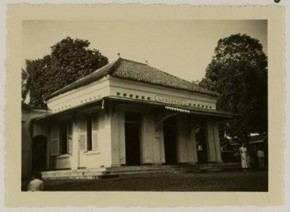Arsitektur
hukum modern memisahkan sanksi pidana (ultimum
remedium, retributif) dan administrasi (primum remedium, korektif). Namun,
proliferasi hukum pidana administratif mengaburkan dikotomi ini, menciptakan
tumpang tindih yurisdiksi. Konsekuensi fundamentalnya adalah patologi duplicatio
poenae (sanksi ganda) atas idem factum (fakta material yang sama).
Problematika ini berakar
pada interpretasi restriktif asas ne bis in idem (Pasal 76 KUHP). Secara
formalistik, asas ini ditafsirkan terbatas hanya pada larangan penuntutan ganda
dalam rezim pidana (intra rezim). Akibatnya, tercipta rechtsvacuum
(kekosongan hukum): sanksi administratif, terlepas dari substansi punitifnya,
tidak menghalangi proses pidana atas fakta yang identik, begitu pula
sebaliknya.
Kesalahan interpretasi
klasik terletak pada fokus terhadap idem delictum (kesamaan
delik/forum), bukan perlindungan atas idem factum. Hal ini memungkinkan
negara, sebagai entitas tunggal, menjatuhkan sanksi dua kali melalui aparatus
berbeda (yudikatif dan administratif).
Meskipun sanksi
administratif formalnya bukan pidana, secara substantif ia menghasilkan efek
penghukuman kedua (quasi punitive effect). Inkonsistensi ini secara
langsung mencederai prinsip proporsionalitas dan kepastian hukum (Pasal 28D
ayat 1 UUD 1945).
Untuk mengatasi
ambiguitas ini dan mencegah interpretatio subjectiva, penting untuk
melakukan diferensiasi konseptual yang tegas antara “sanksi administratif
murni” dan “sanksi administratif punitif”. Demarkasi ini harus didasarkan pada
kriteria objektif. Referensi doktrinal yang otoritatif adalah Kriteria Engel (Engel
Criteria), yang dirumuskan oleh European Court of Human Rights
(ECtHR) dalam putusan Engel v. Netherlands (1976).
Kriteria ini menguji
kapan suatu sanksi, terlepas dari label formalnya, memiliki sifat “pidana”
secara substantif, melalui tiga parameter fundamental. Pengujian dimulai dengan
melihat klasifikasi hukum pelanggaran menurut hukum nasional. Selanjutnya, yang
lebih krusial, adalah analisis terhadap sifat dasar pelanggaran, yakni apakah
tujuan sanksi tersebut bersifat punitif dan preventif, ataukah murni korektif.
Terakhir, pengujian mempertimbangkan tingkat keparahan sanksi yang mungkin dijatuhkan.
Dengan menerapkan
Kriteria Engel, kita dapat membedah contoh kasus secara presisi. Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) pasca putusan
pidana korupsi inkracht bukanlah hukuman kedua atas idem factum.
PTDH adalah tindakan administratif kepegawaian murni yang memiliki ratio
administratif independen, yakni hilangnya syarat subjektif untuk menduduki
jabatan publik. Sifat dasarnya adalah korektif (menjaga marwah birokrasi), bukan
punitif substantif.
Sebaliknya, patologi duplicatio
poenae manifes secara ekstrem dalam hukum pemilu (vide Pasal 285 UU
7/2017), di mana putusan pidana inkracht secara imperatif mengaktivasi
sanksi administratif pembatalan calon. Dalam konstruksi ini, sanksi
administratif kehilangan ratio korektifnya. Hak konstitusional untuk
dipilih tidak otomatis hilang karena pidana ringan atau percobaan. Sanksi
pembatalan tersebut bertransformasi menjadi disguised punishment yang
bersifat punitif murni, sebuah "hukuman mati politik". Karena tingkat
keparahannya yang ekstrem, sanksi ini secara substantif harus dikategorikan
sebagai pidana.
Konsekuensi dari hal ini
adalah insufisiensi doktrin ne bis in idem klasik dalam membendung
duplikasi sanksi lintas rezim. Dengan demikian, sistem yang terfragmentasi ini
menciptakan dilema yudisial akut di dua kamar peradilan. Hakim pidana
menghadapi paradoks. Saat menerapkan asas proporsionalitas, misalnya
menjatuhkan vonis ringan, hakim pidana secara de facto sadar bahwa
putusan proporsional tersebut akan menjadi instrumen predikat hukum untuk
mengaktivasi sanksi kedua yang ekstrem disproporsional di luar yurisdiksinya.
Putusan yang dianggap adil justru melahirkan ketidakadilan yang lebih besar.
Sementara itu, hakim PTUN
dihadapkan pada benturan formalitas legalistik. Ketika subjek hukum menggugat
Surat Keputusan administratif pembatalan tersebut, hakim PTUN seringkali terkunci
pada pengujian formalitas prosedural: Apakah SK KPU didasarkan pada putusan
pidana inkracht? Jika ya, SK tersebut cenderung dianggap sah menurut
hukum positif (Pasal 285).
Fenomena ini
termanifestasi nyata dalam hukum elektoral. Sebagai ilustrasi, seorang kandidat
yang melakukan pelanggaran minor dijatuhi pidana percobaan oleh Hakim Pidana, sebuah
vonis yang proporsional. Namun, ironisnya, putusan terukur ini secara mekanistik
digunakan penyelenggara pemilu sebagai dasar deterministik untuk
mendiskualifikasi kandidat tersebut. Sanksi administratif ini, sebuah
"hukuman mati politik", secara ekstrem disproporsional dibandingkan
pidana awalnya.
Ketika legalitas
diskualifikasi ini diuji di PTUN, pengadilan cenderung terkunci pada pengujian
formal: keberadaan putusan pidana inkracht dianggap cukup untuk
memvalidasi keputusan administratif, tanpa menguji proporsionalitas atau AUPB.
Implikasinya, meskipun hakim PN dan hakim PTUN bertindak sesuai koridor
formalnya, output kolektif sistem ini adalah ketidakadilan substantif
yang dilembagakan.
Keterbatasan ne bis
in idem klasik menuntut evolusi pemikiran hukum menuju asas una via
(electa una via non datur recursus ad alteram): "ketika satu jalan telah dipilih, tidak boleh ada jalan lain yang
ditempuh". Asas una via adalah perluasan logis ne bis in
idem dalam konteks modern, yang menggeser fokus dari idem delictum
(kesamaan delik) ke idem factum (kesamaan fakta).
Prinsipnya fundamental: negara,
sebagai entitas tunggal, harus memilih jalurnya (via) dalam merespons
satu fakta perbuatan. Jika jalur administratif punitif (berdasarkan Kriteria
Engel) dipilih, jalur pidana tertutup. Sebaliknya, jika jalur pidana dipilih,
sanksi administratif tambahan yang bersifat menghukum (bukan konsekuensi
status) tidak boleh dijatuhkan.
Untuk mengoperasionalkan
asas una via secara efektif lintas sektor, penerapannya harus dipadukan
dengan asas lex specialis derogat legi generali. Legislasi sektoral (lex
specialis), seperti UU Pemilu atau UU Lingkungan Hidup, harus
diharmonisasikan dengan asas umum una via melalui norma delegatif yang
jelas. Norma ini harus memberikan kewenangan diskresioner kepada regulator
sektoral sebagai gatekeeper untuk menentukan pilihan jalur penegakan
hukum secara definitif di tahap awal.
Gagasan ini bukanlah
utopia yuridis. Sistem hukum Indonesia secara progresif telah mengadopsinya.
Preseden termutakhir adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Pasal 100A UU P2SK secara
eksplisit memberikan OJK kewenangan diskresioner untuk memilih jalur pidana
atau jalur sanksi administratif. Ini adalah pilihan hukum (pilihan via)
yang dirancang secara sadar untuk mengakhiri sanksi ganda.
Duplicatio poenae yang timbul dari tumpang tindihnya rezim sanksi adalah patologi
hukum yang secara fundamental bertentangan dengan asas proporsionalitas dan
keadilan substantif yang diamanatkan Pancasila, khususnya Sila Kemanusiaan yang
Adil dan Beradab (Sila ke-2) dan Keadilan Sosial (Sila ke-5). Perluasan ne
bis in idem menjadi una via adalah keniscayaan doktrinal.
Untuk mengatasi ini,
diperlukan solusi legislatif (hulu). Pembentuk undang-undang harus melakukan
revisi legislasi sektoral yang tumpang tindih (khususnya UU Pemilu) dengan
mengadopsi model gatekeeper progresif seperti Pasal 100A UU P2SK, yang
terharmonisasi dalam kerangka lex specialis. Berikan kewenangan
diskresioner tunggal kepada regulator (seperti Bawaslu, KLHK, Dirjen Pajak)
untuk memilih jalur administratif punitif atau jalur pidana.
Sembari menunggu solusi legislatif, Hakim diharapkan tidak terperangkap sebagai bouche de la loi yang kaku. Melalui kewenangan rechtsvinding, Hakim PN dapat secara eksplisit mencatat pertimbangan disproporsionalitas sanksi ganda dalam ratio decidendi putusannya.
Secara lebih progresif, dalam menguji SK
administratif, hakim didorong untuk tidak hanya berhenti pada pengujian
formalitas. Hakim harus berani menguji substansi SK tersebut terhadap AUPB
(khususnya asas proporsionalitas), menerapkan Kriteria Engel untuk menilai
sifat punitif sanksi, dan mengujinya terhadap nilai-nilai Keadilan Pancasila
sebagai norma hukum tertinggi, memastikan bahwa putusan akhir sistem peradilan
secara kolektif menghasilkan keadilan substantif, bukan sekadar legalitas
formal yang represif. (ldr)
Baca Juga: Mencermati Nebis In Idem dalam Perkara Perceraian
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI