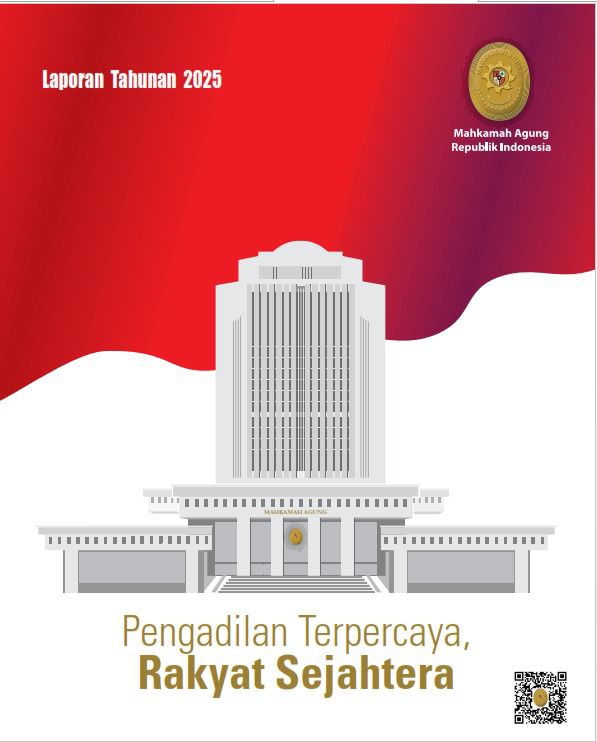Legisme hukum merupakan
salah satu aliran pemikiran hukum yang berkembang pada abad ke-19 dan memiliki
pengaruh besar terhadap konstruksi sistem hukum modern, khususnya di
negara-negara dengan tradisi civil law.
Secara sederhana,
legisme menekankan bahwa satu-satunya sumber hukum yang sah adalah
undang-undang, sehingga hukum identik dengan apa yang tertulis dalam teks
peraturan perundang-undangan.
Pandangan ini sejalan
dengan tradisi positivisme hukum (legal
positivism) yang secara garis besar menolak keterikatan hukum dengan
moralitas. Jeremy Bentham, salah satu peletak dasar positivisme, menganggap
bahwa hukum tidak lain hanyalah "perintah penguasa yang berdaulat" (the command of the sovereign).
Baca Juga: Asas Hukum Sebagai Alat Penafsir Dalam Hukum Acara Pidana
Sedangkan dalam bukunya
The Province Of Jurisprudence Determined, Austin menyatakan “A law is comand
wich obliges a persons or persons, law and other comands are said to proceed
from superiors, and the bind or oblige inferiors.” (Serlika Aprita & Rio Adhitya, 2020,
hal. 102). Dari sudut pandang ini, hukum hanyalah produk
legislasi yang mengikat karena ditetapkan oleh penguasa yang sah.
Jika kita tarik benang merahnya, legisme
hukum adalah ekspresi praktis dari legal
positivism dalam sistem civil law,
khususnya di Eropa Kontinental pasca Kodifikasi Napoleon (1804).
Pada masa itu, hukum dipandang sebagai
“kitab suci” negara modern yang harus ditaati secara literal demi kepastian
hukum, karena itu hakim hanya ditempatkan sebagai "corong
undang-undang" (la bouche de la loi).
Dalam pandangan legisme, hakim dan aparat
penegak hukum tidak boleh melampaui atau menafsirkan hukum di luar kerangka
undang-undang yang telah ditetapkan oleh pembentuknya.
Dalam perkembangannya legisme hukum justru
menimbulkan sejumlah problematika serius dalam dinamika penegakan hukum modern.
Pertama, problem formalisme
hukum. Legisme menempatkan undang-undang sebagai teks
final yang harus diikuti secara literal, akibatnya hukum menjadi kaku, kurang
adaptif terhadap realitas sosial yang senantiasa berubah.
Kedua, problem reduksi peran
hakim. Dalam paradigma legisme, hakim dibatasi
sebatas mulut undang-undang, padahal praktik peradilan selalu berhadapan dengan
kasus konkret yang penuh nuansa, di mana teks undang-undang tidak selalu
memberi jawaban yang memadai.
Ketiga, problem marginalisasi
sumber hukum lain. Legisme cenderung mengabaikan
hukum kebiasaan, yurisprudensi, doktrin, dan nilai-nilai moral yang hidup dalam
masyarakat, akibatnya, sistem hukum menjadi positivistik sempit, jauh dari cita
keadilan substantif.
Keempat, problem legitimasi
dalam era demokrasi. Legisme menekankan
superioritas legislator sebagai pembentuk hukum, namun dalam praktik politik
kontemporer, legislasi seringkali dipengaruhi oleh kepentingan oligarki,
partai, atau kekuatan ekonomi.
Seiring berjalannya waktu penegakan hukum
di era modern menghadapi kompleksitas sosial, ekonomi, dan teknologi yang jauh
melampaui apa yang dapat diakomodasi oleh sekedar mengandalkan undang-undang
sebagai satu-satunya sumber hukum.
Berpegang teguh pada pandangan
positivistik yang kaku bahwa hukum hanyalah apa yang tertulis dalam undang-undang
sudah tidak relevan dan berpotensi menghasilkan ketidakadilan substantif. Hukum
positif kadang-kadang menghambat perkembangan hidup dan sangat merugikan keadilan
(Sukarno Aburaera, Dkk, 2017, hal. 213).
Roscoe Pound, tokoh sosiological jurisprudence, mengkritik bahwa hukum yang hanya
berlandaskan pada teks undang-undang akan kehilangan sensitivitas terhadap
kebutuhan masyarakat yang dinamis. Kritik ini menyingkap kelemahan legisme yang
terlalu menekankan kepastian hukum, namun kerap mengabaikan aspek keadilan
substantif. Disisi lain Radbruch menemukan adanya nilai lain disamping
ada kepastian hukum, nilai lain itu adalah nilai manfaat dan keadilan
Dalam praktik
peradilan, sangat sulit bagi seorang hakim untuk mengakomodir ketiga nilai
tersebut di dalam satu putusan
Di era KUHP Nasional
telah tumbuh kesadaran bahwa penegakan hukum harus bergerak melampaui teks
hukum semata, dan mulai lebih mengutamakan keadilan bagi masyarakat. Kesadaran
inilah yang tercermin dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
tentang KUHP yang menyatakan:
“Jika dalam menegakkan hukum
dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim
wajib mengutamakan keadilan.”
Walaupun prinsip kepastian hukum menjadi
asas utama dalam penegakan hukum, hakim memiliki kewajiban moral dan etis untuk
mengutamakan keadilan ketika terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan
keadilan (Eddy
O.S. Hiariej & Topo Santoso, 2025, hal. 69).
Pasal ini menunjukkan bahwa sistem hukum
pidana nasional kini tidak lagi semata-mata menghukum, melainkan mendorong
pendekatan yang lebih manusiawi dan berkeadilan. Hakim diberi ruang untuk
mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral dari pelaku, bukan hanya
perbuatannya.
Dengan kata lain, penegakan hukum tidak
boleh kaku hanya mengikuti rumusan delik, melainkan harus mempertimbangkan
nilai-nilai keadilan dan konteks peristiwa.
Lebih jauh, pendekatan ini mengubah cara
memandang pelaku tindak pidana, mereka bukan semata “penjahat”, tetapi manusia
yang bisa memiliki latar belakang ekonomi, pendidikan, atau sosial tertentu
yang turut membentuk perilakunya.
Dengan demikian, sistem hukum tidak hanya
menjadi alat kekuasaan yang represif, tetapi menjadi instrumen perbaikan sosial
yang adil dan bijaksana. Penegakan hukum yang adil bukan hanya tegaknya
kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara teks dan konteks,
antara aturan dan nurani.
Pasal 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023
menjadi langkah maju dalam sistem peradilan pidana Indonesia mendorong
peradilan yang lebih berkeadilan dan bermartabat bagi seluruh warga negara.
Kesimpulannya penegakan hukum modern
menuntut pendekatan pluralistik terhadap sumber hukum, undang-undang tetap
menjadi sumber utama dan paling otoritatif, tetapi harus dilengkapi dan
diperkaya oleh sumber lain seperti yurisprudensi, doktrin, asas-asas, kebiasaan
dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
Menempatkan hakim sebagai penafsir,
pembentuk, dan penggali hukum (bukan sekedar corong) adalah langkah mutlak
untuk memastikan bahwa penegakan hukum mampu beradaptasi, relevan, dan yang
terpenting, mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat yang semakin dinamis.
Di era modern, hukum harus dilihat sebagai
alat yang hidup, fleksibel, dan responsif terhadap nurani publik, bukan sekedar
seperangkat aturan mati di atas kertas. (ldr)
Referensi
Aburaera, S., Muhadar, & Maskun. (2017). Filsafat
Hukum Teori Dan Praktik. jakarta: Prenadamedia Group.
Aprita, S.
& Adhitya. R. (2020). Filsafat Hukum. Depok: Rajawali Pers.
Manullang,
E. F. (2017). Legisme, Legalitas Dan Kepastian Hukum. Jakarta:
Prenadamedia Group.
Margono.
(2019). Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan
Hakim. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
Baca Juga: Antinomi Hukum Tujuan Pemidanaan dan Pidana Penjara Pengganti dalam KUHP Baru
Hiariej.
E & Santoso. T. (2025). Anotasi KUHP Nasional. Depok: Rajawali
Pres.
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI