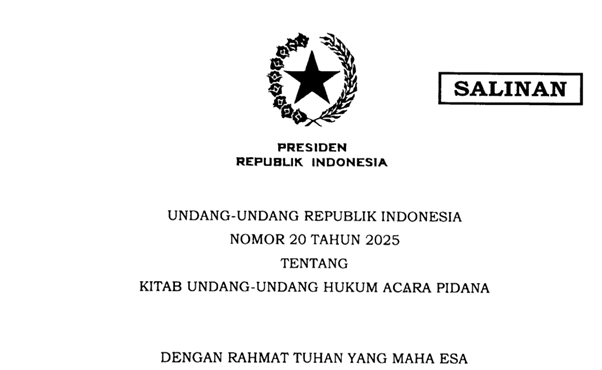Kekerasan seksual dalam rumah tangga masih menjadi masalah serius dalam sistem hukum dan sosial di Indonesia. Dalam banyak kasus, korban tidak hanya mengalami penderitaan fisik dan psikis, tetapi juga menghadapi situasi berulang yang memperparah kondisi mereka.
Sebuah fenomena yang dikenal sebagai viktimisasi berganda. Fenomena ini mengacu pada korban yang mengalami kekerasan secara berulang dalam konteks rumah tangga, dengan pelaku yang seringkali adalah orang terdekat suami, ayah, atau kerabat.
Kekerasan seksual yang terjadi di
dalam rumah tangga seringkali disertai dengan berbagai bentuk kekerasan lain,
seperti kekerasan fisik dan psikologis, sehingga menimbulkan fenomena
viktimisasi berganda—suatu kondisi di mana korban mengalami tekanan dan
penderitaan yang berlapis dari berbagai sisi.
Baca Juga: Femisida Dalam Kerangka Hukum Indonesia
Ironisnya, perlindungan hukum yang seharusnya menjamin rasa aman dan
keadilan bagi korban justru kerap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak dari mereka justru mengalami
reviktimisasi oleh sistem hukum, masyarakat, bahkan keluarga mereka sendiri.
Padahal, negara memiliki tanggung jawab konstitusional dan moral untuk
melindungi warganya dari segala bentuk kekerasan.
Menurut
Data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 ,
ditemukan fakta sebagai berikut:
- Data Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Sistem Informasi Online
Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan, pada 2024 ada
31.947 kasus pengaduan. Sebagian besar kasus kekerasan tersebut (27.658
kasus) dialami oleh perempuan. Pengaduan kasus kekerasan ini banyak
dialami oleh perempuan yang berusia 13-17 tahun (33 persen) dan usia 25-44
tahun (25,7 persen). Dari
latar belakang pendidikan, laporan kekerasan ini banyak diadukan oleh
perempuan dengan tingkat pendidikan SLTA ke bawah. Adapun menurut tempat
kejadian, kekerasan ini banyak dilaporkan terjadi dalam lingkup rumah
tangga (60,6 persen), tempat umum (10,1 persen), dan tempat pendidikan (6,3
persen).
- Ragam kekerasan terhadap
perempuan ini juga tertangkap dari laporan Komisi Nasional Antikekerasan
terhadap Perempuan. Komnas Perempuan mencatat, pada 2023, total
pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 4.374 kasus.
Berbagai bentuk kekerasan pada perempuan masih didominasi pada kekerasan
seksual sebanyak 2.363 kasus atau 34,8 persen dari total kasus. Lainnya,
kekerasan psikis (28,5 persen), kekerasan fisik (27,2 persen), dan
kekerasan ekonomi (9,5 persen). Di ranah personal, kekerasan terhadap
istri tercatat 674 kasus.
- Korban kekerasan seksual dalam
rumah tangga yang melapor ke polisi hanya sekitar 15%, sebagian besar
disebabkan oleh ketakutan akan diskriminasi dan viktimisasi.
- Dari pelapor, sekitar 40% mengalami perlakuan yang kurang empati dan lambat dalam proses peradilan.
Konsep viktimisasi berganda
menyoroti kondisi korban yang terus-menerus menjadi objek kekerasan, baik
secara fisik, psikis, maupun seksual, dalam jangka waktu yang panjang. Tidak
jarang, kekerasan tersebut dimulai sejak usia dini dan berlanjut hingga
bertahun-tahun. Kondisi ini diperparah oleh sikap pasif lingkungan sekitar yang
memilih bungkam, dengan alasan bahwa persoalan rumah tangga adalah urusan
privat.
Viktimisasi
berganda terjadi ketika korban tidak hanya mengalami kekerasan primer tetapi
juga tindakan yang memperburuk keadaan mereka oleh lingkungan sosial dan
institusi. Contohnya:
- Stigma sosial dan diskriminasi: Korban dianggap aib
keluarga, menanggung malu, atau bahkan disalahkan atas kekerasan.
- Pengabaian dan pelecehan dari
keluarga: Dalam
beberapa kasus, keluarga pelaku menekan korban untuk tidak melapor supaya
nama baik keluarga tetap terjaga.
- Respon aparat hukum yang kurang
sensitif: Penyidik
dan petugas sering menunjukkan kurangnya empati, bahkan mempertanyakan
integritas korban.
- Trauma berlapis: Korban mengalami trauma akibat kekerasan dan pengabaian/post-kekerasan yang memperburuk kondisi mental dan fisik.
Secara normatif, Indonesia telah
memiliki beberapa instrumen hukum yang menjamin perlindungan terhadap korban
kekerasan, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua peraturan ini secara eksplisit
menyebut hak-hak korban, mulai dari perlindungan fisik, bantuan hukum, hingga
pendampingan psikologis.
Namun, dalam praktiknya,
perlindungan tersebut sering kali tidak dapat diakses oleh korban. Hambatan
struktural seperti kurangnya sosialisasi, terbatasnya layanan pendampingan di
daerah, serta rendahnya sensitivitas aparat penegak hukum menjadi penyebab
utama lemahnya implementasi. Belum lagi faktor budaya yang menyalahkan korban
dan menormalisasi kekerasan dalam relasi personal.
Dalam ilmu hukum, viktimologi adalah
studi yang berfokus pada korban kejahatan, termasuk hak-haknya dan peranannya
dalam sistem peradilan pidana. Viktimologi menyoroti pentingnya mengubah
pendekatan sistem hukum yang selama ini lebih offender-oriented menjadi
victim-oriented. Artinya, sistem tidak hanya fokus pada hak dan proses hukum
terhadap pelaku, tetapi juga memperhatikan keadilan dan pemulihan bagi korban.
Asas-asas hukum seperti keadilan,
kemanfaatan, dan kepastian hukum seharusnya tidak hanya diterapkan pada pelaku
kejahatan, tetapi juga pada korban. Dalam konteks viktimisasi berganda, asas
keadilan bahkan harus diberi porsi lebih besar mengingat kompleksitas
penderitaan yang dialami korban, termasuk trauma jangka panjang yang memerlukan
pemulihan menyeluruh.
Perbandingan dengan Thailand dan
Filipina memperlihatkan bahwa persoalan kekerasan seksual dalam rumah tangga
serta viktimisasi berganda bukan hanya masalah di Indonesia. Kedua negara
tersebut juga menghadapi tantangan serupa: lemahnya implementasi hukum, budaya
patriarki yang kuat, dan minimnya pendampingan terhadap korban.
Namun demikian, beberapa kebijakan
progresif di negara-negara tersebut seperti penyediaan shelter berbasis
komunitas, pelatihan aparat dalam perspektif gender, serta integrasi sistem
perlindungan korban ke dalam sistem peradilan dapat menjadi inspirasi untuk
reformasi kebijakan di Indonesia.
Baca Juga: Penerapan Perekaman Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Untuk menciptakan sistem hukum yang
adil dan berpihak pada korban, perlu dilakukan sejumlah langkah strategis:
- Revisi
regulasi agar lebih sensitif terhadap bentuk-bentuk kekerasan yang kompleks,
termasuk kekerasan berulang dan kekerasan dalam bentuk pasif (pengabaian).
- Pelatihan
aparat hukum dan petugas layanan terkait perspektif gender dan viktimologi agar
dapat menangani korban dengan empati dan kompetensi.
- Peningkatan
akses layanan korban, baik dalam bentuk bantuan hukum, konseling psikologis,
maupun tempat perlindungan yang aman.
- Sosialisasi
hukum ke masyarakat, guna mengikis anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga
adalah urusan privat yang tidak boleh diintervensi.
- Penerapan
sanksi terhadap pihak yang membiarkan atau menutup-nutupi kekerasan, termasuk
anggota keluarga yang pasif atau aparat yang lalai.
Perlindungan hukum bagi korban
kekerasan seksual dalam rumah tangga masih menyisakan banyak pekerjaan rumah.
Terlebih ketika korban mengalami viktimisasi berganda, ketidakhadiran negara
dalam bentuk perlindungan konkret tidak hanya menciptakan ketidakadilan hukum,
tetapi juga memperpanjang penderitaan korban secara sosial dan psikologis.
Sudah saatnya sistem hukum Indonesia menempatkan korban sebagai subjek utama perlindungan. Bukan hanya karena itu adalah amanat undang-undang, tetapi karena keadilan sejati hanya bisa tercapai ketika suara korban benar-benar didengar dan penderitaan mereka sungguh-sungguh dipulihkan. (zm, ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI