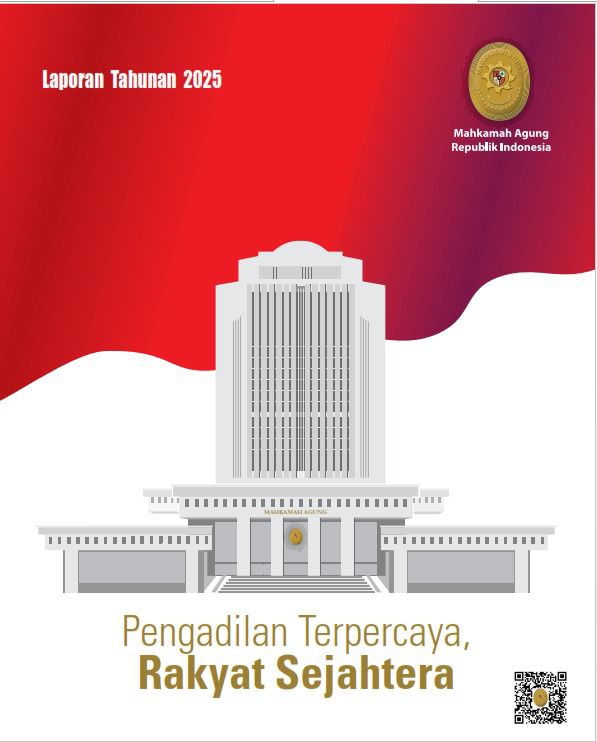GELOMBANG di pesisir Indonesia kini membawa pesan yang getir, di mana hutan mangrove hilang, pantai terkikis reklamasi, dan laut perlahan kehilangan napasnya. Di balik statistik pembangunan ekonomi biru (blue economy) dan jargon ekonomi kelautan dan perikanan, laut kita sedang menuntut haknya, yaitu hak untuk hidup, hak untuk bernapas, dan hak untuk diperlakukan bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai rumah kehidupan bagi seluruh entitas yang terkandung di dalamnya.
Laut yang Tak Lagi Diam
Dari Teluk Jakarta hingga Karimunjawa, dari Batam hingga Balikpapan, dari laut Halmahera hingga perairan perawan Raja Ampat, laut Indonesia menjadi saksi bisu dari komoditi daratan. Proyek reklamasi, penambangan pasir laut, dan ekspansi industri pesisir berjalan atas nama “izin,” padahal izin itu sering kali lebih berpihak pada investasi daripada keberlanjutan.
Baca Juga: Environmental Ethic Sebagai Pilar Keadilan Ekologis
Kita seolah lupa bahwa laut bukan ruang kosong; ia adalah ekosistem hidup dengan jaringan sosialnya sendiri. Ketika lamun tercabut, ikan mati, penyu kehilangan tempat untuk bertelur dan air berubah keruh, yang hancur bukan hanya alam, tetapi juga kebudayaan pesisir, ekonomi nelayan, dan keseimbangan batin kita sebagai bangsa Archipelago.
Dari Pohon ke Laut: Hak Hukum bagi Alam
Pada tahun 1972, profesor hukum lingkungan Amerika, Christopher D. Stone, menulis esai legendaris Should Trees Have Standing? Ia menggugat pandangan hukum yang antroposentris dimana hukum yang hanya mengenal manusia sebagai subjek hukum dan menjadikan alam sebagai benda mati tanpa hak. Stone bertanya: “Jika anak, perempuan, dan korporasi kini diakui memiliki hak hukum, mengapa sungai dan hutan tidak?”
Pertanyaan Stone tersebut adalah seruan moral bagi hukum untuk keluar dari dogma antroposentris. Ia mengingatkan bahwa: Keadilan ekologis tidak akan pernah tercapai jika hanya manusia yang diakui sebagai subjek hukum. Melalui prinsip-prinsip hukum lingkungan di mana nilai intrinsik alam, keadilan antargenerasi, dan prinsip kehati-hatian, maka hukum harus berevolusi menuju paradigma di mana: “Alam tidak hanya dilindungi karena berguna, tetapi dihormati karena ia ada.”
Gagasannya sederhana tapi radikal: alam harus diberi hak untuk membela diri di pengadilan.
Hutan yang ditebang, sungai yang tercemar, atau laut yang dirusak harus bisa diwakili oleh wali hukum (guardian of nature), seperti organisasi lingkungan, lembaga publik, atau bahkan warga yang peduli.
Kini, lebih dari setengah abad kemudian, ide itu tidak lagi utopis. Sungai Whanganui di Selandia Baru, Sungai Atrato di Kolombia, dan Gunung Taranaki di Aotearoa telah diakui sebagai “entitas hukum yang hidup.”
Laut pun seharusnya memiliki kedudukan serupa di Indonesia, bukan karena romantisme hijau, tapi karena tanpa laut, kita kehilangan jati diri dan masa depan sebagai bangsa Archipelago.
Etika Lingkungan: Dari Antroposentris ke Ekosentris
Selama ini hukum
lingkungan kita berakar pada etika lama yaitu “antroposentrisme” di mana keberadaan alam hanya untuk melayani
manusia. Laut dinilai “berharga” hanya jika menghasilkan ikan, minyak, atau pariwisata.
Padahal, nilai laut tidak terletak pada manfaatnya bagi manusia, tetapi pada keberadaannya sendiri. Etika lingkungan (environmental ethics) menawarkan jalan lain yaitu “ekosentrisme” sebuah pandangan bahwa seluruh makhluk hidup dan sistem ekologis memiliki nilai intrinsik (intrinsic value).
Laut memiliki hak untuk tetap eksis, tetap terpelihara keseimbangan ekologisnya dan memulihkan diri dari luka-luka manusia. Nilai ini sejalan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia. Dalam kearifan Melayu disebut, “laut bukan milik siapa-siapa, ia milik semua yang menghuni.” Dalam kosmologi Bugis, laut dipandang sebagai “wija to rilangi”, yaitu benih kehidupan yang disemai para leluhur.
PKKPRL: Instrumen Hukum yang Menentukan Arah Laut
Dalam kerangka hukum nasional, instrumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) seharusnya menjadi benteng utama perlindungan laut. Instrumen ini diatur dalam UU No. 27 Tahun 2007 jo. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), serta diperjelas dalam PP No. 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut. Secara ideal, PKKPRL adalah alat penyaring ekologis yang dimaksudkan untuk memastikan setiap kegiatan di laut sesuai dengan daya dukung, daya tampung, dan fungsi ekologisnya.
Namun dalam praktik, ia sering tereduksi menjadi “stempel legalisasi kegiatan ekonomi.” Kajian lingkungan hanya menjadi formalitas; partisipasi masyarakat pesisir sering diabaikan. Akibatnya, laut yang seharusnya dilindungi justru dijadikan alas kaki investasi. Padahal, secara filosofis, PKKPRL seharusnya menjadi manifestasi dari etika lingkungan itu sendiri yang menempatkan laut sebagai subjek yang memiliki kepentingan, bukan sekadar objek kebijakan.
Laut sebagai Subjek Hukum: Bukan Imajinasi
Mengakui laut
sebagai subjek hukum bukanlah hal mustahil. Prinsipnya sudah tertanam dalam
sistem hukum Indonesia melalui Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan
bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata “dikuasai” dalam konteks itu
bukan berarti dimiliki, melainkan dijaga dan diamanahkan.
Negara bertindak sebagai “wali ekologis” (ecological trustee) dan bertindak sebagai pemegang tanggung jawab untuk melindungi hak-hak lingkungan demi generasi mendatang. Maka, setiap pelanggaran PKKPRL, baik reklamasi tanpa izin, tambang pasir laut, atau pencemaran industri, bukan hanya pelanggaran administratif, tetapi pengingkaran terhadap amanah konstitusi ekologis bangsa.
Ultimum Remedium yang Berkeadilan
Hukum pidana lingkungan sering disebut sebagai ultimum remedium atau dengan kata lain sebagai jalan terakhir. Namun “terakhir” tidak berarti “tidak pernah digunakan.” Ketika kerusakan laut telah mengancam ekosistem, mata pencaharian nelayan, dan keseimbangan ekologis, maka pidana bukanlah bentuk balas dendam, melainkan bentuk pemulihan moral.
Hakim peradilan perikanan atau hakim lingkungan tidak lagi sekedar menimbang kerugian materiil, tetapi harus menakar nilai kehidupan ekologis yang hilang. Putusan hakim yang adil bagi laut bukan yang menghukum pelaku semata, tetapi yang memulihkan laut hingga ia dapat bernapas kembali.
Dari Etika ke Kebijakan: Membangun “Keadilan Laut”
Sudah saatnya kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia diukur bukan hanya dengan indikator ekonomi, tetapi juga indeks keadilan ekologis. Keadilan ekologis yang dimaksud ini mencakup; partisipasi masyarakat pesisir dalam setiap perencanaan ruang laut, transparansi izin PKKPRL, dan pengakuan terhadap hak-hak ekosistem laut untuk tetap lestari. Sebagaimana pengakuan hak asasi manusia pernah menjadi tonggak moral abad ke-20, maka abad ke-21 harus menjadi abad hak-hak ekologis bumi.
Penutup: Mendengarkan Suara Laut
Laut tidak
berbicara dengan bahasa manusia, tapi dengan tanda-tandanya: ombak yang makin
tinggi, ikan yang makin sepi, dan pantai yang makin jauh dari bibir daratan. Ia
tengah menegakkan gugatannya, meskipun bukan di pengadilan manusia, tapi di
ruang nurani bangsa Indonesia yang dua pertiganya adalah entitas dia.
Baca Juga: Konsensus Epistemik Hakim: Fondasi Baru Keadilan Iklim di Indonesia
Seperti kata Stone,
“Hukum berkembang sejauh manusia memperluas
lingkaran simpatinya.” Kini saatnya kita memperluas lingkaran itu,
hingga mencakup laut dan segala isinya. Karena ketika laut kehilangan haknya,
kita kehilangan masa depan kita sendiri dan masa depan generasi mendatang. (ldr)
Untuk Mendapatkan Berita Terbaru Dandapala Follow Channel WhatsApp : Info Badilum MA RI